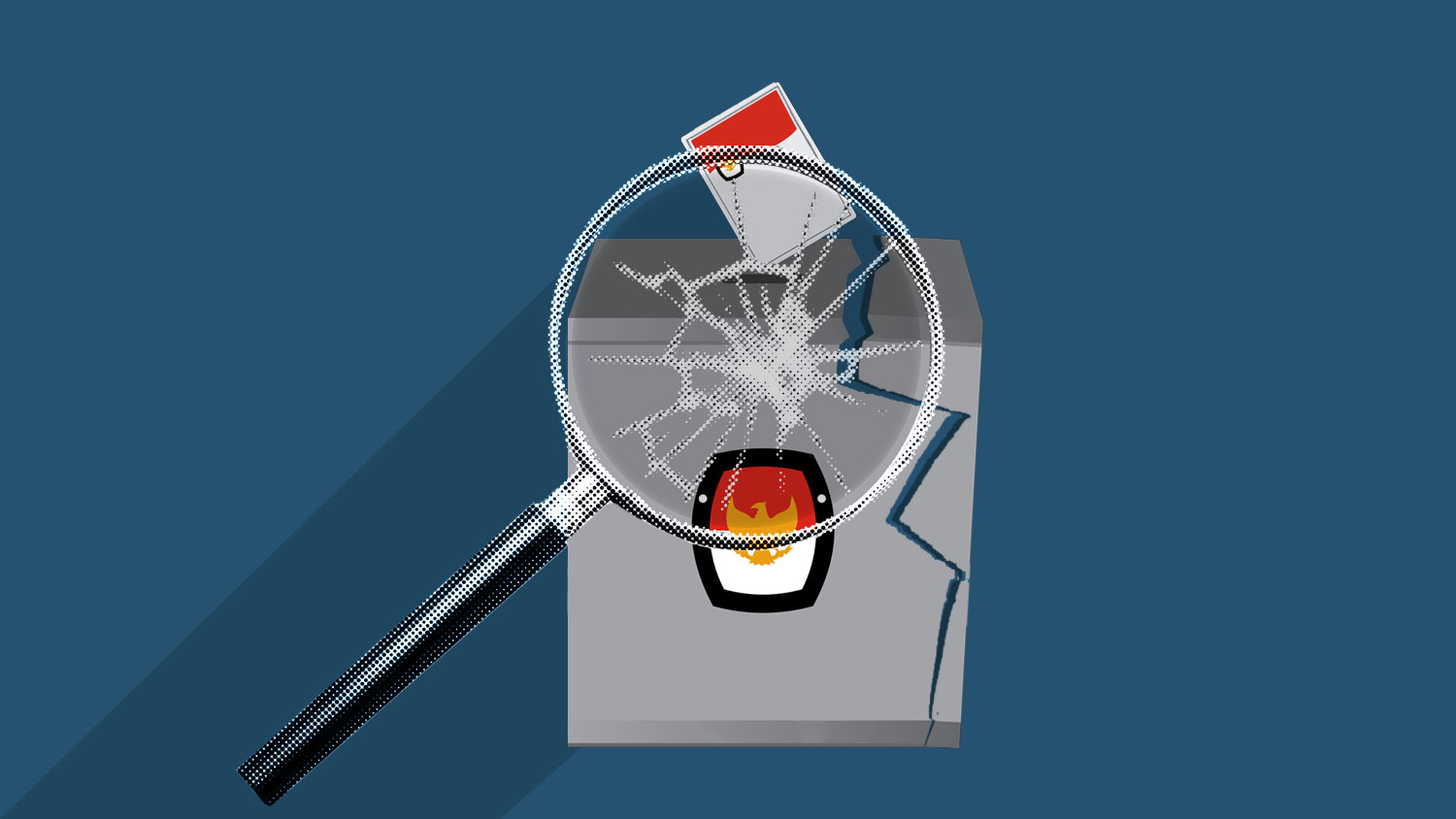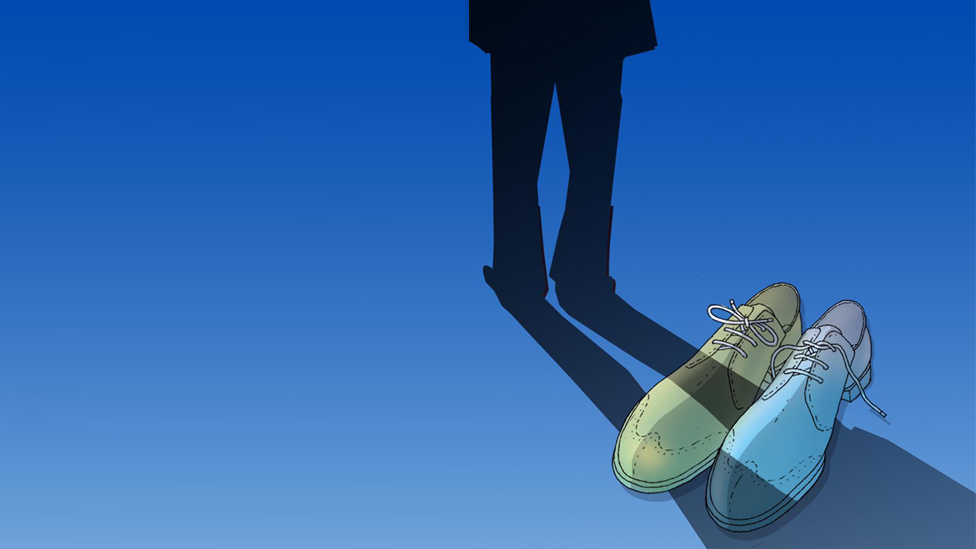Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Haryo Kuncoro
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejak pengumuman resmi pemerintah atas dua kasus pertama wabah virus corona pada awal Maret, seketika itu pula pelaku ekonomi terjangkit "wabah" kepanikan. Rumah tangga konsumen mengalami kepanikan beli (panic buying) dengan memborong berbagai macam bahan kebutuhan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Produsen pun mengalami kecemasan dengan menunda ekspansi bisnisnya. Banyak perusahaan mulai merevisi ke bawah proyeksi kinerjanya sepanjang tahun ini. Pertumbuhan kredit perbankan pada dua bulan awal 2020 yang hanya mencapai 6 persen seakan-akan menjadi justifikasi yang valid.
Imbasnya, harga bahan pangan yang volatil sudah menunjukkan tanda-tanda geliat peningkatan. Kecenderungan ini bisa berlanjut memasuki bulan puasa dan Idul Fitri. Konsekuensinya, target inflasi yang dipatok 3 persen plus/minus 1 persen pada tahun ini sangat terbuka terlanggar.
Pasar modal pun bukan pengecualian. Pemegang saham melepas kepemilikannya di bursa. Sesuai dengan hukum pasar, pasokan berlebih tanpa imbangan permintaan yang sepadan niscaya menekan harga. Indeks harga saham gabungan yang menukik hingga di bawah 4.000 menjadi fakta pendukung yang kuat.
Di pasar obligasi, pemodal asing berskala besar beramai-ramai menjual surat berharga (sell off bonds). Sejak akhir tahun lalu, penjualan obligasi oleh investor asing mencapai Rp 78,76 triliun. Hasil penjualan pemodal asing atas saham dan obligasi kemudian dikonversi ke dalam dolar Amerika Serikat sehingga menekan rupiah.
Sampai minggu ketiga Maret 2020, nilai tukar rupiah anjlok hingga sempat menembus 16 ribu per dolar Amerika, meskipun akhirnya ditutup pada tingkat 15.900 per dolar Amerika. Sementara itu, rekor pelemahan rupiah ketika krisis moneter terjadi pada 18 Juni 1998 yang mencapai 16.200 per dolar Amerika.
Fenomena di atas harus menjadi alarm bagi Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Kebijakan moneter diramu atas dasar asumsi rasionalitas pelaku ekonomi. Saat asumsi rasionalitas secara ekonomi tidak terpenuhi, maka kebijakan tidak akan efektif.
Jika logika secara ekonomi tidak lagi rasional, fenomena "hipotesis terbalik" pun dikhawatirkan akan berlaku. Intervensi BI di pasar spot, misalnya, malah bisa jadi dipandang pemain pasar sebagai fasilitasi terhadap kebutuhan valuta asing. Artinya, berapa pun kebutuhan valuta asing akan segera tersedia.
Intervensi di pasar domestic non-delivery forward (DNDF) juga bisa keliru ditafsirkan sebagai "kerelaan" BI menanggung risiko perubahan kurs. Mekanisme DNDF menghendaki pertukaran valuta asing tanpa diikuti pertukaran fisiknya. Konsekuensinya, BI harus membayar premi selisih kurs.
Pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI di pasar sekunder sangat boleh jadi dianggap sebagai "jaminan" penyerapan SBN yang dilepas pemodal asing. Intinya, pemodal asing bisa menjual berapa pun SBN setiap saat tanpa kekhawatiran, toh sudah ada kepastian calon pembelinya.
Trisula intervensi pasar di atas berbiaya mahal. Selama dua bulan terakhir, BI sudah mengeluarkan dana cadangannya setidaknya Rp 200 triliun. Berkurangnya cadangan devisa di saat prospek ekspor dan arus modal masuk yang serba tidak pasti menjadi terasa semakin berat.
Dengan demikian, BI harus menyiapkan strategi komplementer guna meminimalkan potensi imbal korban antara stabilisasi nilai tukar dan akumulasi cadangan devisa. Dalam konteks ini, kebijakan non-teknis mutlak diperlukan sebagai imbangan kebijakan yang telah dirilis sebelumnya.
Berkaca pada krisis keuangan global 1997/1998 dan 2008, BI harus mampu meredam kepanikan dengan pendekatan persuasi moral. Komunikasi kebijakan yang mengandung muatan edukasi dan literasi penting ditujukan untuk mengembalikan rasionalitas para pelaku ekonomi kembali ke jalur logika semula.
Dalam skala yang lebih luas, BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah perlu memastikan agar pesan edukasi dan literasi lewat persuasi moral sampai pada target guna menurunkan tensi kepanikan tadi. Persuasi moral ini sekaligus untuk meredam aksi spekulasi yang memanfaatkan situasi.
Bagaimanapun, stabilitas nilai tukar menjadi determinan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Lagi pula, sistem ekonomi terbuka yang dianut Indonesia menutup kemungkinan sistem kurs tetap. Ringkasnya, pengaruh faktor eksternal senantiasa mengharu-biru ekonomi domestik.
Untuk itu, persuasi moral juga harus diarahkan agar pemodal domestik membeli SBN yang dilepas asing. Perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) didorong membeli kembali sahamnya. Perbankan perlu dikondisikan agar menurunkan suku bunga kredit kepada industri substitusi impor. Konsumen pun diimbau agar seperlunya membeli barang.
Walhasil, karantina wilayah (lockdown), isolasi, dan pembatasan sosial (social distancing) dalam konteks kesehatan juga perlu ditempuh dalam konteks perilaku. Tujuannya agar kepanikan yang menggerus rasionalitas tidak saling menulari antara pelaku ekonomi satu dan yang lain.
Pada akhirnya, Kementerian Kesehatan harus mampu meyakinkan masyarakat akan tuntasnya penanganan wabah corona. Ketakutan yang berlebihan justru menjadi kendala terbesar bagi semua ikhtiar dalam meredam kepanikan pasar dan irasionalitas logika ekonomi di tengah badai corona.