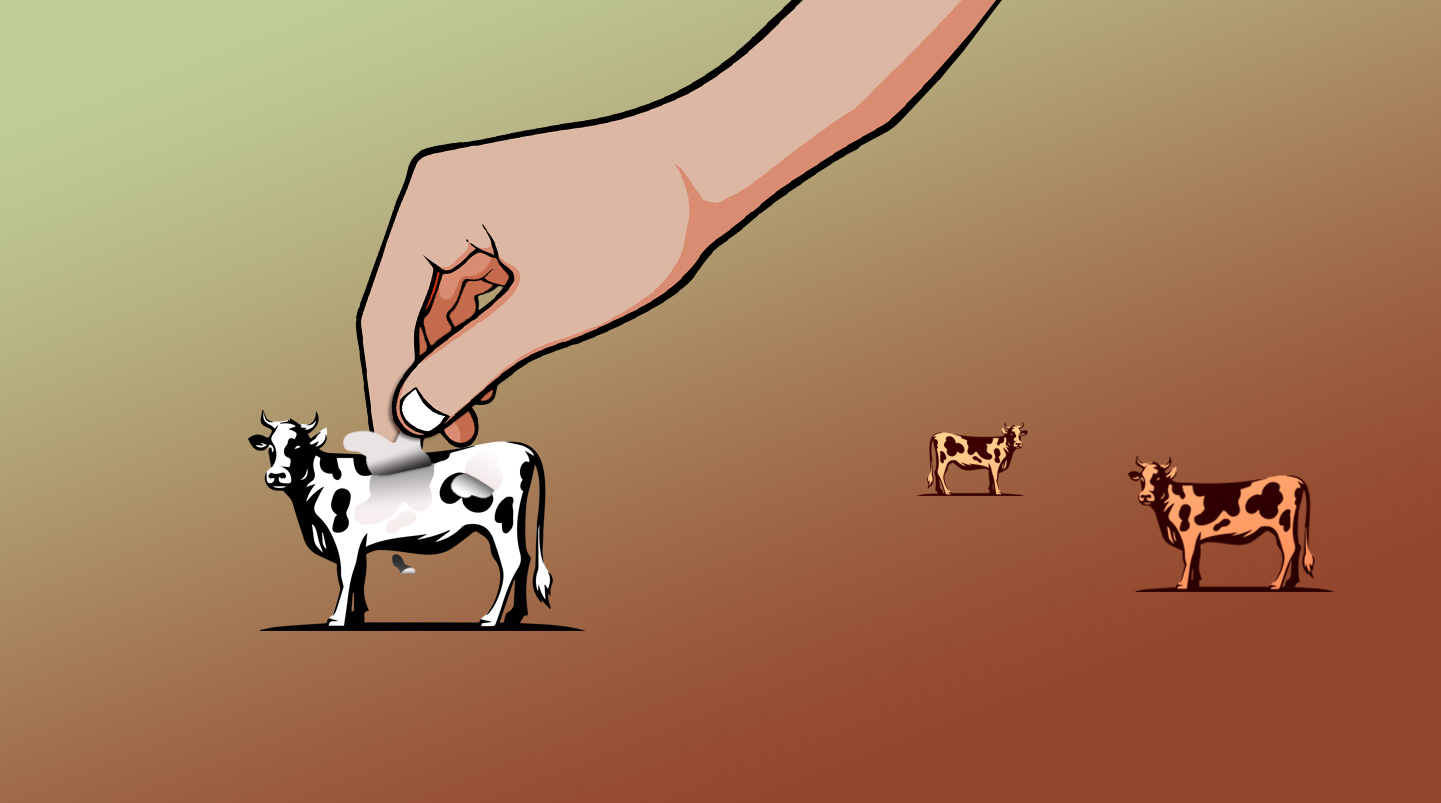Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PRAKTIK berdemokrasi yang sehat menghadapi ujian besar. Rezim-rezim otokratis makin represif dalam menindas suara-suara kritis. Kecenderungan ini terjadi di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Tindakan pemerintah Filipina mengkriminalkan Maria Ressa, jurnalis senior dan pemimpin Rappler, menjadi contoh mutakhir tren ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Demokrasi Filipina di bawah Presiden Rodrigo Duterte memang seperti melompat mundur. Kebebasan berpendapat di negara diberangus sedemikian rupa. Media massa yang kerap mengkritik pemerintah, seperti Rappler dan Philippine Daily Inquirer, terus diserang. Mereka dituduh menyebarkan berita palsu atau mencemarkan nama. Pemerintah menutup paksa ABS-CBN, jaringan televisi dan radio Filipina, dengan tidak lagi memperpanjang izinnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Filipina bukan satu-satunya pemerintahan yang menggunakan undang-undang untuk membungkam lawan politik. Rezim-rezim yang cenderung otokratis di Asia menggunakan hukum semacam itu untuk memberangus para pengkritik. Dengan alasan memerangi terorisme dan kejahatan siber, undang-undang memungkinkan pemerintah memantau dan menghukum orang atau kelompok yang bersuara berbeda.
Para aktivis Hong Kong sedang menghadapi tekanan besar. Pemerintah Cina berupaya menghentikan berbagai unjuk rasa yang menolak campur tangan terlalu dalam mereka ke wilayah itu dengan menerapkan undang-undang keamanan nasional. Aturan ini akan memenjarakan siapa saja yang dianggap membahayakan keamanan nasional, seperti separatisme, subversi, dan terorisme.
Rezim di negara-negara lain juga berusaha memanfaatkan regulasi untuk mengukuhkan kekuasaannya. Kamboja menerbitkan undang-undang siber dan membentuk unit kejahatan siber di kepolisian yang sesungguhnya menjadi alat untuk menekan kebebasan berekspresi dan menyingkirkan oposisi. Myanmar telah menerbitkan 200 regulasi siber yang membatasi apa yang boleh ditulis secara online, memidanakan “pencemar nama” di media daring, dan menghukum berat para pengkritik. Thailand memanfaatkan pasal penghinaan kerajaan (lese majeste) untuk memenjarakan lawan-lawan politik pemerintah yang menyatakan pendapatnya di media sosial.
Indonesia masuk barisan itu ketika menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. SAFEnet, lembaga nirlaba pemantau kebebasan berekspresi, mencatat pasal-pasal karet dalam aturan itu telah digunakan secara masif sejak diundangkan. Pasal yang banyak digunakan adalah pencemaran nama dan ujaran kebencian. Meski telah direvisi pada 2018, aturan lenturnya tak begitu banyak berubah.
Ruang sempit demokrasi ini bahkan tidak hanya terjadi di kawasan Asia. Freedom House, organisasi non-pemerintah di Amerika Serikat yang rutin memantau perkembangan kebebasan politik, menyimpulkan demokrasi di dunia berjalan mundur dalam 13 tahun terakhir. Jumlah negara yang masuk kategori tak bebas terus bertambah—dan, sebaliknya, kebebasan makin berkurang.
Dalam situasi seperti ini, masyarakat sipil sudah selayaknya berkonsolidasi. Di Indonesia, kelompok-kelompok prodemokrasi semestinya segera menyatukan langkah. Harus diingat, suara kritis bukanlah racun yang “merusak pembangunan”, melainkan justru penerang agar kehidupan bernegara terhindar dari bias kepentingan sekelompok orang. Karena itu, demokrasi mesti diselamatkan bersama-sama.