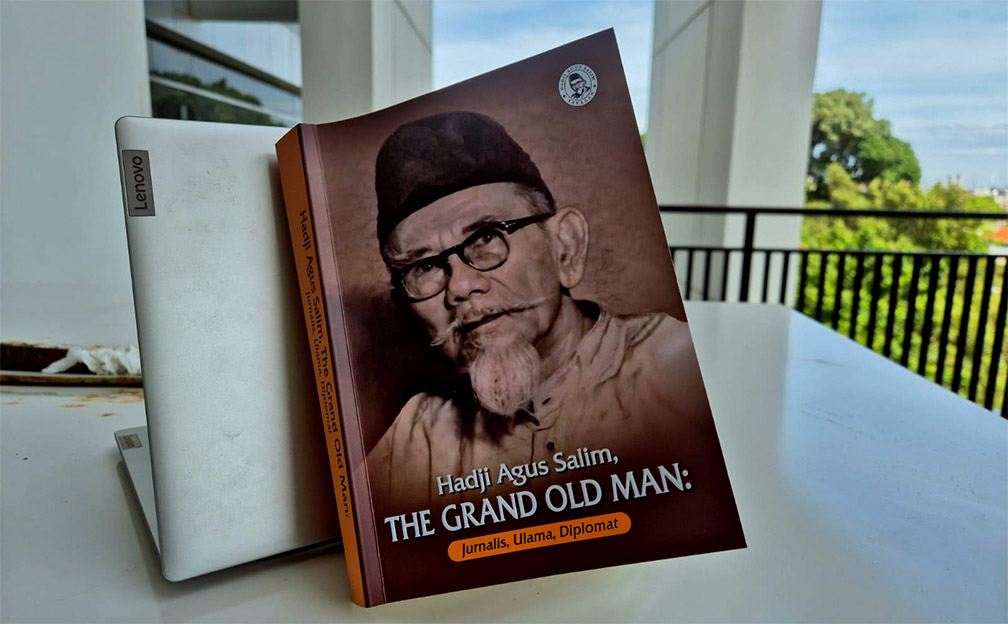Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Kelompok paduan suara Dialita kembali tampil dalam peluncuran buku terbaru tentang Mia Bustam menjelang Hari HAM Sedunia, 10 Desember.
Dialita menyuarakan sejarah kelam tragedi 1965 dengan membawakan lagu-lagu karya tahanan politik peristiwa G30S.
Dengan anggota yang kian sepuh, Dialita mencari generasi penerus.
SEPULUH perempuan anggota paduan suara Dialita khidmat menyanyikan Taman Bunga Plantungan, lagu yang ditulis tahanan politik 1965 di penjara. Mereka tampil sebagai tamu dalam peluncuran buku memoar keempat Mia Bustam—pelukis perempuan Lekra yang ditahan tanpa pengadilan seusai Gerakan 30 September atau G30S—di Beranda Rakyat Garuda, Pinang Ranti, Jakarta Timur, pada Sabtu, 7 Desember 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kelompok paduan suara itu berdiri atas inisiatif bekas tahanan politik dan anak-anak korban tragedi 1965. Dalam perjalanannya, Dialita menjelma menjadi gerakan yang menyuarakan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, dengan lebih dari ratusan ribu orang dieksekusi dan ditahan tanpa pengadilan dengan tuduhan terlibat G30S ataupun menjadi simpatisan Partai Komunis Indonesia, PKI. Suara mereka ikut meramaikan Hari HAM Sedunia yang dirayakan setiap 10 Desember.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dialita yakin peristiwa 1965 harus terus disuarakan. Jalan yang mereka pilih adalah paduan suara. "Kami sendiri tidak tahu kapan mau selesai," kata Ketua Dialita Uchikowati Fauzia kepada Tempo, pada Ahad, 8 Desember 2024.
Uchikowati, 72 tahun, adalah Djauhar Arifin Santosa, Bupati Cilacap periode 1958-1965 yang didukung PKI. Ibunya, Hartati, anggota Gerwani. Orang tua Uchikowati ditangkap tentara pada 1 November 1965. Ibunya baru dilepas pada Mei 1973 dan ayahnya pada April 1980. Menurut Uchikowati, Dialita dapat meneruskan suara korban ketidakadilan tersebut. “Lagu-lagu itu medium buat kami menuturkan sebuah peristiwa kelam,” ucapnya.
Dialita dibentuk dari hasil kumpul-kumpul para eks tapol perempuan penghuni Penjara Bukit Duri, Ambarawa, dan Kamp Plantungan. Kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto membuat mereka tak lagi takut bertemu. Dari rangkaian pertemuan tersebut, muncul ide membentuk kelompok paduan suara. Tepatnya di rumah Utati, di Depok, Jawa Barat, pada 4 Desember 2011.
Utati, 80 tahun, adalah bekas anggota kelompok kesenian Pemuda Rakyat, organisasi sayap PKI. Dia ditangkap di Jakarta pada 1967 dan diterungku di Penjara Bukit Duri, Jakarta Timur. Setelah keluar dari jeruji besi, dia menikah dengan Koesalah Soebagyo Toer, adik Pramoedya Ananta Toer, pada 1979. Koesalah adalah penerjemah novel Hadji Murat karya Leo Tolstoy, dan Jiwa-jiwa Mati bikinan Nikolai Gogol. Dia ditahan di Penjara Salemba.

Kelompok Paduan Suara Dialita di acara peluncuran buku memoar Mia Bustam di rumah Komunitas Beranda Rakyat Garuda, Pinang Ranti, Jakarta Timur, 7 Desember 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Dialita adalah akronim dari Di Atas Lima Puluh Tahun, sesuai dengan usia para anggotanya. Anggota Dialita awalnya 11 orang, lalu berkembang menjadi 22 orang. Mereka tak hanya membawakan lagu nasional, tapi juga syair-syair yang ditulis para tapol.
Utati, misalnya, menulis tiga lagu di Bukit Duri, yaitu Ibu, Buruh Wanita, dan Indonesia Jaya. Ibu tercipta pada tahun pertamanya di balik terali. Saat itu Utati tak berhenti mengingat ibunya di kampung halaman di Purworejo, Jawa Tengah. "Entah dia tahu apa tidak saya ditahan," tuturnya.
Berawal dari sudut perumahan di Depok, Dialita mendunia. Pada Mei 2019, misalnya, mereka menerima penghargaan Hak Asasi Manusia Gwangju dari Yayasan Memorial 18 Mei di Korea Selatan.
Namun, seperti para anggota lain, Utati dan Uchikowati telah sepuh. Mereka kerap membicarakan siapa yang akan meneruskan Dialita. "Sampai sekarang, kami belum berhasil melibatkan anak-cucu kami ikut bernyanyi," ujar Uchikowati.
Utati mengatakan banyak anggota keluarga penyintas takut menyatakan diri sebagai korban tragedi 1965. Bahkan untuk sekadar membiarkan orang tuanya berkumpul dengan sesama korban. "Biar waktu yang menjawab."
Sufmeyeti Masitha, 63 tahun, mengatakan tiga anaknya tak mempermasalahkan dia aktif di Dialita. Namun dia tak pernah mengajak mereka bergabung. Bukan apa-apa. Hingga kini mereka masih didera stigma buruk sebagai keluarga PKI di lingkungan tempat tinggal mereka di Manggarai, Jakarta Selatan. "Biasanya ibu-ibu pengajian yang cerita begitu. Saya diam saja," katanya.
Ayah Sufmeyeti ditangkap dan dipenjara di RTC Tangerang saat Sufmeyeti berusia 7 tahun. Tiga saudara perempuan ayahnya juga diciduk. Sementara itu, almarhum suaminya, Hari Syafi'i, pernah dipenjara di Nusa Kambangan, Jawa Tengah, hanya karena menjadi pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia—yang secara struktural tidak berhubungan dengan PKI.

Penampilan Paduan Suara Dialita pada Penghargaan Akademi Jakarta,di Taman Ismail Marzuki Jakarta, 16 November 2022. TEMPO/Muhammad Ilham Balindra
Uchikowati, yang juga aktivis Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), mengatakan di Dialita ada anggota berusia di bawah 50 tahun. Mereka adalah keluarga korban 1965. Dia berharap mereka mau meneruskan Dialita. Menurut dia, ada sejumlah alasan Dialita Next Generation perlu berasal dari keluarga korban 1965.
Pertama, mereka tidak alergi membawa nama Dialita. Kedua, mereka bisa mempertahankan keberadaan kelompok paduan suara ini sesuai dengan visi yang tertanam. Dengan demikian, nilai-nilai yang dibawakan sebagai sebuah gerakan untuk menyuarakan persahabatan dan perdamaian, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dibelokkan. ”Kami berhati-hati di bagian ini," ucap Uchikowati.
Hal lain yang dihindari Dialita adalah komersialisasi. Itu sebabnya para biduan tersebut pantang memasang tarif setiap kali mengamen. "Itu akan menghilangkan nilai-nilai perjuangan," ujarnya.
Uchikowati mengatakan kesulitan mencari penerus Dialita. Untuk itu, mereka membuka diri. Anggotanya kini tak harus keluarga penyintas tragedi 1965, tapi siapa pun yang punya perspektif HAM yang sama. "Itu tertulis dalam piagam kesepakatan," tuturnya.
Hal terpenting bagi Dialita adalah pengakuan bahwa mereka keluarga korban 1965. Uchikowati mengatakan label tersebut masih diselimuti stigma negatif. Dia mencontohkan suatu acara di Jakarta Pusat pada Oktober 2014. Saat itu, sahibulbait meminta rekannya melatih Dialita dan menambahkan empat penyanyi temporer. Menjelang pementasan, empat orang itu baru mengetahui latar belakang kelompok paduan suara tersebut dan menolak disebut sebagai keluarga korban 1965. "Di situ muncul kata 'alergi' terhadap penyintas 65," ujar Uchikowati.
Seusai insiden itu, sang pelatih menemui Utati di Depok untuk meminta maaf. Sang tuan rumah tidak marah. Dia hanya mengatakan mereka sebagai korban ketidakadilan hanya ingin berkumpul, bernyanyi, dan bercerita untuk memulihkan trauma. "Seharusnya trauma itu dipulihkan oleh negara, tapi negara tidak berbuat apa-apa kepada kami," kata Uchikowati menirukan ucapan Utati saat itu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo