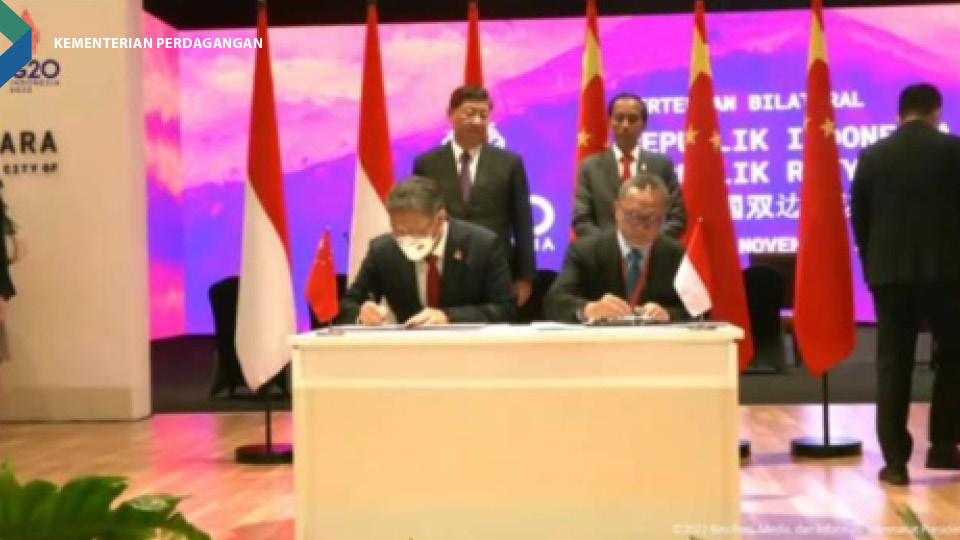Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Memasuki tahun ajaran baru, dunia pendidikan, khususnya tingkat Perguruan Tinggi harus terus meningkatkan kewaspadaan terhadap paham dan gerakan kekerasan, terutama yang ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan legitimasi yang didasarkan pada pemahaman agama yang salah. Paham dan gerakan tersebut adalah intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Catatan Global Terrorism Index 2022 menyebut bahwa sepanjang tahun 2021, terdapat 5.226 aksi terorisme di seluruh dunia. Korban meninggal dunia yang berjatuhan akibat aksi tersebut mencapai 7.142 jiwa. Tidak sedikit dari jumlah tersebut adalah anak-anak, perempuan, dan golongan usia renta; hal ini menunjukkan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, bukan gerakan keagamaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Pertanyaan pentingnya adalah, kenapa anak-anak muda kita tertarik pada narasi atau bahkan gerakan intoleran dan radikal?,” kata Komjen. Pol. Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, M.Si. dalam tulisannya dengan judul “Melindungi Dunia Pendidikan dari Paham dan Gerakan Kekerasan”.
Menurut Gatot, setidaknya terdapat lima sebab, pertama, mereka sedang mencari identitas diri. Studi yang dilakukan oleh The United States Institute of Peace pada 2010 menunjukkan bahwa 2.032 militan asing jaringan Alqaeda berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar; mereka adalah orang-orang yang sedang mengembara untuk menemukan jati dirinya. Kedua, mereka membutuhkan perasaan kebersamaan. Kelompok teroris pandai memanfaatkan para remaja yang sedang resah terhadap kondisi emosionalnya. Mereka ingin mencari kebersamaan yang kadang tidak mereka dapatkan dari keluarganya.
Ketiga, mereka ingin memperbaiki apa yang dianggap mencederai rasa keadilan. Para remaja ini memiliki semangat yang menggebu-gebu dan idealisme yang tinggi untuk melakukan perubahan, hal inilah yang juga dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Keempat, mereka sedang membangun citra diri. Kelompok remaja sangat ingin terlihat menonjol atau eksis, karenanya mereka cenderung tidak segan untuk melakukan berbagai cara untuk tampil impresif, termasuk di antaranya adalah dengan menjadi bagian dari kelompok dan gerakan ekstremis. Kelima, mereka memiliki akses yang luas untuk berinteraksi dengan siapa pun di dunia maya, termasuk dengan kelompok radikal. Persinggungan di dunia maya inilah yang kerap menjadi permulaan bagi kalangan muda untuk bergabung dengan kelompok teroris.
Menurut Gatot, khusus pada poin terakhir, banyak kalangan yang menyebut media sosial telah membuat kalangan anak-anak muda semakin rentan, terutama –sebagaimana dikemukakan dalam temuan Wahid Foundation (2017). “Karena kalangan muda lebih senang belajar agama dari media sosial, dengan ustaz/ah yang belum tentu terjamin kualitas keilmuan dan akhlaknya,” tulis dia.
Melawan dengan Kebersamaan
Penanggulangan bahaya radikalisme dan terorisme di kalangan perguruan tinggi harus diprioritaskan, selain karena hal ini merupakan bagian dari tiga dosa besar di dunia pendidikan yang sedang gencar dihilangkan oleh pemerintah, radikalisme dan terorisme juga berpotensi besar menghancurkan bukan saja negara, tetapi kemanusiaan dan peradaban kita. Untuk itu, Polri serius membangun kerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia untuk melawan segala bentuk ajaran dan gerakan kekerasan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kesiapsiagaan nasional, masifikasi program kontra-ideologi, deradikalisasi, netralisasi media, serta netralisasi situasi.
Pihak kampus pun harus lebih aktif menjadi, meminjam istilah Kadensus 88, kampus inklusi anti-intoleransi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan pertama, membuka lebih banyak ruang perjumpaan di dalam kampus; tak boleh ada organisasi mahasiswa yang bersifat eksklusif. Kampus juga harus tegas soal regulasi anti-radikalisme di internal masing-masing. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan kesepakatan bersama untuk selalu patuh dan menjunjung tinggi empat komitmen dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kampus juga harus selalu memastikan materi pembelajaran mengandung pandangan keagamaan moderat dan bernuansa wawasan kebangsaan. Hanya dengan komitmen dan kebersamaan, kita dapat bersama-sama mengalahkan paham dan gerakan kekerasan.
Di Indonesia, data yang dimiliki oleh Densus 88 terkait aksi terorisme dan penangkapan terhadap pelakunya juga menunjukkan angka yang tinggi. Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari penyebaran paham dan gerakan radikalisme dan intoleransi yang utamanya, menyasar kalangan anak-anak muda, termasuk dengan masuk ke wilayah pendidikan. Dalam lima tahun terakhir ini saja, dunia pendidikan kita, khususnya kampus, masih menjadi incaran utama kelompok radikal-terorisme.
Proses infiltrasi paham dan gerakan radikal dan ekstremisme masuk dengan berbagai cara, mulai dari menyusup di kegiatan-kegiatan keagamaan (CISForm, 2018), masjid-masjid kampus (INFID, 2018), dan persebaran buku-buku (PPIM, 2018). Pola penyebarannya pun tidak lagi dilakukan hanya melalui medium dakwah dan forum-forum halaqah, tetapi sudah merambah ke media sosial (cyber space) dan jalur-jalur pertemanan. Hasilnya, sebagaimana dilaporkan PPIM (2020), 24,89% mahasiswa Indonesia terindikasi memiliki sikap intoleran. Dari sumber lain, Alvara Research (2020) melaporkan bahwa 23,4% mahasiswa dan pelajar Indonesia mengaku anti-Pancasila dan malah pro-khilafah. Data-data ini tentu mengkhawatirkan, tetapi bukan berarti tidak bisa kita kalahkan.
Sel Tidur
Sebagai pintu terakhir sebelum menggumpal menjadi terorisme, radikalisme adalah sikap atau mental yang menyetujui dan mendukung penggunaan aksi-aksi kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. secara lebih spesifik menjelaskan bahwa seseorang dapat dicurigai terjangkit radikalisme apabila menunjukkan bentuk-bentuk aksi seperti mengapresiasi aksi terorisme, tidak mengecam aksi terorisme, menunjukkan dukungan melalui unggahan di media sosial, mencurigai aksi teror sebagai rekayasa, dsb. Jika sikap dan pemahaman ini tidak segera diintervensi, sangat mungkin seseorang yang sudah radikal menjadi teroris. Yang bersangkutan bukan lagi mendukung dan menyetujui aksi-aksi kekerasan, tetapi sudah terlibat langsung dengan menjadi pelaku atau eksekutor aksi-aksi kekerasan tersebut.
Hal yang harus dipahami bersama adalah, radikalisme terjadi secara bertahap dan dengan kadar yang berbeda-beda pula. Umumnya, radikalisme bermula dari intoleransi, yakni sebuah pemahaman dan sikap yang menolak keberadaan kelompok lain; risih dengan perbedaan. Itu sebabnya, tidak sedikit pakar dan pengamat yang menyebut radikalisme ibarat sel tidur yang sewaktu-waktu dapat tergerak untuk melakukan aksi-aksi anarkis.
Lebih jauh tentang ini, Webber dan Kruglanski (2017) dengan sangat yakin menyatakan bahwa seseorang tidak mungkin tiba-tiba menjadi teroris, setiap individu yang menjadi pelaku teror pasti melalui proses radikalisasi. Dan ketika titik pertemuan antara kebutuhan untuk mencari signifikansi diri, narasi propaganda, dan jejaring ke kelompok teror (Webber menyebutnya sebagai 3N Approach: needs, network, narratives), individu yang terpengaruh paham radikal tadi sangat berpotensi menjadi teroris/terlibat dalam aksi teror.