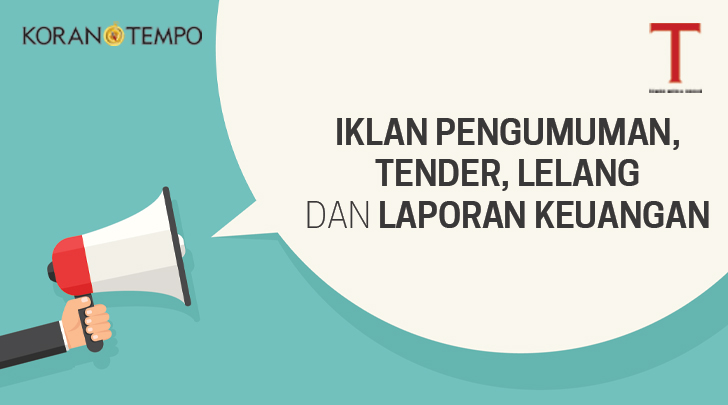Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

INFO NASIONAL -- Sebelum ada ilmu kedokteran, masyarakat menggunakan tanaman sebagai obat-obatan. Secara turun temurun tanaman obat itu dirawat masyarakat lokal, tanpa merusak lingkungannya. Untuk memetik tanaman obat pun ada aturannya.
“Sebenarnya, penemu sejati itu kearifan lokal,” kata Pelestari Tanaman Obat Indonesia Oday Kodariyah pada acara Focus Group Discussion “Potensi Bioprospeksi Indonesia untuk Pembangunan Hijau: Membangun Mekanisme Bioprospeksi Berkeadilan dan Berkelanjutan”, di Gedung Tempo, 27 September 2022.
Oday pun mengaku tidak rela jika tanaman-tanaman itu punah tergilas oleh zaman. Dia pun melatih ratusan pemuda di Kabupaten Bandung untuk mempelajari tanaman obat-obatan.
“Saya akan berjuang mengoleksi tumbuhan dan tanaman obat. Mungkin saya tidak punya pengetahuan penelitian, tetapi saya memiliki kemampuan agar tanaman ini masih ada,” kata peraih penghargaan Kalpataru 2018 kategori Perintis Lingkungan yang setidaknya telah menanam 900 tanaman obat di kebunnya di Kampung Manggu, Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu.
Direktur Program Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) Rony Megawanto mengatakan, masyarakat adat atau masyarakat lokal lah yang merupakan penemu sebenarnya kearifan lokal. “Masyarakat adat atau lokal harus mendapatkan perlindungan.”
Selain itu, menurutnya, masyarakat juga harus mendapatkan benefit ketika produk-produk bioprospeksi ini dikembangkan. “Hanya memang mengembangkan bioprospeksi itu tidak mudah. Butuh proses yang panjang dan belum tentu berhasil,” tambah Rony.
Dia pun berharap, Indonesia sebagai negara megabiodiversitas, saatnya melirik dengan serius keanekaragaman hayati dari sisi genetiknya. “Karena potensi besarnya ada di situ. Itu bisa bermanfaat bagi banyak pihak. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat seharusnya dapat manfaat. Itu yang seharusnya menjadi fokus kita.”
Kolaborasi, kata Rony, menjadi kunci. Karena tidak bisa hanya masyarakat, namun diperlukan juga riset, sektor privat yang melakukan investasi. Namun dia mengakui, untuk tanaman herbal atau obat-obatan masih menjadi kendala karena belum semasif obat-obatan yang diciptakan di laboratorium.
 Pelestari Tanaman Obat Indonesia, Oday Kodariyah saat mengikuti secara daring acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Potensi Bioprospeksi Indonesia untuk Pembangunan Hijau: Membangun Mekanisme Bioprospeksi Berkeadilan dan Berkelanjutan”, di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 27 September 2022. (Foto: Norman Senjaya)
Pelestari Tanaman Obat Indonesia, Oday Kodariyah saat mengikuti secara daring acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Potensi Bioprospeksi Indonesia untuk Pembangunan Hijau: Membangun Mekanisme Bioprospeksi Berkeadilan dan Berkelanjutan”, di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 27 September 2022. (Foto: Norman Senjaya)
Head of the Tropical Biopharmaceutical Study Center (TropBRC) IPB University Irmanida Batubara menuturkan, telah disusun Roadmap Obat Herbal dan Biomedis 2021 – 2030. Selama ini, katanya, banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa telah memaparkan “secara gratis” pengetahuannya terkait tanaman obat dan herbal. “Saat berinteraksi dengan masyarakat lokal, mereka tidak sadar untuk menjaga pengetahuan dan memanfaatkan pengetahuan.”
Irma pun menuturkan pentingnya inventarisasi pengetahuan lokal. Mengoleksi spesimen bahan baku, kemudian disimpan di database. “Namun pertanyaannya, setelah ini siapa yang pegang database nasional kita?”
Dia bilang, kita juga perlu melakukan standarisasi kualitas ketika mengeksplorasi tumbuhan di Indonesia. Setelah menemukan yang prospektif, dicarikan standar budidaya yang baik. Tanaman-tanaman itu, menurutnya, perlu dilindungi dan dilestarikan serta diperlukan dukungan dana. Selama ini, kata dia, salah satu tantangan ada pada industri yang tidak tertarik untuk mendanai pengembangan tanaman obat dan herbal.
Irma mencontohkan keberhasilan lembaganya mengolah kulit dari buah mangrove untuk kesehatan kulit di Sulawesi Selatan. Ketika mengembangkan produknya, mereka pun menghargai masyarakat lokal dengan memberikan transfer teknologi untuk menyediakan bahan baku. Selain itu, pihaknya tak lupa melibatkan putra daerah untuk studi. “Pemanfaatan lestari dengan memperhatikan konservasi.”
Sementara itu, Dian Rosleine dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB mengamati keberadaan dukun yang jumlahnya terus menurun. Padahal, dukun-dukun itu lah yang kerap memberikan informasi tanaman-tanaman obat dan herbal di daerah. Sedangkan keinginan belajar masyarakat generasi muda tidak seperti dulu. “Jangan sampai budaya dari dulu, yang baik, hilang.”
Di Siberut, Mentawai, Dian bersama mahasiswa menemukan bagaimana masyarakat adat memanfaatkan tumbuhan untuk keperluan adat. Berdasarkan hasil studi mahasiswa, untuk mendokumentasikan keanekaragaman hayati di Siberut, ditemukan 163 sample tumbuhan obat yang biasa dimanfaatkan masyarakat di antaranya untuk penyakit cacingan, wasir, demam. “Semua diobati dengan tanaman”.
Dia pun mengingatkan untuk tidak over eksploitasi saat memanfaatkan tumbuhan endemik. Pendidikan konservasi untuk masyarakat adat perlu dilakukan untuk tujuan keberlanjutan itu sendiri.
Kekayaan keanekaragaman hayati harus dijaga sehingga tetap berlanjut. “Keanekaragaman hayati kunci untuk menjaga sustainability. Peranan peneliti sangat penting bagi aspek bioprospeksi, sementara orang yang bekerja untuk konservasi menjaga nilai ekonomi dan ekologi terjaga.” Menurutnya, penelitian untuk bioprospeksi sangat memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak.
 CEO PT Mega Inovasi Indonesia (MIO) Dippos Naloanro Simanjuntak saat mengikuti secara daring acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Potensi Bioprospeksi Indonesia untuk Pembangunan Hijau: Membangun Mekanisme Bioprospeksi Berkeadilan dan Berkelanjutan”, di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 27 September 2022. (Foto: Norman Senjaya)
CEO PT Mega Inovasi Indonesia (MIO) Dippos Naloanro Simanjuntak saat mengikuti secara daring acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Potensi Bioprospeksi Indonesia untuk Pembangunan Hijau: Membangun Mekanisme Bioprospeksi Berkeadilan dan Berkelanjutan”, di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 27 September 2022. (Foto: Norman Senjaya)
Namun, CEO PT Mega Inovasi Indonesia (MIO) Dippos Naloanro Simanjuntak mengingatkan, “ketika kita berbicara bioprospeksi, tanpa kesiapan yang matang, akan mendorong terjadinya biopiracy, Jadi jika kita ingin mengkapitalisasi bioprospeksi maka harus mengkapitalisasi berbagai persiapan dalam mengimplementasikan pelestarian sumberdaya hayati, termasuk kearifan lokalnya”
Menurutnya, Indonesia masih belum siap dalam berbagai hal. Dia pun khawatir, pihak luar bakal mengintervensi atau masuk ketika melihat celah ketidaksiapan Indonesia saat menuju bioprospeksi.
Bioprospeksi, kata CEO Mega Inovasi Organik itu, basisnya biodiversity. Apa yang terjadi dengan biodiversity Indonesia dengan konsep investasi sudah ditinggalkan sejak 50 tahun yang lalu. Pemerintah dengan kebijakannya memaksa petani untuk keluar dari tradisi lokal masyarakat . “Kita bisa bayangkan pemerintah memaksa petani untuk menanam jagung berhektar-hektar, tanpa mengindahkan tradisi pengelolaan sumber daya hayati lokal yang ada.”
MIO, kata Anro, sejak 12 tahun lalu bergerak dalam pengembangan produk organik berbasis komoditas. Perusahaannya membangun 2500 petani organik di Pulau Jawa dengan berbasiskan biodiversity. Menurut pengalamannya, hampir semua privat sector berjuang sendiri untuk dapat mengangkat kearifan lokal menjadi menjadi produk bernilai di pasar global. “Perlu kerja sama untuk melakukan pengembangan.”
Sub Koordinator kerja sama bilateral, Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Eka Fridayanti mengatakan institusinya siap melindungi kekayaan intelektual. Menurutnya, DJKI sudah melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. “Masyarakat bisa berkonsultasi langsung kepada DJKI bagaimana tata cara untuk menginventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK),” katanya. KIK adalah Kekayaan Intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.
Tempo bekerja sama dengan KEHATI dan German Watch menyelenggarakan FGD dengan pemantik yaitu Direktur Program KEHATI Rony Megawanto, Kepala Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN Ocky Karna Radjasa, Kepala Pusat Studi Regulasi dan Aplikasi Kekayaan Intelektual (RAKI) di Departemen Hukum Telekomunikasi, Informasi dan Kekayaan Intelektual, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran Miranda Risang Ayu Palar, serta ragam penanggap baik dari kalangan akademisi, pemerintahan, peneliti dan media.
Di akhir diskusi Moderator Angga Dwiartama memaparkan bagaimana kearifan lokal butuh dilindungi. Alasannya, pertama, tidak ada bentuk kearifan lokal yang didokumentasikan. Kedua, kearifan lokal didokumentasikan dengan baik tapi belum terbangun kelembagaan yang melindungi kearifan lokal tersebut. Ketiga, kelembagaan sudah dibangun dengan baik, tetapi belum tertuang dalam peraturan pemerintah yang melindungi masyarakat adat/kearifan lokal. Keempat, kearifan lokal terdokumentasikan, terlindungi dalam lembaga masyarakat yang kuat, dan didukung oleh kebijakan/peraturan pemerintah di tingkat lokal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini