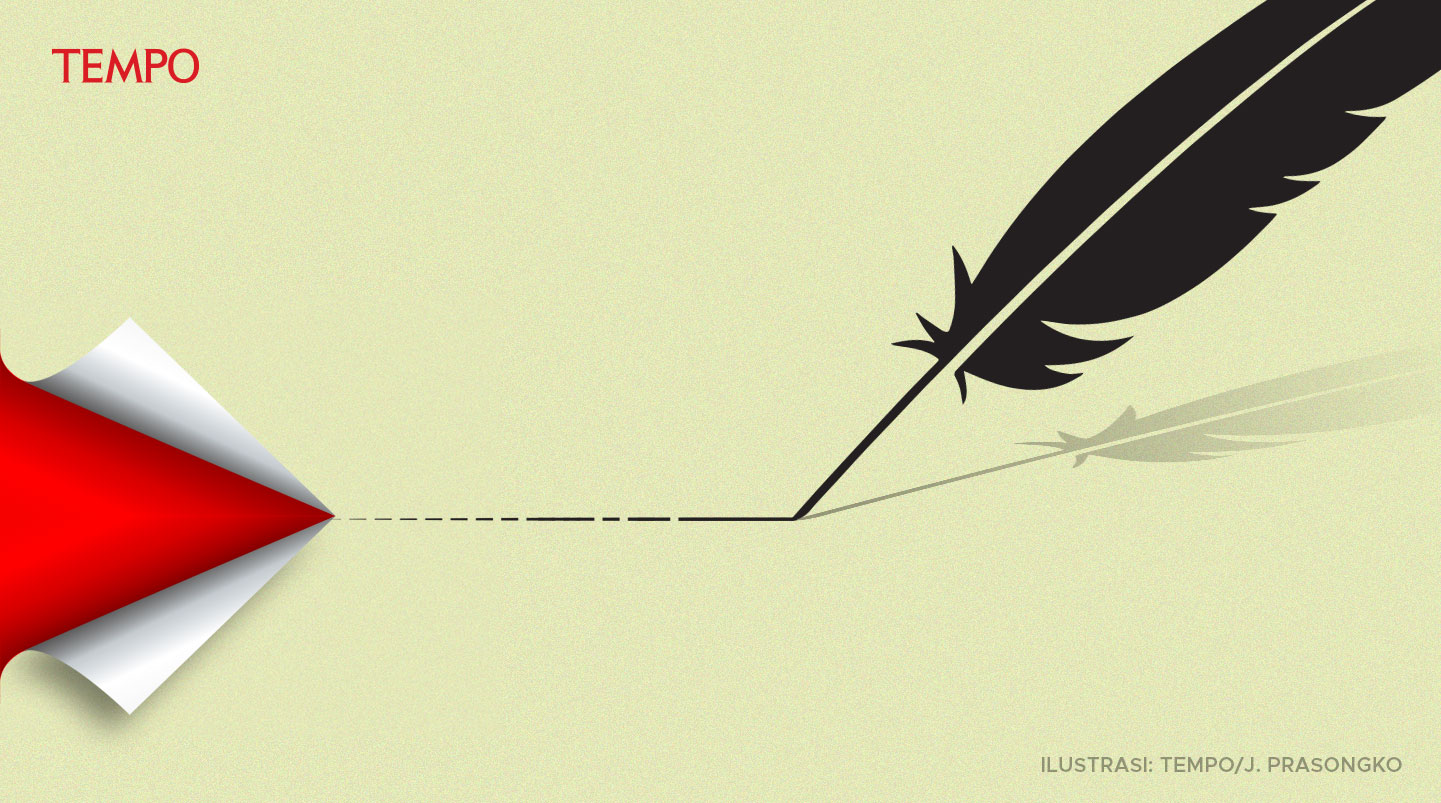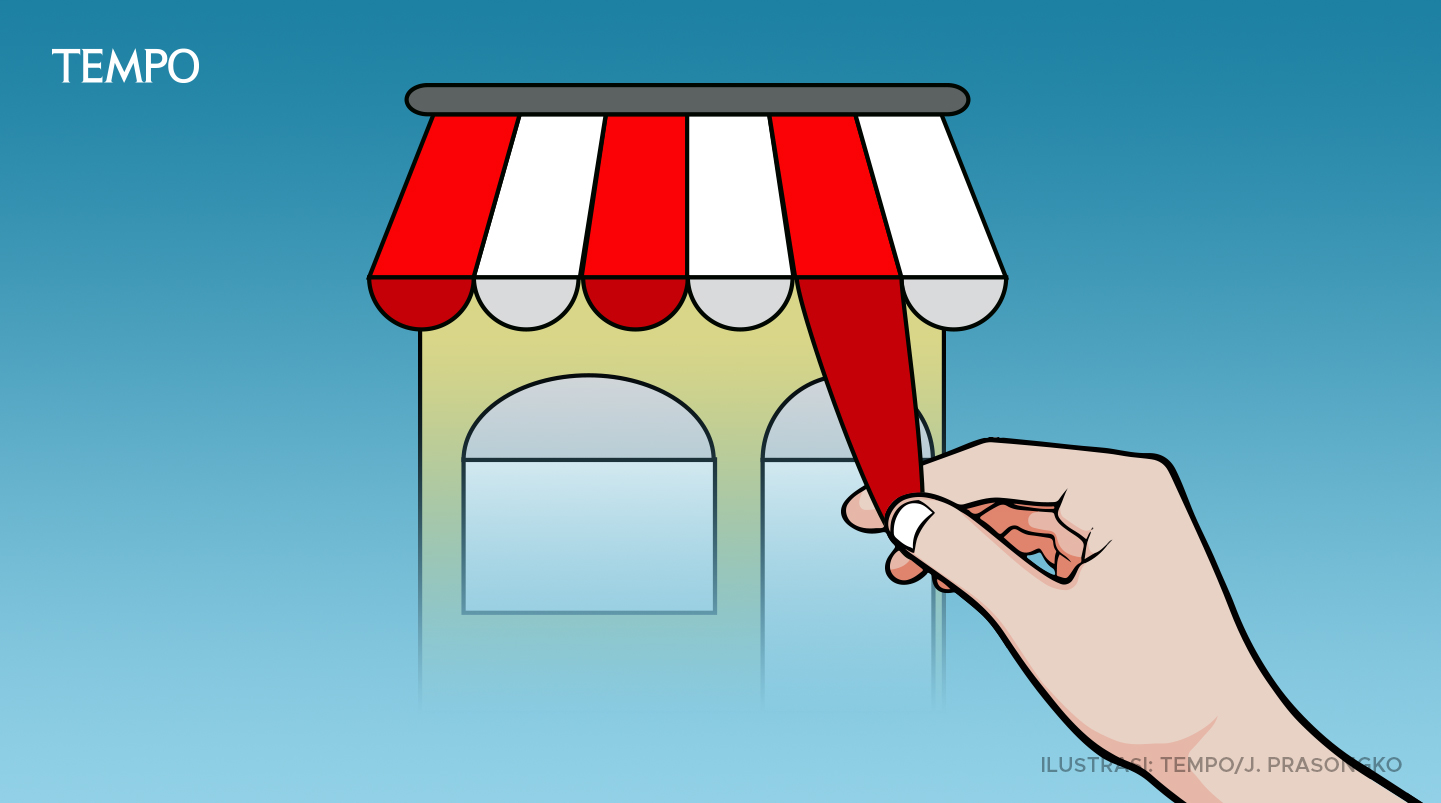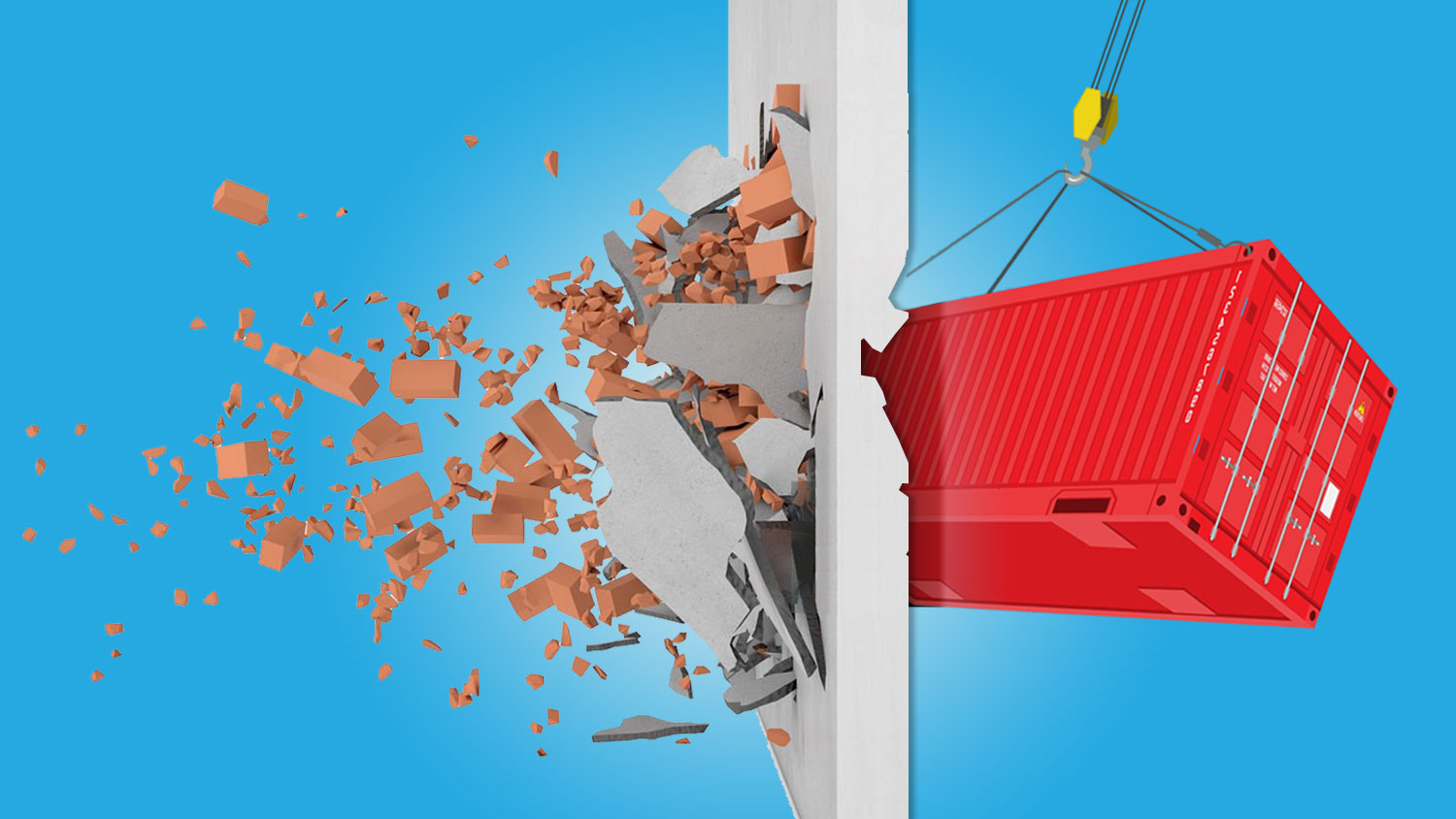Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita
Pemujaan kepada 'gus' dan 'habib' menunjukkan feodalisme agama yang makin kental.
Bisa juga menunjukkan longsornya otoritas agama akibat segelintir kiai acap terlibat perebutan kekuasaan.
Penguasa melegitimasi penceramah yang populer tanpa latar belakang valid untuk pencitraan.
PEMUJAAN kepada mereka yang bergelar “gus” dan “habib” makin mengukuhkan feodalisme yang berakar kuat dalam budaya orang Indonesia. Budaya itu yang membuat Miftah Maulana Habiburrahman, yang acap dipanggil “Gus Miftah”, punya pengikut tak sedikit meski tindak tanduknya tidak mencerminkan seorang penceramah agama yang punya ilmu mumpuni.