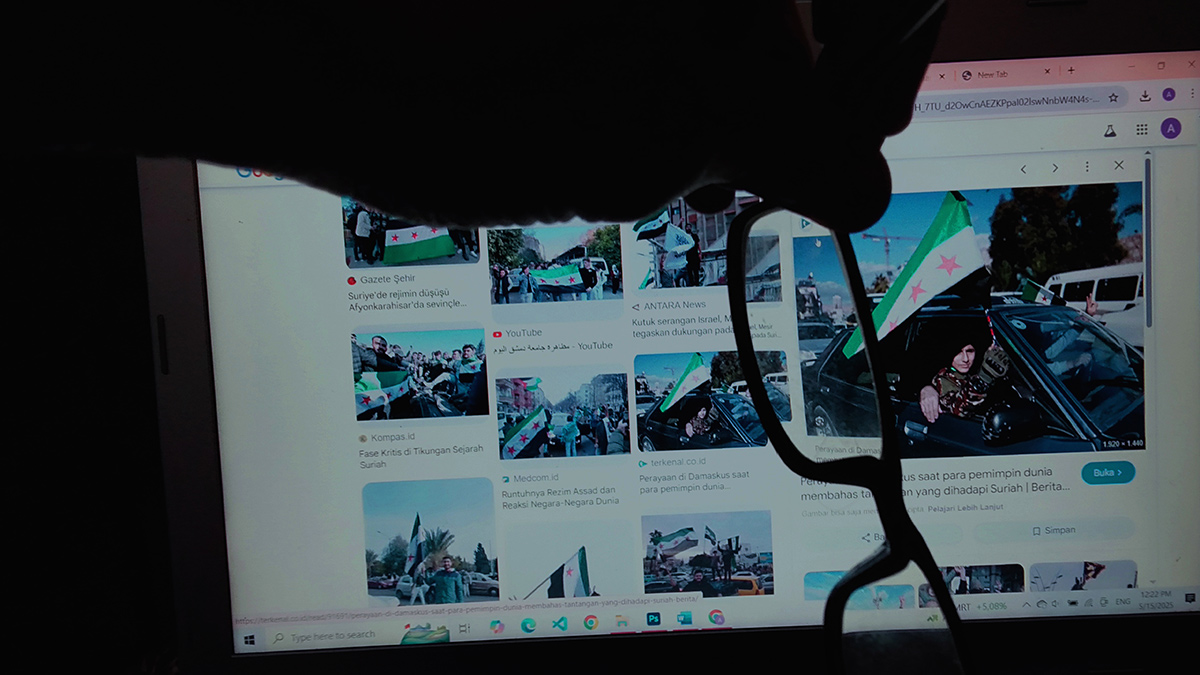Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sehari setelah tragedi 11 September 2001, Presiden Pakistan Jenderal Pervez Musharraf mendapat telepon dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat—ketika itu Colin Powell.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo