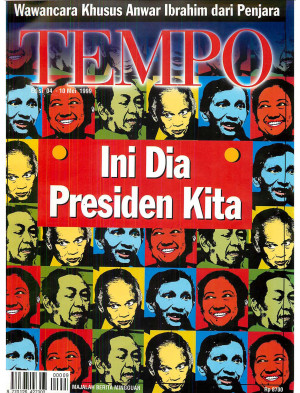MALAM sudah lama turun di Desa Sukaresik. Namun, hawa pesisiran yang hangat di bulan April membuat sebagian penduduk enggan masuk kamar. Oneng Suharya bahkan masih tergelak di ruang tamunya, menjelang tengah malam, bersama seorang kawan lama. Tiba-tiba, dua orang muncul begitu saja dari balik tabir malam. Tak jelas, apa percakapan antara tuan rumah dan tamu-tamunya. Adegan selanjutnya mirip film horor yang diputar lepas tengah malam.
Pembunuhan Oneng Suharya hanya satu kisah seram dari pembantaian para dukun teluh di Kecamatan Ciamis, Parigi, dan Pangandaran, pertengahan April lalu. Daerah pembunuhan ini praktis menjadi kota mati selama sebulan terakhir. Teror dan ancaman seperti hantu, bergentayangan menakut-nakuti penduduk. Tukang becak, ojek, pedagang makanan kecil, yang biasanya lalu-lalang hingga subuh, kini mengunci diri selepas magrib. Kalaupun terpaksa keluar malam, mereka lebih suka melakukannya secara kolektif: nongkrong bersama di pusat-pusat wisata.
Tragedi manusia di daerah "pekidulan"—sebutan penduduk untuk pesisir selatan Jawa Barat dari Ciamis selatan hingga Banten—ini kian mengentalkan suasana mistis yang memang pekat, melengkapi segala legenda dan mitos tentang penguasa hutan dan laut. Kecamatan Parigi, Pangandaran, Kalipucang, Cijulang, dan Cimerak berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia alias Laut Selatan.
Banyak cerita rakyat yang terserak di bukit-bukit, hutan, dan pesisir sepanjang daerah selatan. Dari keangkeran Leuweug (hutan) Sancang dalam mitos Prabu Siliwangi hingga Maung Lodaya (harimau jenis Panthera Tigris Sundae), yang dipercaya sebagai jelmaan Prabu Siliwangi. Maung ini, konon, tak pernah lelah berkelana di sepanjang pekidulan.
Pesisir Selatan adalah pusat ilmu gaib bagi sebagian orang Sunda, terutama ilmu-ilmu hitam seperti teluh (santet), pelet (pengasih), dan "werejit" (sejenis ilmu hitam khas Sunda). Beberapa tempat dikeramatkan karena dipandang memiliki hubungan dengan dunia gaib, misalnya Gunung Wayang, di Kecamatan Parigi. Inilah pertapaan sekaligus tempat mendalami ilmu hitam. Para dalang wayang golek "ditahbiskan" di tempat ini sebelum menggelar pentas perdananya.
Pembantaian dukun santet bukan hal baru di pesisir selatan. Pada 1972, Ki Juni, dukun santet yang menjadi juru kunci makan kuno Eyang Kertasedana di Pasir Kored—sekitar 3 kilometer dari Desa Pagergunung, Pangandaran—dihabisi delapan warga setempat. Di tempat yang sama, Tarmuji, 60 tahun, juru kunci pengganti Ki Juni, dibunuh warga sekitar dua bulan lalu.
Cara-cara pembunuhan dan pembuangan jenazah korban juga memperlihatkan betapa masyarakat setempat tak bisa melepaskan diri dari pola-pola mitos dan legenda yang sudah puluhan tahun hadir dalam kehidupan masyarakat setempat. Unsur sadisme, misalnya, menurut sebagian tersangka, perlu untuk menghindari roh korban bergentayangan.
Alhasil, kendati sulit dibayangkan, adegan ini sungguh-sungguh terjadi: di ujung selatan tanah Priangan yang subur, tempat penduduknya hidup dengan keramahan dan suasana bersahabat, beberapa pria membunuh kenalannya dengan tenang. Tubuh korban dipotong-potong di halaman rumahnya—agar rohnya bisa berpulang ke tempat yang seharusnya. Lalu, dalam keadaan bercucuran darah, potongan-potongan tubuh itu disate ke bambu runcing. Ironisnya, para pembantai ini dielu-elukan warga sebagai pahlawan yang membebaskan warga dari "derita santet dan teluh".
Setelah itu, masya Allah, warga setempat mengarak "sate manusia" ini beramai-ramai ke hutan atau ke sungai. Tempat dan cara pembuangan jenazah pun dipilih menurut pola kebiasaan turun-temurun, guna mencegah mondar-mandirnya para arwah penasaran.
Tempat pembuangan mayat lain yang populer adalah Sungai Ciwayang, 15 kilometer dari Pangandaran. Kabarnya, inilah lokasi favorit pembuangan mayat sejak pembantaian DI/TII, G30S/PKI, korban pembersihan dukun santet versi 1970-an dan 1980-an, hingga pembantaian dukun teluh, pertengahan April lalu.
Edi S. Ekadjati, ahli sejarah dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, menjelaskan, ilmu teluh adalah warisan masa lampau yang terus bertahan dalam kehidupan masyarakat Sunda, sampai sekarang. Edi merujuk pada sebuah dokumen abad ke-16, yang tertulis di daun lontar, yang dinamai Sanghyang Siksa Kandang Karesian—semacam ensiklopedia adat-istiadat orang Sunda—yang kini tersimpan di Perpustakaan Nasional. Dokumen itu menyebutkan bahwa teluh adalah perasaan "sakit hati, murung, dan tak senang" yang dialihkan kepada orang lain. Naskah ini menjelaskan, orang yang telah kena teluh tak akan bisa diobati, jampi-jampinya tidak mempan, dan niatnya tak akan terlaksana. Edi menjelaskan, ada perubahan makna pada teluh. Kalau dulu yang sakit adalah hati, sekarang yang dikenai adalah fisik orang lain.
Menurut Edi, kecenderungan mistik pada orang Sunda pesisir tak bisa dilepaskan dari faktor alam: hutan lebar, pantai curam, ombak Laut Selatan yang ganas, dan kehidupan yang sulit karena kemiskinan daerah itu. Kemiskinan kadang memaksa orang mencari penghidupan secara tidak lazim. Dari situlah kemungkinan motif utama orang mempelajari ilmu teluh. Dalam perkembangannya, orang-orang yang sakit hati meminta bantuan kaum berilmu ini untuk membalaskan dendam mereka lewat kekuatan mistik.
Tragedi pesisir selatan bukan fenomena baru dalam masyarakat Indonesia. Bahkan bukan khas masyarakat pesisiran pula. Masyarakat Banyuwangi juga digegerkan pembantaian serupa beberapa bulan lalu. Dalam skala yang lebih kecil—dan personal—saling mengirim sihir merupakan bentuk pertarungan "ilmu-ilmu mistik", dengan tujuan baik maupun jahat. Santet, misalnya, adalah salah satu teknik mengirimkan sihir itu.
Tujuan sihir itu sendiri bermacam-macam: defensif, destruktif, hingga homeopathic (mengobati). Bronislaw Malinoswki, antropolog Inggris kelahiran Polandia, yang melakukan banyak studi lapangan tentang mitos dan sihir, mengatakan bahwa konsep sosiologis dari sihir adalah "mengekspresikan, mempertinggi, dan mempertebal keyakinan. Sihir juga menyelamatkan dan memperkuat moral, serta mengandung aturan-aturan praktis untuk memandu manusia."
Dari studi lapangan bertahun-tahun di Pulau Trobriand, Papua Nugini, Malinoswki menyimpulkan dalam Magic, Science, and Religion bahwa magic bukanlah sesuatu yang simbolis, melainkan ekspresi langsung dari "sesuatu": misalnya nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Penjelasan ini barangkali bisa membuat kita memahami absurditas dunia perteluhan: pembantai dianggap pahlawan. Atau, warga yang soliter dituduh sebagai sumber segala penyakit yang aneh dalam sebuah masyarakat pedesaan.
Malinoswki menekankan, untuk memahami dunia sihir dan bagaimana pembalasan terhadap sihir bisa terjadi, orang harus mengamati sebuah konteks sosial sehingga orang bisa mengerti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Praktek perdukunan sendiri sudah hadir sekitar 25 ribu tahun di atas muka bumi. Prakteknya secara "modern" menyebar di Eropa Barat selama 300 tahun (1450-1750). Itulah masa ketika para dukun dibakar hidup-hidup di seluruh daratan Eropa. Amerika juga mencatat salah satu peristiwa terkelam dalam lembaran sejarahnya lewat pembunuhan ratusan orang yang dicurigai sebagai dukun santet di kawasan Salem, Massachusetts, pada 1692.
Sejarah menunjukkan secara jelas bahwa perteluhan, atau apa pun istilahnya, bukan hanya hadir di Ciamis, Pangandaran, atau Banyuwangi. Manusia di berbagai belahan dunia mengenal, meyakini, dan menjalankan praktek-praktek perdukunan dengan berbagai tujuan. Praktek itu terjadi dalam konteks sosial yang berbeda-beda, tapi sesungguhnya memiliki bahasa yang sama.
Sihir mengandung fenomena natural sekaligus supernatural. Sihir juga mengandung tipuan (seperti dalam permainan sulap) maupun kenyataan yang kejam (seperti jarum yang mengeram dalam perut)—antara ada dan tiada. Namun, dalam banyak kasus, orang lebih terkesan pada yang nyata dan kejam tadi, bahkan meyakininya sebagai kebenaran—ketimbang mengingatnya dari sisi yang sebaliknya. Dan itulah yang membuat pembalasan ala Ciamis, Banyuwangi, Bavaria, atau Salem bisa berlangsung begitu kejam, tapi, ironisnya, memperoleh toleransi sosial yang bahkan "jauh lebih kejam".
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini