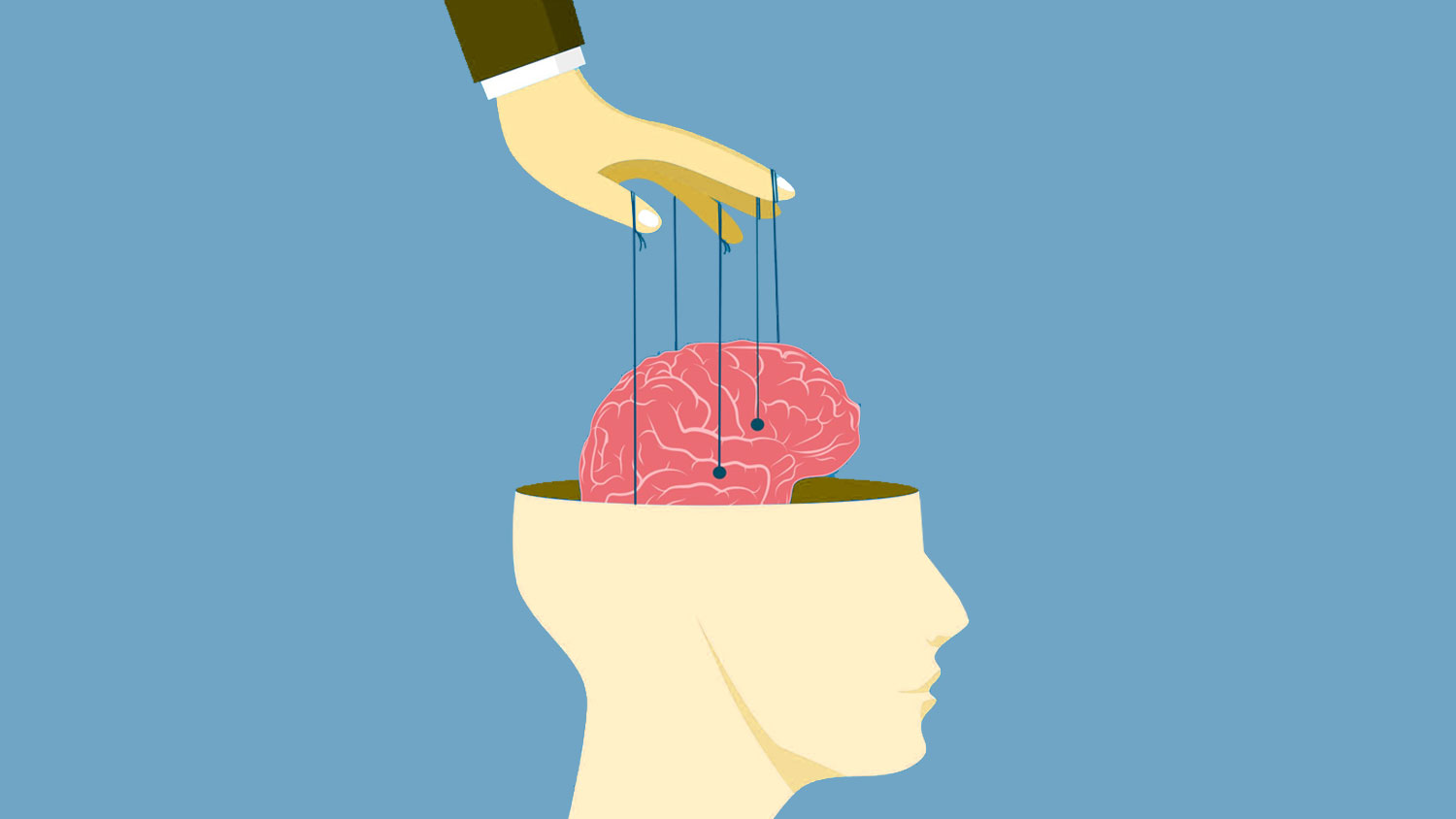Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Seorang ibu yang tak pernah dimuliakan adalah Gandari. Ia berada di pihak yang kalah dan dibenci.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Dalam epos Mahabharata, ia ibu para Kurawa. Suaminya lahir sebagai pangeran buta, dan sebab itu tak diberi kesempatan memegang tampuk kekuasaan. Anak-anaknya dikisahkan sebagai orang-orang dengki yang pada akhirnya tewas. Klannya kalah, tak mendapatkan kerajaan yang 12 tahun mereka rebut dari para Pandawa. Dan Gandari dikisahkan sebagai perempuan yang tak hendak mendidik anak-anaknya; para dalang, pencerita, dan penonton tak pernah memperlihatkan simpati kepadanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Tapi sebenarnya ia penting dalam cerita ini: perempuan yang teguh itulah yang memperlihatkan bahwa Mahabharata sebuah tragedi. Memang ini cerita kepahlawanan, tapi juga cerita destruksi dan kemerosotan. Setelah Bharatayudha, yang tragis tak hanya menimpa kehidupan Kurawa, tapi juga Pandawa.
Akhir perang besar itu tak membawa kepastian. Klan Panchala berkuasa, dan Yudhistira, pangeran sulung, memerintah selama 36 tahun. Tapi ada yang menakutkan mendekat: Kali Yuga.
Apa yang didapat setelah pertempuran 18 hari dan 80 ribu jiwa tewas di Kurusetra? Generasi muda punah: Bima kehilangan Gatutkaca, Arjuna tak punya lagi Abimanyu. Hanya tinggal sebelas kesatria yang hidup, termasuk lima kakak-adik Pandawa.
Dan Gandari menanggungkan dua duka: kematian 100 anaknya dan nama buruk yang melekat pada mereka, kekejaman nasib dan kesewenang-wenangan langit. Kresna, titisan Wishnu, yang seharusnya bisa mencegah perang yang mengerikan itu, tak melakukannya. Bahkan ia yang mendorong agar Arjuna tak bimbang membunuh Karna. Kekuasaan, juga kesaktian, tak menyelamatkan.
Gandari dengan pahit mengutuk.
Dan konon karena itu Kresna, raja Dwaraka yang dipuja-puja itu, mati secara sepele: sebatang anak panah tak disengaja mengenai kakinya. Arjuna, konon titisan Wishnu juga, tak mampu menyelamatkan penduduk Kerajaan Dwaraka dari bencana dan perampok.
Menyadari kejayaannya pudar, Pandawa pun meninggalkan takhta. Mereka mendaki Himalaya, menuju surga. Tapi mereka ditolak, kecuali Yudhistira, kesatria yang tak pernah menghina makhluk yang lemah sekalipun.
Demikianlah kekuasaan yang direbut lepas-tapi orang mencarinya lagi. Sejarah penuh kisah seperti itu. Kekuasaan memang punya pukau. Orang akan berikhtiar memperolehnya, menghimpunnya, bila perlu dengan menyuap dengan uang triliunan agar mendapat posisi, mengorbankan keyakinannya sendiri, mematikan apa yang dalam hatinya diketahui benar. Kalau perlu, berdusta dan membinasakan.
Kekuasaan, terutama kekuasaan di dunia publik, tentu ada gunanya bagi orang lain; ayah Ahok-yang murah hati kepada sesama-menasihati anaknya agar mendapatkan jabatan untuk bisa menolong lebih banyak orang.
Tapi takhta bisa dimakan waktu.
Alkisah, setelah Bharatayudha, kekuasaan diteruskan Pariksit. Raja ini pernah berhasil menghentikan Kali Yuga masuk ke wilayahnya. Tapi kemudian, dengan halus, kekuatan pembawa mala dan kegelapan itu masuk ke mahkota emas Pariksit.
Dari sana, Kali Yuga mengacau jiwa Baginda. Pariksit mulai bersikap tak semena-mena. Pada suatu ketika ia mengalungkan tubuh ular mati ke leher seorang tua yang tak menjawab pertanyaannya-ia tahu orang itu sedang bertapa bisu. Perbuatan itu menyebabkan ia dikutuk. Pariksit mati terbakar api Naga Taksaka.
Kekuasaan berakhir dengan mudah-dan bisa dari dalam diri. Mungkin karena kekuasaan sebuah tenaga yang seakan-akan bisa membuka kekuatan lebih tapi sebenarnya tidak. Nietzsche, yang melihat hidup bergerak karena "hasrat akan kuasa", der Wille zur Macht, menulis satu kalimat yang sering dilupakan: "Sering kulihat hasrat memerintah sebagai tanda kelemahan batin: mereka takut akan jiwa budak dalam diri mereka sendiri, dan menutupinya dengan jubah kerajaan." Tapi akhirnya, "Mereka tetap jadi budak para pengikut mereka, kemasyhuran mereka…."
Manusia tak jadi budak bila menganggap kekuasaan tak penting. Itulah yang akhirnya ditunjukkan Airlangga di abad ke-12 di Kediri: meninggalkan singgasana dan bertapa jauh di hutan.
Tapi sosok anarkis utama adalah Malang Sumirang, penyair dan sufi yang tak tunduk kepada tatanan agama dan istana. Ia dihukum bakar di alun-alun Demak, tapi api yang dinyalakan raja tak mengenainya. Malang Sumirang turun dari unggun, setelah menulis puisi yang tak diartikan. Dari sana ia menghilang ke dalam rimba berduri, tanpa pengiring, tanpa pengikut. Ia lepas dari "sang panginte", Yang Mengintai.
Ia merdeka dari kekuasaan di luar dan di dalam dirinya. Ia bebas dari tragedi raja-raja yang menang dan Gandari yang kalah.
Goenawan Mohamad