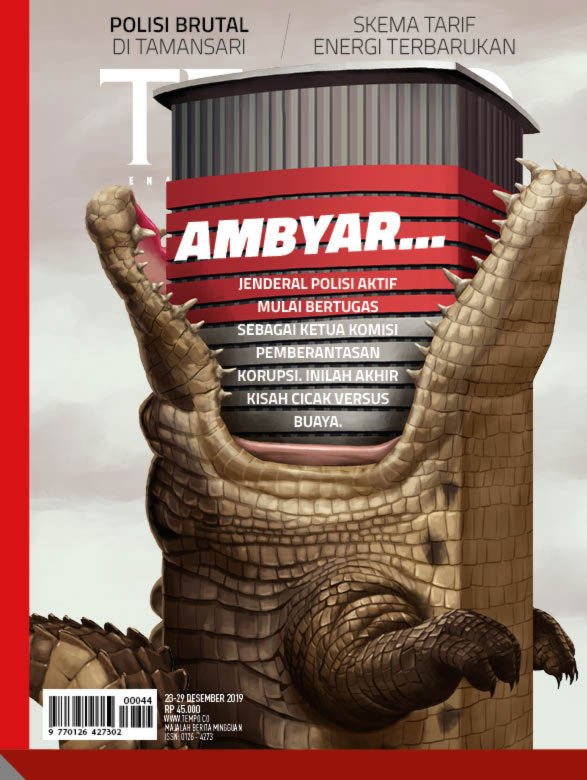Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Pengalaman pendaki amatir naik ke gunung tertinggi di dunia, Everest, hingga ke kakinya.
Sempat didera sakit akibat gagal beradaptasi dengan ketinggian dan oksigen tipis.
Cara berdamai dengan diri sendiri ketika naik gunung.
Wartawan Tempo Bagja Hidayat mendaki Everest di Nepal pada 9 November lalu. Butuh delapan hari ia tiba di kaki gunung tertinggi di dunia itu. Selain merekam eksotisme dataran tinggi Himalaya dan jalur pendakian musim kemarau, yang menyibak langit ke warna birunya yang asli, ia merekam denyut turisme Everest yang menghidupi suku-suku di tebing gunung serta bercengkerama dengan para sherpa dan porter yang menjadi tulang punggung bisnis pendakian.
***
BUKAN dingin dan trek panjang menanjak yang menjadi momok para pendaki gunung-gunung Himalaya, tapi sakit kepala. Pusing akibat ketinggian dan kekurangan oksigen ini bisa menyerang siapa saja, pendaki dengan otot liat atau mereka yang ringkih karena berat badan. Acute mountain sickness (AMS) menyerang tak pandang bulu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo