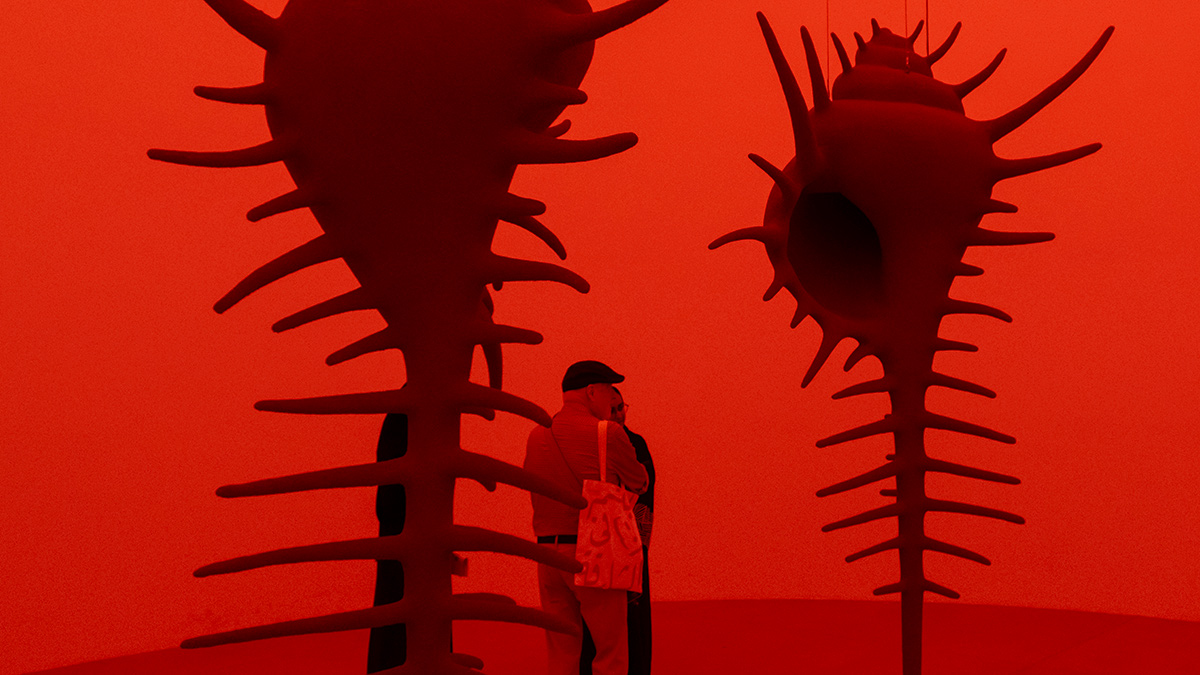Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Francisca Fanggidaej jadi buronan politik pemerintah Orde Baru sejak G30S pecah di Jakarta.
Dia eksil selama 20 tahun di Cina sebelum mendapat suaka di Belanda.
Dia mengalami dua kali operasi militer pada 1948 dan 1965.
DIA tengah berada di kamar hotelnya di Santiago, Cile, pada 2 Oktober 1965 saat mendengar kabar tentang pecahnya Gerakan 30 September di Jakarta. Saat itu Francisca Casparina Fanggidaej meninggalkan rumahnya di Tebet, Jakarta; Supriyo, suaminya yang wartawan senior Antara; dan tujuh anaknya untuk menghadiri Kongres Organisasi Jurnalis Internasional.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo