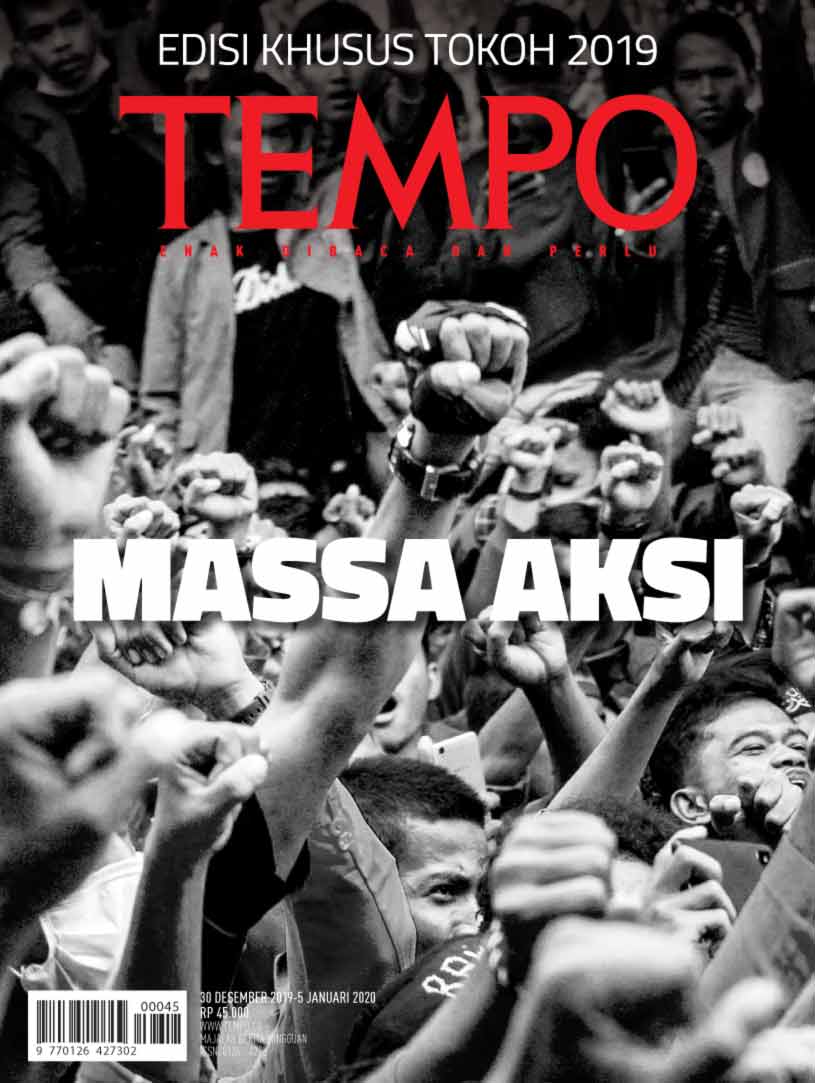Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Gambia, didukung Organisasi Kerja Sama Islam, mendakwa Myanmar melakukan genosida terhadap Rohingya di Mahkamah Keadilan Internasional (IJC)
Suu Kyi menilai pengungsian Rohingya sebagai ekses operasi militer menghadapi milisi bersenjata ARSA.
Hingga kini militer Myanmar terus membakar rumah-rumah Rohingya di Rakhine.
AUNG San Suu Kyi, di luar dugaan, datang ke Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda, untuk menghadapi gugatan Gambia, yang menuduh Myanmar melakukan genosida. Konselor Negara Myanmar dan penerima Hadiah Nobel Perdamaian 1991 ini dikritik dunia internasional karena berdiam diri atas dugaan pembersihan etnis di negaranya yang menyebabkan lebih dari 740 ribu warga Rohingya lari dan sebagian besar mengungsi ke Bangladesh.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kejutan Suu Kyi berikutnya adalah apa yang disampaikannya di depan Mahkamah pada Rabu, 11 Desember lalu. Dia membantah adanya genosida dan menyebut terusirnya ratusan ribu warga Rohingya seusai peristiwa serangan 25 Agustus 2017 itu sebagai ekses operasi militer menghadapi milisi bersenjata yang meminta otonomi atau merdeka: Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pembelaan Suu Kyi terhadap pemerintah militer Myanmar ini memicu kritik luas. "Kami orang Rohingya merasa frustrasi karena Aung San Suu Kyi masih menolak mengakui kebenaran. Kami memiliki semua bukti bahwa pemerintah Myanmar melakukan genosida," kata Zafar Ahmad bin Abdul Ghani, Presiden Organisasi Hak Asasi Manusia Etnis Rohingya Myanmar di Malaysia, kepada Tempo, Rabu, 18 Desember lalu.
Dalam gugatannya, Gambia juga mengajukan permintaan langkah provisi segera kepada Mahkamah. Di antaranya memerintahkan Myanmar segera mengambil semua langkah untuk mencegah genosida terus berlangsung. Menurut Human Rights Watch, berdasarkan pengalaman gugatan Bosnia terhadap Herzegovina pada 20 Maret 1993, Mahkamah mengabulkan permintaan itu sekitar tiga minggu kemudian.
Ketua tim pencari fakta kasus Myanmar bentukan Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Marzuki Darusman, menyatakan jadwal keluarnya putusan kasus Gambia versus Myanmar ini memang belum bisa dipastikan. "Memang tak ada batasan waktu. Tapi ada desakan dunia untuk membuat putusan cepat karena ini kasus genosida," ucap mantan Jaksa Agung Republik Indonesia itu, Senin, 23 Desember lalu.
Dalam gugatannya ke Mahkamah, Gambia mengidentifikasi dua unsur penganiayaan Myanmar terhadap kaum Rohingya sebagai "indikasi niat genosida". Pertama, penolakan sistematis terhadap hak hukum untuk warga Rohingya, terutama pembatasan pada pernikahan, kelahiran, dan kebebasan bergerak. Kedua, kampanye kebencian yang meluas yang ditujukan untuk menjelekkan dan merendahkan kaum Rohingya.
Ihwal tindakan genosida, Gambia menunjuk "operasi pembersihan" oleh militer pada Oktober 2016 dan Agustus 2017. Ini mencakup eksekusi massal pria, wanita, dan anak-anak serta pembakaran sistematis desa-desa, juga pemerkosaan dan kekerasan seksual lain dalam skala besar terhadap kelompok etnis Rohingya. Gambia juga menyoroti genosida yang terus berlangsung, terutama penghancuran lebih dari 30 desa sepanjang November 2018-Mei 2019. Kini masih ada 600 ribu warga Rohingya di Myanmar yang hidup di bawah ancaman genosida lebih lanjut.
Suu Kyi menyebut informasi yang disodorkan Gambia "tidak lengkap dan menyesatkan". Ia menyatakan konflik bersenjata antara ARSA dan militer Myanmar sebagai pemicu tragedi itu. "Tragisnya, konflik bersenjata ini menyebabkan eksodus beberapa ratus ribu muslim dari tiga kota paling utara Rakhine ke Bangladesh," ujarnya.
Ada dua konflik bersenjata setelah serangan ARSA. Serangan pertama terjadi pada 9 Oktober 2016 terhadap tiga pos polisi di Maungdaw dan Rathedaung. Dalam serangan itu, sembilan polisi tewas, lebih dari seratus warga sipil hilang, dan 68 senjata serta 10 ribu amunisi lebih dicuri. Serangan kedua ARSA terjadi pada 25 Agustus 2017 terhadap lebih dari 30 pos polisi dan desa serta sebuah pangkalan militer di Rakhine utara.
Suu Kyi juga mengklarifikasi penggunaan istilah "operasi pembersihan" yang dipakai Gambia. Pada awal 1950-an, kata dia, istilah ini digunakan selama operasi militer melawan Partai Komunis Burma. Sejak itu, militer menggunakan ungkapan ini dalam operasi kontra-pemberontakan dan antiterorisme. Tidak dapat dimungkiri, Suu Kyi mengungkapkan, ada penggunaan kekuatan tidak proporsional oleh militer dan kegagalan mencegah warga sipil menjarah atau menghancurkan properti setelah pertempuran.
Myanmar, Suu Kyi menambahkan, sekarang berusaha memastikan semua komunitas menikmati hak dasar yang sama. Anak yang lahir di Rakhine, terlepas dari latar belakang agamanya, mendapat akta kelahiran. Pengaturan telah dibuat untuk memungkinkan lebih banyak pemuda muslim masuk universitas.
Marzuki Darusman menyebut pembelaan Suu Kyi itu sebagai upaya mengecilkan masalah Rohingya. Dia menilai jumlah personel dan senjata yang digunakan militer Myanmar serta kekerasan setelah serangan ARSA itu jauh dari kesan pemulihan ketertiban. "Dengan skala kekerasan di Negara Bagian Rakhine, itu tidak lagi bisa disebut sebagai ekses. Itu sudah memenuhi kualifikasi dalam definisi hukum internasional sebagai genosida," tuturnya.
Dalam laporan 435 halaman yang dirilis pada 17 September lalu, tim pencari fakta merinci kekerasan terhadap warga Rohingya. Laporan itu menyebutkan respons militer atas peristiwa 25 Agustus 2017 bersifat brutal, terencana, berpola, dan sangat tidak proporsional. Meski niatnya menghilangkan "ancaman teroris" ARSA, operasi tersebut menargetkan dan meneror semua penduduk Rohingya. Aparat dan pejabat berwenang menyebutnya sebagai "operasi pembersihan". Selama operasi itu, menurut tim, lebih dari 40 persen desa di Rakhine hancur.
Tim juga menyebutkan sifat, skala, dan organisasi dalam operasi ini menunjukkan tingkat perencanaan dan desain pemimpin militer Myanmar. Ini konsisten dengan visi Panglima Tertinggi Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang pada puncak operasi pembersihan itu mengatakan, "Masalah Bengali (sebutan untuk warga Rohingya) adalah masalah lama yang menjadi pekerjaan yang belum selesai."
Seusai operasi pembersihan itu, menurut tim pencari fakta, tercatat setidaknya 9.208 warga Rohingya meninggal dan 1.358 lainnya diduga hilang atau terbunuh. Sebanyak 2.157 orang berada di tahanan dan 1.834 perempuan menjadi korban pemerkosaan. Ini belum mencakup soal kematian tanpa kekerasan, misalnya mereka yang tenggelam di sungai saat berusaha lari dari kejaran tentara.
Zafar Ahmad dengan tegas membantah klaim Suu Kyi bahwa operasi militer itu bertujuan menindak ARSA. "Bagi Rohingya, ini kebohongan besar karena pemerintah Myanmar tidak bisa membunuh dan memperkosa warga sipil Rohingya dan menghancurkan rumah-rumah kami hanya karena melawan serangan ARSA. Tindakan pemerintah Myanmar jelas ingin memusnahkan Rohingya," ujarnya.
Zafar lahir di Kota Buthidaung. Ia melarikan diri dari Myanmar pada 1988 setelah dicari pemerintah militer karena keterlibatannya dalam demonstrasi pada tahun itu. Ia sempat ditangkap intelijen Burma di Bangladesh dan disiksa selama tiga hari. Saat berhasil kabur, ia lari ke India sebelum masuk ke Malaysia pada 1992 dan terdaftar sebagai pengungsi di Komisariat Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR).
Warga Rohingya yang tersisa di Rakhine, kata Zafar, kini seperti dikurung di penjara terbuka. Setiap aspek kehidupan mereka dikendalikan. "Militer terus membakar rumah-rumah Rohingya di Buthidaung dan Maungdaw. Warga Rohingya yang meminta perawatan di klinik pemerintah di Sittwe malah disuruh pergi ke ICJ," ujarnya.
Reed Brody, penasihat Human Rights Watch, mengatakan, dalam pembelaannya, Suu Kyi bahkan tak mengucapkan kata "Rohingya", kecuali saat menyebut Tentara Penyelamat Rohingya Arakan. Bagi Brody, itu adalah "ilustrasi bagaimana Myanmar menyangkal keberadaan Rohingya". "Penolakan identitas kami adalah bagian dari kebijakan genosida," ucap Zafar.
ABDUL MANAN (LA TIMES, WASHINGTON POST, HUMAN RIGHTS WATCH)
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo