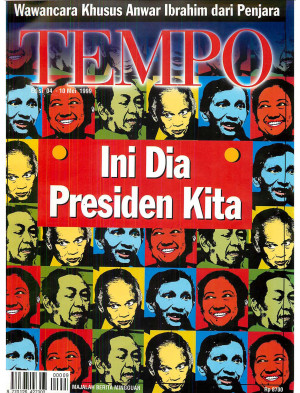HOROR itu berjudul "Pembantaian Dukun Teluh dari Ciamis Selatan". Alur ceritanya absurd sekaligus memualkan. Cara Oneng Suharya menjemput ajal adalah contohnya.
Malam itu, pertengahan April lalu, rumah Oneng di Desa Sukaresik, Kecamatan Pangandaran, disatroni dua orang yang mengenakan ikat kepala khas Sunda. Tanpa ba-bi-bu lagi, ia langsung diringkus. Lehernya dijerat tali plastik dan ia digeret ke luar. Massa sudah menunggu dengan golok dan bambu runcing terhunus. Oneng sempat melolong memanggil nama anak keduanya, "Aa, Aaa ...!" Setelah itu horor. Dalam sekejap mata, tubuh renta itu sudah bersimbah darah. Empat hari kemudian, mayatnya ditemukan mengambang di Sungai Ciwayang dalam kondisi mengenaskan. Badannya hancur lebur, muka bonyok, seluruh kuku dicabuti, dan leher tertebas.
Padahal, Oneng bukan juru tenung. Lelaki yang taat beribadah ini adalah pemilik bengkel sepeda dan warung kecil. Ia memang tak disukai warga karena dikenal pendengki. Suatu ketika seorang tetangganya membuka bengkel serupa. Oneng yang tak suka disaingi itu lalu mengumbar serapah. Sang tetangga lalu disumpahi takkan pernah nyenyak tidur dan nikmat makan, jika tak segera menutup usahanya. Setelah itu, kebetulan, beberapa warga yang pernah berselisih paham dengannya meninggal dunia. Langsung saja, ia pun dituding punya kemampuan ngaheureuyan (menjaili) dengan ilmu hitam.
Nasib seorang maling motor kambuhan, Thoyib, tak kalah tragis. Di tengah malam buta, delapan truk dan puluhan motor menderu ke rumah mertuanya—tempat ia tidur malam nahas itu—di Desa Legokjawa, Kecamatan Cigugur. Thoyib dibantai tak kurang biadab. Di depan mata istrinya, Sentot, salah seorang algojo, menebasnya berkali-kali. Craas...crass! Edan, tubuhnya berikut alat vitalnya lalu dijagal menjadi tiga bagian dan dipanggang memakai bambu runcing. Tiga sate raksasa itu lalu diarak sebelum dibuang. Padahal, tak satu warga pun menyatakan bahwa residivis yang sudah puluhan kali keluar masuk bui itu adalah dukun teluh. Cuma, kabarnya ia punya ilmu kebal tubuh. "Dia baru mati kalau ditebas lehernya," kata Sugito, karibnya sejak kecil. Yang jelas, malam sebelum terbunuh, Thoyib dipergoki mencoleng motor kepunyaan salah seorang warga Desa Sukaresik yang menyerbunya malam itu.
Absurd memang. Tapi, apa mau dikata, warga keburu gelap mata. Dendam, syak wasangka, dan keresahan karena teluh, bercampur aduk menjadi semacam pelampiasan kesumat. Apalagi, pola pembunuhan yang sadistis diyakini sebagai pakem untuk melenyapkan kesaktian sang dukun. Tujuan lain adalah untuk mencegah agar arwahnya tak bergentayangan menghantui para pembunuhnya.
Dalam urusan itu, kisah brutal pembantaian Ki Djuni (72 tahun) pada 1972 silam hampir-hampir jadi legenda yang selalu dirujuk. Nama penjaga makam keramat Mbah Eyang Kertasedana di Pasir Kored itu kondang sebagai penguasa ilmu hitam yang kerap menebar maut. Beberapa warga menuturkan, seperti halnya para dukun teluh, Ki Djuni menguasai aji rawa rontek. Suatu ilmu perekat nyawa yang hanya bisa sirna jika kepala sang empunya ilmu ditebas dari tubuhnya. Itu pun setelah digorok delapan jawara, saking saktinya sang dukun masih bisa merapal mantra.
Tak jelas betul, apakah dari sana "kebiasaan" menjagal dukun teluh bermula. Soalnya, pada tahun pembantaian Ki Djuni itu, beberapa dukun lain cuma ditangkap, lalu digelandang ke balai desa. Di muka pamong desa, mereka lalu diminta menanggalkan ilmu hitamnya. Itu saja.
Toh tiga dasawarsa kemudian, Tarmuji (60 tahun)—penerus sekaligus murid utama Ki Djuni—tetap "mewarisi" nasib tragis sang guru. Mayatnya ditemukan tergantung di sebuah jembatan dekat makam yang setia ditungguinya, dengan tubuh yang nyaris tak lagi berbentuk. Selama ini warga memang enggan bersinggungan dengannya. "Takut salah bicara, tahu-tahu perut sudah membusung," kata seorang pencari kayu di sana. Ia juga tak pernah dilihat warga saat salat Jumat. Padahal, selain dikenal tukang santet, Tarmuji juga mampu menyembuhkan penyakit.
Penentuan kriteria dukun teluh pun tak jelas benar. Satu-satunya ukuran adalah kabar dari mulut ke mulut yang lalu dipercayai. Kepala Desa Sukaresik, Maman Rukman, mengakui pihaknya melakukan identifikasi semata-mata berdasarkan informasi dari masyarakat. Contohnya, Kasna, korban perdana gelombang pembantaian. Seorang warga, Rochmadi, yakin betul bahwa Kasna adalah tukang tenung. Awal mulanya, suatu hari ia terlibat pertengkaran kecil dengan Kasna. Tiba di rumah, tak lama kemudian ia dan istrinya mendadak sakit perut. Lalu, perut mereka menggelembung, seperti sedang hamil. Mereka pun berobat ke Jawa Tengah. Seorang dukun di sana lalu mengeluarkan pisau dan duri salak dari perut mereka yang konon dikirim Kasna. Masyarakat di pakidulan—sebutan orang Sunda untuk pesisir selatan Ja-Bar—memang percaya betul keberadaan teluh.
Karena itulah, buat para pelaku, membantai dukun teluh bukan persoalan besar. Atau, apalagi, dosa yang harus disesali. Ditemui TEMPO di sel Kepolisian Sektor Pangandaran yang pengap dan dingin, dengan lugunya mereka seperti tak menanggung beban apa pun saat mengisahkan penjagalan. Pengakuan mereka jelas tak perlu dikorek polisi melalui bogem mentah.
Tengoklah wajah lugu Elang bin Sadro saat berkisah. Warga Dusun Ciokong, Desa Sukaresik, Kecamatan Pangandaran, ini enteng-enteng saja saat mengaku telah membantai 10 orang. Tak ada sebersit pun kerisauan ketika diberi tahu dialah yang memicu gelombang pembantaian. November silam, buruh penyadap nira kelapa ini adalah orang pertama yang membantai dukun teluh. Nama jebolan kelas dua SD ini langsung kondang di seluruh pesisir laut kidul. Semua mata memandangnya kagum: sang penjagal. Ia bahkan dianggap pahlawan. Sejak itu, kawanan berjumlah 18 orang yang dipimpinnya, kebanjiran "pesanan".
Tapi, semua ketenaran itu tak mengubah kehidupan melaratnya. Ditemui di gubuk mereka yang reot, Jumsih, istrinya, menuturkan selama ini suaminya tak pernah memberikan uang lebih dari Rp 10 ribu. Hal itu tak berubah setelah Elang jadi jawara. Dalam bahasa Sunda campuran, perempuan desa ini mengatakan suaminya tak pernah membawa pulang uang sepeser pun setelah beroperasi. Bahkan, setelah tiang keluarga itu dibui, kemelaratan makin menghimpitnya. Untuk makan sehari-hari, ia harus berutang beras dari kiri kanan. "Abdi ge dugi ka ngiring bedugan deui (saya sampai harus memburuh di sawah lagi)," keluhnya.
Hal yang sama juga ditemui pada Sentot (32 tahun) dan Hendrik (29 tahun) yang mengaku masing-masing telah menjagal empat dan dua orang. Sentot sendiri tak lebih dari seorang buruh tani dan penarik ojek yang keranjingan judi koprok dan ronggeng. Sementara itu, Hendrik adalah seorang sopir truk.
Sasaran mereka cuma "musuh warga". Elang, misalnya, tak begitu saja menyanggupi setiap order pembantaian. Ia selalu meminta kepastian dulu apa orang yang akan mereka habisi itu benar dukun teluh. Caranya, warga desa diminta meneken surat persetujuan. Jika dinilai cukup, baru mereka bergerak. Kepala Desa Sukaresik, Maman Rukman, mengungkapkan bahwa Elang bahkan pernah menghardik Sentot, "Kalau sampai membunuh orang yang tak bersalah, kamu akan saya bunuh."
Ini memang seperti kejahatan kolektif yang didukung nyaris seluruh warga desa. Setiap pembantaian, ratusan bahkan ribuan penduduk terlibat. Menurut Sentot, sekali operasi jumlah massa tak pernah kurang dari 400 orang, sebagian ikut merajam, sebagian lagi cuma menonton. Yang tak setuju, boro-boro berani membela. Mereka pun diancam ikut dibantai. Elang, Sentot, dan Hendrik mengaku tak pernah menyembelih sendiri korbannya. Tugas mereka cuma meringkus, menjerat leher korban dengan tali plastik, lalu menyeretnya ke luar. Selebihnya jadi urusan parang dan bambu runcing yang dihunus massa yang gelap mata.
Karena itulah pembantaian sulit dicegah. Aparat keamanan yang memang lagi ciut nyalinya, juga dibuat kewalahan. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Ciamis, Letkol Pol. Martono mengungkapkan rasa jeri aparat saat meringkus pelaku. Tiga hari setelah operasi digelar, ribuan warga dari empat desa berbondong-bondong mendatangi markas polres. "Mereka dianggap pahlawan," ujarnya.
Tambahan lagi, kurun waktu pembunuhan berbarengan dengan pencalonan kepala desa. Persoalannya, hampir seluruh calon kepala desa mengaku tak mau mempertaruhkan kansnya dengan melakukan tindakan yang tak populer: menghalangi pembantaian dukun teluh. "Saya tak bisa mencegahnya, itu akan mempengaruhi dukungan terhadap saya saat pemilihan," kata salah seorang calon. Maman Rukman yang baru saja terpilih sebagai Kepala Desa Sukaresik malah mengaku telah jauh-jauh hari mengetahui rencana pembunuhan terhadap Kasna dan Oneng. Ia bahkan sempat memperingatkan mereka untuk mengungsi ke luar desa. Masalahnya, mantan bintara pembina desa ini juga tak segera melaporkan ke atasannya. "Daripada hancur, saya kan sedang mencalonkan diri untuk menjadi kuwu (kepala desa)," katanya dengan enteng.
Tapi, berbagai alasan itu tentu saja tak boleh berarti bahwa penjagalan serupa boleh terulang lagi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini