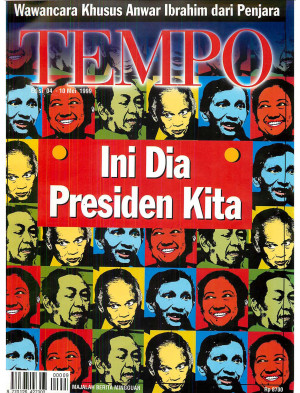SEJARAH negeri ini seakan sedang bergerak mundur ke Abad Kegelapan, ke suatu masa berabad-abad lalu di Eropa, ketika ribuan orang yang dicap sebagai juru tenung ditangkap ramai-ramai, lalu dipanggang hidup-hidup.
Tragedi Banyuwangi belum lagi pupus dari ingatan. Oktober tahun lalu, di daerah tapal kuda Jawa Timur itu, lebih dari 100 orang yang dituding sebagai "dukun santet" dibantai secara sadistis. Horor yang mendirikan bulu roma itu kini bergeser ke arah barat. Di Ciamis Selatan, Jawa Barat, sejak November silam, setidaknya 37 nyawa telah melayang. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bahkan menunjuk angka 57. Sebagian besar diyakini—lebih tepatnya diduga—sebagai "dukun teluh" (santet versi Sunda).
Banyuwangi episode kedua ini tak cuma lebih menyeramkan, tapi juga memualkan. Hampir semua mayat ditemukan dalam keadaan terjagal. Nyaris tak ada yang utuh. Berpuluh-puluh onggokan daging busuk manusia mengambang di Sasak Ciwayang di wilayah itu—sungai angker yang konon bisa menyirnakan segala ilmu hitam. Bumi Ciamis bersimbah darah. Bau anyir menyengat di mana-mana.
Di Banyuwangi, pembantaian dilakukan orang bertopeng, mirip ninja, yang berkelebat di kegelapan malam. Jurus Ciamis lebih gila: terang-terangan, tanpa kedok, melibatkan ribuan massa, bahkan di tengah siang bolong. Dan sang algojo, ya ampun, malah dianggap sebagai pahlawan. "Setelah dukun teluh tidak ada, warga desa mah ngaraos tiis (merasa tenteram)," ujar Sapdi Sumawijaya, 71 tahun, mantan kepala desa Sukaresik.
Ketercekaman warga memang telah berlangsung turun-temurun. Kawasan di tepi Laut Selatan ini—konon dikuasai Nyai Loro Kidul—sudah lama kondang sebagai pusat dunia hitam. Berbagai ilmu santet—teluh, pelet, werejit—berkembang subur di sepanjang datarannya. Riwayatnya mungkin setua sejarah Ciamis sendiri. Menurut Prof. Dr. Edi S. Ekadjati, pakar sejarah Sunda dari Universitas Padjadjaran, Bandung, naskah kuno daun lontar berjudul Sanghyang Siksa KandangKaresian telah mencatatnya sejak tahun 1518 Masehi.
Kisah penyembelihan dukun teluh juga bukan cerita anyar. Pada 1970-an, seorang juru kunci makam keramat, Aki Djuni, 72 tahun, dan enam orang lainnya di Desa Pagergunung mati dirajam massa. Mayatnya juga dibuang ke Sungai Ciwayang. Di seputar tahun itu, kawasan tetangganya—Cianjur, Sukabumi, dan Tasikmalaya—digegerkan berbagai kasus serupa. Sampai pernah, pada 1975, Bupati Ciamis menginstruksikan agar semua tukang tenung di sana melapor. Jika tidak, mereka diancam ditangkap dan dibuang ke luar Jawa.
Daerah ini memang seperti menyimpan malapetaka. Tujuh belas tahun lalu, banjir besar menyapu habis rumah dan sawah milik 25 ribu warganya. Pada akhir 1991, wabah kolera menjangkiti 55 desa. Hanya dalam waktu sebulan, 2.400 orang tertular dan 17 di antaranya meregang nyawa. Kawasan seluas 25.910 hektare itu—terdiri atas 11 kecamatan—juga merupakan daerah termiskin di bumi Parahyangan, yang terkenal elok dan subur. Sebagian besar penduduk menyambung hidup sebagai buruh penyadap nira kelapa. Perangai mereka juga keras. Prinsip "hutang uyah (garam) bayar uyah" dipegang teguh. Garam adalah kiasan untuk nyawa.
Pembantaian dukun teluh bisa jadi merupakan malapetaka paling kelam dalam sejarah Ciamis. Saat ini, warga dicekam ketakutan dan menaruh curiga pada setiap wajah asing. Istri korban menemui setiap tamu dengan parang terhunus. Jendela dan pintu rumah tertutup rapat. Pangandaran, salah satu "ladang pembantaian", berubah menjadi "kota hantu". Sebelumnya, kawasan wisata ini tiap tahun biasa dikunjungi ribuan pelancong. Taman Laut Pananjung, yang ada di sana, terkenal dengan hamparan pasir putih dan air lautnya yang bening kebiruan. Menurut legenda, di sini Nyai Loro Kidul jarang murka.
Bencana berawal pada November silam. Di bulan Rajab itu (menurut kalender Sunda dan Islam), Elang bin Sadro menghabisi Kasna, yang dikenal sebagai tukang tenung, di Dusun Ciokong. Kasna, demikian keyakinan Elang, telah "mengirimkan sesuatu" ke perut ayah dan adiknya. Perut mereka membusung, lalu mereka muntah darah, dan kemudian menggelepar mati. Berbagai "orang pintar" yang ditanyai Elang menunjuk ke arah Kasna. Dicekam kesumat, ia lalu mengumpulkan ratusan warga untuk mengusir Kasna. Sang dukun ternyata sakti mandraguna. Menurut Elang, meski Kasna dikepruk habis-habisan, lukanya langsung pulih begitu ia mengusap wajah. Baru pada penyergapan kedua, nyawa Kasna lepas juga dari raganya. Dengan leher terjerat dan kepala remuk, mayatnya dikarungi lalu dibenamkan ke dasar Sungai Ciwayang. Sejak saat itulah nama Elang membubung tinggi sebagai jawara.
Bak virus, pembantaian lalu mewabah. Ribuan warga seperti kesetanan memburu setiap nama yang diyakini punya keahlian mengirim sihir. Sampai pekan lalu, polisi telah meringkus 43 tersangka pelaku. Selain Elang, dua gembong lain telah diprodeokan: Sentot alias Aji Jaka Purnama dan Hendrik.
Teori konspirasi, yang tengah merasuki publik, kontan bertebaran. "Skenario politik dari Jakarta" diyakini berada di balik gelombang pembantaian ini. Kontras, misalnya, melihat adanya suatu persekongkolan jahat. Beberapa temuan disodorkannya: wilayah sebar yang mencapai radius puluhan kilometer, pengorganisasian yang terhitung rapi, dukungan dana yang berlimpah, dan penentuan target korban yang selalu didahului dengan investigasi. Bahkan, dicurigai adanya keterlibatan beberapa aparat kepolisian dan Angkatan Darat. Sayang, Munir, Ketua Badan Pekerja Kontras, enggan menyebut nama.
Benarkah? Teori konspirasi selalu membentur satu kenyataan: sulit dibuktikan secara empiris. Yang jelas-jelas terjadi adalah sebuah fenomena tempat mitos, ketakutan, dan dendam menggumpal di satu titik. Perut membusung, muntah darah, lalu menggelepar mati dipercaya sebagai ciri korban teluh. Dan hutang uyah bayar uyah, nyawa dibayar nyawa: sang dukun harus mati. Sesederhana dan seabsurd itu. Penelusuran TEMPO di lapangan menunjukkannya.
Soal "pembunuh bayaran", misalnya, agak berlebihan. Memang, para penjagal mengaku menerima sejumlah uang—berkisar antara Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Cuma satu kasus yang melibatkan dana Rp 500 ribu. Yang lain bahkan "gratis". Menurut pengakuan puluhan saksi, dana itu berasal dari hasil saweran (iuran) warga yang memang gerah dengan keberadaan sang dukun. Seusai operasi, uang itu ludes dibelikan rokok dan makan-minum ratusan warga. Ibu Sentot menuturkan, "Kalau benar anak saya pembunuh bayaran, paling tidak ada saenclek (setetes) buat anaknya. Ini tak pernah," katanya dalam bahasa Sunda kasar.
Istilah "daftar korban" dan "investigasi" juga terlalu hiperbolis. Daftar memang ada. Dan itu diakui oleh para pelaku. Hanya, itu adalah kumpulan tanda tangan persetujuan warga sebelum beroperasi. Sentot juga disebut sering berhalo-halo di telepon genggam pemberian sang dalang. Tapi rasanya sulit membayangkan penyadap nira dan tukang ojek yang cuma jebolan SD dan tak fasih berbahasa Indonesia itu bisa menggunakannya. "Nyekel ge can pernah (menyentuhnya pun belum pernah)," katanya.
Malah, mungkin karena terlalu sering dicecar pertanyaan berbau konspirasi, ia sampai perlu mengarang cerita bohong. Suatu hari, katanya, ke rumahnya pernah datang dua orang berperawakan tinggi besar yang mengendarai sedan mengkilat. Mereka menyodorkan sekoper uang Rp 100 juta dan dua pistol untuk "menggoyang" Pangandaran. Tapi, begitu ditanyai identitasnya, mereka langsung ngacir. Cerita ini agaknya cuma isapan jempol. Penyisiran TEMPO ke gubuk Sentot di Desa Pagergunung membuktikan bahwa jalan curam berbatu cadas itu mustahil dilewati kendaraan sejenis sedan.
Bau politik, kalaupun ada, cuma sebatas konflik lokal di seputar tuntutan untuk "mereformasi" (demikian mereka menyebutnya) seorang kepala desa Wonoharjo yang dinilai korup. Selebihnya adalah pelampiasan dendam belaka, misalnya yang terlihat dalam kasus pembantaian Thoyib, seorang maling motor kambuhan di Kecamatan Cigugur.
Lalu, kenapa masyarakat menjadi begitu beringas? Selama ini, menurut pakar kriminologi Universitas Indonesia, Mulyana W. Kusumah, keluarga korban cuma bisa menyimpan dendam. Teluh—tentu saja—tak pernah bisa dibuktikan secara empiris. Dan karena itu, jerat hukum tak sanggup menjangkaunya. Lalu, muncullah sebuah peluang dari situasi politik yang relatif lebih bebas. Hasilnya adalah letupan energi radikal yang mengartikan reformasi sebagai keleluasaan main hakim sendiri. Apalagi, selama ini, masyarakat bersikap permisif, bahkan menghalalkan tindakan brutal itu.
Kelambanan aparat keamanan—memang lagi loyo—melengkapi berbagai faktor penyebab di atas. Kontras malah menuding bahwa hamba hukum bukan cuma tak tanggap, tapi juga cenderung membiarkannya. Faktanya memang tak terbantahkan: penjagalan pertama telah terjadi lima bulan lalu, sementara penanganan serius baru dilakukan beberapa bulan kemudian, setelah jatuh puluhan korban. Korban niscaya akan semakin banyak jika tragedi ini tak juga dijadikan pelajaran.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini