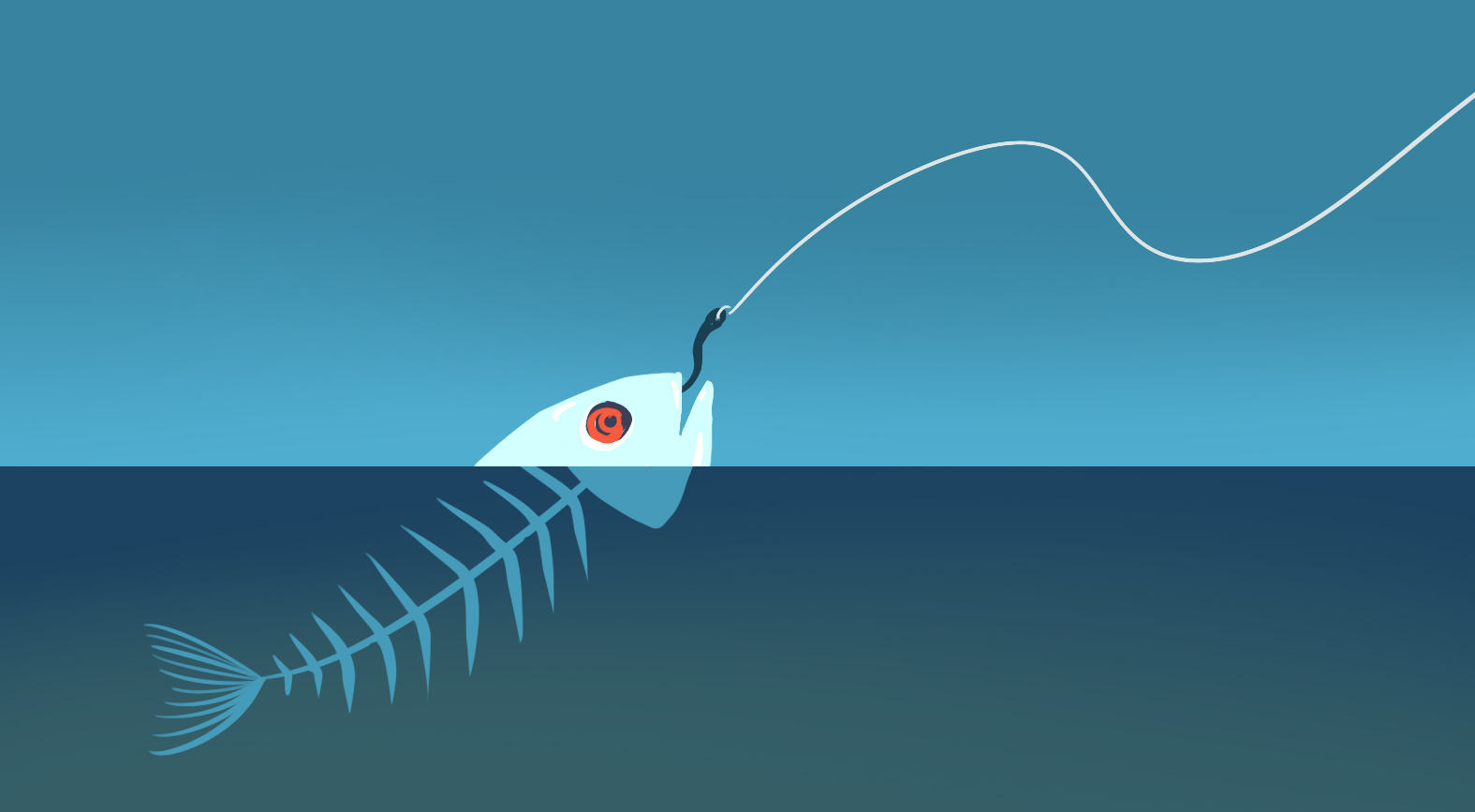Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Kebijakan perikanan di Indonesia cenderung berpihak pada investasi asing.
Perlu pembagian ruang bagi nelayan kecil dalam kebijakan wilayah pengelolaan perikanan.
Perlu pengembangan perikanan laut yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Muhamad Karim
Peneliti Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim dan Dosen Universitas Trilogi Jakarta
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo