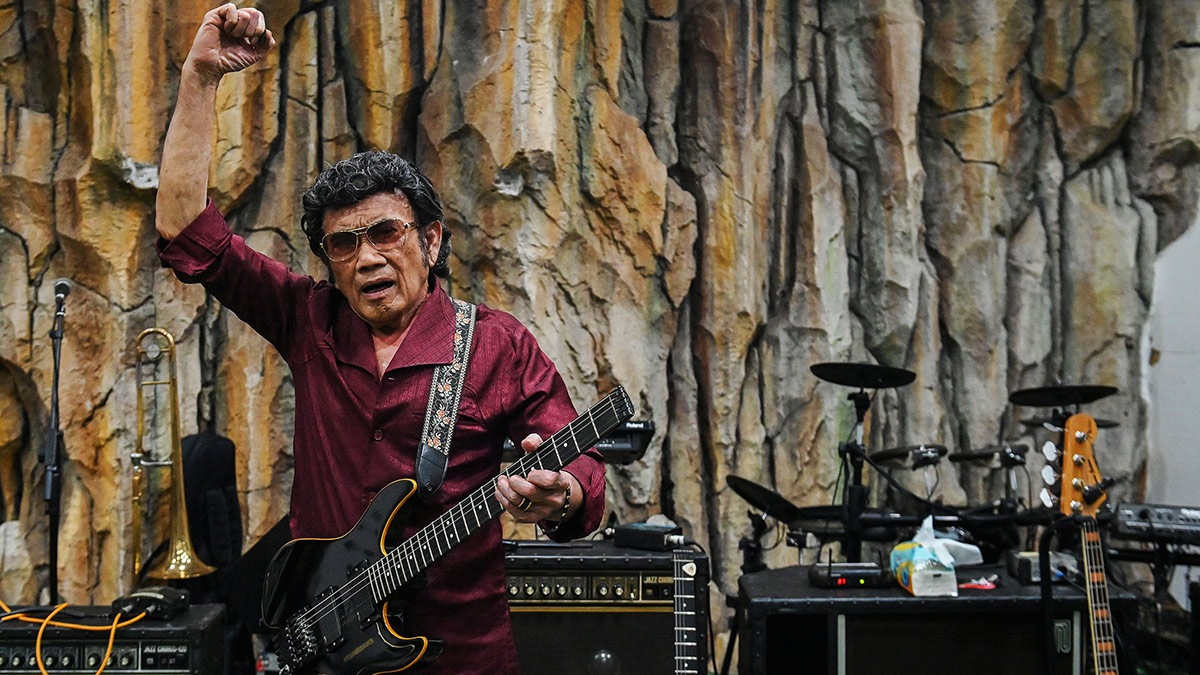Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

22 Maret 1978. Hari itu pukul 14.50 saya menerima telepon dari ajudan Presiden Soeharto. Dia mengatakan Pak Harto meminta saya datang ke rumah di Jalan Cendana pukul 19.00. Waktu itu saya sedang bekerja di kantor Center for Strategic and International Studies. Teman-teman sekantor gembira ketika saya beri tahukan kabar itu. Mereka mengatakan saya pasti dicalonkan menjadi menteri. Saya buru-buru pulang ke rumah dan menceritakan kabar itu kepada istri saya, Sri Soelastri. Dia hanya berpesan: jangan masuk ke departemen dengan kepala kosong.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo