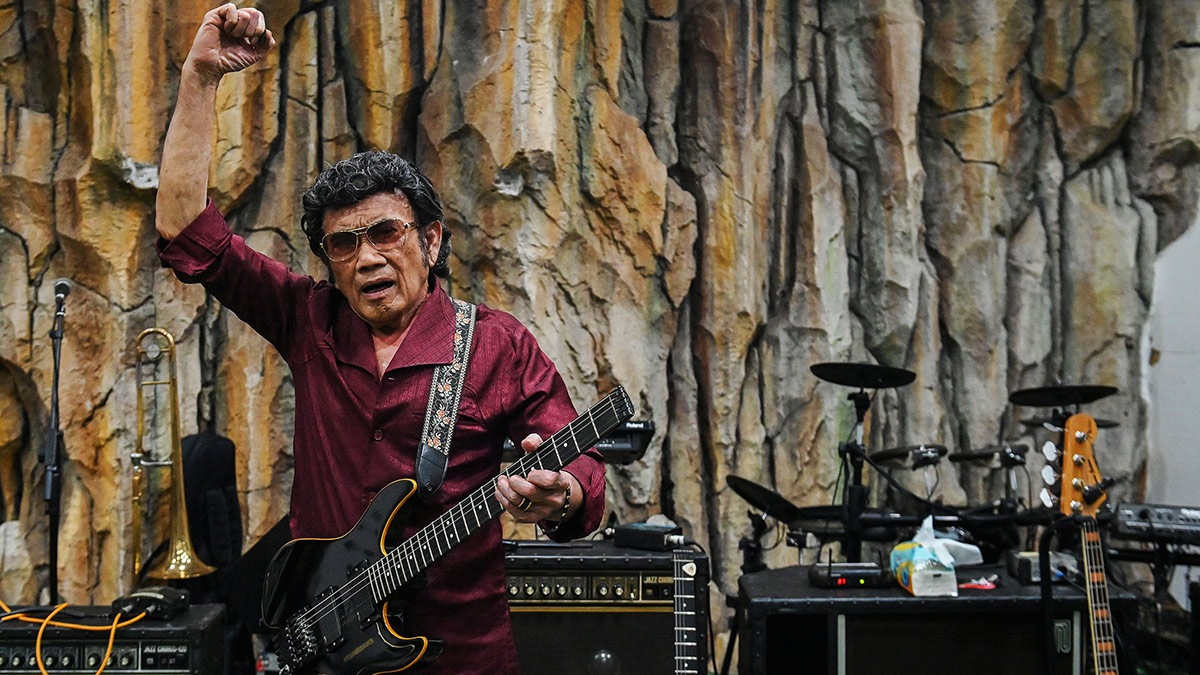Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

FOTO hitam-putih Toeti Heraty ketika berusia 38 tahun terpajang di kartu undangan perayaan ulang tahunnya yang ke-83. Matanya mengerling dengan senyum yang menampakkan barisan giginya. Rambut dikonde rapi dan di bagian depannya diberi sedikit sasak. Giwang berukuran sedang menempel di kedua telinganya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo