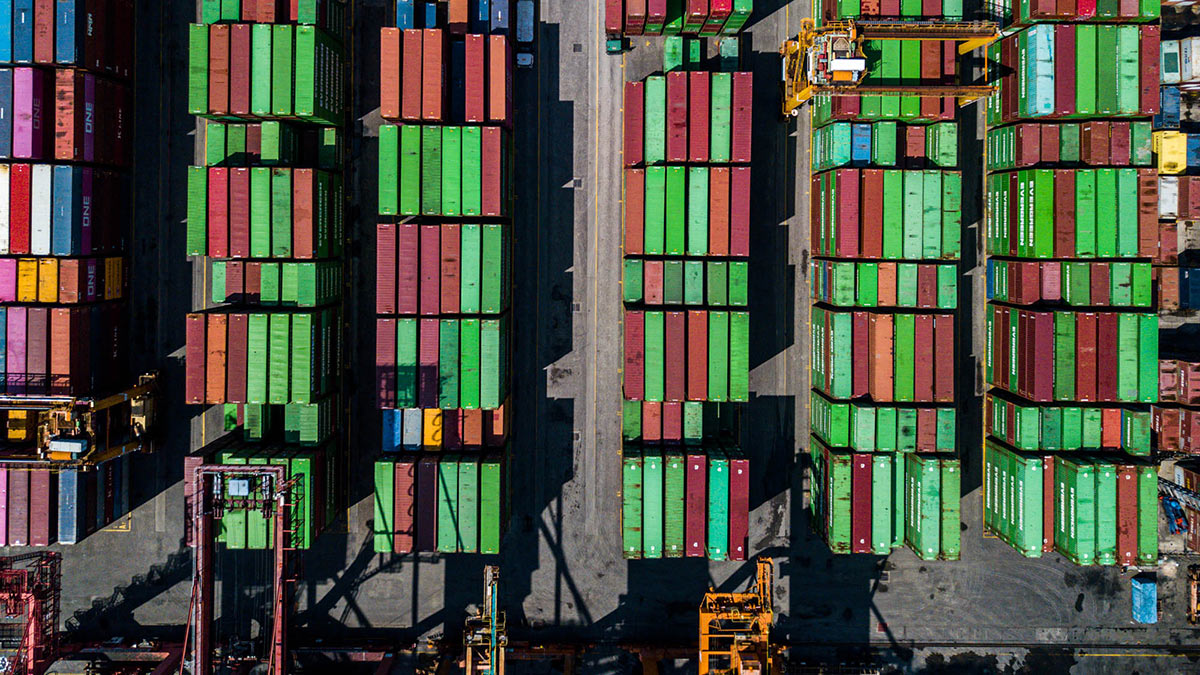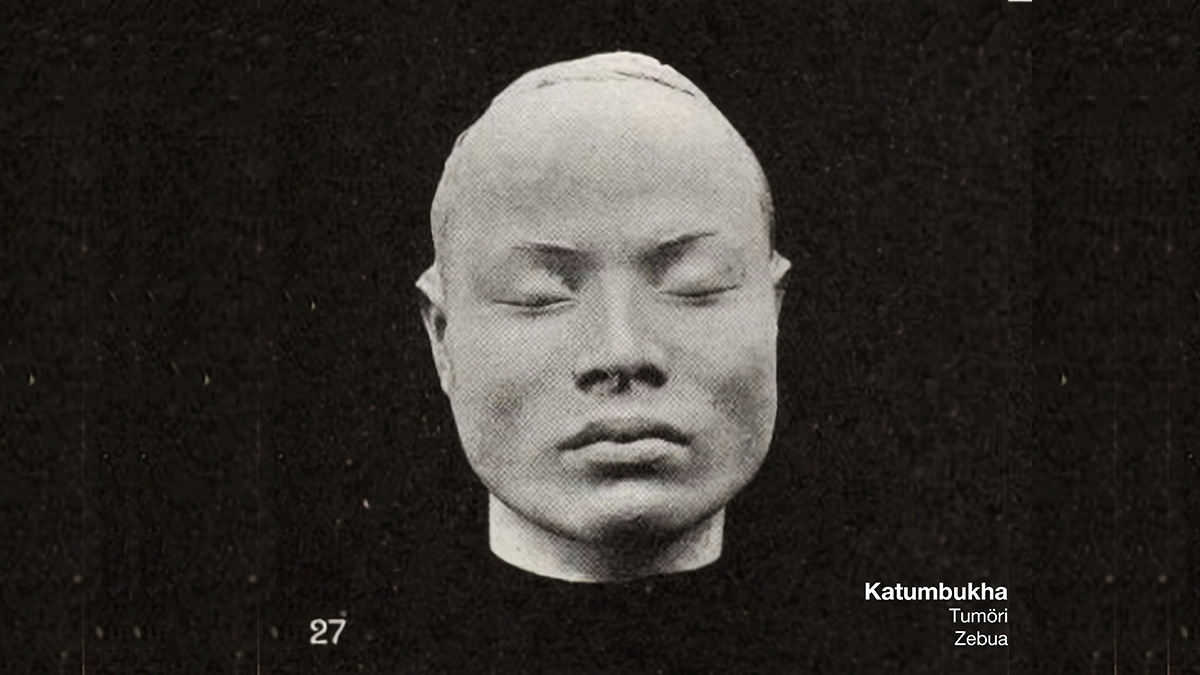Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ringkasan Berita
Lahan basah di sejumlah wilayah Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, mengering lima bulan terakhir. Peternak kerbau rawa terkena imbasnya.
Dampak kemarau berkepanjangan merembet ke sumber pendapatan para ibu. Wujud nyata kelompok perempuan paling rentan terhadap efek perubahan iklim.
El Nino hanya memperparah keadaan. Nyatanya, rawa gambut di Ogan Komering Ilir telah lama terdegradasi oleh industri kehutanan, perkebunan sawit, dan proyek-proyek infrastruktur.
SERATUSAN kerbau rawa (Bubalus bubalis) bergegas keluar dari sebelas kandang di Pulau Tapus, Desa Bangsal, Kecamatan Pampangan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mereka berbaris menuju Lebak Kuro, lalu menyebar dalam sejumlah kelompok. Sabtu pagi itu, 11 November lalu, rerumputan yang baru tumbuh di rawa gambut tersebut sudah menunggu untuk disantap.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Laporan khusus ini merupakan hasil kolaborasi Koran Tempo dan Tempo Institute.
Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan turut mendukung pendanaan peliputan pada sektor pertanian.