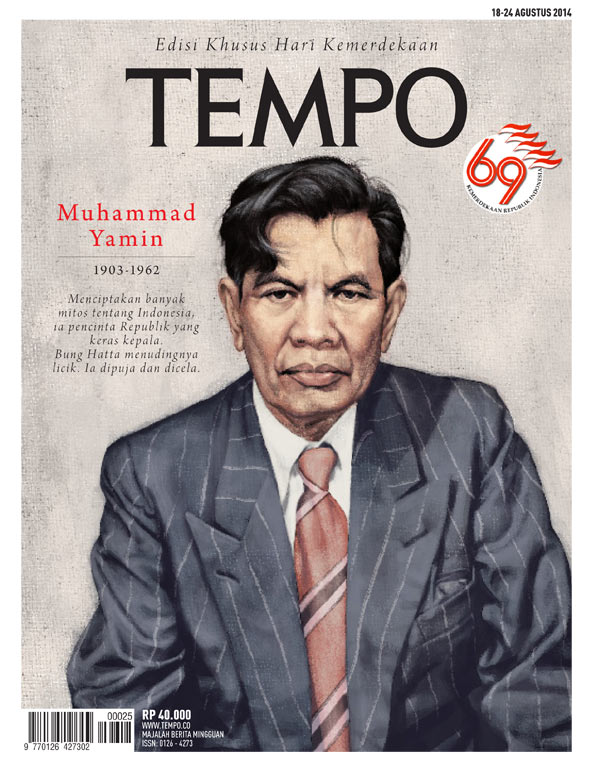Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DI keluarganya, Oesman Bagindo Chatib dikenal sosok yang kerap kawin-cerai. Dan Siti Saudah, ibunda Yamin, adalah satu dari istri-istri yang diceraikannya. Kenyataan ini mendorong Yamin keluar dari rumah dan hidup bersama kakaknya lain ibu, Muhammad Yaman. Bersama Yaman, dimulailah petualangan Yamin cilik berpindah-pindah tempat tinggal, mengikuti sang kakak, seorang guru yang kerap berpindah tugas.
Tak pelak, ini berpengaruh pada pendidikan Yamin kecil. Pendidikan sekolah rakyat dijalaninya berpindah-pindah dari Talawi, Sawahlunto; Solok; sampai Padang Panjang.
"Dengan hidup berpindah-pindah, justru ia banyak melihat dunia. Terekspos hal-hal yang berbeda. Di Padang Panjang, misalnya, sangat kuat agamanya, sementara Sawahlunto kuat dengan pengaruh Belanda," ujar Fadjar Ibnu Thufail, salah satu keturunan dari Muhammad Yaman.
Yamin memulai pendidikan awalnya di Sekolah Dasar Bumiputera Angka II pada usia 7 tahun. Sekolah ini menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Ya, "Mula-mula bahasa pengantar yang digunakan di sekolah rakyat itu bahasa Melayu. Tapi, setelah kongres pemuda, keluar keputusan Belanda untuk menggantinya ke bahasa Minang," kata sejarawan Taufik Abdullah.
Selain Sekolah Dasar Bumiputera Angka II, terdapat Sekolah Dasar Bumiputera Angka I, yang pada 1911 diubah menjadi Hollandsch-Inlandsche School (HIS). Tiga tahun kemudian, bahasa Belanda mulai menjadi bahasa pengantar sekolah ini, diajarkan sejak kelas I, dengan guru kepala orang Belanda. Sementara itu, dalam buku tulisan Momon Abdul Rahman dan Darmansyah disebutkan bahwa Belanda mendirikan HIS ini pada 1914.
"HIS ini biasanya untuk mereka yang berpenghasilan relatif tinggi dan pegawai kelas menengah. Adanya di kota kabupaten," ujar Taufik.
Mengingat kedudukan ayahnya sebagai pegawai mantri kopi—kedudukan yang terpandang kala itu—Yamin relatif tak sulit untuk berpindah ke HIS. Setelah mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar Bumiputera Angka II selama sekitar lima tahun (dalam sumber lain disebutkan ketika Yamin duduk di kelas IV), ia melompat ke HIS tempat Muhammad Yaman mengajar dan mulai mempelajari bahasa Belanda.
Untuk pendidikan tingkat dasar kala itu, mata pelajaran yang diberikan kepada murid mencakup menulis, membaca, juga aritmatika. Taufik Abdullah memperkirakan kecintaan Yamin pada sastra mulai tumbuh sejak bangku sekolah, karena anak sekolah kala itu juga mempelajari pantun dan kaba atau cerita rakyat berbahasa Minang, seperti Cindua Mato atau Malin Kundang.
"Mereka juga banyak belajar lagu-lagu Minang, yang umumnya berisi tentang kecintaan atas kampung halaman. Dan sajak-sajak Yamin yang pertama kan juga tentang rasa cinta pada Sumatera," Taufik menambahkan. Sejak kecil, masyarakat Minang telah dididik tentang kecintaan terhadap Sumatera.
Selama empat tahun bersekolah di HIS, Yamin lulus pada 1918 pada usia 15 tahun. Artinya, ia lulus dari pendidikan setingkat sekolah dasar setelah bersekolah 8-9 tahun. Saat itu, waktu yang umumnya dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan dasar adalah 7 tahun. Perubahan sistem pendidikan Belanda kala Yamin bersekolah dan tempat tinggalnya yang berpindah-pindah diperkirakan ikut mempengaruhi hal ini.
Meskipun Yamin sedikit terlambat menyelesaikan pendidikan dasarnya, Restu Gunawan dalam bukunya, Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan, memperkirakan justru Yamin memiliki keuntungan karena menjadi lebih mampu berbahasa Melayu sekaligus Belanda. Ini berbeda dengan sekolah HIS di tanah Jawa yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, sementara bahasa Melayu hanya diletakkan sebagai mata pelajaran ekstra sekali seminggu dengan tambahan uang pembayaran sebesar setalen.
Lulus dari HIS, Yamin sempat belajar selama setahun di Hofden School atau sekolah guru (sekolah raja) di Bukittinggi. Namun ia akhirnya memutuskan hijrah ke Bogor begitu menerima tawaran beasiswa sekolah pertanian (Landbouw en Veeartsenijschool) di sana.
Taufik Abdullah menyebutkan semangat intelektual tengah menggelegak pada masa Yamin muda hidup di Sumatera Barat. Dengan makin banyaknya kaum terpelajar di Sumatera Barat, sejak akhir abad ke-19 mulai muncul kesadaran mengenai pentingnya pendidikan untuk memasuki dunia yang lebih maju.
Ia mencontohkan, pada 1901-1904 muncul majalah bulanan Insulinde atas inisiatif seorang guru sekolah raja sekaligus ahli bahasa Melayu, Van Ophuysen. Majalah ini berada di bawah pimpinan Dja Endar Muda, editor media massa Nauli dan Pertja Barat yang terbit di Padang. Para pengisinya adalah kaum terpelajar dari tanah Sumatera dan Jawa, karena itu Taufik memperkirakan Insulinde juga dibawa ke tanah Jawa.
"Yang ditekankan benar oleh majalah ini adalah cita-cita kemajuan dan yang kedua adalah memasuki dunia maju," ujarnya. Ada pula Abdul Rivai, pelajar Minang yang bersekolah kedokteran Belanda, yang menganjurkan hal serupa lewat majalah Bintang Hindia, tempat ia menjadi editornya.
Selain itu, kondisi sosial-politik di Sumatera Barat memiliki pengaruh besar. Lewat Plakat Panjang—pernyataan sikap yang dibuat Belanda d Perang Padri—Sumatera Barat tidak diharuskan membayar pajak kepada Belanda. Sebagai gantinya, masyarakat Sumatera Barat diminta memperluas perkebunan kopi dan menjual hasil bumi tersebut kepada Belanda.
Sempat menerima keuntungan dari kopi yang mencapai puncaknya pada 1864, pendapatan Belanda dari komoditas ini terus menurun hingga awal abad ke-20. Ini terjadi karena rakyat Sumatera Barat mulai mengurangi menanam kopi—menggantinya dengan tanaman lain yang tidak masuk monopoli Belanda.
Pada 1905, Belanda mulai berupaya agar pajak dapat diterapkan di daerah ini dengan menggelar musyawarah bersama tokoh masyarakat, tapi tak kunjung mendapatkan titik temu. Pemerintah pusat kemudian memutuskan secara sepihak bahwa pajak harus diberlakukan—mulai awal 1908.
"Bagi masyarakat Minang, semua harus dirundingkan. Karena itu, orang Minang berontak karena tidak diajak berunding," ucap Taufik. Pemberontakan berdarah yang tidak seimbang terjadi selama sekitar lima bulan di berbagai daerah di Sumatera Barat—berakhir dengan kemenangan di pihak kompeni.
"Pemberontakan tahun 1908, bagi Sumatera Barat, sangat penting. Setelah kalah, orang Minang baru sadar betul bahwa untuk mengalahkan orang Belanda tidak menggunakan otot, tapi otak," ujar Taufik.
Selepas pergolakan tersebut, semangat masyarakat mengejar pendidikan semakin berkobar. Anak yang bersekolah semakin banyak. "Pada 1912, persentase orang Minang yang bersekolah paling tinggi. Pesaingnya hanya Minahasa. Angka perempuan yang bersekolah di Sumatera Barat juga tinggi," katanya.
Karena itu, Taufik menambahkan, bukan hal yang mengherankan bila Sumatera Barat menjadi salah satu pusat pergerakan politik nasional pada 1920-an, selain Jakarta.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo