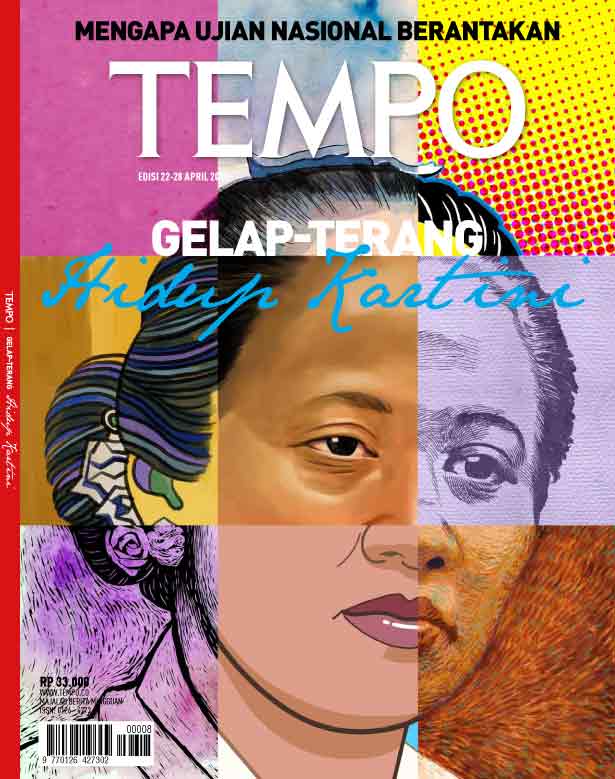Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Dia Minta Dipanggil Kartini Saja
Kartini memberontak terhadap feodalisme, poligami, dan adat-istiadat yang mengungkung perempuan. Dia yakin pemberian pendidikan yang lebih merata merupakan kunci kemajuan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo