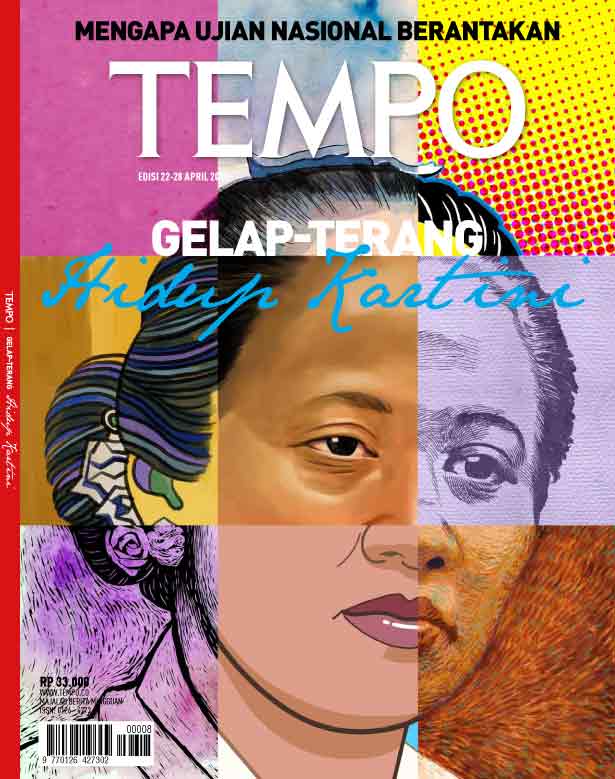Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

KARTINI kecil sakit keras. Badannya menggigil. Dokter yang didatangkan ayahnya, Bupati Jepara Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, tak sanggup mengobati anak tujuh tahun itu. Lalu datanglah seorang Cina yang sedang dihukum pemerintah Hindia Belanda bertamu ke rumahnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo