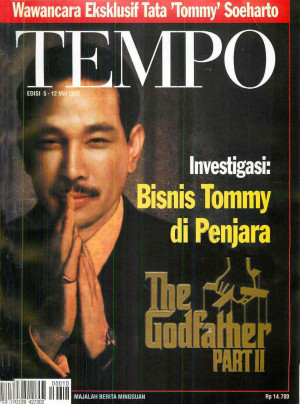Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

”... dan begitu saja anak muda itu mendekat dengan cepat dan memeluk Sri. Dan Sri begitu saja juga membalas pelukan itu dengan memeluk anak muda itu erat-erat. Mata Sri dipejamkan kuat-kuat dan beberapa titik air mata terasa menetes di pinggiran pipi Sri. Di tengah pelukan yang kuat itu, adalah dua makhluk manusia, se-orang perempuan dengan usia hampir lima puluh tahun, se-orang laki-laki hampir tiga puluh tahun, terlibat dalam percakapan sendiri di dalam bahasa mereka sendiri....”
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo