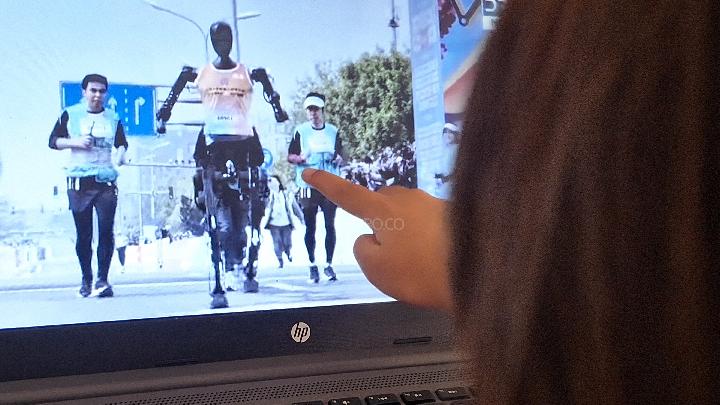Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Berbagai kelompok etnis minoritas Myanmar ikut bergabung dalam aksi unjuk rasa menentang kudeta militer.
Warga Rohingya mengecam kudeta militer, tapi tak mendukung Aung Sang Suu Kyi.
Rencana repatriasi warga Rohingya setelah kudeta militer terjadi kian suram.
ISU krisis yang menimpa kelompok minoritas muslim Rohingya turut diusung para demonstran Myanmar dalam aksi memprotes kudeta militer sejak awal Februari lalu. Di jalanan, mereka membawa poster berisi ungkapan solidaritas bagi warga Rohingya. Lewat media sosial, banyak kaum muda Myanmar menyampaikan permintaan maaf karena tidak bersuara atas operasi militer di Negara Bagian Rakhine pada 2016-2017. Kebrutalan tentara Myanmar atau Tatmadaw kala itu memaksa lebih dari 750 ribu warga Rohingya mengungsi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo