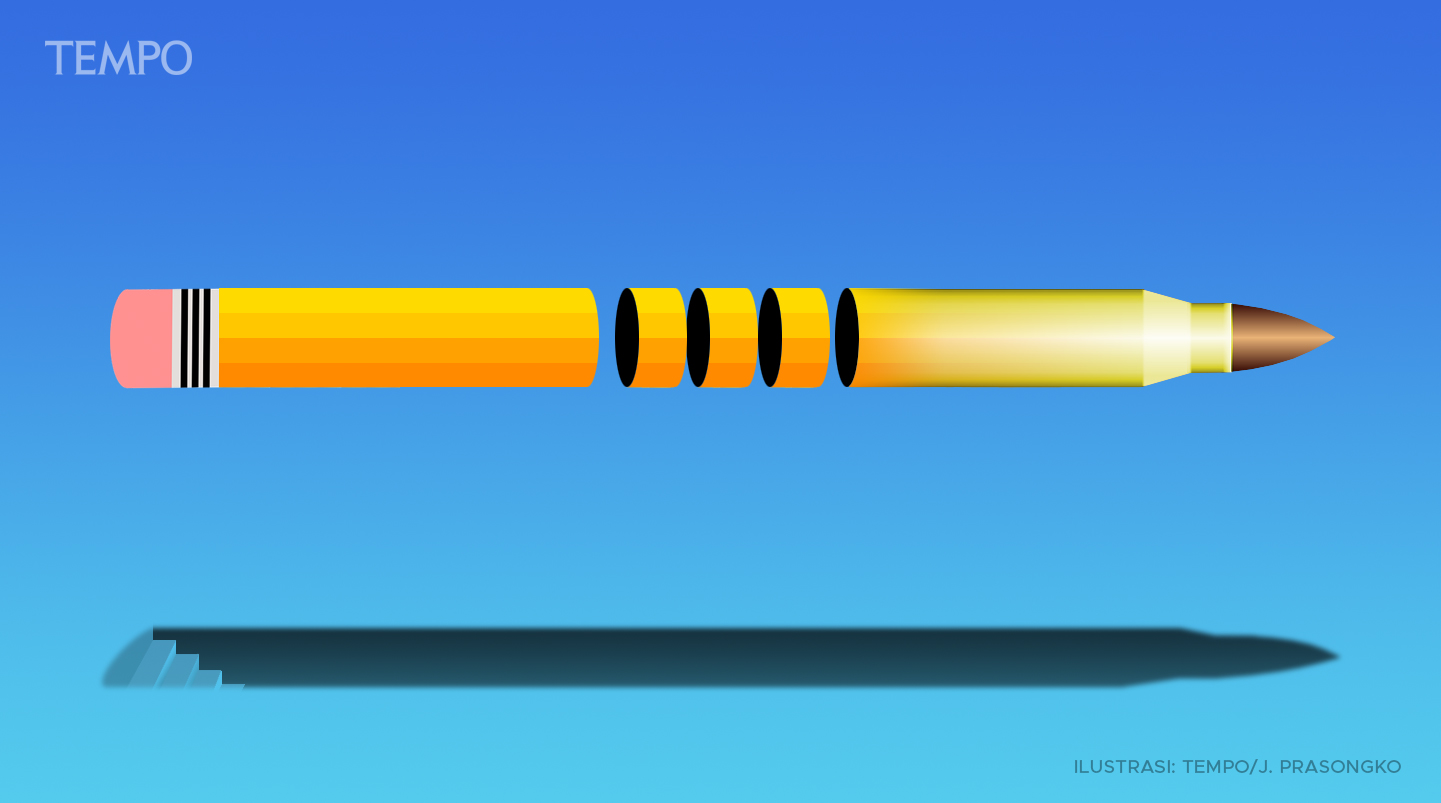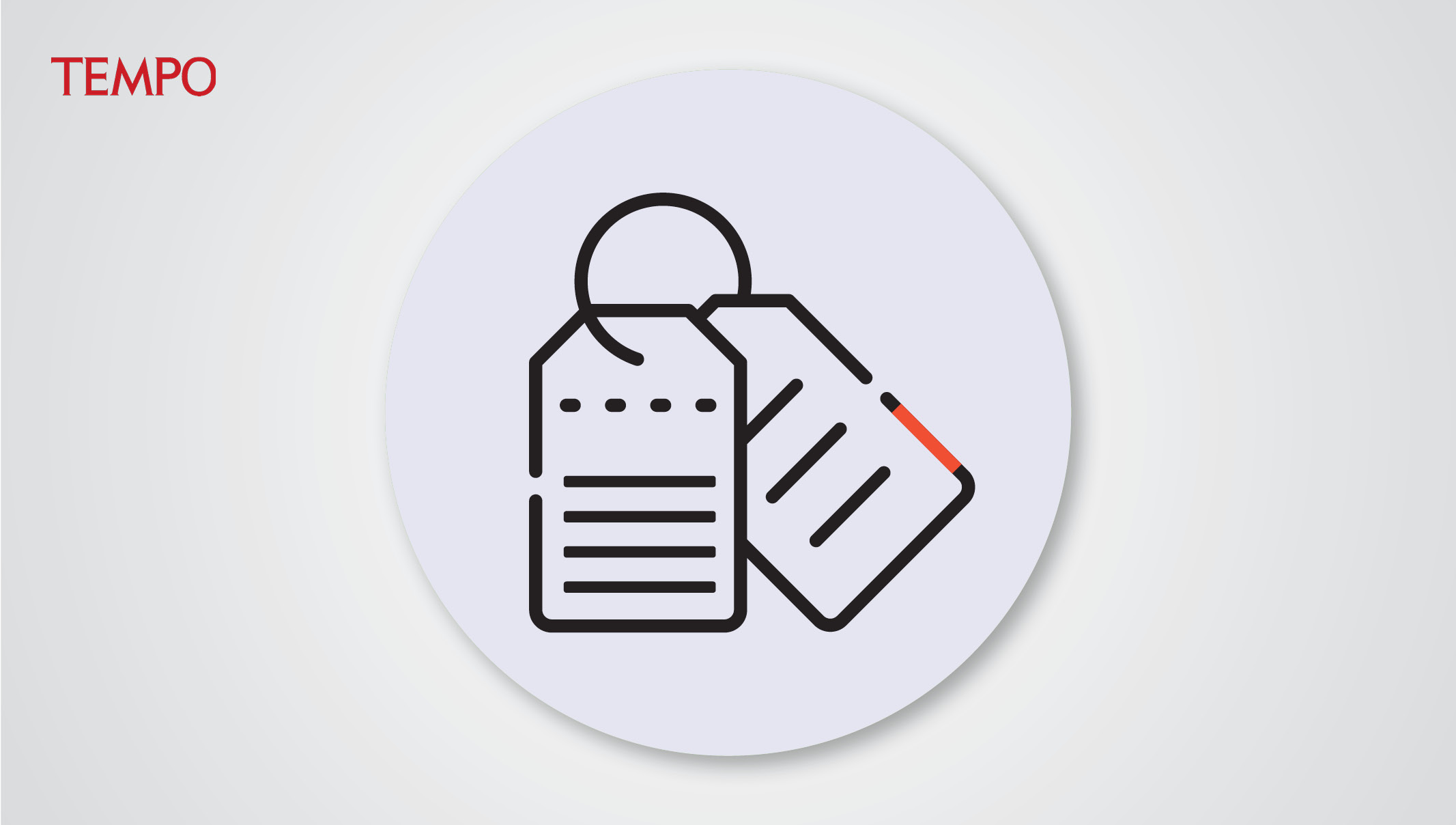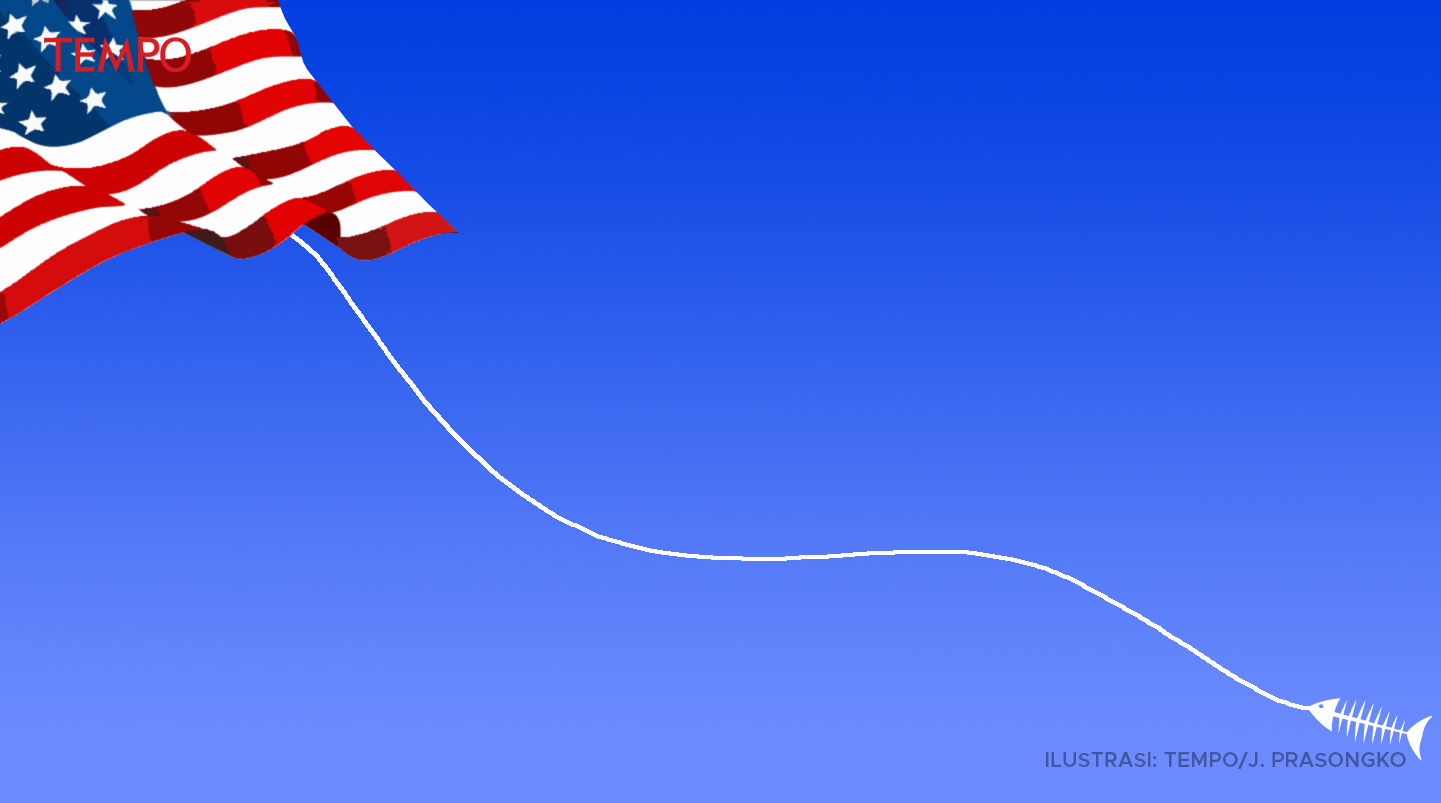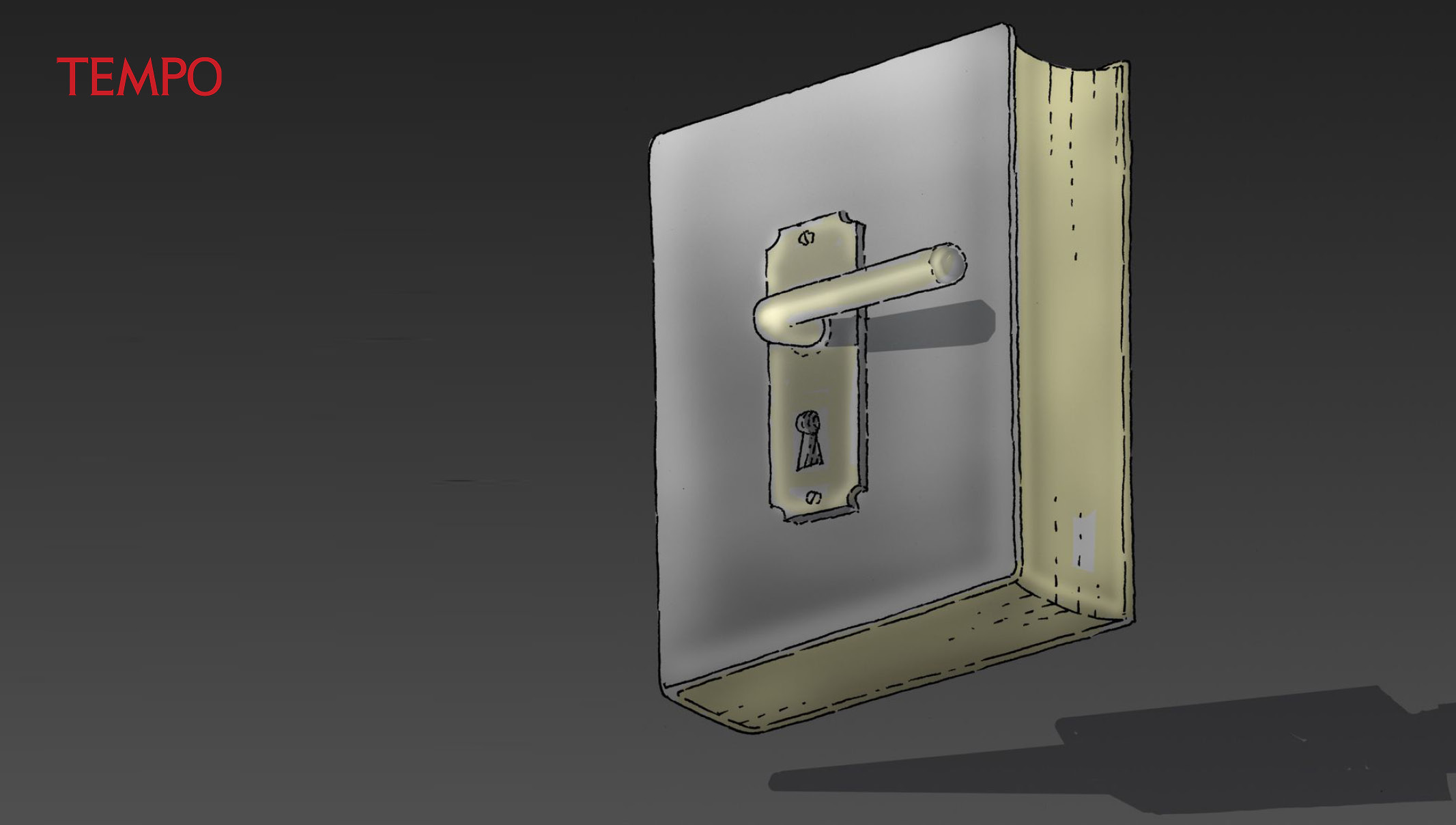Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Muhamad Karim
Dosen di Universitas Trilogi serta peneliti di Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo