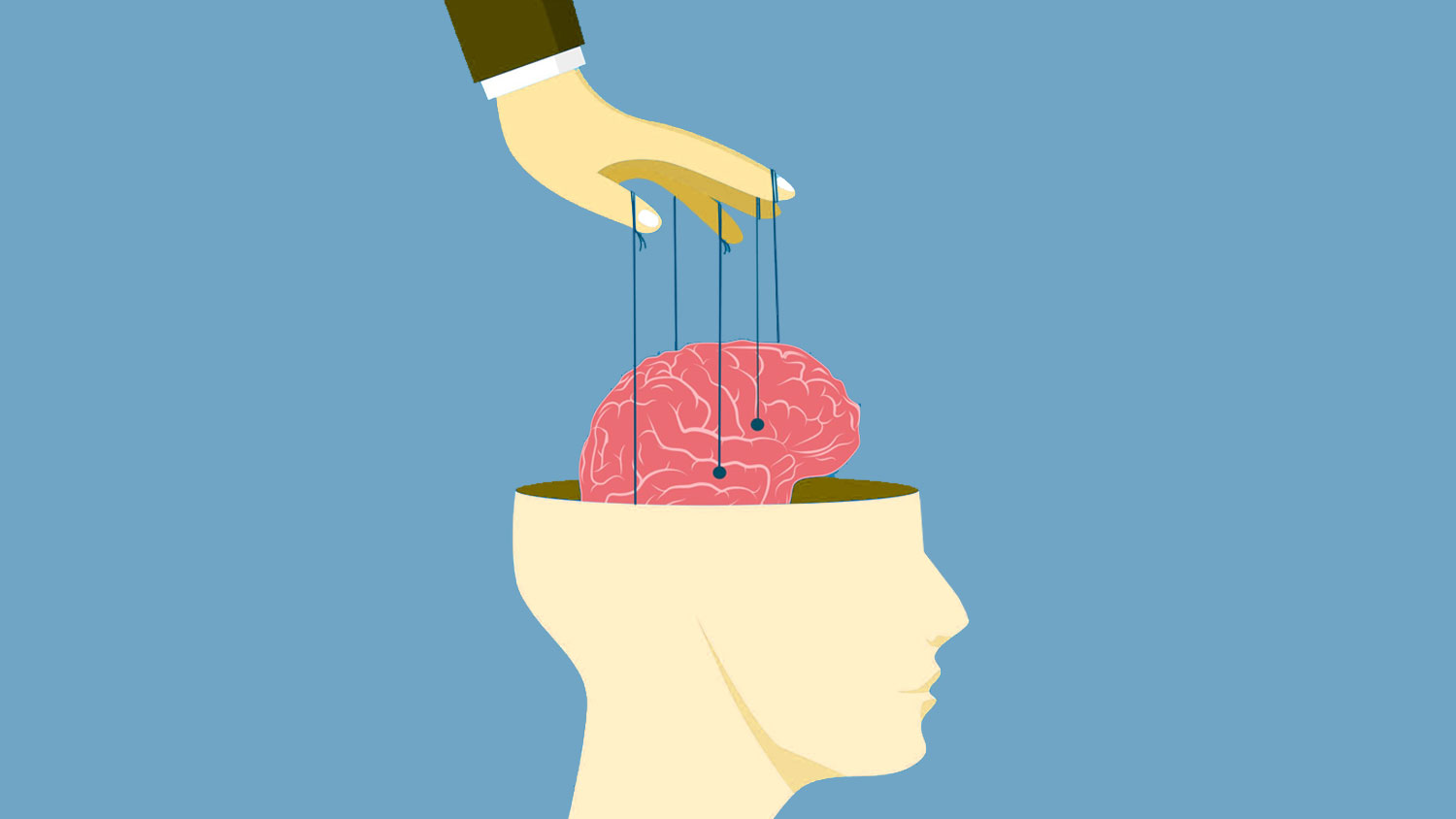Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Kemala Atmojo
Pengamat Hukum
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Kata "fiksi”, "fiktif”, dan "pasca-kebenaran” (post-truth) belakangan ini makin populer. Apalagi setelah budayawan Ridwan Saidi melontarkan komentar bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah fiktif. Gemparlah dunia media sosial dengan segala komentar, caci maki, dan kritiknya. Apakah ucapan Ridwan Saidi salah atau benar tentu masih perlu diuji secara keilmuan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Namun fiksi, fiktif, atau pasca-kebenaran yang dianggap sebagai kibul, bohong, bukan kenyataan, tidak ilmiah, dan seterusnya itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak zaman purba. Bahkan, menurut Yuval Noah Harari, Homo sapiens adalah spesies pasca-kebenaran yang kekuatannya bergantung pada penciptaan dan kepercayaan fiksi. Manusia lebih banyak berpikir dalam cerita ketimbang dalam fakta atau angka.
Harari mengutip satu contoh fiksi yang memakan korban besar, yakni ketika ditemukan tubuh seorang bocah bernama Hugh di sebuah sumur di Kota Lincoln, Inggris, pada 1255. Rumor menyebar bahwa Hugh dibunuh secara ritual oleh orang Yahudi setempat. Akibatnya, 19 orang Yahudi diadili dan dieksekusi dengan tuduhan pembunuhan. Setelah itu, pada 1290, semua penduduk Yahudi diusir dari Inggris. Penulis ternama dan juga sastrawan terkenal Inggris ikut menambah cerita sehingga banyak orang Yahudi digantung dan diusir.
Padahal tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana Hugh itu sampai meninggal di dalam sumur. Dia dimakamkan di Katedral Lincoln dan dihormati bagaikan orang suci. Para peziarah datang dari berbagai penjuru. Lalu apa yang terjadi kemudian? Sekian ratus tahun kemudian, tepatnya pada 1955, Katedral Lincoln menyangkal fitnah berdarah itu. Bahkan sebuah plakat dipasang di dekat makam Hugh dengan kalimat "Kisah-kisah yang dikarang-karang tentang ‘pembunuhan ritual’ anak-anak Kristen oleh komunitas Yahudi umum terjadi di seluruh Eropa selama Abad Pertengahan bahkan jauh di kemudian hari. Fiksi-fiksi ini membuat banyak orang Yahudi yang tidak berdosa menjadi korban. Lincoln memiliki legenda sendiri dan korban yang diduga dibunuh ini dimakamkan di Katedral pada 1255. Kisah-kisah semacam itu tidak boleh terulang demi reputasi kekristenan.”
Di Indonesia, dongeng atau kisah-kisah fiksi juga ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Beratus-ratus cerita legenda, mitos, kisah pewayangan, dan aneka fiksi lain dipercaya sebagai kenyataan yang pernah ada. Bahkan hingga kini banyak orang masih percaya bahwa Indonesia pernah dijajah Belanda selama 350 tahun.
Kibul-kibul baru juga terus disemburkan banyak orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalnya, Presiden Joko Widodo adalah anggota Partai Komunis Indonesia, Barack Obama tidak lahir di Amerika Serikat, dan Hillary Clinton adalah kepala jaringan perdagangan anak yang dipergunakan sebagai budak seks.
Namun tidak semua fiksi itu buruk. Banyak ide dan fiksi yang menyatukan, menyenangkan, dan menginspirasi. Hak asasi manusia, yang disebut melekat dalam diri manusia sejak lahir karena pemberian Tuhan, adalah ide yang menyenangkan. Tanaman punya hak hidup adalah pemikiran yang menginspirasi.
Namun belakangan ini muncul lebih banyak fiksi yang menghancurkan citra seseorang atau yang merusak demokrasi. Misalnya, menjelang dan selama proses pemilihan presiden 2019, media sosial dengan segala kibulnya mengarahkan orang untuk memilih pasangan calon tertentu dengan cara membuat cerita palsu. Dalam euforia kebebasan menggunakan media sosial, berlangsunglah praktik-praktik manipulasi fakta, angka, penyebaran kebencian, hoaks, dan fitnah. Percakapan politik warga di ruang virtual lebih banyak memancing emosi. Di media sosial, menjelang dan selama pemilihan, sulit ditemukan percakapan warga negara yang santun, obyektif, jujur, dan bermutu. Emosi lebih penting ketimbang akal sehat. Perasaan lebih utama ketimbang pikiran.
Hal itu menunjukkan bahwa Internet dengan media sosialnya tidak hanya mendemokratisasi kesempatan, tapi juga kepanikan dan kibul. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana bertukar informasi dan mendekatkan hubungan sosial, tapi juga sebagai alat manipulasi untuk merusak kehidupan politik dan demokrasi yang sehat.
Barangkali ini memang risiko hidup di era sekarang. Internet dengan "idea” globalisasinya-meminjam istilah Thomas L. Friedman-menjadikan paus makin besar dan ikan kecil makin kuat. Dunia meninggalkan Anda makin cepat dan cepat sekaligus mengejar Anda makin cepat dan cepat. Ia memungkinkan kita untuk menggapai dunia yang tak pernah terjadi sebelumnya dan juga memungkinkan dunia menggapai kita dengan cepat, yang juga tak pernah terjadi sebelumnya.
Intinya, kita harus selalu berani mempertanyakan kembali semua pelajaran, kepercayaan, informasi, atau cerita yang pernah dan sedang kita peroleh. Harus ada keberanian untuk menggugat, meski hal itu dikatakan sebagai sejarah. Siapa tahu, semua itu cuma kibul.