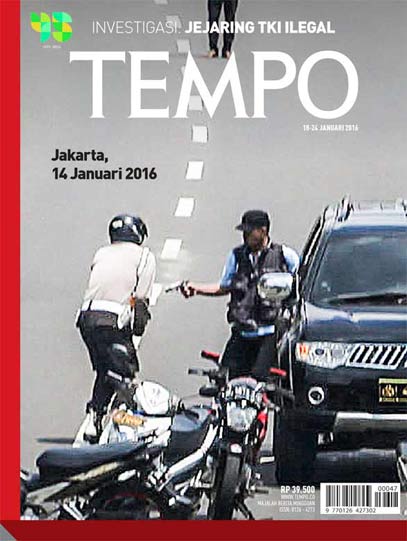Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebagai orang Italia, Claudio Ranieri tak hanya gemar pizza. Pria 64 tahun ini juga menjadikan makanan itu sebagai gambaran filosofi yang dianutnya dalam melatih tim sepak bola, termasuk Leicester City, yang kini terus panen pujian karena rentetan kejutan yang dibuatnya di Liga Inggris. "Apa yang kami lakukan tak beda dengan membuat pizza," katanya.
Senyum seperti biasa tersungging di bibirnya. Ia berbicara kepada wartawan di meja lonjong besar di restoran Peter Pizzeria di pusat Kota Leicester, Inggris, akhir Oktober tahun lalu. Di sekeliling meja itu, para pemain Leicester tampak bersenda gurau sambil asyik menikmati pizza yang baru mereka bikin sendiri. Semua personel tim berkumpul untuk sebuah momen spesial. Para pemain mendapat hadiah dari Ranieri berupa kesempatan makan pizza bersama, setelah bermain tanpa kebobolan untuk pertama kalinya, saat menang 1-0 atas Crystal Palace, dalam laga ke-10 di Liga Inggris pada musim ini.
Ranieri meneruskan bicaranya sambil menggerakkan tangannya, seperti tengah membuat adonan pizza di atas meja. "Bumbu terpenting yang harus dimiliki adalah semangat tim dan menikmati latihan," ujarnya. Tangannya lalu bergerak seperti menaburkan sesuatu ke atas meja. "Seperti pizza, keberuntungan adalah garam. Anda harus melakukan segalanya dengan benar, tapi garam keberuntungan sangat penting. Dan, jangan lupa, supporter seperti tomat. Tanpa tomat, itu bukanlah pizza."
Berbekal racikan seperti itu, Leicester mengguncang Liga Inggris. Saat Ranieri mentraktir pemainnya dengan pizza, tim itu sudah dianggap hebat karena mampu menempati urutan kelima klasemen. Langkah ajaibnya terus berlanjut. Dua bulan kemudian, saat Natal tiba, tim berjulukan The Foxes (Rubah) itu sudah tiga minggu berada di puncak klasemen.
Sudah tentu hal itu menjadi pencapaian luar biasa bagi Leicester, yang baru menanjak ke kancah utama sepak bola Inggris dua musim sebelumnya dan nilai total gaji pemainnya hanya Rp 408 miliar semusim, seperempat dari Manchester City. Padahal, pada periode Natal musim sebelumnya, The Foxes berada di posisi paling bawah klasemen. Prestasi Leicester itu mengingatkan orang pada pencapaian Nottingham Forest, yang mendadak digdaya di bawah arahan Brian Clough pada 1975-1993 dengan meraih satu gelar liga, dua trofi Piala Eropa, dan empat Piala Liga.
Gary Lineker, legenda sepak bola Inggris yang juga mantan pemain Leicester, kini harus menelan kata-katanya sendiri atas pencapaian Ranieri bersama timnya itu. Pada awal musim, dialah yang paling keras mengkritik saat pelatih ini ditunjuk menggantikan Nigel Pearson. "Claudio Ranieri? Serius?" kicau pria 55 tahun ini di akun Twitter-nya. "Ia jelas sangat berpengalaman, tapi ini adalah pilihan tak inspiratif dari Leicester."
Bila melihat kondisi saat itu, komentar Lineker tersebut terbilang wajar. Ranieri sebelumnya pernah melatih 13 tim, termasuk Chelsea, Inter Milan, Juventus, AS Roma, dan AS Monaco. Tapi hampir tak ada pencapaian besar yang bisa diingat dari pelatih ini, sehingga banyak pihak menyebutnya pelatih spesialis "nyaris". Yang lebih buruk, sebelum direkrut Leicester pada 13 Juli 2015, ia menganggur tujuh bulan setelah dipecat tim nasional Yunani, yang baru empat bulan memakai jasanya. Media Inggris menyebut kejadian itu "Tragedi Yunani".
Yang mungkin tak diketahui Lineker, Ranieri justru menggunakan masa menganggur itu untuk kembali belajar. Ia menemui dan mengobrol dengan Juergen Klopp, pelatih Liverpool, yang saat itu masih menangani Borussia Dortmund. "Saya juga melihat Pep Guardiola, melihat Bayer Leverkusen, Augsburg. Pada musim dingin lalu, saya pergi ke Jerman dua kali untuk melihat sepak bola. Saya ingin belajar," katanya, seperti dikutip The Telegraph, akhir Desember tahun lalu. Dengan usia sudah 64 tahun dan pengalaman segunung, Ranieri masih bersemangat untuk terus menggali hal baru. "Saya ini seperti kamera Jepang. Saya mengambil foto dan makin membaik."
Dari proses itu pula Ranieri belajar menjadi lebih fleksibel. Saat melatih Chelsea pada 2000-2004, ia dikenal dengan julukan The Tinkerman karena kegemarannya mengotak-atik formasi dan terus mengubah susunan pemain yang jadi starter. Saat datang ke Leicester, hal itu tak lagi ia lakukan.
Ia mempertahankan kerangka tim dari musim sebelumnya dan hanya menyelipkan beberapa pemain baru rekrutannya, termasuk Shinji Okazaki dan Gokhan Inler. Ranieri juga tetap mempertahankan mayoritas jajaran staf kepelatihan. "Seorang pelatih dengan kemampuan adaptasi seperti itu adalah fantastis," kata Kasper Schmeichel, kiper Leicester.
Dalam melatih, Ranieri lebih berfokus pada penguatan fisik dan kerja sama pemain. Urusan taktik, menurut gelandang Marc Albrighton, hanya dilakukan 10-15 menit setiap hari. Taktik yang dipakai pun umumnya memiliki ide sama. "Ia ingin kami bermain menyerang dan lebih kompak saat lawan menguasai bola," ujarnya.
Yang juga ditekankan pelatih ini adalah agar semua pemain berjiwa petarung. Di ruang ganti, Ranieri kerap menyetel lagu Fire yang dibawakan Kasabian, band rock dari Leicester, untuk menggelorakan daya juang pemainnya.
Meski mempertahankan kerangka tim, Ranieri tetap melakukan beberapa perubahan penting terkait dengan posisi pemain, yang kemudian terbukti berujung pada sukses. Jamie Vardy, yang oleh Pearson ditempatkan sebagai pemain sayap kiri, ia pindahkan jadi penyerang utama. Hasilnya mengejutkan. Sementara pada musim lalu hanya menyumbang 5 gol, kini pemain 28 tahun itu sudah mencetak 15 gol dan jadi pencetak gol terbanyak Liga Inggris bersama Romelu Lukaku (Everton). Dalam prosesnya, Vardy juga memecahkan rekor Ruud van Nistelrooy dengan menorehkan 11 gol dalam 11 laga secara beruntun.
Ranieri juga mengubah peruntungan Riyad Mahrez, 24 tahun. Pemain asal Aljazair ini sebelumnya kerap jadi cadangan di bawah Pearson. Ranieri menjadikannya pilihan utama dan memindahkan posisinya dari tengah ke sayap kanan. Hasilnya, pemain ini sudah mencetak 13 gol dan 7 umpan berbuah gol (assist). Kini ia pun dipuji sebagai pemain serba bisa.
Di luar lapangan, Ranieri juga selalu berusaha mencari cara untuk menjaga kekompakan tim. Ajakan makan pizza bersama setelah timnya mampu bermain tanpa kebobolan salah satu caranya. Ia yakin hal seperti itu bisa membuat pemainnya menjadi kian dekat dan akrab. "Sangat penting bagi mereka untuk menjadi sangat dekat, menjadi teman. Kami tak memiliki tim berkualitas seperti Manchester City, tapi kami bertarung bersama. Bagi kami, setiap bola yang didapat adalah seperti bola terakhir," ucapnya.
Belakangan, kecemerlangan Leicester sedikit mengendur. Setelah mengakhiri tahun 2015 di puncak klasemen, pada tahun baru The Foxes digeser Arsenal ke posisi kedua. Tiga laga tanpa kemenangan—dikalahkan Liverpool 1-0 serta ditahan seri Manchester City dan Bournemouth—jadi penyebabnya. Posisi Leicester di urutan kedua pun terancam oleh Manchester City, yang hanya terpaut satu angka di bawahnya.
Toh, Ranieri tak khawatir. Ia yakin timnya akan segera bangkit. Lagi pula, ibarat membuat pizza, topping (taburan di bagian atas) yang ia rencanakan sudah ia dapat. Pada awal musim, Ranieri hanya menargetkan meraih 40 poin. Kini nilai itu sudah diraih dalam setengah musim. Jadi ia hanya perlu mengejar topping yang lain dengan lebih rileks. Lalu apa topping yang ada di pikirannya? "Saya belum tahu, saya berpikiran terbuka," kata Ranieri sambil tersenyum.
Ya, topping pelengkap pizza-nya masih bisa merupakan hal istimewa, termasuk tiket Liga Champions musim depan, dengan memastikan Leicester finis di posisi empat besar atau bahkan meraih gelar juara. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa Ranieri bukan lagi sekadar pelatih spesialis "nyaris". Untuk itu, dia harus kembali menemukan jurus untuk memacu para pemainnya dengan cara menyenangkan, seperti saat menjanjikan pizza gratis.
Nurdin Saleh (Guardian, Mirror, BBC, Reuters)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo