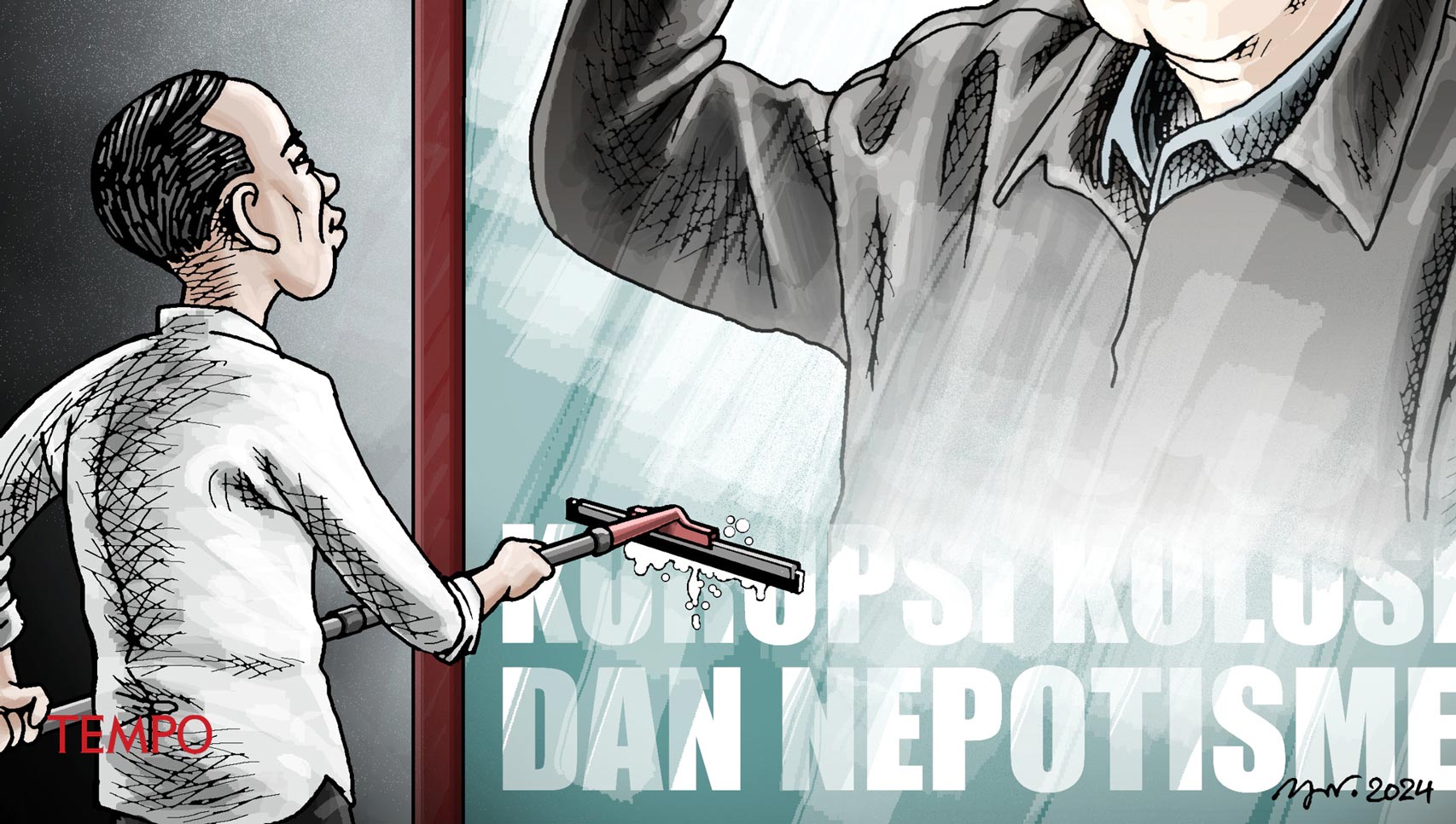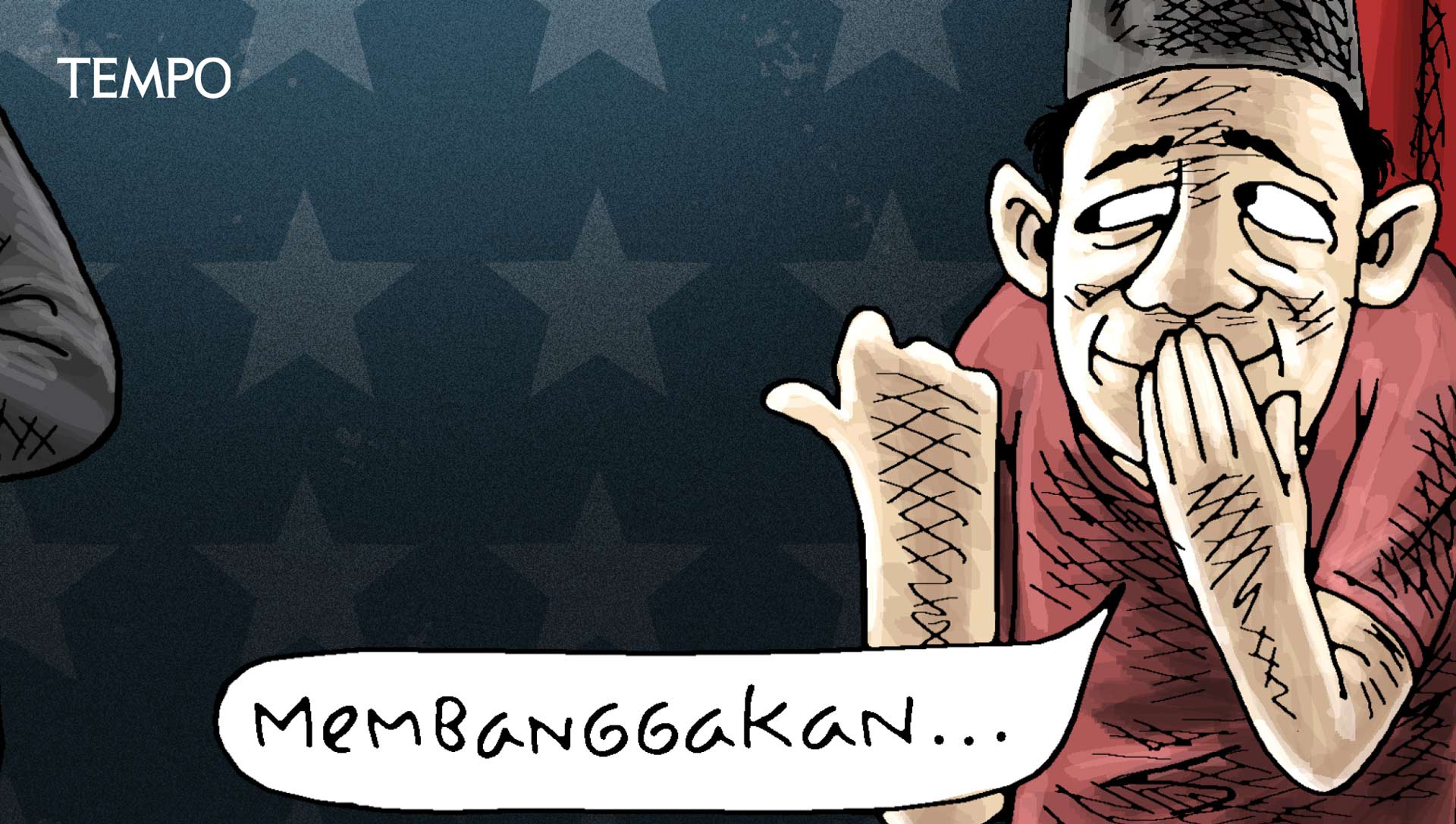Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
BECAK-BECAK memacetkan lalu lintas. Baiklah. Dan, karena itu, Ibu Kota sudah setahun ini menentukan tapal batas operasinya. Tapi sejumlah jalan sekarang, seperti di Gunung Sahari, Cokroaminoto, dan Sisingamangaraja serta puluhan jalan besar lain di Jakarta, meskipun sudah dibebaskan dari kendaraan roda tiga tadi, masih suka "dinodai" oleh kehadiran penjual makanan pinggir jalan. Mereka terdiri atas pedagang es, rokok, roti, atau makanan jenis warung Tegal, beroda atau bertiang cabut-cabutan.
Niagawan-niagawan semacam ini tampaknya memberi andil pula dalam memacetkan lalu lintas. Di sepanjang Jalan Gunung Sahari, misalnya, mereka bergerombol di trotoar sehingga tak hanya menghambat pejalan kaki, tapi juga mendesaknya turun ke aspal. "Kalau mereka dibiarkan terus, bisa bikin celaka pejalan kaki," kata Syariful Alam sambil menggelengkan kepala. Kepala Humas DKI Jakarta itu kemudian menghubung-hubungkannya dengan larangan bagi daerah tertentu dilewati gerobak dorong dan sejenisnya, seperti yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.
Andai ada pejalan kaki yang keseruduk mobil di tempat itu, pemerintah daerah tentu tidak memikul tanggung jawab. Tapi petugas-petugas keamanannya tak luput mengobrak-abrik para pedagang yang menjajakan dagangan di atas kendaraan beroda mirip becak itu. "Mereka memang bukan tukang becak, tapi mereka memang barang dagangannya di daerah terlarang," ujar Syariful.
Seandainya tidak mangkal di pinggir jalan, apakah mereka akan ditindak pula karena melanggar "daerah bebas becak"? Syariful menjamin mereka tidak akan ditindak, "Tapi mana mungkin mereka tidak akan mangkal? Siapa yang mau belanja?" Ini artinya para pedagang itu tidak terlarang menyusup ke daerah bebas becak asalkan tidak berhenti di pinggir jalan. Masuk ke pekarangan rumah orang yang mau berbelanja, misalnya.
Pihak pemerintah daerah masih punya urusan lain yang cukup banyak dan memusingkan kepala. Pedagang-pedagang itu sementara boleh merasa aman di pangkalannya asalkan tidak mengganggu lalu lintas dan kebersihan. Tapi kebebasan itu tidaklah berkepanjangan. Sebab, "Sudah menjadi tujuan pemerintah daerah membersihkan kaki lima dan pinggiran jalan dari para pedagang. Untuk kelancaran lalu lintas dan kebersihan kota."
Kalau keputusan itu diibaratkan pedang, keterangan tadi merupakan matanya yang satu. Sedangkan mata yang lain tersimpul dalam kata-kata Syariful berikutnya, "Juga untuk menahan arus urbanisasi." Urbanisasi bukanlah sesuatu yang jelek. Ia berarti pertambahan tenaga kerja. Tapi mereka yang membanjiri Jakarta bukan merupakan tenaga kerja yang baik. Kurang terdidik dan kurang terlatih. Maklum, mereka kebanyakan petani dan DKI belum mampu menyediakan lapangan kerja buat mereka.
Diperkirakan ada 45 ribu pedagang yang menongkrongi kaki lima dan pinggir jalan Ibu Kota. Berapa persenkah dari jumlah itu yang mundur ke desa karena tak tahan diuber-uber petugas ketertiban DKI? "Sukar menghitungnya. Belum pernah ada penyelidikan. Dan, di antara 45 ribu orang tadi, hanya beberapa persen yang benar-benar profesional, yang benar-benar hidup dari pinggir jalan."
Dan yang lebih repot lagi, menurut Syariful, pedagang-pedagang yang sudah tertampung di berbagai perusahaan digantikan oleh pedagang muka baru. Artinya, meski tidak dikatakan Syariful, pengusiran dan kembalinya para penjual itu ke tempat semula seperti tambal-sulam saja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo