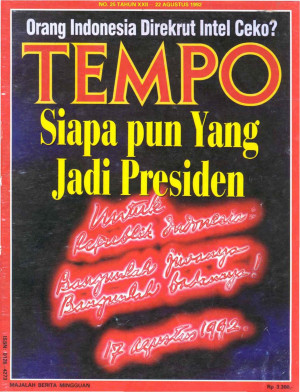MENJADI SEORANG KEPALA POLISI Pernahkah anda memakai wig gondrong, baju berbunga, syal di leher, merokok Ji Sam Sooe tapi purapura teler? Itulah pekerjaan gila yang pernah saya lakukan ketika saya menjabat sebagai Kepala Polisi, menyamar jadi hippies dan bergaul diantara para pecandu narkotik. Ini bukan adegan televisi. Saya memang gemar menyamar untuk mengetahui persoalanpersoalan yang sesungguhnya. Tidak mudah menjadi polisi yang baik. Ia adalah alat hukum dan ia mudah menjadi sasaran jika kejahatan dan pelanggaran berlangsung dengan mulus. Bayangkan juga bagaimana sulitnya kedudukan polisi jika ia harus menangkap pelanggar lalu lintas yang ternyata seorang supir yang gajinya tak seberapa. Tapi mungkin tantangantantangan itulah yang menyebabkan saya ingin jadi polisi. Ketika akhirnya saja jadi Kapolri tahun 1968, saya punya banyak citacita. Seperti banyak orang, saya menaruh banyak harapan pada periode Orde Baru karena Orde Baru menjanjikan koreksi total terhadap kesalahan Orde Lama. Dan seperti banyak orang Indonesia lain, meski saya pengagum Bung Karno, saya sangat menyadari kelemahan Bung Karno terhadap wanita dan persoalan manajemen ekonomi. Persoalan berat yang dihadapi polisi dari masa ke masa adalah soal citra. Dari sebutan prit,jigo (artinya polisi yang menangkap pelanggar lalulintas bersedia disogok agar pelanggar tak perlu ditilang) hingga citra tukang pukul tahanan. Penyamaran saya sebagai hippies mungkin karena saya selalu menekankan pedagogi daripada intimidasi. Karena itu saya sangat memperhatikan Program Antidrugs. Ini memang program dasar kepolisian, tapi di awal tahun 1970an, korban obat bius di kalangan remaja luar biasa tingginya. Yang saya dengar, marijuana sedang banyak digemari dan kebetulan ditanam di Aceh. Sebelumnya, saya tidak tahu bahwa marijuana termasuk obat yang dilarang, karena saya mengira marijuana hanya bumbu yang biasa dipakai orang Aceh dalam gulainya. Baru ketika menghadiri Interpol Conference tahun 1971, saya baru tahu. Maka ketika saya pulang ke Indonesia, saya menaruh perhatian besar terhadap penyalahgunaan mariyuana. Untuk menegtahui daerah anakanak muda pengisap marijuana, saya harus menyebarkan banyak anakanak buah ke berbagai tempat. Soalnya ada yang sampai menjualnya di tukangtukang rokok dengan cara penyelundupan. Dan anak-anak muda yang ketagihan akan tahu tukang rokok mana yang menjual barang-barang terlarang itu. Saya juga tertarik menyelidiki kenapa anakanak muda itu begitu gandrung menggunakan marijuana. Kelihatannya, mereka menggunakannya sebagai pelarian. Tapi ada juga yang ingin ikutikutan. Mode, katanya. Ini sungguh memprihatinkan. Karena saya ingin tahu kenapa mereka menggemari marijuana, saya harus turun sendiri. Itulah asal muila ide penyamaran muncul. Anak-anak buah saya mengusulkan agar saya menyamar dan berdandan seperti anak-anak muda tahun 1970-an. Maka, saya pakai wig gondrong, kemeja bunga-bunga, syal di leher, pokoknya seperti orang gila. Saya berjalan kemana-mana selama berhari-hari dan tak ada satu orangpun yang mengenali saya sebagai Hoegeng. Saya mendatangi beberapa tempat perkumpulan anak-anak muda di Jakarta. Yang menggelikan, selama penyamaran itu, saya tetap tak berani mencoba marijuana. Saya selalu merokok dan bertanya macam-macam kepada anak-anak muda itu. Dari penyamaran itu, saya menemukan beberapa anak muda yang yang berasal dari keluarga broken home. Tapi banyak juga yang berasal dari keluarga baik-baik dan kaya raya. Pernah suatu malam seorang polisi membawa seorang anak muda. "Ada apa?" tanya saya. Mereka menjawab bahwa anak ini terlibat soal ganja. Anak itu saya ajak bicara dan saya tanyakan siapa orangtuanya. Mula-mula dia tidak mau memberitahu nama orangtuanya. Karena saya tanyakan terus, akhirnya dia mengaku bahwa ia anak seorang menteri. Saya kaget. "Apakah ayahmu tahu kau mengisap ganja?" Anak itu menggelengkan kepala. Maka malam itu juga saya menelepon menteri tersebut. "Mas, puteranya ditangkap polisi dan dibawa pada saya. Ia mengaku suka mengisap ganja. Bagaimana, apa bisa mengurusnya sendiri atau biar saya saja? Kalau u tak bisa memperbaikinya, terpaksa saya ambil tindakan." Soal 'prit jigo' adalah citra polisi yang paling menjengkelkan saya. Itu memang sudah terlanjur menjadi istilah populer dan disukai rakyat maupun polisi. Orang bisa saja memberi alasan bahwa gaji polisi terlalu kecil, dan memang gaji polisi tidak mencukupi. Tapi memang anggarannya terbatas. Jadi, saya harus membangun moralitas para polisi. Cara saja memberantas budaya prit jigo itu dengan mengkader para polisi bahwa mereka harus selalu turun ke lapangan dan tidak bekerja melulu di belakang meja. Bahwa saya berbintang empatpun, saya tetap seorang agen polisi biasa. Saya kasih contoh dan mendekati mereka bahwa tanpa kekayaan apapun, kita bisa berdedikasi pada pekerjaan. Untuk selalu berhubungan dengan anak buah, saya memiliki berbagai saluran langsung. Kebetulan saya punya hobi radio. Disamping menjadi anggota Orari, saya juga punya sender dari polisi. Dengan demikian saya selalu berhubungan langsung dengan anak-anak buah, seperti pak Widodo Budidarmo, dan saya bukan hanya tidur dengan isteri, tapi juga dengan walky talky. Ini artinya, saya tak boleh keberatan dibangunkan tengah malam. Tantangan lain yang harus dihadapi selama jadi Kapolri adalah sogokansogokan yang muncul dari berbagai arah. Saya mendengar laporan bahwa orang masuk ujian polisi saja sudah diperas, agar bisa lulus. Lalu, saya mencoba memberikan bimbingan agar hal-hal semacam ini tidak terjadi. Alhamdulillah, kejadian pemerasan ini berkurang. Tapi saya tak tahu bagaimana keadaan selanjutnya setelah saya mengundurkan diri dari kedudukan saya sebagai Kapolri. Man, Money, Material adalah prinsip 3 M yang harus ditentang. Artinya,jangan tergoda oleh ketiga hal ini. Kerasnya prinsip ini saya tanamkan. Dan saat itu, saya merasakan anak-anak buah saya mendukung hal ini. Meski saya harus siapdibohongi anak buah, karena jarang ada anak buah yang mau bersikap jujur pada atasan jika mereka menentang atasan. Konsep kewajiban memakai helm memang adalah kebijakan saya. Inspirasi itu timbul ketika saya mengikuti perjalanan Pak Harto ke Malaysia dan Thailand. Selanjutnya, saya lihat lagi bagaimana helm wajib dipakai di Belanda, Inggris dan Jerman Barat. Saya menganggap Indonesia pun harus melaksanakan kebijaksanaan itu, karena pengendara motor Indonesia sangat banyak jumlahnya. Sayang sekali, meski kebijaksanaan itu diterima, tapi pelaksanaannya tidak didukung. Seingat saya mas Ali (Sadikin, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI) dan Oemar Senoadji (menjabat sebagai menteri kehakiman) dan Frans Seda (yang menjabat sebagai menteri keuangan) mendukung program ini. Tapi dukungan mereka tak cukup. Saya mengharapkan kerjasama dari pihak Hankam, dan ternyata saya dilepas begitu saja. Persoalan yang timbul dengan program wajib pakai helm ini ketika adanya bisnis helm. Cilakanya saya mendengar ada orangorang dalam kepolisian yang memperjualbelikan helm. Saya jadi jengkel betul. Saya keluarkan larangan keras bagi polisi untuk berbisnis helm. Saat olahraga golf menjadi mode permainan pejabat teras, saya tidak bermain golf bukan karena anti golf, tapi karena itu permainan mahal. Harga stik golf sangat mahal dan saya tidak punya uang. Saya juga tak bersedia memintaminta. Salah satu menteri sampai pernah mengeluh, " Mas Hoegeng, kami semua sudah main golf, kok Mas Hoegeng belum. Mbok ya main, tentang stik itu beres deh. Nanti ada orang yang kasih..." jawab menteri tersebut. "Wah,saya ndak mau dibeliken stik golf. Nanti saya beban hutang budi," kata saya lagi. Budaya upeti ini memang populer saat itu. Rupanya karena orang sudah tahu saya tidak senang diberi upeti, maka tak pernah ada yang berani memberi barang apaapa kepada saya, karena saya pasti tidak menerimanya. Suatu hari, Dirjen Bea Cukai melaporkan pada saya bahwa ada orang yang menyelundup tekstil untuk orang Kostrad. "Baik, saya ambil oper persoalan ini dan saya akan menghadap pak Harto." jawab saya. Lalu saya minta bertemu dengan pak Harto. Saya informasikan pak Harto tentang kegiatan orang India tersebut. Dua hari kemudian, Pak Harto mengatakan "terserah Hoegeng saja." Saya menindaknya dengan menyita barangbarang selundupan itu dan mendeda seberat-beratnya. Rupanya saya dianggap berbahaya oleh berbagai "tuan besar" karena katanya saya terlalu sering menangkapi orang. Saya mendengar desas-desus ini, terutama ketika saya menyelidiki kasus Robby Tjahjadi. Beberapa rekan di bea cukai dan kepolisian memberi informasi tentang adanya penyelundupan mobil-mobil mewah, termasuk Mercedes. Saya menyadari bahwa tentu saja ada berbagai pihak yang tidak senang melihat kami mengutak-utik masalah penyelundupan ini. Tapi kepolisian toh menginvestigasinya seperti kasus kriminalitas biasa. Sungguh mati saat itu saya tak tahu hubungan Robby Tjahjadi dengan para pembesar. Ketika mulai tercium gerak-geriknya dan korankoran sudah mulai menulis tentang kegiatannya, saya merasakan banyak sekali pejabat yang berlomba-lomba ingin melepas Robby Tjahjadi. Lho, saya heran, Robby Tjahjadi ini siapa? Kok banyak betul yang ingin membantunya. Tapi saya dan rekan-rekan tak perduli. Mungkin kami dianggap naif. Kami betulbetul ingin menangani kriminalitas tanpa melihat pangkat dan jabatan. Sayang sekali, ketika akhirnya ia ditangkap dan diadili, saya tidak menjabat sebagai Kapolri lagi. Pada tanggal 6 September 1971 saya dipanggil Presiden Sooeharto, "bagaimana jika Hoegeng jadi dutabesar di Belgia." "Kalau di Indonesia masih ada lowongan, saya lebih bersedia. Tapi jangan jadi dutabesar," jawab saya. Wongsaya belajar untuk menjadi polisi, bagaimana saya bisa jadi dutabesar? Pak Harto menjawab di Indonesia tidak ada lowongan. Ya wis, saya mengundurkan diri saja. Pak Harto setuju. Maka sayapun mengundurkan diri tanggal 2 Oktober 1971. Hingga kini, saya merasa alasan saya diberhentikan tidak terlalu jelas. Rekanrekan saya banyak yang menyalahkan saya, karena katanya saya terlalu bergairah dalam menangani kasus Robby Tjahjadi. Saya sendiri tidak mau menghubung-hubungkan satu kasus dengan kasus lainnya tanpa bukti. Alasan lain secara resmi diberitakan di koran-koran adalah, pergantian saya dengan Jendral Hasan adalah untuk "peremajaan". Padahal pengganti saya, jendral Hasan waktu itu sudah berusia 51 tahun, artinya ia dua tahun lebih tua daripada saya. Waktu perpisahan, anak-anak buah saya memberi wayang kulit Brotoseno. Mereka bilang sifat saya seperti Brotoseno, selalu jujur dan pantang kompromi. Dan saya memang selalu suka pada sifat-sifat Brotoseno yang pantang menyembah itu. Bagaimanapun hubungan saya dengan beberapa kawan-kawan di Polri tetap baik. Sampai Kapolri Anton Soedjarwo, saya masih diundang hadir dalam perayaan Hari Bhayangkara. Ada juga kawan yang saya lihat tulus. Misalnya, Kunarto. Sehari sebelum pak Kunarto dilantik dia datang ke rumah saya. Saya sampai kaget. kok Kunarto sampai datang ke rumah saya secara mendadak. Bagaimana saya ndak kaget. Saya bilang, "wah,ndak salah nih." "Bapak kan senior saya,"jawabnya "Terima kasih," jawab saya. Dengan Pak Domo saya tetap baik, demikian juga dengan Emil Salim. Ini artinya, mereka bukan tipe pejabat yang bakal menghindar kalau ketemu saya. MASA SEKOLAH: Sejak kecil, saya selalu mengagumi polisi. Saya melihat mereka sebagai pahlawan yang bisa membantu rakyat kecil. Semula, saya memperhatikan gerak-gerik Pak Ating Natadikusuma ayah Slamet Bratanata yang menjabat sebagai Kepala Polisi Jakarta Raya pertama. Pak Ating memang berkawan baik dengan ayah saya, Kepala Jaksa Keresidenan Pekalongan. Melihat Pak Ating mengenakan sepatu laars dan membawa revolver, saya kagum betul. Betapa gagahnya dia. Tidak itu saja. Saya selalu ingat wejangan Pak Ating yang diberikan kepada saya, "Geng, kalau kamu nanti mendapat suatu jabatan dan jabatan itu tinggi artinya kamu mendapatkan kekuasaan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan itu, tapi pergunakanlah untuk menolong rakyat kecil, yang lemah." Kata-kata itu saya tancapkan ke dalam kepala saya dan sejak itu saya bercitacita untuk menjadi polisi. Melalui pak Ating, saya melihat bagaimana polisi dapat menolong rakyat kecil secara langsung. Ayah saya, Soekaryo, tidak keberatan dengan cita-cita saya. Sejak saya lahir di Pekalongan, 14 Oktober 1921, 71 tahun silam sebagai anak tertua dari tiga bersaudara, ayah dan ibu saya selalu memberikan kebebasan pada kami untuk menentukan masa depan. Cita-cita saya menjadi polisi berjalan cukup mulus pada awalnya. Mula-mula saya bermaksud untuk sekolah AMS dulu, untuk kemudian dilanjutkan ke R.H.S. (Rechts Hoge School). Sayang tentara Jepang terlanjur datang. Maka, terpaksa sekolah saya tertunda dan saya bekerja sebagai pegawai radio. Tapi, kemudian saya mendengar bahwa seorang Inspektur Polisi dicari karena Jepang menangkapi Inspektur Polisi Belanda. Maka saya memberanikan diri untuk ikut ujian sekolah kepolisian Jepang. Dari 130 pelamar, hanya ada 11 orang yang lulus, dan saya termasuk di dalamnya. Tapi baru belakangan saya baru tahu bahwa setelah lulus dari sekolah itu, kami tidak akan menjadi inspektur polisi, melainkan Hoofdt Agent. Dan saya tak tertarik. Paman saya yang menjadi walikota Tegal Meester Besar menyarankan agar saya masuk sekolah Kehakiman saja. Baru saja saya mau memutuskan untuk mengikuti saran paman saya, ternyata ada pengumuman pembukaan Sekolah Tinggi DAI Ika Koto Keisatu Gakko (Sekolah Pendidikan Kepolisian Tingkat Tinggi). Saya dianjurkan banyak orang untuk ikut ujian tersebut. Dengan rasa enggan, saya menjawab ujian itu dengan asal-asalan supaya ndak lulus. Saya sudah terlanjur tak bernafsu karena segalanya tak menentu. Tapi kok lulus. Begitu diumumkan lulus ujian pada pukul 11 pagi, tiga jam kemudian kepala kami sudah digunduli. Esok harinya kami langsung ke Sukabumi untuk mendapatkan pendidikan di DAI Ika Koto Keisatu Gakko. Kemudian saya ditempatkan di Semarang sebagai Junsa Butyo. Ternyata Semarang digempur Belanda. Maka saya terpaksa pulang ke Pekalongan. Di sana saya bertemu dengan KASAL pertama Indonesia, Pak Nasir. Ia menyarankan saya untuk bergabung dengan Angkatan Laut karena toh AL akan mendirikan PMLC (Polisi Militer Laut Choesoes). Ya saya mengikuti saran tersebut. Tapi toh ketika Akademi Polisi Indonesia di Yogyakarta dibuka, saya keluar dari AL dan masuk Akademi Polisi yang pertama di Indonesia itu. Pada zaman revolusi itulah, saya bertugas di Yogyakarta, saya mulai dekat dengan Mery. Sebetulnya kami sudah pernah bertemu di Pekalongan, tapi hubungan kami menjadi romantis di Yogyakarta. Saat itu, Mery bekerja sebagai penyiar radio militer Indonesia. Kebetulan radio militer itu mengadakan kegiatan drama di bawah pimpinan Kapten Iskak dan kami sama-sama bergabung. Lebih seru lagi, karena drama yang akan diperdengarkan adalah drama berjudul SAIJAH DAN ADINDA, sebuah adaptasi dari novel karya Multatuli. Saya berperan sebagai Saijah dan Mery jadi Adinda. Setelah kenal beberapa lama, kami betulbetul menjadi Saijah dan Adinda di luar drama. Apalagi, atas permintaan Bung Karno, drama itu juga dibawakan di RRI, Yogya. Kami pacaran enam bulan dan saya langsung melamarnya dan menikah tanggal 30 Oktober 1946. Saya takut Mery digaet orang lain karena ia cantik sekali. Kami memiliki tiga orang anak, Renny, Didit dan Ayu. Setelah Indonesia merdeka dari Belanda, kami semua ke Jakarta. Saya meneruskan sekolah di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) yang bertempat di jalan Tambak sedangkan isteri saya menjadi penyiar RRI Jakarta. BERTEMU BUNG KARNO Saya mulai mengenal Bung Karno secara dekat ketika saya menjadi penjaganya saat ia berpidato di Semarang (atau di zaman revolusi, di Yogya). Kemudian ketika saya masih mahasiswa Akademi Polisi, pada pidato 17 Agustus tahun 1947, Mungkin karena senewen, pagi itu saya lupa sarapan. Akibatnya, di tengah gegap gempitanya pidato Bung Karno, perut saya kelaparan. Karena saya tahu pidatonya bakal lama sekali, saya memberanikan diri untuk njlintis ke dapur belakang. Lha, saya ketemu mertuanya Bung Karno, ayahnya Ibu Fatmawati. "Lho, ada apa?' tanyanya. "Saya lapar." "Yoo, ayo makan..."sambutnya ramah. Saya buru-buru makan. Setelah kenyang, saya kembali ke posisi saya semula untuk menjaga Bung Karno. Saya tidak menyadari bahwa sebenarnya Bung Karno melirik ketika saya njlintis tadi. Setelah selesai, Bung Karno bertanya, "darimana tadi ?" "Dari belakang," jawab saya. "Mau apa ke belakang?" "Makan." "Lho, kok makan?" "Saya belum sarapan." "Nanti malam siapa yang jadi ajudan?" tanya Bung Karno lagi. "Saya ndak tahu pak." "Ya, sudah. Kamu saja yang jadi ajudan lagi." Wuaduh, cilaka! Dus saya disetrap jadi ajudan lagi. Sejak itulah Bung Karno ingat saya, karena saya nekad meninggalkannya di tengah pidato. Setelah saya lulus dari PTIK pada tahun 1952 saya bertemu lagi dengan Bung Karno. Sebagai grup pertama yang lulus dari PTIK, kami semua beserta para isteri diundang Bung Karno ke istana. Saya begitu terkesan dengannya, karena dia bersedia berbincang dengan kami satu persatu. BERTUGAS DI MEDAN Tahun 1952 saya ditempatkan di Surabaya sebagai kepala DPKN ( Dinas Pengawasan Keselamatan Negara) se Jawa Timur. DPKN adalah badan intel kepolisian jaman itu dan di sini saya belajar banyak tentang dunia intelijens. Setelah tiga tahun menjadi intel, saya ditugaskan ke Medan. Sebagai AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) di Bagian Reserse Kriminil. Menurut saya, Medan adalah tempat yang mengajar saya tentang berbagai hal karena saya mengenyam banyak pengalaman, misalnya menghadapi PRRI , penyelundupan, judi dan korupsi. Saat itu banyak sekali kelompokkelompok yang hidup dari penyelundupan, judi dan korupsi. Kelompok yang hidup dari tempat perjudian dan penyelundupan ini biasa menyogok pejabat agar usahanya aman. Mereka biasa menyelundupkan karet ke Malaysia dan sebagai tukarnya, Malaysia mengirim barang-barang luks ke Indonesia. Jaringan mereka begitu luas, ruwet dan lengkap. Selain memiliki banyak tukang tembak, mereka memiliki dukun segala. Karena itu, sebelum saya berangkat ke Medan saya memastikan diri agar mempelajari persoalan-persoalan di Sumatera Utara. Salah seorang rekan saya bernama Tengku Aziz yang mengenal Sumatera Utara dengan baik mengatakan bahwa saya harus hati-hati dengan penyogokan. Ternyata apa yang dikatakan Tengku Aziz benar. Soalnya,begitu tiba di Medan, kok tiba-tiba saya melihat ada satu delegasi tak dikenal yang menjemput kami. "Pak Hoegeng, kami sudah sediakan rumah di sini dan juga mobil. Tak usah khawatir," kata salah seorang penjemput itu sambil menyalami saya. Saya diam saja, terheran-heran. Tak lama kemudian datanglah kawan-kawan saya dari kepolisian. Saya langsung mengucapkan terimakasih pada delegasi pertama tadi dan langsung bergabung dengan rekan-rekan kepolisian. Kami sekeluarga masuk Hotel De Boer dan kawan-kawan kepolisian Medan menceritakan masalah kepolisian di Sumatera Utara. Esok harinya, kami ke rumah dinas yang disediakan buat saya yang sudah kosong. Tiba-tiba, lha, orang-orang yang tempo hari menjemput saya sudah ada di sana dan mengisi rumah tersebut dengan lemari es, piano, dan seperangkat mebel yang lengkap. "Pak, rumah Bapak sudah komplit kami isi." "Wah, bagaimana kalau barang-barang saya datang ? Saya minta maaf,tolong keluarkan barang-barang anda," kata saya. Ia tidak bergerak dan memandang saya dengan aneh. Mungkin dia menganggap saya polisi yang bodoh karena tak mau menerima pemberiannya. "Saya kasih waktu sampai jam dua. Kalau tidak dikeluarkan, saya suruh anak buah saya mengeluarkan barang-barang tersebut."Ternyata hingga jam dua, barang-barang baru itu tetap ada di sana. Terpaksa saya menyuruh anak-anak buah saya memanggil kuli untuk mengeluarkan barang-barang itu. Setelah kejadian tersebut, beredarlah desas-desus bahwa sikap saya keras dan menolak sogokan. Karena itu paling-paling saya hanya bisa bertahan enam bulan. Ternyata saya bertahan di Medan selama empat tahun. Dan selama itu pula, saya ditawarkan macam-macam. Pernah seorang India menyebarkan desas-desus bahwa isteri saya pernah terima cincin berlian. Wuaduh, mangkel betul saya. Saya panggil dia dan di muka isteri saya, "kenal sama wanita ini ?" Waktu dia menggeleng, saya bentak, "Ini isteri saya. Kata anda, ia menerima cincin berlian dari anda...?" Orang itu ciut dan dengan gemetar ia mengaku menyebar berita bohong. Bukan main marahnya saya. Saking marahnya, saya lempar dia dengan tong sampah. Waduh, dia kaget dan ketakutan betul dan langsung permisi pulang. Masa-masa di Medan juga mengingatkan pengalaman saya yang seru menghadapi PRRI. Saat itu, PRRI sedang mengadakan persiapan untuk memberontak. Entah bagaimana, saya diundang pada pertemuan dengan Mayor Boyke Nainggolan. Saya ndak tahu Mayor Baoyke PRRI. Belakangan saya baru tahu, kami diundang karena PRRI mau mengecek siapa yang masih ada dan perlu diculik. Mauluhi Sitepu, salah satu anak buah saya memberikahukan saya, "Pak Hugeng, saya dengar nama Bapak ada di daftar yang mau diculik." Saya terkejut, "ha ? siapa lagi yang namanya ada di daftar ?" "Pak A.J.M. Pieter (Kepala Polisi Medan) Panglima Jamin Ginting, dan masih banyak lagi. Mereka menganggap Bapak dan yang lainnya ini sebagai orang pusat dan ingin dibersihkan," kata Mauluhi. Wah cilaka. Keesokan harinya, dengan terengah-engah Pongki Soepardjo (Mayor Laut) dari ALRI datang dari Belawan. "Mas, mas, saya mau diculik, mas, saya nginep di rumah mas saja." "Lho, kata orang, saya juga mau diculik," Pongki segera mencari tempat lain. Ketika malam tiba, saya ditelepon Nyonya Pieter yang terdengar menangis, "Pak Pieter ditangkap PRRI." Jadi memang terjadi juga. "Begini saja Yu. Yu Pieter jangan pergi, biar saya yang cari mas Pieter." Malam itu juga saya mengenakan seragam dan membawa revolver saya . Sedangkan revolver saya yang lain saya letakkan di rak sepatu. Tak lama, sebuah mobil tahanan datang. Wah, mungkin itulah mobil PRRI yang akan menangkap saya. Polisi yang menjaga rumah saya langsung berteriak "barang siapa berani masuk, saya tembak !" Ternyata yang menjemput adalah kawan saya, Koomisaris Muda Purwanto. Bersama Brig pol Simbolon, Inspektur Toorop, Komisaris Purwanto, kami mengelilingi kota Medan untuk mencaritahu tentang Pak Pieter. Keadaan cukup menegangkan karena tidak jelas lagi siapa lawan dan siapa kawan. Saya menelepon kesana kemari, ke Palinglima Sumut Jamin Ginting, ke Kastaf Hasan Kasim dan sampai ke Kapol Asahan, Sutan Mompang. Lha ternyata Sutan Mompang sudah membelot ke PRRI. Ketika saya menelepon Kepala POM Mayor Sukandi, yang menerima orang PRRI sambil menjawab, "Kardi sudah kami tahan !" Keadaan semakin kacau, kami mau ke Glugur karena mendengar Djatikusumo ada di sana. Ternyata di sepanjang jalan kami melihat truk-truk dengan bendera putih yang memberi indikasi PRRI. Akhirnya kami ke lapangan udara Polonia. Di sana kami bertemu dengan salah seorang komandan yang memberitahu bahwa jam 05.30, lapangan udara itu akan dimortir oleh Boyke Nainggolan. Maka saya berusaha ke Medan, dari jarak yang tak terlalu jauh, kami bisa mendengar bunyi ledakan mortir itu. Ternyata ketiga kawan saya terluka kena tembak pula. Dalam keadaan bingung, seseorang mengatakan saya dan pak Jamin Ginting dicari oleh gubernur Sumut Kumala Pontas. Jadi saya harus mencari pak Jamin di Sibolangit. Di sana kami menentukan langkah-langkah kami. Eh, ternyata hari ketiga, kami mendengar Boyke Nainggolan dan kawankawan mengundurkan diri dan lari ke Tarutung. Meski demikian, saya kira tiga hari yang menegangkan itu memberikan banyak pelajaran bahwa dalam keadaan krisis, kita baru mengenal siapa kawan dan siapa lawan kita. DIANGKAT MENJADI MENTERI Tahun 1960, saya diangkat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi. Karena saya sekaligus menjadi pegawai negeri, maka saya mencoba mentaati semua peraturan yang diterapkan pada sipil. Misalnya ada peraturan bahwa pegawai negeri dan keluarganya tak diperbolehkan berbisnis. Saat saya diangkat, isteri saya baru saja mendirikan perusahaan bunga yang dinamakan Leilani. Karena saya diangkat jadi Kepala Jawatan Imigrasi, maka saya meminta Mery untuk menutup perusahaan bunganya. Saya khawatir nanti orang jadi berbaik-baik pada saya dengan membeli bunga isteri saya. Dan Mery mengerti keputusan saya. Pada jaman itu, saya juga mencoba menghapuskan konsep cegah dan tangkal. Zaman itu, yang adalah tokoh kriminalitas yang masih dalam proses pengadilan dan saya mencoba membuat peraturan agar kebijaksanaan pencekalan ini dievaluasi setiap enam bulan sekali,karena manusia selalu berubah. Karena itu, betapa ironisnya sekarang saya malah kena korban cekal, sebuah konsep yang saya tidak setujui. Pada masa itu keadaan politik Indonesia memanas. Banyak orang menuduh Bung Karno terlalu memberi angin kepada PKI (Partai Komunis Indonesia). Menurut saya, Bung Karno memang selalu mencoba dekat dengan pihak manapun, jadi tak hanya PKI saja yang diberi angin. Saya tak tahu jelas bagaimana arah pemikiran Bung Karno saat itu. Yang jelas, beliau tahu saya sangat menentang komunis dan saya tidak setuju dengan peran PKI yang dominan. Tapi saya tak pernah mempertanyakan sikap Bung Karno yang sebenarnya terhadap PKI. Suatu hari di tahun 1965, Bung Karno memanggil saya dan isteri saya ke istana Bogor. "Geng, saya panggil kamu kemari karena Hoegeng mau saya jadikan menteri." Saya diam saja menanti katakata Bung Karno selanjutnya. "Nah,sekarang seumpamanya kalau ada karbon yang saya katakan berwarna hitam, Hoegeng bilang akan bilang warnanya apa?" Saya heran, kok mau jadi menteri ditanyakan warna karbon segala. Saya jawab, "begini Pak. Bapak suka melukis, saya sendiri suka melukis. Kalau karbon ini dikatakan hitam, saya akan mengatakan ini bukan hitam, tapi Pruisis Blauw atau Prussian Blue. Tetapi seumpamanya Bapak memberikan keputusan karbon ini hitam, saya selaku menteri Bapak punya tiga pilihan. Pertama, saya menyetujui bahwa karbon hitam. Kedua, saya tidak seratus persen setuju. Ketiga, saya tak setuju dengan Bapak tapi saya jelaskan kenapa saya menganggap karbon itu berwarna Prussian Blue. Nah dengan ketiga pilihan ini, saya akan bisa menentukan sesuai dengan permasalahannya," jawab saya. Ternyata dengan bersemangat Bung Karno menanggapi, "Ya, itu yang saya kehendaki." Kemudian, Bung Karno bertanya pada isteri saya, "Mery kenal dengan bu Fatmawati ?" Isteri saya menjawab, "kenal. Kami satu pengajian." "Bagaimana dengan Haryati?" tanya Bung Karno lagi. "Kenal," jawab isteri saya, "soalnya waktu di Surabaya, rumah Haryati berhadapan dengan rumah kami." "Lalu dengan bu Hartini?" "Belum," jawab isteri saya. "Bu Dewi?" "Belum juga," jawab isteri saya. "Nah, Mery, kamu layani salah satu isteri saya yang Mery kenal," kata Bung Karno. Kami samasama terdiam. saya tahu betul pendirian isteri saya. Jaman itu, pelayanan yang habishabisan terhadap isteri Bung Karno atau terhadap ibu menteri menjadi sebuah mode. Bahkan pelayanan itu dibarengi dengan membeo cara hidup para isteri menteri. Isteri saya tidak ingin larut dalam mode semacam itu. Semua isteri-isteri Bung Karno dianggapnya sama saja. "Maaf Pak," kata isteri saya kemudian. "Saya tidak bisa melakukan itu." "Kenapa?" "Semua isteri bapak yang berjumlah empat itu saya anggap sama, kalau saya hanya meladeni salah satu, maka tidak enak dengan yang lain dan pasti akan ada ketegangan." "Ya, itu betul," ia mengangguk. "Baiklah." Dari jawaban Bung Karno terhadap pendirian kami, saya menyimpulkan betapa demokratnya beliau. Ia tidak marah dengan keterusterangan kami. Begitu kagumnya saya pada Bung Karno maka sampai hari ini saya masih memasang foto Bung Karno di ruang tamu saya. Buat saya, ia adalah pemimpin yang demokrat dan seorang Bapak Negara. Tak lama kemudian saya diangkat menjadi menteri Iuran Negara di dalam Kabinet 100 menteri. Dari jauh,saya mulai mengenal Pak Harto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad. Kesan saya adalah ia orang yang pendiam dan tenang dan sukar dibaca pikirannya. Sementara itu, keadaan politik dan ekonomi makin memburuk. Saya ingat ketika ada rapat di istana, kami mendengar ribut-ribut di luar. Katanya ada penyerangan pasukan yang tidak pakai badge. Orang mengatakan itu pasukan Kostrad. Tapi sampai sekarang, saya tak merasa pasti siapa yang datang ke depan istana. Yang jelas, saya ingat betul bagaimana Bung Karno membaca sebuah surat yang disodorkan kepadanya dan buru-buru ia pergi. Lantas saya ingat bagaimana Menteri Soebandrio ikut tergopoh-gopoh di belakangnya hingga ketinggalan sepatunya. Kami semua tetap tinggal dan sibuk membicarakan dan nebak-nebak kejadian tersebut. Bahkan tanggal 30 September 1965 masih penuh tekateki buat saya. Pagi itu, seperti biasa saya mengenakan seragam dan menyetir sendiri. Di jalan saya lihat seorang tentara memberi salut kepada saya, saya balas dan saya masih tidak menyadari ada kejadian seperti itu. Di kantor, saya mau menelpon, ternyata hubungan telepon terputus. Tak lama kemudian, utusan dari rumah, mengatakan bahwa isteri saya baru saja dengar tentang pak Haryono MT keponakan kami yang diculik PKI. Datang pula laporan dari kepolisian tentang adanya penculikan jendral-jendral dan usaha penculikan pak Nasution. Ini semua mengingatkan gejala di Madiun. Di situ baru ada asumsi kuat bahwa PKI lah yang sedang bergerak. Sorenya saya menyetir sendiri ke rumah tanpa kejelasan apa yang terjadi. Keesokan harinya kami ditelepon bahwa Haryono dan yang lain sudah jenazah. Anak-anak Haryono melihat sendiri bagaimana bapaknya diseret hingga berdarah. Saya betulbetul sedih dan sakit mendengar berita itu. Mungkin karena keadaan begitu kacau, saya menaruh banyak harapan pada masa yang disebut orang sebagai periode Orde Baru. PETISI 50 Rekanrekan saya terheran-heran melihat kegemaran saya menyanyi musik Hawaii. Mereka menganggap mestinya polisi kasih kesan angker pada rakyat, kok saya malah nyanyi di televisi. Saya meniru pak Ating Natadikusuma, bahwa kita harus friendly dan bersikap ramah. Tak perlu bersikap garang kalau tak perlu. Polisi yang baik bukan yang cuma pandai membentak dan plintir kumis. Jadi saya tak melihat salahnya untuk menyanyi di televisi. Kegemaran ini sudah saya mulai sejak saya duduk di di MULO (SMP jaman Belanda). Saya selalu main musik dengan Hawaiian Guitars, gitar,ukulele, piano dan biola. Saya pernah belajar secara formal bertahun-tahun. Saya juga sempat menciptakan beberapa lagu, misalnya lagu pembukaan Hawaiian Seniors. TVRI rajin menyiarkan acara Hawaiian Seniors sebulan sekali setiap Minggu malam. Setelah saya bergabung dengan Petisi 50, saya terpaksa berhenti nongol di TV. Dikira kalau saya nongol dan menyanyi di TV, saya bisa mempengaruhi orang-orang, sering heran kok sampai sekarang saya masih hidup. Buat saya ini larangan yang menggelikan. Mula-mula saya mendengarnya melalui anak-anak buah saya. "Pak, kami dengar katanya Menpen Ali Murtopo melarang Bapak main di televisi lagi." Lalu saya mengecek. Tak lama kemudian, Direktur Televisi mengatakan: "Pak, buat bulan ini, acara bapak mau diganti," "Mau diganti oleh apa?" "Hawaiian Senior tidak ada lagi. Diganti dengan acara lagu-lagu nasional." "Lo,lagu-lagu nasional. Hawaiian seniors tidak boleh lagi?" "Betul pak. Tapi buat bulan ini karena sudah direncanakan satu pengambilan rekaman, ya kita lakukan saja, tapi tidak akan diputar. Untuk disimpan Bapak saja." "Wah, terimakasih deh. Ndak usah saja. Saya mau tanya, mengapa saya tidak boleh tampil di TV?" Dia kikuk dan menjawab ngalor ngidul. Lalu saya bilang,"terus-terang saja, karena saya menandatangani Petisi 50 ya ?" "Wah,kok bapak tahu..." "Ya saya kan bekas polisi." "Bapak tidak marah pada saya kan?" "Saya tidak akan marah pada siapa-siapa." Tak lama kemudian, saya bertemu dengan Menpen Ali Moertopo di sebuah undangan. Ali Moertopo dan saya sudah kenal baik sejak revolusi. "Li, kenapa acara Hawaiian Seniors tak boleh tampil lagi di televisi?" Dia tidak memberi jawaban dan malahan merangkul saya. "Ala, wis mas, ora susah diomongke, wong wis sudah jadi fakta..." "Ya wis ora..." Jadi kita bicara soal perjuangan revolusi. Ali mengatakan, "mas nanti di Pekalongan akan diadakan suatu pertemuan reuni dari eks pejuang 45. Mas Hoegeng rawuh ya." "Lha saya ndak diundang toh..." kata saya. "Iya, diundang," kata Ali. "Ya tapi tahun lalu saya juga ndak diundang. Sejak saya menandatangani Petisi 50 saya ndak diundang lagi." Ali Moertopo terkejut dan diam. Lalu saya sambung, "sudah, ndak apa. Saya kan bukan pejuang, saya kan Petisi 50" Wajah Ali nampak kecut lalu saya tinggal saja. Keterlibatan saya dalam menandatangani Petisi 50 memang berakibat banyak, tapi rekanrekan penandatangan maupun saya tak pernah menyesali keputusan itu. Anggota Petisi 50 yang saya kenal baik sebelumnya adalah Ali Sadikin. Ketika kami mengeluarkan Surat Keprihatinan itu, saya kira kami tak menyangka bahwa akan membawa pengaruh yang berkepanjangan hingga sekarang. Banyak kesulitan saya menjadi penandatangan petisi 50. Ada seorang kawan dari Departemen Hankam yang mungkin kasihan pada saya yang penghasilannya tidak tetap sejak pensiun dari Kapolri. Suatu hari kawan saya itu datang. "Mas Hoegeng, ini ada seorang kawan yang mau mantu. Dia ingin memberikan hadiah pada bakal mantunya, sebuah lukisan. Ia ingin Mas Hoegeng yang melukis." Maka orang yang ingin lukisan itu, seorang pengusaha, diantar kawan saya ke rumah. Ia menginginkan sebuah lukisan besar yang menggambarkan Kintamani di Bali dan diselesaikan pada tanggal 17 Agustus. "Wah, itu hanya satu setengah bulan, saya tak tahu bisa atau tidak," jawab saya. Tapi saya kemudian berjanji mencoba sebisa saya. Persoalan lain yang saya kemukakan adalah, saya sudah lama sekali tak ke Kintamani sehingga saya sudah lupa bagaimana panoramanya kini. "Jangan khawatir Pak, saya punya fotonya..." Akhirnya saya melukis berdasarkan foto tersebut. Saya menyelesaikannya tepat tanggal 17 Agustus. Saya segera menelepon pemesannya. "Pak, lukisan ini sudah selesai. Tapi harap dilihat dulu apakah bapak menyukainya atau tidak," kata saya. Ia segera datang dan sangat menyukainya. Saya tidak menentukan harganya dan membiarkan pemesannya saja yang mengirangira sendiri harganya. Setelah mengamati seluruh lukisan yang ukurannya besar itu, tibatiba ia terkejut melihat tandatangan saya di pojok lukisan. "Wah, pak, ini kok ditandatangani oleh Hoegeng ? Tanggalnya sudah betul, tapi kok tandatangannya Hoegeng?" "Lha,kenapa sih? Ini kan yang bikin memang saya ?" jawab saya. "Nanti saya dikira hubungan dengan Petisi 50." "Jadi,anda mau nama Hoegeng ini diganti nama lain?" "Iya pak..." "Wah, ya ndak mau saya. Biarlah ndak jadi saja...." Dalam Petisi 50 kami semua punya pandangan yang sama, cuma yang satu bisa meledak, yang lain bisa ditahan. Biasanya mas Brata almarhum sering menjadi 'rem' mas Ali kalau sedang meledak. Setelah mas Brata almarhum, saya menggantikannya untuk ikut rapat Kelompok Kerja setiap Selasa. Sebetulnya dalam rapatrapat itu kami membicarakan masalah politik secara umum seperti halnya warganegara lain lantas memutuskan apakah kami harus bersikap atau menulis surat. Dulu, yang pandai menyusun adalah mas Brata. Kami kehilangan kehadiran mas Brata, selain orang yang pandai, masa Brata adalah kawan yang baik. Orang menganggap saya nekad karena terus menerus bergabung dengan Petisi 50 yang dianggap barisan di luar sistem. Kami semua tahu tantangan untuk berani bicara di negeri ini sungguh besar, tapi kami akan jalan terus. Kawan saya pernah mengatakan saya terlalu jujur dalam menjalankan segala sesuatu. Mungkin itu benar. Contohnya ketika terjadi Operasi Sapu Jagat yang mengharuskan kaum sipil ataupun eks tentara atau polisi menyerahkan senjata. Dulu saya memiliki banyak senjata, meski kebanyakan senjata kenang-kenangan yang lebih digunakan sebagai dekorasi. Misalnya, senjata saya bekas revolusi, lalu ada yang saya dapat dari Kastaf Prancis, sebuah senjata dari Kepala Polisi Jakarta Pertama (pak Ating) dan senjata dari Jerman dan Belanda. Ada dua senjata yang biasa saya pakai ketika saya memegang jabatan Kapolri, yakni Colt dan Mauser. Semuanya saya serahkan ke polisi karena saya ingin mematuhi "Operasi Sapu Jagat". Belakangan, saya sedih juga karena saya tahu dari kawankawan bahwa senjata kenangkenangan itu bisa saja disimpan. Temanteman lain sampai bilang saya terlalu jujur dan bikin rugi. "Ndak perlu dikasih semua, yang hadiah itu kan buat kenang-kenangan. Yang penting jangan ada pelurunya." Sekarang saya betulbetul tanpa senjata, totally disarmed. PEKERJAAN SAYA SEHARIHARI Di usia yang sudah 70 tahun, saya tetap bangun pukul 03.15 setiap pagi. Lalu saya membuka semua jendela, lantas olahraga sepeda. Olahraga ini saya tingkatkan terutama setelah saya terserang lichte stroke dua tahun silam dan sampai dirawat di rumah sakit Polri. Setelah shalat saya menuju jalan Jambu dan jalan Usaha, itu rumah anakanak saya. Saya antarkan cucucucu saya ke sekolah. Lalu saya mendengarkan radio Hilversum yang menyiarkan beritaberita Indonesia sambil saya rekam untuk keperluan diskusi Petisi 50. Biasanya rekaman itu memakan waktu dua jam. Setelah makan siang dengan isteri saya, saya beristirahat sedikit. Sorenya saya mendengarkan lagi Australian Broadcasting System. Dari kedua siaran itu, saya menganggap siaran Australia kebanyakan mementingkan kepentingan Australia sendiri. Di waktu senggang dan kalau sedang mood, saya biasa melukis. Ini kegemaran saya sejak kecil. Kebetulan isteri saya juga senang melukis. Kami sering melukis sama-sama dan bernyanyi bersama. Obyek saya bisa pemandangan, wanita, anggrek, apa saja. Biasanya saya sket dulu objeknya,lalu saya melukis. Satu lukisan bisa saya selesaikan dalam satu bulan jika sedang mood dan intens. Pernah saya melukis seorang wanita, dan saya bikin sket wajahnya, tapi tubuhnya saya bikin lukisan wanita itu dengan blus terbuka hingga baju dalamnya kelihatan. Waduh, dia marah. Kegemaran saya yang lain adalah bersenda gurau dengan binatangbinatang peliharaan saya. Sekarang saya memiliki duaburung kakaktua jambul kuning, ayam kate dan puluhan burung lainnya. Dulu saya memiliki tiga orang utan. Yang diberi Pak Domo saya namakan Soedomo, lalu satu lagi saya namakan Sri Utaningsih. Ketiga orang utan itu bertahuntahun saya pelihara dan selalu berpelukan dengan saya. Mereka sangat manja pada saya. Waktu pemilu, kami bikinkan baju dengan tulisan Golmon (Golongan Monyet). He, dia lepas sampai dikejar-kejar polisi dan masuk rumah gedongan. Dengan enaknya dia nyemplung ke kolam renangnya, jluung... Ternyata keluarlah peraturan bahwa binatang-binatang seperti itu harus dikembalikan ke hutan dan saya patuh, meski hati saya sedih. Ketika mereka harus disuntik, saya tak tega melihatnya, maka saya pergi saja dari rumah. Sedih sekali. Kesedihan melepas ketiga orangutan ini jauh lebih dalam daripada ketika saya harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai Kapolri. Tapi saya harus mengingat kepentingan mereka bahwa mereka memang lebih baik di hutan. Yang bikin saya mangkel adalah, pernah saya melihat beberapa monyet di airport, katanya, milik beberapa menteri. Jadi, menteri pun banyak yang melanggar peraturan. Saya semakin sedih. Kehidupan kami memang sederhana karena kami hidup dari pensiun dan hasil jual lukisan. Saya tidak berbisnis karena tidak bisa. Dulu, saya ditawari kedudukan oleh sebuah maskapai, tapi saya tolak. Syukur alhamdullilah anak isteri saya mengerti kehidupan saya yang pas-pasan. Mereka tidak tergiur rekan-rekan saya yang hidup mewah. Mery dan saya mengisi masa tua kami dengan menyanyi dan melukis bersama. Yang penting, kami selalu hidup berdasarkan nurani. Leila S.Chudori
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini