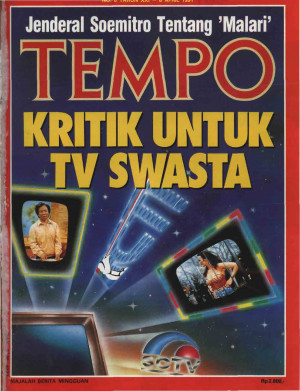Jenderal (purnawirawan) TNI AD, yang lahir di Probolinggo 13 Januari 1927 ini menyatakan bahwa pada tahun 1933, generasi pengganti-pengganti akan bermunculan. Ia pernah menjabat Panglima Kalimantan Timur. Berbagai jabatan penting pernah dipangkunya. Terakhir sebagai Panglima Kopkamtib Wapangab. Sempat melangit pada masa peristiwa Malari. Ketika hendak dijadikan dubes AS, ia memilih mengundurkan diri. Beliau kini menjadi pengusaha dan pembaca Alvin Toffer yang mengaku selalu optimistis. Sebagian riwayat hidupnya di bawah ini dituturkan kepada Leila S. Chudori atas permintaan TEMPO. DI LAPANGAN Golf yang hijau membentang, saya mencoba berkonsentrasi. Tiba-tiba, seorang kawan mengatakan "tembak!" Menggelegak hati saya. "Saya tidak bisa menembak! entak saya. Kata 'tembak' itu milik masa lalu saya. Saya bukan tentara lagi. Dan kata itu seolah bertentangan dengan batin saya. Pada dasarnya, saya adalah orang yang lebih suka melihat ke depan. Saya sangat senang meramal apa yang akan terjadi dalam tingkat mikro maupun makro. Itulah sebabnya saya suka membaca buku-buku Alvin Toffler. Dalam melihat apa yang akan terjadi, saya juga memilih bersikap optimistis. Misalnya pada tahun 1993 nanti akan muncul generasi pengganti-pengganti yang masih segar dan muda. Generasi yang sekarang sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kehidupan konstitusional telah dikembalikan, kita selamat dari PKI, toleransi beragama diciptakan, dan stabilitas nasional dipertahankan. Pak Harto sudah sangat berhasil menciptakan itu semua. Menurut saya, generasi yang akan mengisi tahun 1993 nanti harus mulai berani terbuka dan bersiap diri. Ini sudah zamannya exercise dengan otak dan intelektual, bukan dengan otot lagi. Kita harus berani keluar dengan visi dan persepsi baru. Jika saya menengok kembali setelah 64 tahun, saya mengalami begitu banyak pengalaman baik yang manis maupun yang penuh penderitaan. Saya sudah mulai tua dan saya tidak ingin dihadapi masalah hidup lagi. Dan saya tak pernah menyesali apa yang pernah terjadi .... Suatu saat sebelum Agresi Belanda I, tahun 1947, saya duduk-duduk di bawah pohon kopi di perkebunan Kertosastro, di Dampit, Malang Selatan. Bersender sembari memejamkan mata. Wajah ibu saya berkelebat terus. Tanpa saya sadari, saya mengucapkan, "Ibu sudah tidak ada ...." Ketika ada keputusan gencatan senjata, saya ke Probolinggo. Dan baru saat itulah saya ketahui bahwa Ibu betul-betul sudah tidak ada. Rupanya, beliau meninggal karena mendengar berita-berita yang menyusahkan hatinya. Ibu saya mendengar bahwa kakak lelaki saya satu-satunya, Mas Mudji, terpegang Belanda. Menyusul lagi berita yang sengaja dilontarkan oleh Belanda bahwa saya gugur. Ternyata, justru Ibu yang meninggalkan kami semua. Saya, Mas Mudji serta ayah saya Sastrodiardjo hingga kini masih hidup. Sebenarnya, ibu saya, Meilaeni pernah punya keinginan agar saya menjadi dokter. Tak ada yang pernah membayangkan bahwa saya akan terjun ke militer. Ayah saya bekerja sebagai kasir kepala pabrik gula Gending. Dan memang saya lahir di pabrik gula Gending, Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kawedanan Gending, Kabupaten Probolinggo, Malang, pada 13 Januari, 64 tahun silam. Saya sangat mencintai ayah saya. Karena itu, pada tahun 1967 ketika usianya mencapai 67 tahun saya memintanya pensiun karena sudah waktunya beliau istirahat. Lantas, kegiatannya di Partai Nasional Indonesia (PNI) juga saya usulkan agar dihentikan. Soalnya, saya khawatir, jangan-jangan setua itu dia akan "dipakai". Dan ayah saya nurut. Sampai hari ini, ayah saya masih segar bugar, lo, bulan Juni mendatang usianya 91 tahun. Zaman Jepang Waktu kecil, saya pernah bercita-cita menjadi insinyur. Tapi, ketika saya berusia 16 tahun, ada sesuatu yang "membelokkan" perhatian saya. Ketika itu, Jepang baru masuk. Bersama Gatot Supangkat, kawan pondokan, saya iseng-iseng main jailangkung. Pertanyaan pertama yang saya lontarkan adalah, "besok saya akan jadi apa?" Sang jailangkung menunjuk huruf-huruf M, A, J, O, R .... ha, ha ..... ha. Maklumlah, masa kecil saya di desa, dan kota penuh dengan perkelahian. Pak Domo (Menko Polkam -- Red) sering melihat saya berkelahi, soalnya kami kawan sekolah di Probolinggo. Ya, namanya garis hidup, saya betul-betul jadi tentara. Semuanya mengalir begitu saja. Saya mendengar ada permintaan menjadi perwira pembela sukarela yang kita kenal sebagai Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (Peta). Wah, namanya saja sudah menarik buat saya. Bersama kawan-kawan saya di Probolinggo, saya mendaftar dan dites mulai dari ujian di Probolinggo, Malang, hingga Surabaya untuk diperiksa kesehatan. Akhirnya kami beramai-ramai ke Bogor untuk jadi Peta. Pada zaman sekolah di Bogor itu saya merasakan betapa keras dan disiplinnya pendidikan Jepang. Hukuman yang kami dapatkan terjadi secara kolektif. Selain itu, kami selalu ditekankan untuk cinta kepada bangsa dan diiming-imingi untuk merdeka. Secara militer, kami dilatih bertempur mulai unit yang kecil hingga tingkat komandan batalyon. Saat itu, saya terkenal paling nakal dan sering keluar pagar asrama untuk cari makan. Ha, ha, ha .... Saya tak akan lupa ketika dihukum karena pernah bikin ramai dengan intelijen Jepang. Waktu itu saya mau ke Leces 'nengok pacar saya. Saya mau beli karcis di stasiun. Karena saya tentara, saya ndak usah antre, saya sudah bawa jiosaken (karcis kereta api). Tiba-tiba, ada yang menegur dari belakang "Saudara kan pemimpin. Lihat yang lain antre ...." Wuah! Muarahnya saya ... saya hantem dia. Saya tonjok dia! Lantas kawan saya melerai kami. Setelah itu, saya mendapat panggilan dari kenpentai. Saya tanya pendapat kawan-kawan saya, "kalau saya ndak bisa kembali, gimana?" Kawan-kawan menjawab, "berontak!" Lantas saya menelepon ayah saya untuk minta doa. Saya pun dijemput dan ditanya oleh kenpentai. Saat itu, saya masih fasih berbahasa Jepang. Mereka menanyakan, kenapa saya berbuat seperti itu. Saya jelaskan bahwa saya tersinggung. "Saya seorang perwira, dan dia seorang bintara Jepang. Kok beraninya kurang ajar pada saya di muka bangsa Indonesia. Karena itulah saya memukul dia." Lo, kok pemimpinnya malah menyukai saya. Dia ndak jadi marah. Waktu pulang, saya dikasih rokok KOA. Wuah, rokok itu dari Jepang dan sangat enak, lo. Ha, ha, ha .... Ternyata Daidancho saya sangat akrab dengan kepala kenpentai Sayang, saya ndak bisa bahasa Jepang lagi. Ketika Jepang jatuh, saya berusaha melupakan bahasa itu, sebab saya benci sekali dengan perlakuan mereka. Kepala Intelijen Selama perjuangan melawan Belanda ketika Clash II, konsep perang yang diinstruksikan oleh Panglima Komando Jawa, Kolonel Nasution, untuk menghadapi serangan Belanda adalah taktik Wingate. Ini sebuah strategi yang ditemukan oleh Jenderal Wingate dari Burma. Yakni menerobos, menyerang di sela-sela serangan musuh, dan masuk ke daerah belakang musuh. Dan kami juga melaksanakan perang wilayah atau webrkreise stelsel dan taktik gerilya. Selama perjuangan itu saya tak pernah ditahan. Syukur alhamdulillah, saya juga ndak pernah luka. FDR baru saja memukul kita tahun 1948. Saya ingat, ketika saya menjabat Wakil Komandan Sub Wehkreis II di Pujon, Malang Barat, kami pernah menangkap pelarian FDR (Federasi Demokrasi Rakyat) II. Saat itu saya sudah berpangkat kapten. Sebenarnya komandan kompi kami mau menembaknya saja, soalnya kami tahu bagaimana pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan komunis di Madiun. Saat itu, istilahnya mati harus ditebus mati. Tapi ketika mau ditembak, ternyata dia lari entah ke mana. Di kemudian hari saya bertemu dengannya lagi. Di masa gerilya, saya masuk ke daerah pendudukan Belanda dengan menyamar. Nah, sebelum Serangan Malang I, saya diundang ikut rapat kaum buruh. Rapat tersebut terletak di gedung Taman Siswa di Sawahan yang terletak di muka RS Lafayette. Sementara itu, di belakang RS Lafayette adalah markas Brigade X Belanda. Dengan mengenakan piyama, peci, dan sarung, saya ke gedung itu dengan mengendarai bemo. Di saku saya ada KTP dengan nama Tasrin, nama samaran saya, dengan alamat Desa Selokerto. Tiba di gedung, saya kaget. Orang FDR yang dahulu hampir ditembak komandan kompi saya itu ada di sana. Melihat saya, dia mau lari lagi. Tapi saya cegah. "Jangan lari. Kita menghadapi musuh yang sama. Kita seperjuangan melawan Belanda." Akhirnya dia tak jadi lari. Rapat itu dipimpin oleh bekas Komandan Brigade XIII, Kolonel Zaenal Alimin. Ia menjelaskan bahwa dia memimpin kota Malang, dan menguasai kaum buruh. Tujuan rapat, selain menjelaskan adanya organisasi yang dipimpinnya, juga ada janji dari kaum buruh kalau kita, TNI, mengadakan serangan kota Malang, kaum buruh akan membantu. Umpamanya kaum buruh anim (sekarang PLN) akan memblackout Malang. Tapi setelah serangan dilaksanakan, janji itu tak dipenuhi. Selain itu Alimin menjelaskan bahwa dia sudah mempunyai kelompok-kelompok yang ditempatkan di desa-desa di sekeliling Malang. Saya langsung curiga bahwa kelompok tersebut dari FDR yang menyusup kota. Saya sadar betul bahwa Alimin agak kekiri-kirian. Tapi saya tenang saja, wong pasukan ada di belakang saya. Dia kan ndak punya pasukan. Kemudian saya bertanya apakah semua desa yang katanya sudah di tangan mereka itu punya intelijen. Mereka jawab ndak. Wuah, saya bilang, intelijen itu penting di daerah pendudukan. Kalau ndak ngerti, hancurlah kita. Maka, orang pun meminta saya menjadi kepala intelijen. Saya pun minta diperkenalkan kepada orang-orang desa tersebut. Pada saat itu, kami semua bekerja sama melawan Belanda. Tapi pada saat yang sama saya juga mengeliminir kelompok-kelompok yang saya anggap bisa menjadi pengganggu sesudah perang, macam GRK (Gerakan Rakyat Kota) Malang, FDR, dan TPRI (Tentara Pembebasan Rakyat Indonesia). Artinya, saya melucuti senjata mereka saja. Persis sebelum perang selesai, saya diangkat menjadi Komandan Batalyon I di Malang. Saya segera membersihkan seluruh Kota Malang. Orang-orang GRK dan FDR itu saya lucuti senjatanya atau saya bubarkan mereka semua. Kenapa? Karena mereka adalah kekuatan-kekuatan yang tidak teratur. Memang kami pernah bertempur bersama melawan Belanda, tapi sesudah perlawanan dengan Belanda usai, saya menganggap harus hati-hati terhadap mereka. GRK, FDR, dan lain-lainnya adalah kekuatan-kekuatan yang tidak termasuk ke dalam organisasi ketentaraan. Suatu ketika di tahun 1951, Mayjen. Bambang Sugeng memanggil saya ke kantornya. "Kapten, kalau saya serahi tugas untuk menyelesaikan keamanan di daerah segi tiga Sidoarjo, Mojokerto, dan Pasuruan, kamu butuh berapa lama?" tanyanya. Karena begitu senang dengan kepercayaan ini, saya spontan menjawab, "Enam bulan!" Lo! Saya kaget sendiri. Kok berani-beraninya bilang enam bulan. Batalyon lain gagal menangani daerah ini. Maka, saya pun berpuasa selama enam bulan. Kami semua berhasil memegang kepala gerombolan itu. Senjatanya saya rampas. Tercapailah semuanya. Kebetulan, saat itu, Bung Karno pindah dari Sidoarjo ke Pasuruan. Saya dipanggil Komandan Brigadir Abimanyu untuk menghadap Bung Karno di Pasuruan. Di situlah, pertama kalinya, saya bertemu dengan Bung Karno. Dia mengucapkan terima kasih. Betapa bahagianya hati saya. Peristiwa 17 Oktober 1952 Saat sebelum Peristiwa 17 Oktober 1952, saya dan beberapa kawan kebetulan sedang ikut pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) Angkatan I. Kami sedang sibuk latihan manuver di Bogor Selatan ketika mendengar ada peristiwa tersebut. Lantas kami ditarik ke asrama di Jakarta. Mayor Rusman -- yang berasal dari intelijen dan mengerti peta politik Indonesia saat itu -- memberikan kami brifing bahwa petisi perwira Gerakan 17 Oktober itu isinya menentang Bung Karno. Seingat saya, orang Jawa Timur, baik sipil maupun militer, mendukung Bung Karno. Saya pribadi menganggap, kok, tentara sudah mulai berpolitik. Saya menganggap bahwa kami semua adalah tentara profesional. Kami berasal dari Peta, bukan mahasiswa atau anak sekolahan. Kami adalah elitenya. Jadi, peristiwa semacam itu -- yang sudah melibatkan tentara dalam politik -- kami tentang. Karena menentang, pasukan Resimen VII di bawah pimpinan Kemal Idris sempat mau menggrobyok rumah kami. Malam itu, kami kebetulan sedang rapat tim Jawa Timur yang dihadiri oleh Mayor Minggu -- ketua -- Mayor Rusman, Mayor Bambang, Kapten Siswadi, Kapten Bowo, dan saya. Ketika gerombolan itu datang, eh, mereka salah alamat. Yang digrobyok malah rumah di muka rumah kami. Wuah, ya, kami lari ke kebun karet dan bersembunyi sampai pagi. Esoknya, saya diperintah Mayor Rusman untuk melapor ke Letkol. Abimanyu di Jawa Timur. Mayor Rusman menceritakan bahwa ia baru saja diberi brifing oleh Kolonel Suwondo, yang isinya: membenarkan petisi dan menyalahkan Bung Karno. Jadi, saya pun keluar dari tempat persembunyian dengan mengenakan pakaian preman. Dalam perjalanan menuju rumah saya yang dulu, di daerah Mayestik, sebuah patroli menyetop saya. "Saya mau berangkat kerja, Pak," kata saya. Aman. Saya berhasil menemui istri saya yang sedang mengandung anak kami yang kedua pada saat itu. Saya ceritakan semua permasalahannya dan saya pamit ke Ja-Tim. Di Ja-Tim, saya laporan kepada Letkol. Abimanyu. "Dik Mitro," kata Letkol. Abimanyu, "kalau sampai terjadi kup, Dik Mitro saya beri tiga batalyon supaya dipimpin masuk ke daerah Jakarta Raya untuk membela pemerintah pusat". Nah, malamnya, saya berkunjung ke rumah Pak Abimanyu. Lo, kok, saya lihat ada Kol. Soewondo di sana. Lebih hebat lagi, Kol. Soewondo bercerita versi lain soal petisi itu. Ia menunjukkan seolah-olah dia tak turut serta dalam gerakan petisi. Padahal, saya kan baru dapat brifing dari Mayor Rusman bahwa Kol. Soewondo membela petisi itu. Wuah, saya ndak tahan dengannya. Dengan kasar, saya bilang, "Kolonel seorang kolonel, tapi kok mencla-mencle mulutnya." Kami bertengkar mulut. Tapi, saya tetap hormat kepadanya karena dia atasan saya. Akhirnya, Kol. Soewondo keluar rumah Pak Abimanyu. Di luar, sudah ada pasukan bekas batalyon saya, Batalyon 512 dengan Komandan Resimen Surabaya Letkol Surachman. Akhirnya, Kol. Soewondo kami tahan dan digantikan Pak Dirman. Belakangan, Kol. Soewondo dibebaskan juga. Saya tinggal selama sebulan di Jawa Timur karena takut dipegang oleh Siliwangi. Ha .... ha ..... ha .... Tak lama kemudian, datanglah telegram dari ketua tim Mayor Minggu, yang ditulis dalam bahasa Belanda: "Mitro, lekaslah kembali ke Jakarta, kita menghadapi ujian akhir. Ini kesempatan terakhir, kalau tidak, Anda tidak lulus." Saya laporan ke Pak Abimanyu soal telegram ini. "Silakan Dik Mitro kembali ke Jakarta, kalau sampai Dik Mitro terpegang, kami akan ke sana," kata Pak Abimanyu memberi jaminan. Jadi, saya mendapatkan gambaran bahwa pendapat umum di Jawa Timur menyimpulkan bahwa yang menggerakkan Peristiwa 17 Oktober 1952 itu adalah Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan sekjennya Ali Budiardjo, S.H. Selain itu, kalangan militer dan sipil Ja-Tim juga beranggapan bahwa Jenderal T.B. Simatupang dan Kemal Idris sangat dekat dengan PSI. Militer di Ja-Tim sendiri punya dua praduga. Pertama, PSI adalah partai yang menganggap bahwa jika mereka menguasai elite teratas, mereka akan diikuti oleh rakyat. Kedua, PSI adalah partai yang senang lempar batu sembunyi tangan. Pada umumnya, kami menilai Jenderal Nasution bukanlah orang partai. He is a professional soldier. Tapi ia toh bersedia bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan berhenti dari jabatannya. Setelah ia berhenti, saya malah melihatnya menghadiri upacara penutupan rapat perwira rekonsiliasi antara militer Jawa Barat dan Jawa Timur (Kodam Siliwangi dan Brawijaya) yang diselenggarakan di Yogyakarta. Ia datang dengan mengenakan baju sipil. Aduh, saya terharu dan makin hormat kepadanya. Itu menunjukkan betapa kesatrianya Pak Nasution. Pak Sim, kok, malah ndak datang waktu itu. Kalau saya ditanya pendapat pribadi saya tentang peristiwa ini, saya betul-betul tak tahu siapa yang menggerakkan. Harus mereka sendiri yang mengakuinya. Panglima Kalimantan Timur: Tahun 1958, saya mengikuti Sekolah Lanjutan Perwira II (Regular Officer's Advance Course) di Fort Benning, AS, selama 11 bulan. Satu hal yang mengesankan saya tentang masyarakat Amerika adalah mereka sangat kritis dan pandai berargumentasi. Tapi, menurut ukuran Timur, sikap mereka agak kurang ajar terhadap atasan. Di Jerman, saya juga mendapatkan kesempatan pendidikan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Fuerungs Akademie der Bundeswehr, Hamburg, selama dua tahun. Saya perhatikan bahwa orang-orang Jerman adalah bangsa yang punya watak dan sudah mapan. Mereka sangat disiplin dan perfeksionis dalam mengerjakan segala sesuatu. Saya ingat, meski para perwira muda sering mengolok perwira tua jebolan Perang Dunia II dengan sebutan Nazi, sesungguhnya anak-anak muda ini memiliki tingkat kedisiplinan yang sama dengan yang tua. Dan dari pengalaman tersebut, saya merasakan bahwa budaya nasional kita belum mapan. Karakternya sangat tidak jelas. Sepulang dari Jerman, saya bermaksud untuk ngumpul dengan keluarga yang telah lama saya tinggalkan. Beberapa kali saya diminta jadi panglima. Mayjen Pranoto, asisten personil Menpangad, mengusulkan saya agar jadi Panglima Ir-Ja. Saya menolaknya. "Saya sudah puas dengan jabatan saya. Banyak yang antre pengin jadi panglima. Saya puas jadi ketua harian dewan perencanaan AD," jawab saya. Bukannya apa-apa, saya juga sedang riung dengan keluarga dan anak tertua yang baru dikhitan. Tulang belakang saya menderita slippeddisc, yakni tulang belakang yang keluar dan kena urat. Sakitnya setengah mati, hingga jalan saya masih miring-miring menghindari sakit. Sesudah acara khitanan anak saya, tiba-tiba saya dipanggil Jenderal Yani. Dengan pinggang yang masih miring, saya ke rumahnya, karena ia tak ada di kantornya. Ternyata, di sana sudah ada Mayjen. Panggabean, Kol. Hardiman (Ketua SOKSI), Brigjen. Taswin, dan Ibu Yani. Dalam pertemuan itu, sambil bergurau, Jenderal Yani berkata kepada istrinya dalam bahasa Jawa, "Bu, Bu, lihat Mitro ..... perutnya perut panglima." Wah, kuping saya jadi merah. Kok ngomongin panglima. Betul juga. Mas Yani berkata, "Mit, kamu pergi ke Balikpapan, gantikan Haryo." "Ini perintah atau masih tanya pendapat?" tanya saya. "Perintah," jawab Mas Yani. Namanya prajurit, ya, harus menurut perintah. Hidup prajurit itu ditentukan oleh perintah. "Ya, sudah, apa boleh buat, saya laksanakan," jawab saya. Dan tidak saya ceritakan penderitaan di pinggang saya itu. Memang sudah lama kami di Jakarta mendengar bahwa Brigjen. Suharyo yang jadi panglima di Kalimatan Timur itu terlalu dekat dengan PKI. Saya juga mendengar bahwa setiap kali Haryo ke Jakarta, dia keluar masuk Istana tanpa diketahui Jenderal Yani. Ini artinya dia cukup dekat dengan Bung Karno. Saya pun berangkat ke Balikpapan. Di lapangan terbang, Brigjen. Haryo merangkul saya erat-erat. "Waduuuh," katanya, "saya bahagia sekali akan diganti kawan saya sendiri." Dan dia memang tak basa-basi. Kami memang kawan. Waktu zaman gerilya dulu, saya komandan batalyon di Malang dan dia komandan Korps Mahasiswa. Pada saat timbang terima untuk menjadi Pangdam IX Mulawarman, Mas Yani ndak bisa datang, maka Pak Harto sebagai Pangkostrad datang sebagai inspektur upacara. Inilah pertemuan saya yang pertama kalinya dengan Pak Harto karena sebelumnya saya memang belum pernah jadi bawahannya langsung. Saya hanya sering mendengar bahwa Pak Harto adalah orang yang tenang, sederhana, berwibawa, dan tidak suka rame-rame. Dengan jalan yang masih termiring-miring karena sakit pinggang, saya ikut dalam upacara pemeriksaan barisan. Ketika defile dimulai, tiba-tiba saya melihat ada spanduk besar yang bertuliskan: "Selamat jalan, Bapak Brigadir Jenderal Suharyo". Di belakangnya ada yang membawa spanduk. "Selamat datang, Saudara Brigadir Jenderal Soemitro!" Wah, kok ini ada "bapak" dan ada "saudara". Tapi saya diam saja. Malam hari, mereka mengadakan pesta perpisahan yang besar di aula yang dipenuhi tamu undangan. Saya ingat, hampir empat jam Haryo berpidato. Sedikit-sedikit para tamu bertepuk tangan dan bersorak. Entah bagaimana, saya merasakan suasana PKI di situ. Tiba-tiba, di tengah pidatonya, Haryo berkata, "Sebenarnya saya masih ingin lebih lama di sini. Tapi orang Jakarta tidak mengerti revolusi." Bukan main terkejutnya saya. Apa-apaan ini? Apalagi ketika Ketua Front Nasional mereka juga ikut-ikutan memberi pidato sambil berkata, "Bapak Suharyo, Saudara Soemitro ...." Saya menyikut Kastaf Kodam Kolonel Sukadyo. "Dyo, dari partai mana orang ini?" "Dari PNI," jawab Sukadyo. Saya diam menahan marah. Dalam batin, saya mengatakan seandainya saya gebuk dia, PNI bisa hancur di Kalimantan Timur. Saya merasakan betapa kuatnya ke-Nasakom-annya PNI. Akhirnya saya memberi kata sambutan yang hanya lima menit panjangnya. "Saya belum kenal Saudara dan Saudara-Saudara belum kenal saya. Saya tidak ada keistimewaan dan kemampuan khusus. Yang ada hanyalah keinginan mengabdi pada daerah." Esok paginya, Haryo dan saya bertemu di tempat penginapan Pak Harto di Shell Guest House. Begitu ketemu di ruang depan, saya ndak bisa menahan diri lagi. "Katanya kamu senang diganti kawan sendiri. Kenapa kamu pidato begitu lama dengan mengatakan kamu masih ingin di sini. Berapa tahun kamu sudah bicara di sini? Lalu, apa maksudmu mengatakan orang Jakarta tak mengerti revolusi. Kamu masih prajurit atau tidak? Kamu pandai menembak tapi kamu tidak punya pengalaman perang. Buat saya, pergantian komandan bukan hanya sekali dua kali. Kemaruk kamu!" Kata-kata saya memang pedas karena saya sangat sakit hati. Sementara kami bertengkar, Pak Harto ada di dalam. Saya tak tahu apakah beliau mendengar pertengkaran ini atau tidak. "Lho, jangan marah," tanya Haryo. "Ndak. Saya sakit hati." Karena kawan, persoalan itu selesai. Malah dia meminta agar saya berbicara baik-baik tentang dirinya di depan Jenderal Yani. Sebenarnya, seingat saya, Haryo bukan terlalu dekat dengan PKI seperti yang diduga banyak orang. Dia dekat dengan PSI. Saya yakin, sebenarnya dia bukan PKI. Minggu-minggu pertama saya menjabat panglima di Kalimantan Timur, tak meluncur dengan mulus. Ada-ada saja yang ngrasani saya. Misalnya Ketua PKI di Balikpapan mengatakan saya seorang jenderal yang tak tahu revolusi dan dicap jenderal kanan. Wuah, saya panggil orangnya. Sayang, saya lupa namanya. Yang jelas, saya bilang, "Kalau sampai sekali lagi kamu mengucapkan begitu, kamu tahu akibatnya." Pernah ada satu insiden lagi pada hari Kartini. Saat itu, seperti biasa, hari Kartini dirayakan dengan resepsi dan berbagai pertunjukan. Tiba-tiba, seorang wanita muncul di panggung dan membacakan sajak. "Ada jenderal yang kanan ...." dan seterusnya. Saya tersinggung betul, tapi saya diam saja. Esoknya, saya panggil panitia penyelenggara hari Kartini itu dan pembaca sajak tersebut. Ternyata, saya dengar wanita pembaca sajak itu adalah anggota Gerwani. "Sayang, Anda perempuan. Kalau Anda lelaki, sudah saya sobek mulut Anda. Apa salah saya pada Saudara?" Mereka diam saja, tidak menjawab. Pada tanggal 1 Mei, terjadi lagi insiden lain. Hari itu adalah hari Buruh. Wah, PKI di Kalimantan Timur kan kuat sekali. Ada SOBSI, Perbum, dan sebagainya, karena ada kilang minyak Shell. Sebuah rapat raksasa diselenggarakan dan saya menjadi pembicara terakhir. Ketika ketua SOBSI bicara, lagi-lagi disinggung soal "jenderal kanan yang tidak mengerti revolusi". Saya mendongkol betul. Saya lihat ada tiga perwira yang tertawa-tawa. Lalu saya naik ke podium. "Saudara semua bicara tentang revolusi? Waktu revolusi melawan penjajah ada di mana? Saudara-Saudara saat itu masih kecil, masih pesing, masih piyik. Apa yang kalian ketahui tentang revolusi? Kalau mau perang, ikut saya ke perbatasan. Jangan hanya mulut besar di belakang." Tiba-tiba ada yang teriak, "Bubarkan Murba!" "Siapa yang bicara itu? Keluar!" teriak saya. Lalu suasana kembali diam. Ketika acara selesai, saya memanggil Komandan Batalyon Infanteri Balikpapan dan Komandan CPM Letkol Murtiyono. Saya tanyai mereka apakah mereka sanggup melaksanakan perintah saya. Mereka bilang sanggup. Saya mengumpulkan semua perwira. Saya marahi semua. "Kalian memakai baju hijau, tapi kenapa jadi begundalnya PKI? Kamu, kamu, kamu berhenti!" Saya pecat tiga orang Komandan Batalyon dan Komandan Kodim Samarinda Letkol Sudjono Komandan Kodim Balikpapan Letkol Sukartono Asisten V Teritorial Letkol Rusmono. Mereka adalah yang menertawai saya ketika ketua SOBSI mengejek saya. Setelah itu, saya menangkapi semua pengurus PKI, Perbum, SOBSI, Gerwani, Pemuda Rakyat Wilayah Balikpapan saya tutup, termasuk lapangan udara serta pelabuhan. Saya ke Banjarmasin untuk melapor ke Panggabean. Panggabean dan saya kawan sangat baik. "Peng, saya menangkapi orang-orang PKI." "Apa lagi kamu, Mit," komentarnya. Panggabean menyuruh saya melapor ke Jenderal Yani di Jakarta. Jenderal Yani pun hanya berkomentar, "Apa lagi kamu ini." "Ya, saya disuruh jadi panglima. Tapi saya ndak mau dihina PKI. Kalau mau tarik saya, silakan ...,"jawab saya. "Ya sudah. Besok pagi, kita melapor ke Bung Karno." Esok harinya, kami diterima di ruangan kecil di belakang Istana. Kami diajak makan pagi bersama dengan Bung Karno. Selain Jenderal Yani dan saya, ada juga Chaerul Saleh yang saat itu menjabat sebagai waperdam, dan Saifudin Zuhri yang saat itu adalah menteri agama. Waktu itu Bung Karno sarapan dengan roti yang disiram madu Arab. Di sebelah piringnya terdapat satu seloki yang berisi berbagai obat yang warnanya aneh-aneh dan bentuknya kecil-kecil. Tiba-tiba Bung Karno bertanya, "Saya dengar Jenderal Mitro sering ngrasani saya .... Saya kaget "Ngrasani apa, Pak?" "Mengenai perempuan ....". "Oh, ndak pernah, Pak. Saya bisa merasakan tengkuk saya, saya bisa ngrogoh githok saya sendiri ..." "Oh, bagus, bagus ... " katanya. Lalu makan dilanjutkan lagi. Lo, tiba-tiba dia bertanya lagi, "Ngrasani apa, Jenderal Mitro?" "Saya tidak ngrasani. Saya cuma belajar dari kesalahan-kesalahan Bapak." "O, bagus, bagus," jawab Bung Karno lagi. Mendadak kaki saya diinjak Mas Yani. Aduh! Pasti maksudnya saya ndak boleh bicara lagi. Saya malah jadi bingung. Jadi, saya berbisik-bisik pada Mas Yani dalam bahasa Jawa, "Saya lapor ndak? Lapor ndak?" "Wis, menengo cangkenmu" (Tutup mulutmu!) jawab Jenderal Yani. Akhirnya saya tidak jadi melapor. Tapi perasaan saya mengatakan Bung Karno sudah tahu apa yang terjadi di Balikpapan. Peristiwa Gerakan 30 S-PKI Malam Jumat Legi, September 1965. Bersama Brigadir Jenderal Wahyu Hagono, kami ke perbatasan. Kami naik helikopter dan lantas naik motorboat. Karena hujan lebat, kami tertubruk di sana-sini, tapi akhirnya berhasil mencapai Tarakan. Paginya saya kembali ke Balikpapan. Yang menjemput saya adalah Kastaf Kolonel Sukadyo dan Asisten I Mayor Soedjarwo. Asisten saya melaporkan secara rinci apa yang terjadi di Jakarta. Saya menganggap, jangan mengambil keputusan dulu karena belum tahu siapa yang salah. Tapi sebenarnya, jauh sebelumnya saya ingat kata-kata Pak Jayusman, Asisten Intelijen Brawijaya. Ia mengatakan bahwa ada ancaman-ancaman PKI. Saya sendiri merasakan panasnya keadaan politik ketika saya menengok orangtua saya di Probolinggo. Di mana-mana ada demonstrasi dan gerakan massa PKI. Karena itu, ketika terdengar peristiwa Lubang Buaya, asosiasi saya langsung ke PKI. Kenapa PKI gagal dalam kup mereka? Secara teoretis, menurut saya, mereka bisa saja berhasil. Bayangkan, mereka dilindungi oleh Bung Karno secara pribadi. Setiap kali kami menghantam PKI, Bung Karno pasti menghantam balik dengan mengatakan "Nasakom-fobi komunisto fobi". Ya, siapa yang ndak takut pada Pemimpin Besar Revolusi pada saat itu? Kedua, mereka diberi landasan legalitas, yakni melalui konsep politik nasional Nasakom. PKI menguasai front nasional dari pusat sampai ke daerah. Dalam rangka kompetisi Manipol, rasanya tak ada satu partai pun yang bisa menyaingi PKI. Apalagi, secara teoritis, Nasakom dianggap sebagai perpaduan aspirasi berbagai aspek. Nyatanya, kompartementasi politik PKI lebih kuat. Saya kira, salah satu penyebab PKI bisa dihancurkan karena rasa esprit de corps AD sangat besar. Kami di AD berperang bersama, melarat bersama, dan menderita bersama. Kami dipojokkan terus-menerus selama PKI sedang berkuasa. Hal lain yang menyebabkan PKI gagal, karena mereka terlalu bernafsu buru-buru ingin memegang kekuasaan. Akhirnya mereka kalah. Saya ditarik ke Jakarta bulan November 1965 dari jabatan saya sebagai panglima di Kalimantan Timur dan diangkat menjadi Asisten Operasi Menpangad. Setelah Gerakan 30 September/PKI: Saat-saat sesudah peristiwa Gerakan 30 September itu, banyak sekali yang membuat saya berpikir. Buat saya Bung Karno memang punya karisma, seorang grand strategist, dan pemimpin ulung. Dia adalah salah satu genius politician yang saya kagumi. Tapi, namanya manusia, tentu saja ia tak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Beberapa kali, saya mengalami hal-hal yang mengejutkan selama Orde Lama. Misalnya, ketika suatu hari Mas Yani dan saya mengantarkan seorang kepala adat besar Dayak dari Long Alango. Ia ingin sekali ketemu dengan Bung Karno karena merasa ada yang penting untuk diutarakan. Kami semua diterima di beranda belakang Istana. "Bapak, saya datang kemari hanya untuk meminta tambahan garam, tembakau, ikan asin. Serta kami minta diberi pacul untuk bercocok tanam." Jawaban Bung Karno mengejutkan saya, "Saya tidak hanya memperhatikan daerah Saudara saja. Saya memperhatikan semua daerah dari Sabang sampai Merauke yang berpenduduk 140 juta orang". Ucapan itu betul-betul di luar dugaan saya. Pada saat itu pula, ada seorang perempuan muda membawa map berisi surat-surat yang harus ditandatangani. Saya semakin kaget. Betapa tidak? Perempuan itu berjalan jongkok di muka Bung Karno. Apa-apaan ini. Lantas, datang pula seorang anggota Lekra yang membawa foto-foto patung yang direncanakan untuk minta persetujuan Bung Karno. Patung itu sampai kini masih ada di muka markas AURI sedangkan yang di muka Bappenas sudah lama dihapus. Lo, anggota Lekra itu juga jongkok, dan Bung Karno dengan tenangnya menandatangani ini-itu. Betapa kecewanya saya melihat adegan-adegan tersebut. Bung Karno selalu menyatakan dirinya sebagai penyambung lidah rakyat. Kenapa permintaan kepala adat yang datang jauh-jauh dari daerah terpencil harus dijawab demikian? Apa, sih, ruginya untuk pemimpin besar seperti Bung Karno memberikan kata-kata yang menyenangkan orang daerah. Kan yang diminta hanya pacul, garam, ikan asin, dan tembakau. Hal lain yang membuat saya kecewa adalah adegan-adegan jongkok itu. Kenapa anak perempuan pembawa map dan anggota Lekra itu harus jongkok di mukanya, ya? Akhirnya saya berkesimpulan, Bung Karno sudah semakin tua. Saya melihat adanya divergensi antara cita-cita dan perbuatannya. Mungkin orang yang sudah semakin tua cenderung berbuat yang aneh-aneh. Tapi saya mencoba memahaminya. Orang yang semakin tua bisa menjadi matang atau bisa juga menjadi kekanak-kanakan. Tapi, biar bagaimana, Bung Karno adalah salah satu tokoh yang saya kagumi selain Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, dan Jenderal A. Yani. Sebelum Supersemar Lahir Suatu malam menjelang sidang kabinet, kami berkumpul di kamar Asisten I Sugiharto -- bekas jaksa agung -- mengadakan rapat. Saat itu Pak Harto menjabat sebagai Menpangad, dan saya menjabat Asisten II Menteri Panglima AD. Asisten III adalah H.R. Dharsono, Asiten IV dijabat Pak Hartono. Jabatan Asisten V dipegang Daryatmo dan asisten VII Alamsjah Ratuperwiranegara. Di dalam rapat diputuskan bahwa sejumlah menteri dari kabinet 100 menteri harus ditangkap. Tapi Bung Karno sendiri jangan ditangkap dan jangan sampai luka. Keputusan ini saya beritahukan kepada Sarwo Edhie, Komandan RPKAD. Tiba-tiba, esok paginya Alamsjah menelepon saya. Saat itu pasukan RPKAD sudah mengepung Istana untuk menangkapi 100 menteri. "Mit, saya baru dipanggil Pak Harto. Saya diperintahkan Pak Harto agar keputusan penangkapan 100 menteri itu dicabut." "Wah, ndak mungkin. Pasukannya sudah jalan." "Ya, terserah kamu, deh, Mit," kata Alamsjah. Pada saat itu saya kecewa dan sempat mau berhenti saja dari jabatan saya. Kenapa keputusan yang sudah keluar akan dicabut kembali? "Bu," kata saya pada istri saya, "kalau begini caranya, saya berhenti saja jadi tentara." "Kalau kamu berhenti, kita makan dari mana? Kita ndak punya apa-apa," jawab istri saya. Lalu saya jawab, "Ya, gampang, deh, Bu. Ada Amirmachmud dan Jusuf. Mereka kan selalu membantu." Kedua kawan ini memang selalu membantu bila saya sedang tidak ada uang. Akhirnya istri saya menyarankan saya ke Bandung untuk menenangkan diri. Saya pergi ke Bandung Rabu siang, dan Jumat sorenya, 11 Maret, saya sudah merasa agak tenteram. Tanggal 11 Maret itu bertepatan dengan hari ulang tahun istri saya. Weton-nya juga sama dengan weton istri saya, yakni Jumat Paing. Suatu siang sekitar pukul dua, Pak Harto memanggil saya ke kamar beliau. Sambil memegang buku hariannya yang berwarna merah, beliau bercerita tentang perasaan-perasaannya terhadap Bung Karno. Katanya, "Kalau saya berbuat begini, akibatnya bisa A, kalau saya tidak berbuat begini, akibatnya akan B ...." Di situlah saya merasakan bahwa Pak Harto sedang dalam keadaan dilematis. Saya mendapat kesan, Pak Harto ingin menjaga agar Bung Karno jangan sampai dilukai. Ia tidak ingin berbuat keliru terhadap Bung Karno. Mungkin Pak Harto khawatir perintah menangkap 100 menteri itu akan membuat pasukan bertindak terlalu jauh, terutama terhadap Bung Karno. Itulah sebabnya Pak Harto mencabut perintahnya. Menjadi Pangkopkamtib Pada 1969 saya diangkat menjadi Kepala Staf Hankam dan pangkat saya letjen. Tugas saya, mengadakan reorganisasi Hankam dan ABRI. Saya laksanakan dalam waktu kurang lebih enam bulan. Reorganisasi Hankam dan ABRI tak lepas dari proses denasakomisasi. Reorganisasi itu menghilangkan fungsi menteri dan menghilangkan fungsi komando dari menpangad, kembali pada kepala staf angkatan. Kemudian, jabatan tertinggi dalam ABRI adalah Menhankam/Pangab. Itu berarti menghilangkan fungsi politik, fungsi komando, akses langsung ke anggaran belanja, fungsi-fungsi teritorial di semua angkatan kecuali AD, fungsi intelijen di angkatan-angkatan -- semua ditarik ke Hankam. Selesai melaksanakan tugas, saya melapor ke Pak Harto. Dalam susunan baru itu nama saya tidak ada. "Lo, Pak Mitro mana?" tanya Ali Moertopo. "Ya, ndak usah mikirkan saya. Saya jadi penasihat militer senior Pak Harto saja. Saya tidak ingin jabatan apa-apa. Saya hanya ingin dekat dia." Eh, tiba-tiba keluarlah keputusan bahwa saya menjadi Wapangkopkamtib, jabatan yang dikreasi oleh Pak Harto. Waktu itu Pangkopkamtib dijabat oleh Pak Harto. Saya tidak ditanya dulu apakah saya mau atau tidak, ha, ha, ha .... Tahun 1970, pangkat saya naik menjadi jenderal. Sedangkan jabatan Wapangkopkamtib ini saya pegang hingga tahun 1971. Pak Harto memanggil saya lagi. Saya dinaikkan menjadi Panglima Kopkamtib dan merangkap Wakil Pangab. "Kamu pilih siapa untuk menjadi wakilmu?" Pak Harto menyodorkan dua nama, yakni Laksamana Sudomo dan Marsekal Rusmin Nuryadin. Saya memilih Laksamana Sudomo karena, di dalam pikiran saya, saya ingin mengembalikan kekuatan angkatan laut. Indonesia adalah negara archipelago. Jadi, angkatan laut dan darat minimal harus seimbang. Saya juga ingin Domo bisa punya kesempatan menjalin hubungan akrab dengan para senior AD sehingga, pada saatnya dia harus mengembangkan konsep AL, dia tidak perlu dicurigai orang AD. Buat saya, bekerja menjadi pembantu Pak Harto sangat menyenangkan. Saya belajar banyak darinya dan saya menganggap ia mempunyai intuisi yang kuat. Dia sering mengatakan tidak setuju tentang sesuatu tanpa menjelaskan kenapa ia tak setuju. Tetapi setelah lama berselang, saya mulai mengerti dan menemukan mengapa ia tak menyetujuinya. Percakapan dengan Pramudya Tahun 1973 saya berangkat ke Aljazair untuk ikut konperensi Nonblok. Waktu itu saya menjadi wakil ketua delegasi, sedangkan ketuanya adalah Adam Malik. Pada saat itu, saya sudah punya keinginan untuk melepaskan satu badge para tapol Buru. Saya ingin mengetahui sampai di mana kemampuan coverage pihak keamanan kita sampai di mana reaksi masyarakat sekitar terhadap PKI, dan saya juga ingin cari tahu apakah para tapol masih meneruskan ilusi komunismenya. Ketika saya dipanggil Pak Harto yang meminta saya berdialog ke kampus-kampus, saya sekaligus meminta izin untuk ke Pulau Buru dulu. Menurut saya, pada dasarnya tahanan politik tidak bisa terus-terusan ditahan. Indonesia kan bukan Rusia. Pak Harto menyetujui rencana saya. Saya pun mengajak para wartawan senior dari berbagai media massa, antara lain Rosihan Anwar, Mochtar Lubis, dan Jakob Oetama. Saya juga mengajak tim psikologi dari UI yang diketuai oleh Prof Dr. Fuad Hassan dan salah satu anggotanya adalah Saparinah Sadli. Tim psikologi ini gunanya untuk mempelajari psikologi para tahanan, cara mereka berpikir, dan sikap keluarga mereka. Para tapol itu sudah lama sekali ditahan. Ketika kami tiba di sana, yang pertama ingin saya temui adalah Pramudya Ananta Toer. Tapi hari itu saya tak bisa menemuinya karena dia sedang diisolasi. Saya mendapat kabar bahwa malam sebelumnya ia berontak dan merebut senjata. Jadi, ia dipegang dan dimasukkan ke dalam sel. Akhirnya, hari itu, dengan menggunakan human approach, saya berbicara di depan para tapol di sebuah ruangan yang besar. Saya kemukakan pada mereka bahwa saya mengerti sepenuhnya penderitaan mereka. Ndak ada orang yang senang pisah dengan keluarga, apalagi banyak dari mereka yang masih bertanggung jawab atas seluruh keluarganya. Saya memakai human aproach. Saya katakan inilah risiko berpolitik. Dan kalau kalah, ya ini akibatnya. Karena mereka terisolasi, saya ceritakan pula pada mereka bahwa dunia sudah berubah. Peking sendiri sudah berubah, sudah mengadakan hubungan dengan Amerika. Sedangkan, lama atau tidaknya mereka ditahan akan tergantung dari sikap mereka dan kondisi politik nasional. "Kalau Saudara-Saudara bersikap kooperatif dan kondisi politik membaik, tidak ada alasan untuk tidak melepas kalian." Saya lihat mereka tersentuh mendengar kata-kata saya. Lalu saya ngobrol dengan beberapa tokoh di situ, salah satunya adalah Prof. Slamet, S.H., guru besar UI lulusan Leiden. Sore hari, para pemimpin redaksi meminta izin agar bisa bertemu dengan Pramudya Ananta Toer tanpa kehadiran saya. "Baik," jawab saya. Buat saya, ini malah menguntungkan karena ini bisa membuat mereka bisa lebih bebas. Jadi, malam itu ia dikeluarkan dari sel dan dipertemukan dengan para pemimpin redaksi. Saya betul-betul tidak hadir karena tidak mau mencampuri. Tapi saya mendengar laporan bahwa dalam pertemuan itu, Pramudya mengolok-olok para editor. Menurut laporan, ia bilang, "kalian enak saja bicara .... apalah saya ini. Tak punya masa depan. Mati sekarang atau esok sama saja." Besoknya, saya mengundang Pramudya untuk berdialog. Kami berbicara di tepi laut, di pinggir teluk kecil, di bawah pohon lo yang rindang. Pak, Fuad dan timnya mendampingi kami. "Pak Pramudya, ketika saya di luar negeri begitu banyak yang menyampaikan salam kepada Bapak. Pak, saya mendengar bahwa Pak Pramudya diisolasi karena berontak dan semalam saya dengar pula bahwa Pak Pramudya marah-marah pada kolega saya, para pemimpin redaksi. Sebenarnya, saya tak berhak menasihati Pak Pramudya karena saya lebih muda. Tapi, saya ingin mengatakan sesuatu. Pertama, tahanan politik bukannya selama-lamanya akan ditahan. Apabila kondisi politik mengizinkan dan kelakuan tapol kooperatif, tak ada alasan pemerintah untuk menahan Bapak lebih lanjut. Sementara itu, Pak Pramudya mengatakan apa artinya hidup. Saya ingin menyampaikan pepatah Jerman yang berbunyi: Man kann alles verlieren, nur die Hoffnung nicht, Hoffnung das schoenste des Lebens yang artinya orang bisa kehilangan segala-galanya, kecuali harapan, karena harapan itu adalah yang terindah dalam hidup manusia. Pak Pramudya, wartawan dan penulis selalu mencari alam bebas ketika menulis. Sesungguhnya kota sudah penuh kesemuan dan kebohongan. Ada pepatah Jerman yang mengatakan Die Natur aendert sich nicht, der mens wohl. Artinya adalah, 'Alam itu tidak akan berubah. Yang berubah adalah manusianya.' Alam yang indah diberikan kepada Pak Pramudya kenapa tidak dimanfaatkan. Mengapa Pak Pramudya tidak melampiaskan perasaan Pak Pramudya di sini. Lihat gelombang laut, rasakan ritmenya yang harmonis. Lihat sekitar pantai yang begitu hijau. Rasanya, keliru sekali kalau Pak Pramudya mengatakan apa beda mati sekarang atau besok." Saya ingat, dia tersentuh sekali. Matanya berkaca-kaca. Entah Pak Fuad ingat peristiwa ini atau tidak. Saya kemudian menanyakan kenapa Pramudya masuk Lekra. "Saya ingin menyalurkan profesi saya, hanya PKI yang punya program, partai lain tidak," jawab Pramudya. "Besok saya kembali. Apa ada yang bisa saya bantu?" tanya saya. Pramudya termenung. Akhirnya dia berkata, "Bolehkah saya meminta mesin ketik, karbon, kertas ketik, dan notes. Kalau bisa, saya juga minta kamus bahasa Prancis." "Baik, akan saya mintakan," jawab saya. Ketika saya kembali ke Jakarta, saya memerintahkan mengirimkan semua permintaannya. Lantas, di kemudian hari, saya juga memerintahkan melepaskan Pramudya dari sel. Sayang, tak lama kemudian Peristiwa Januari 1974 (saya tak pernah memakai istilah Malari) meletus dan saya minta berhenti dari jabatan saya sebagai Pangkopkamtib. Karena itu saya tak bisa mengecek apakah permintaan itu dikirim atau tidak. Tapi saya ingat betul, ketika Pramudya sudah dikeluarkan dari tahanan, dia datang ke kantor saya di Kemang untuk menemui saya. Saya tanya, apakah dia pernah menerima kiriman saya. Dia bilang, "Tidak pernah." Yah, itulah kenyataan birokrasi kita. Peristiwa Januari 1974 Pada awal tahun 1971, saya mendengar desas-desus bahwa Ali Moertopo adalah rival saya. Saat itu, Ali Moertopo menjabat Kepala Opsus. Pada tahun yang sama, sebenarnya saya pernah mengusulkan kepada Pak Harto untuk membubarkan Kopkamtib, dan membubarkan Opsus. Namun, jawaban Pak Harto adalah: "Belum waktunya." Mengapa saya mengusulkan untuk membubarkan dua hal itu? Karena saya menganggap Kopkamtib dan Opsus adalah sebuah kreasi untuk saat-saat yang extra-ordinary. Jadi, kehidupan Pangkopkamtib dan Opsus itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Saya menganggap sudah waktunya kembali pada kehidupan institusional. Menurut saya, Ali harus melepaskan diri dari Opsus, supaya Bakin bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Soalnya, dengan adanya Opsus, bisa terjadi konflik kepentingan antara intel lainnya, misalnya Bakin atau intel Kopkamtib, sehingga wilayah pekerjaan mereka overlapping. Kadang-kadang terjadi ketegangan yang sebenarnya tak perlu. Sementara itu perasaan saya Ali kepengin menjadi kepala Bakin. Dia sendiri tak pernah mengucapkannya pada saya. Pada 1973, ketika kabinet baru dibentuk, saya mengatakan pada Pak Harto, sebaiknya Ali jangan diangkat jadi Kabakin, karena ia tak cocok pada jabatan itu. Masalahnya, ia masih menangani Opsus. Lha, Opsus itu tugasnya untuk menyelesaikan yang action, misalnya ia merombak semua kekuatan politik yang berbau Nasakom. Nah, sebagai kepala Opsus dia sudah meninggalkan luka di mana-mana. Jadi seandainya ia jadi kepala Bakin, belum-belum orang sudah punya prasangka terhadapnya. Apalagi, sebagai Kabakin ia tak boleh berbicara di mana-mana. Ali, karena ia karismatik dan mampu menarik perhatian orang, ia lebih cocok jadi menteri penerangan. Ternyata Ali mendengar dari orang lain tentang usul saya itu. Dia menghampiri saya. "Pak saya tak mau jadi menteri penerangan." Pada waktu itulah saya menanyakan isu rivalitas yang diembus-embuskan orang. "Li, suara di luar mengatakan bahwa kamu rival saya. Itu tidak bisa, saya ini masih militer tak punya tujuan politik. Kamu bintang dua, saya bintang empat, kamu deputi Bakin, saya Pangkopkamtib dan Wapangab. Jarak kita terlalu jauh untuk jadi rival. Tapi kalau kamu mau jadi presiden, itu hakmu." Jawaban Ali, "O, tidak, tidak. Tidak ada pikiran seperti itu." Kemudian saya kan pergi ke Aljazair untuk delegasi Nonblok. Pulang saya dari Aljazair, Sudjono Humardani melaporkan kepada saya bahwa kampus-kampus resah. Karena Djono bukan intel, saya masih biasa-biasa saja. Ketika Sutopo Juwono -- yang saat itu adalah Kepala Bakin -- melaporkan hal yang sama, baru saya mulai berpikir. Saat itu Pak Topo dan Kharis Suhud -- yang saat itu adalah Asisten Intelijen Hankam -- mengatakan bahwa ada dokumen Rahmadi. "Lha, apa itu?" tanya saya. Mereka mengatakan bahwa isi dokumen Rahmadi itu menokohkan saya untuk dihadapkan sebagai rival Pak Harto. "Sudah dilaporkan kepada Pak Harto?" tanya saya pada Pak Topo. Pak Topo bilang sudah. "Apa reaksi Pak Harto?" tanya saya lagi. Menurut Pak Topo, Pak Harto mengatakan, "Ah, mereka hanya memakai nama Mitro saja." Ya, sudah, saya jadi tenang. Seminggu setelah kejadian itu, saya dipanggil Pak Harto. Bersama Sudomo dan Pak Topo kami semua menghadap. Pak Harto bercerita tentang keadaan kampus yang resah dan menanyakan apakah saya bisa menenangkan kampus-kampus. Lalu saya menjawab, "Saya bersedia. Tapi izinkan saya ke Pulau Buru dulu. Lalu ke kampus Jawa Timur karena saya berasal dari Jawa Timur. Kalau saya berhasil di sana, baru saya ke kampus-kampus lain." Pak Harto menyetujui. Saya sengaja tidak bersedia ke UI karena Ali Moertopo dan Opsusnya yang menggarap dan saya tak mau mencampuri. Jadi, saya baru melakukan dialog di kampus Unair di Surabaya dan kampus-kampus lain di Jawa Timur. Lantas saya ke Gama di Yogya dan ITB. Saya dengarkan semua keluhan mereka. Dialog itu memang perlu karena mereka merasa resah. Saya juga memesankan kepada asisten saya kalau sampai ada sikap atau ucapan mahasiswa yang ndak enak, ya jangan marah. Kalau sampai kita marah, ya ndak ada bedanya antara tua dan muda, dong. Kita harus mendengarkan mereka. Anak muda kalau didengarkan pasti senang. Tapi mungkin karena saya datang ke kampus ini dikira saya dekat dengan mahasiswa. Wong waktu Hariman Siregar terpilih sebagai DMUI, ia datang malam-malam menceritakan bahwa DMUI sudah terbentuk. Lantas, anehnya, dia menceritakan juga bahwa ia ada hubungan dengan Tanah Abang (Opsus). Yaaa, ... saya sih ndak apa-apa. Setelah selesai pertemuan itu, Hariman pergi. Saya bilang sama Pak Domo, "Binalah mereka. Kok kayaknya mereka belum punya kepercayaan kepada diri sendiri. Belum mandiri. Habis, ada urusan apa menceritakan hubungannya dengan Tanah Abang III itu. Kalaupun memang ada hubungan dengan Tanah Abang III, buat apa melapor pada saya. Saya ndak ngerti apa maksud Hariman menceritakan itu. Beberapa hari sebelum tanggal 15 Januari, kami rapat Wanjakti (Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi). Jenderal Panggabean duduk sebagai ketua dan saya wakilnya. Waktu itu suasana politik sudah memanas. Sementara rapat berlangsung, Pak Domo bolak-balik memberikan surat kepada saya yang berisi bahwa Brigjen Herman Sarens melaporkan keadaan semakin gawat. Kemudian, hari itu juga sudah terjadi pembakaran. Setiap kali saya mau pergi, Pak Panggabean selalu bilang "tunggu dulu, Mit." Sampai selesai rapat, baru saya keluar dan menemui Pak Domo. Pak Domo menjelaskan apa yang terjadi. Saya katakan, demonstrasi itu tetap saya larang. Kalau toh ada demonstrasi, jangan sampai mereka masuk ke Monas dan tak boleh melampaui jembatan di belakang Istana. Kalau demonstran itu sampai masuk ke Monas, saya tak akan bisa menjamin mereka tak akan masuk ke Istana. Dan kalau sampai para demonstran masuk ke Istana, Presiden Republik Indonesia -- siapa pun presidennya -- akan dihina di muka tamu asing. Saya tak mau sampai itu terjadi. Dan Pak Domo telah melaksanakannya dengan baik. Tapi ada masalah kekurangan pasukan. Pak Domo butuh dua batalyon. Maka, saya langsung menelepon Panglima Jawa Timur Widjojo Sujono dan Panglima Jawa Tengah yang terkenal jago perang, Mayor Jenderal Jasir. Saya meminta agar masing-masing mengirimkan satu batalyon dalam waktu 24 jam. Saya juga meminta Pak Domo untuk mengendalikan daerah Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung sebagai satu keutuhan yang taktis. Ketika berbicara begitu, saya dengar laporan bahwa para demonstran sudah sampai ke Jalan Thamrin. Saya langsung meloncat ke jip dan menuju ke Jalan Thamrin. Saya khawatir jika mereka sampai masuk ke Monas. Ketika saya menghampiri demonstran itu, saya melihat ada seseorang yang membawa batu bueesssar, dan dia melemparkannya ke sebuah bis. Waduh, saya loncat, saya kejar dia. Tapi dia sudah menghilang ke tengah massa. Lalu, saya hampiri anak-anak demonstran. Kebanyakan anak-anak SD, SMP, dan SMA, di belakangnya kelihatan mahasiswa memimpin naik skuter. Ha-ha-ha... wong muda-muda semua. Melihat saya, yang naik skuter lari. Saya ajak mereka, "Ayoooo, ikut saya, kita jalan sama-sama ke Kebayoran!" Maksud saya, saya mau mem- buat tujuan mereka menyimpang, supaya jangan sampai ke arah Monas. Tapi tidak bisa tembus, terpaksa berhenti di muka Sarinah. Kami berdialog. Mereka semua mendengarkan kata-kata saya dan semuanya menurut ketika saya perintahkan bubar. Saya juga sudah mendengar adanya pembakaran dan penjarahan di Senen, Glodok, dan bahkan Blok M. Itulah risiko demonstrasi, selalu ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan. Sebenarnya saya menawarkan dialog antara DMUI dan Tanaka. Charge d'affair-nya melapor pada saya bahwa Tanaka bersedia berdialog dengan mahasiswa pada tanggal 16 Januari. Tapi ternyata DMUI menjawab bahwa "dialog diganti dengan dialog jalanan". Ha-ha-ha ... yah, akhirnya mereka mengadakan demonstrasi dengan segala akibatnya. Semuanya sudah terjadi. Saya memerintahkan Sudomo untuk meminta DMUI bertanggungjawab. Dalam hal ini Hariman Siregar dan kawan-kawan. Tapi saya tak pernah memerintahkan menangkap Syahrir. Setelah Tanaka pergi, saya menghadap Pak Harto. "Pak, saya minta maaf. Saya sudah berbuat sebisa saya. Tapi toh semuanya terjadi. Semua ini tanggung jawab saya. Karena itu, izinkan saya mengundurkan diri." Pak Harto menjawab, "Mengundurkan diri tidak menyelesaikan permasalahan. Ini bukan hanya kesalahan Mitro. Ini kesalahan kita semua." Saya menjadi tenang mendengar jawaban Pak Harto. Saya dibebaskan dari tugas saya sebagai Pangkopkamtib dan tetap menjadi Wapangab. Tapi suatu hari saya dipanggil Pak Harto. "Begini, Mitro, ini ada satu organisasi yang memakai nama Mitro untuk tujuan yang ndak baik. Namanya Rahmadi ...," demikian Pak Harto mengungkapkan. Saya diam saja. "Untuk itu," tutur Pak Harto lagi, "saya meminta Mitro mengalah sementara. Mitro jadi dubes di Amerika ...." Saya meminta waktu untuk berbicara dengan keluarga saya. Keluarga saya tidak ada yang setuju. Maka, saya menghadap lagi kepada Pak Harto. Saya katakan bahwa saya tak bersedia menjadi dubes di Amerika dan saya minta diberhentikan saja. "Kok, jadinya begini, Mit?" kata Pak Harto. Sampai detik ini saya tak tahu siapa Rahmadi, bertemu pun belum pernah. Saya dengar dari laporan dalam kelompok Rahmadi, antara lain, ada Letjen Suadi, bekas dubes Indonesia di Etiopia Laksamana Muda Mardanus, bekas menteri perindustrian maritim dan Puguh. Saya merasa aneh karena mereka orang-orang yang dekat dengan Ali Moertopo dan Sudjono Humardani. Sebenarnya saya sangat sayang pada Ali Moertopo. Ia orang lapangan, dan banyak membantu saya. Sudjono bahkan sering tidur malam-malam di kantor saya menjelang Peristiwa Januari 1974. Tapi saya tak curiga pada mereka. Soal Keterbukaan Setelah saya pensiun, ternyata hidup saya lebih enak. Dan anehnya, banyak sekali orang yang membantu saya untuk hidup. Tahun 1979, saya mulai berpikir bahwa tak mungkin saya hidup dari gaji pensiunan. Sebenarnya, saya bisa saja melakukan commission hunting, tapi etika saya melarang saya berbuat itu. Tahun 1980 saya memutuskan terjun ke dunia bisnis. Saya mulai dari nol. Betul-betul nol. Di sini saya mulai merasakan korban perasaan. Saya segera membuang jabatan dan kepangkatan. Saya datang ke dirjen dan menunggu dua jam. Dan saya katakan pada dirjennya bahwa saya datang ke sana bukan untuk ngemis. Ada belasan perusahaan yang bernaung di bawah Rigunas Group, tapi semua perusahaan itu otonom. Lapangan kami bermacam-macam. Dan saya hanya presiden komisaris dari perusahaan-perusahaan ini dan mengarahkan kebijaksanaan saja. Biar anak, mantu, dan kawan-kawan saya yang berkiprah betul-betul. Meski sudah tidak dalam pemerintahan lagi, saya tetap senang mengamati politik. Dan saya menganggap sudah saatnya ada keterbukaan di dalam negeri kita ini. Ekonomi sudah stabil, tapi entah bagaimana tak ada yang berani bicara. Nampaknya DPR menyadari bahwa saya menginginkan keterbukaan. Maka, dalam DPR saya membicarakan beberapa pokok yang perlu dirombak, misalnya saya katakan bahwa fungsi politik dan birokrasi harus dipisahkan. Politik harus keluar dari birokrasi nasional. Saya juga menganggap pegawai negeri tidak boleh jadi anggota partai atau Golkar. Pegawai negeri boleh memilih tapi tidak boleh membantu partai atau Golkar dalam bentuk apa pun. Kini, dalam usia saya yang 64 tahun, saya bahagia. Saya bahagia dikerubungi cucu-cucu saya karena saya cinta pada mereka. Sesekali, di sela kesibukan, saya bermain golf. Sesekali saya bernostalgia, ah, enaknya dulu ketika sebelum saya jadi panglima di Kalimantan Timur. Keadaan begitu melarat. Kopi, beras, gula beli sendiri. Tapi kok bahagiaaa ... sekali. Mungkin karena ndak ada beban. Terkadang, saya juga mengisi waktu dengan baca buku politik sambil sesekali bertemu dengan kawan lama. Meski hidup terkadang susah, saya selalu melihatnya dengan optimisme .... LSC
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini