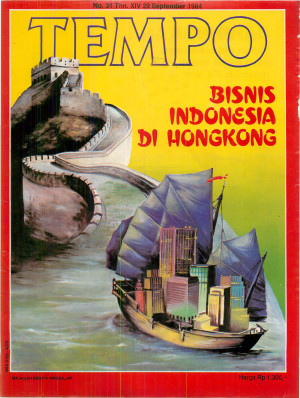CINA adalah negeri yang selalu dikocok revolusi. Yang terakhir, 1966-1967, adalah Revolusi Kebudayaan (Wenhua geming) yang hampir merontokkan negeri itu dari dalam. Ini adalah usaha Ketua Mao dan kelompoknya untuk unjuk kekuatan, setelah tersisih akibat kegagalan mereka dalam "Loncatan Jauh ke Depan," program pembangunan yang justru menghancurkan perekonomian. Waktu itu mereka membangun isu - dan memproklamasikannya sebagai tujuan utama Partai bahwa kaum moderat, yang justru mengusahakan perbaikan ekonomi negeri, telah menempuh jalan kapitalis. Karena itu, mereka - Liu Shao-qi, Deng Xiao-ping, dan para simpatisannya - harus dibersihkan. Dan Cina pun praktis mengalami perang saudara. Tetapi Revolusi Kebudayaan ternyata tidak punya garis jelas. Dan karena pergolakan itu berendeng dengan gerakan-gerakan lain, revolusi itu hanya melengkapi corak sejarah Cina yang tampak mondar-mandir. Perubahan-perubahan besar, yang sekadar mengikuti gerak emosi Mao - dan juga seluruh kecemasannya - itu cuma membuahkan kebingungan luar biasa di kalangan rakyat. Sikap yang hari ini dipuji besok dikecam habis-habisan. Sampai pun orang plintat-plintut tak lagi mampu menyusun strategi untuk membangun teknik menjilat. Dan di situlah drama kehidupan - yang tak tertahankan, bagi mereka yang tabah sekalipun muncul di banyak keluarga. Satu rumah tangga, yang semula terpaksa pecah karena revolusi, masih pula harus bingung karena perpecahan yang mahal itu - dan masih bisa dianap salah. Dan hukuman lain pun menanti. Ikatan keluarga yang sudah patah patah bisa remuk sama sekali. Dan keluarga Liang salah satu korban keadaan itu. Suami-istri Liang adalah aktivis Partai. Namun, mula-mula, ibu dalam ke luarga itu dikecam - dengan restu suaminya. Ia dianggap "antek kanan". Lalu musibah berlanjut: sang ayah sendiri dicap "intelektual tengik" pada saat RevoIusi Kebudayaan. Keluarga itu pun cerai-berai. Setelah Revolusi Kebudayaan berlalu, dan zaman berganti, Liang Heng, anak dalam keluarga itu, mengisahkan keruntuhan tragedi yang mereka alami. Sebuah tema yang menarik adalah ini: betapa pahitnya menanggungkan "dosa turunan" sebagai seorang "anak reaksioner". Itu bisa kita dapatkan dalam bukunya Son of the Revolution. Kami petikkan: *** Menjelang usia empat tahun, saya sekali waktu pernah memutuskan untuk lari saja dari panti asuhan. Rasanya, senantiasa berat menunggu sampai Sabtu tiba, saat bertemu keluarga. Seperti biasanya waktu itu saya, berendeng dengan anak-anak lain di dekat pintu masuk, meneriaki nama sebagian anak yang hari itu "diselamatkan" oleh saudara mereka. Rasanya, saya jadi makin konyol, gamang menghadapi kenyataan. Tampang memelas Waipo, nenek saya dari garis Ibu, terus muncul. Ia biasanya menjemput saya. Tapi minggu ini saya sungguh sebal harus menunggu begitu lama sampai akhir mimggu. Saya tahu, pintu dapur yang berhubungan dengan Jalan Changsha biasanya sedikit dibiarkan menganga oleh para tukang masak, mengingat angin musim dingin sudah lewat. Maka, pada waktu tidur siang, sesudah makan, saya menyelinap - melewati deretan tempat tidur teman-teman - dan berjingkat di samping Bibi Nie yang terkantuk-kantuk di kursi. Saya merangkak ke dapur - yang suram akibat asap pembakaran batu bara. Dan, sampailah saya di udara luar yang merdeka. Panti asuhan sungguh menyebalkan. Di sana kita tidak bisa makan permen. Sebelum perawat membolehkan makan, tangan harus lebih dulu ditaruh di punggung lantas menyanyikan sebuah lagu. Kemudian, kalau ada yang makan terlalu cepat, perawat akan menampar dengan alat pemukul lalat. Nyanyian dan tarian-tarian - seperti Menyapu Lantai, Berkarya di Pabrik, dan Bercocok Tanam di Pedesaan - memang menyenangkan. Tapi saya selalu senewen pada saat harus memainkan tarian mencangkul. Habis, saya maunya tarian serdadu. Saya juga sebal terhadap kesempatan beristirahat yang berlama-lama. Kami dilarang bangun dari pembaringan, walaupun badan terasa segar. Berjam-jam saya hanya memandani tahi lalat kecil di kaki saya. Waktu itu, pendidikan merupakan barang istimewa yang hanya diberikan kepada anak-anak kader. Peringkat orangtua saya, sebagai kader, tidak begitu tinggi. Tapi kedudukan Ayah sebagai redaktur sekaligus anggota pendiri koran Partai, Harian Hunan, dan pekerjaan Ibu dalam Biro Keamanan Umum Changsha, sudah cukup memenuhi syarat sehingga saya bisa bersekolah di panti asuhan itulah. Orangtua saya sendiri tak punya banyak kesempatan mendidik, dan tenggelam dalam kegairahan mengubah Cina menjadi negeri sosialis yang mahaagung. Senantiasa rela berkorban. Senantiasa bermimpi untuk dianggap murni dan setia sebagai syarat menjadi anggota Partai. Wajar kalau urusan keluarga menjadi nomor dua. Tugas Ayah di koran sering menyebabkan ia harus pergi ke pelosok-pelosok selama berbulan-bulan, sementara Ibu hanya pulang pada hari Minggu. Ibu punya kamar di unit tempatnya bekerja, harus tinggal di sana untuk bisa menghadiri rapat-rapat setiap malam. Maka, dalam umur tiga tahun, saya sudah dimasukkan ke panti asuhan: menjalani kehidupan kolektif, menerima pendidikan awal sosialisme, dan jauh dari pengaruh buruk kehidupan keluarga yang manja. Tentu saia bai Nenek hal itu sangat menyedihkan. Nenek-nenek saya, baik dari pihak Ibu maupun Ayah, sebelumnya senantiasa sibuk mengurusi kami bertiga - saya dan kedua saudara perempuan saya. Mula-mula, saya tinggal bersama nenek dari pihak Ayah, Nai Nai, seorang wanita yang tinggi, keras dengan tulang-tulang bertonjolan, yang selalu mengenakan baju tradisional hitam. Beliau menempati apartemen jatah Ayah dari Harian Hunan yang terdiri dari dua kamar dan terletak di lantai dua asrama kader - dengan dapur milik bersama dan kakus di luar. Sebagai seorang Budhis yang saleh, Nai Nai vegetarian, keras terhadap diri sendiri dan orang lain, kecuali kepada cucu-cucunya. Sebelum disapih, saya disusui tujuh orang yang disewa Nai Nai. Semuanya tidak memuaskan saya. Yang kedelapan, gadis desa berusia 19 tahun, baru sanggup melayani kebutuhan saya akan susu. Harap maklum, dengan berat 10 pon saya lahir sebagai bayi paling besar di Rumah Sakit No. 1 Changsha. Akhirnya, karena si gadis yang menyusui saya tidak memiliki KTP, ia harus segera pulan. Saya pun dipindahkan ke rumah Waipo, nenek dari pihak Ibu, tak jauh dari rumah Nai Nai di sebuah gang yang berllku. Di rumah Waipo pembagian ruangan jauh lebih padat. Dalam sebuah ruang sempit yang suram tinggal pula Paman Yan, istrinya, dan seorang anak mereka. Toh suasana lebih hidup dan saya lebih senang, terutama karena Waipo selalu memberi saya permen. Kalau mereka ke pasar, saya juga diajak. Waipo bertubuh mungil, giginya bergelombang, tangannya keriput. Lebih hidup dan banyak ngomong, juga ceria - jauh berbeda dari Nai Nai. Suaminya meninggal ketika beliau masih muda, mewariskan dua anak. Sementara itu, Nai Nai sudah beranak sembilan waktu suaminya terpelanting di jalanan bersalju di depan gerbang kota. Dalam masyarakat lama, seorang janda - supaya tetap terhormat - tidak menikah lagi. Maka, Waipo, bertahan hidup dengan membuat sol sepatu di rumah. Pekerjaan ini dilanjutkannya meskipun kemudian Ibu dan Paman Yan sudah bekerja. Dan sobekan-sobekan sol adalah mainan saya yang pertama. Alasan lain saya lebih nyaman tinggal bersama Waipo adalah karena Ibu, pada hari Minggu, lebih banyak datang ke sini ketimbang ke rumah mertuanya. Hubungan Ibu dengan mertuanya memang kurang baik. Selain itu, ikatan Ibu dengan rumah Ayah kurang kuat. Sebelum menikah, mereka boleh dibilang kurang saling mengenal. Seseorang telah menjodohkan mereka. Waktu itu Ayah tengah bekerja di Guilin. Mereka saling berkirim surat beberapa kali. Ayah lebih terpelajar. Sebagai wartawan, ia pernah ikut pendidikan Partai, memiliki pengetahuan yang baik mengenai kesusastraan, dan ulung sebagai penyair juga sebagai komposer amatir dan konduktor. Sebenarnya, Ibu orang yang berpotensi. Kemauannya keras, tapi pribadinya menyenangkan kalau sedang tidak sibuk. Beberapa tahun setelah saya tinggal pada Waipo saya sadar babwa perkawinan Ayah dan Ibu kurang serasi. Paling tidak, mereka sangat jarang bersama. Rumah Waipo merupakan pusat perkembangan emosi saya yang pertama. Dan ke situ saya menuju begitu minggat dari panti asuhan. Saya menyeberangi jalan raya - untung tak terjadi kecelakaan - lalu meneruskan lari beberapa ratus depa menyusuri gang yang kelabu. Saya kaget: ternyata Waipo tidak senang saya muncul. "Buyung, mau apa kamu di sini?" katanya. Dan segera beliau merangket tangan saya dan menyeret saya ke kompleks Harian Hunan, menuju rumah Nai Nai. Di sana dua nyonya tua itu merengkuh dan menyeret saya kembali ke panti asuhan yang bagai kurungan, tanpa sedikit pun mengacuhkan teriakan protes saya. Para pengasuh di panti asuhan tak kalah garang. Tanpa sungkan-sungkan mereka memaki dan menyumpahi saya di depan Nai Nai dan Waipo. Begitu nenek-nenek saya pulang, saya dikurung bersama dua anak lain yang ternyata juga melarikan diri. "Kalian benar-benar bukan anak manis seperti kemauan Ketua Mao tidak menjunjung tinggi disiplin revolusi. Kalian tinggal di sini sampai semuanya beres," kata seorang pengasuh. Untung, saya sudah belajar bahwa Ketua Mao adalah matahari kehidupan. Di rumah, Mao adalah kata yang selalu saya ucapkan sesudah Mama, Papa, dan Nai Nai biasanya sambil memelototi gambar besar berbingkai di atas pintu, yang dipasang Ayah. Sesudah itu saya belajar berteriak, "Saya mencintai Ketua Mao. Jayalah Ketua Mao!" Ketua Mao selalu membayangi saya pada saat-saat bermain atau istirahat - lambang dewa kebaikan. Dan saya percaya bahwa apel, anggur, dan lain-lain diberikan kepada kami lantaran Ketua Mao mencintai kami. Ketika keesokan harinya, setelah saya kabur, perawat bilang bahwa Ketua Mao memaafkan saya, saya merasa menjadi anak paling bahagia di dunia. Secara bertahap, pada tahun ketiga dan keempat di panti asuhan, saya mulai menulis huruf-huruf Cina yang membentuk kalimat: "Ketua Mao adalah bintang penyelamat kami yang agung" "Kami semua adalah anak-anak manis Ketua Mao" "Partai Komunis secerah matahari" "Pada saat saya besar saya akan menjadi buruh". Di samping itu, tentunya, kami juga mempelajari ilmu ukur, lipat-melipat kertas, dan belajar bertanggung jawab menyirami tanaman atau membersihkan kelas. * * * Setiap saya mengunjungi Waipo, saya selalu berharap Ibu ada di sana. Saya sungguh mencintainya meski kami jarang bertemu. Tapi, ketika saya berusia empat tahun, saya mulai merasakan suasana sudah tidak beres lagi. Ibu datang dengan tampang cemas dan tak lagi bermain-main dengan saya. Hanya selalu berbicara dengan Paman Yan dalam logat daerah Liuyang yang tak saya mengerti. Buntutnya, pada Sabtu siang Nai Nai menjemput saya. Ibu sudah pergi, katanya, dan saya tak usah ke rumah Waipo lagi. Bertahun-tahun kemudian saya baru mengerti apa yang telah terjadi. Pada awal 1957 dilancarkan Gerakan Seratus Bunga. Tujuan Partai dengan gerakan itu adalah memberikan kesempatan massa mengkritik. Waktu itu Ayah sedang di pedalaman meliput sesuatu, tapi di Biro Keamanan Umum Changsha dilangsungkan suatu pertemuan dan setiap orang didesak untuk melontarkan pandangan-pandangan mereka. Ibu bingung. Tak ada alasan untuk mengkritik Partai, pikirnya. Partai telah memberinya pekerjaan dan menyelamatkannya dari kemiskinan. Toh pimpinannya memaksa setiap orang yang mampu berpikir aktif dalam gerakan ini, terutama yang kelak ingin menjadi anggota Partai. Ibu terbujuk. Dengan keyakinan penuh sebagai orang yang sedang menjalankan tugas, Ibu akhirnya mengutarakan tiga hal yang mesti diperhatikan. Ibu bilang, ketua seksi di tempatnya bekerja sering berkata kasar dan menjelek-jelekkan orang. Pembantu di rumahnya disuruhnya tidur di lantai, dan, pada saat kenaikan gaji, pimpinan itu tidak mengindahkan pendapat orang banyak. Sungguh celaka: Gerakan Seratus Bunga dibelokkan menjadi Gerakan Anti-Kanan. Barangkali pihak Partai grogi melihat jumlah oposisi, makanya perlu diambil tindakan mematikannya. Atau, seperti yang pernah saya dengar, Gerakan Seratus Bunga sebenarnya perangkap untuk melenyapkan unsur Kanan. Bagaimanapun juga, setiap unit harus mengumpulkan sejumlah nama yang termasuk Kanan. Dan di Biro Keamanan Umum nama Ibu termasuk dalam daftar - inilah awal malapetaka itu. Memang brengsek. Pada 1978, ketika diberi kesempatan melihat-lihat arsip, Ibu tahu bahwa ia dicap Kanan semata-mata karena tiga kritiknya itu. Mungkin ketua seksinya marah, atau bisa juga karena unit tempatnya bekerja mengejar target jumlah yang mesti disikat. Pada saat kejadian, tentu saja, tak ada proses pengadilan. Ibu langsung dikirim kerja paksa di daerah Yuan Jia Ling. Peringkat yang sudah ia capai sebagai kader hilang, dan gajinya digunting dari 55 menjadi 15 yuan per bulan. Pada saat Ibu dicap sebagai anti-Partai, Ayah di unitnya justru aktif ikut Gerakan Anti-Kanan. Ayah percaya sepenuh hati terhadap Partai - bahwa Partai tidak mungkin melancarkan tuduhan palsu. Persoalan jadi ruwet. Perasaan Ayah sebagai penganut Konfusius mengharuskan Ayah membela Ibu, tapi kesetiaannya kepada Partai memaksanya menistakan Ibu. Akhirnya, komitmennya dengan Partai menang. Ia berpikir bahwa cara itulah yang bisa menyelamatkan keluarganya. Saya ingat ketika pertama kali Ibu berkunjung ke rumah. Pada sebuah hari Minggu, dengan guyuran hujan, di akhir musim gugur, ketika Ayah dan Nai Nai sedang pergi ke luar, terdengar langkah menaiki tangga dan koridor. Lalu ada ketukan di pintu, pelan sekali - seperti ragu. Liang Fang membukakan pintu. Ibu hampir tak bisa dikenali lagi. Baju petani yang dikenakannya bertambal-tambal, lumpur menyelaputi tubuhnya sampai lutut. Kullt di wajahnya yang bundar tampak tebal kasar, sangat kotor, dan seseorang rupanya telah memangkas rambutnya secara serampangan. "Mama," pekik Liang Fang, kakak tertua saya. Liang Wei-ping, adik saya, dan saya sendiri lari mendekat kami bertiga direngkuhnya sekaligus. Ibu tersedu-sedu, dan lupa menaruh payung kertasnya. Kemudian, sewaktu kedua kakak perempuan saya sibuk menyiapkan air hangat untuk cuci muka, dan teh, Ibu duduk di dipan sembari mendekap saya berlama-lama. Setelah beristirahat, Ibu segera sibuk melakukan pekerjaan yang tersisa yang masih ditinggalkan Nai Nai. Menyapu, mengelapi debu, merauti pensilpensil kami, mencuci pakaian, dan membersihkan jendela-jendela. Tak sedikit pun ia bercerita tentang ikhwalnya. Hanya menanyakan kesehatan kami, tugas-tugas sekolah, dan kesehatan Ayah. Suasana ketika itu menyenangkan kami pikir kami mendapatkan ibu kembali. Ibu sedang mengikat kepangan rambut Liang Fang ketika Ayah datang dengan muka tidak ramah dan menghardik: "Apa yang kamu kerjakan di sini? Kamu sudah minta izin belum untuk ke sini?" katanya kepada Ibu. Dergan salah tingkah Ibu menundukkan muka. "Ya, tentu saja saya minta izin," jawabnya. "Saya bisa pulang sekali sebulan." Selama beberapa menit semua diam. Ayah berjalan selangkah demi selangkah mengitari ruangan, sembari berkacak pinggang. Sikap tubuhnya menunjukkan penguasaannya atas Ibu, sebuah sikap yang mirip Nai Nai dalam menghadapi Ibu. Tiba-tiba Ayah menerocos, mengobral kata-kata politik semua mengenai Gerakan Anti-Kanan, kewajiban Ibu untuk menyadari kesalahannya, dan memperbaiki diri. Ayah telah berubah menjadi mesin propaganda. Pada mulanya, Ibu hanyadiam, kepalanya menunduk. Tapi lantas protes: "Ya, ya, ya. Saya memang orang Kanan. Semua salah saya. Tapi cobalah jangan bicara begitu lagi, kepala saya hampir meledak. Semua itu sudah saya dengar berulang-ulang, setiap minggu menuliskan kritik diri, dan kini saya pulang, duh. . . untuk mendengar semua itu lagi." "Rasanya kamu belum menyadari apa yang telah kamu lakukan. Kamu menyiakan-nyiakan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam kerja bakti," hardik Ayah. "Bagaimana kamu seyakin itu," tanya Ibu, mukanya menengadah dan pucat. Ayah meledak: "Kanan, kamu. Jangan coba-coba mempengaruhi anak-anak!" Ibu pun kehilanean kontrol: "Apa sih salah saya? Partai menghendaki saya berbuat begitu, maka saya kerjakan. Coba kamu tunjukkan, di mana...." Kalimat Ibu tak selesai lantaran Ayah tiba-tiba menampar mukanya. Ibu terpelanting ke dipan, sesenggukan. Ayah meninggalkan ruangan dan membanting pintu. Dengan perasaan pedih, Ibu pelan-pelan memungut jaketnya yang kotor dan payungnya. Kami menangis. Menjelang Ibu sampai pintu, Ayah muncul lagi dan memekik: "Jangan ke sini lagi sebelum memperbaiki dirimu sendiri! Anak-anak di rumah ini membutuhkan ibu yang revolusioner, bukan yang kekanan-kananan." Ibu berhenti, memalingkan mukanya yang basah oleh air mata - hanya menengadah. Suara Ayah menjadi lunak: "Apa pun yang kamu katakan di sini, tidak akan saya sebarkan ke orang-orang. Tapi hati-hati dengan perkataanmu di kamp kerja bakti. * * * Meskipun Ayah tetap bengis, setiap bulan Ibu masih datang menjenguk kami. Demi kerinduannya kepada kami, ia bertahan menghadapi "wejangan-wejangan" Ayah dan pertengkaran yang tak bisa dielakkan. Kadang-kadang ia tidur di dipan Ayah, dan saya menyelip di situ. Tak pernah Ibu berbaring tenang, dan di pagi hari bantalnya selalu basah oleh air mata. Di Yuan Jia Ling, semua yang dicap Kanan berusaha keras membuktikan kepada pejabat politik bahwa mereka masing-masing sudah memperbaiki diri dan bersiap untuk pulang. Ada berbagai macam orang, intelektual, kader berperingkat tinggi, para buruh biasa. Strategi yang baik untuk meyakinkan petugas adalah selalu melaporkan kesalahan orang lain. Dan kesalahan yang ditunjuk sungguh beragam. Menjatuhkan butiran padi ke lantai saja sudah bisa dianggap kesalahan fatal, karena itu berarti tidak menghargai jerih payah para petani. Dalam proses rehabilitasi itu, para pesakitan harus pula membuat laporan secara terus-menerus mengenai isi pikiran diri sendiri. Beberapa orang karena tulisan-tulisan itu merasa bahwa mereka benar-benar unsur Kanan. Menulis laporan seperti ini menjadi semacam kebiasaan, dan Ibu pun hampir percaya, semua laporannya adalah gambaran pribadinya yang sebenarnya. Cara terakhir untuk bebas adalah dengan kerja keras. Masing-masing memamerkan daya tahannya untuk menderita. Misalnya pergi ke ladang tanpa caping di bawah sengatan matahari musim panas. Atau bertahan terus bekerja di bawah hujan, sementara yang lain sudah meninggalkan tempat. Dalam waktu tiga tahun, akhirnya Ibu sudah sanggup menggendong batu seberat seratus pon lebih. Suatu hari seorang pengawas memanggilnya. Ibu diberitahu bahwa ia sudah tidak kekanan-kananan lagi, berarti boleh pulang. Hampir tengah malam ketika Ibu datang. Tampak seperti pengemis yang menggelandang menenteng perkakas pribadi. Tapi nada bicaranya sudah terang dan mantap. "Liang," katanya kepada Ayah, "saya kini sudah menjadi manusia lagi." Ibu diangkat menjadi buruh untuk pabrik industri di Jalan Satu Mei. Gajinya jelas jauh lebih rendah dibandingkan ketika di Biro Keamanan Umum dulu, sementara peringkatnya sebagai kader hilang untuk selamanya. Yang penting, dia susah bebas, menjadi anggota masyarakat sebagai manusia normal lagi. Saya dan kedua kakak saya mengira, semua persoalan sudah rampung. Tapi malam itu, ketika saya ikut tidur di kamar Ayah, yang saya dengar bukan rundingan untuk sebuah keluarga baru. Tapi urusan perceraian, dan kami tiga bersaudara harus tinggal bersama Ayah. Seputar hari perceraian orangtua saya, pada 1960, seluruh Cina menderita. Saya menjelang usia tujuh tahun. Beras, minyak sayur, dan semua bahan makanan yang terbuat dari kacang kedelai dijatah dengan ketat. Daging, gandum, gula secara perlahan-lahan lenyap dari pasar. Sayuran segar tak terjangkau, dan mantau (semacam roti) yang kami beli di ruang makan umum berubah menjadi kasar dan kusam - gandum yang bagus juga sudah lenyap. Kami semua kelaparan. Menurut Ayah, terjadi banjir akibat sungai dan danau meluap, sehingga para petani tak bisa berladang. "Kalian untung," katanya. "Tinggal di kota besar ibu kota provinsi, dan Partai serta Ketua Mao sanggup memberi makan yang diambilkan dari gudang-gudang. Tapi para petani harus berusaha sendiri untuk mendapatkan makanan mereka." Situasi mungkin menggawat bulan demi bulan, dan akhirnya genap setahun. Saya menjadi terbiasa pergi di Taman Pahlawan bersama kakak-kakak saya untuk mencari rerumputan yang bisa dimakan. Itu kami campur dengan bekatul, kami rebus, menjadi kue duka. Berhubung rumput itu makin habis, kami mesti berjalan bermil-mil mencarinya di tempat lain. Tak pelak lagi, beri-beri akhirnya menyerang kami. Nai Nai meninggal. *** Begitu saya lulus SD, Mei 1966, yaitu ketika saya menginjak usia ke-12, Revolusi Kebudayaan mulai menampakkan diri. Koran-koran penuh kritikan terhadap Desa Tiga Keluarga, sekelompok penulis yang karya-karyanya dianggap rerumputan liar beracun. Baru dua minggu saya balik di rumah - setelah mengungsi ke pelosok sehubungan dengan pengumuman pemerintah, pada bulan April 1962, bahwa Chiang Kai-shek akan melancarkan serangan ke Daratan dan kami semua harus siap menghadapi perang dengan kaum nasionalis Taiwan - saya diharuskan ikut berkumpul lagi di sekolah, untuk sebuah rapat. Seperti orang yang sudah dewasa saja. Ini pertama kalinya saya dan teman-teman sekelas mulai mengenal apa itu studi politik. Sebuah aktivitas yang kini sudah menyatu dalam kehidupan urban Cina, misalnya antre di ruang makan umum untuk sarapan dengan mantau dan bubur. Guru kami menerangkan isi koran-koran, bahwa ada musuh dalam selimut yang dengan terang-terangan melancarkan serangan, dan memojokkan Partai dan sosialisme. Para "musuh" tersebut telah mencemoohkan Gerakan Loncatan Jauh ke-Depan di akhir tahun 1950-an sebagai bualan besar. Mereka telah menghujat kekuasaan proletariat, bahkan menganjurkan partai yang agung beristirahat. Menurut guru kami, kaum buruh, petani, dan tentara harus bersatu menggempur kaum intelektual kesasar yang busuk, musuh dalam selimut itu. Dan meski kami masih kanak-kanak, katanya, kami harus ambil peranan. Kami memulai dengan membuat karangan yang menyerang musuh. Saya bingung juga mesti menuliskan apa, ketika suatu kali diharuskan mengkritik. Akhirnya, ada beberapa kalimat yang rasanya klop: "Dusun Tiga Keluarga adalah bajingan". Mereka telah menyerang Partai dan sosialisme. Mampuslah bersama unsurunsur kapitalis. Ganyang Wu Han! Sikat Deng Tuo! Habiskan Liao Mo-sha." Saya sangat sibuk dan merasa penting. Sesudah rapat, saya segera bergegas ke rumah, menceritakan semua kepada kakak-kakak saya. Mereka rupanya mengalami hal yang sama di sekolah mereka. Kami juga mulai menyanyikan lagu-lagu yang berisi ejekan kepada kaum anti-Partai itu. Semua kegiatan itu sungguh menyenangkan, merupakan warna bagi kehidupan saya yang tak menentu di kompleks asrama Harian Hunan. Saya kecewa ketika rapat-rapat sudah berlalu. Meski begitu, di Changsha gelombang kritik masih terus dilancarkan. Revolusi Kebudayaan Proletar Besar sudah makin terang bagi kami. Antara lain membelejeti kaum reaksioner kapitalis dalam segala bentuknya - terutama yang menggunakan kewenangan akademis untuk menyerang Partai dan sosialisme. Suasana menggetarkan. Tanggal 16 Juli 1966, Ketua Mao selama satu jam berenang mengarungi Sungai Yangtze. Seluruh negeri bersukacita, karena pemimpin yang tercinta itu sanggup menghadapi tantangan alam sedemikian rupa pada usianya yang sudah 70-an. "Arus di Yangtze sangat deras dan berombak. Jika seseorang tak ragu untuk bertahan, ia juga akan sanggup mengatasi segala kesulitan," kata Ketua Mao. Acara berenang itu telah membuktikan kekuatannya dan ketangguhannya dalam politik - sebuah sisi lain revolusi. Setiap unit merayakan kejadian itu dengan gegap gempita tambur dan mercon bertalu-talu di jalanan. Changsha seperti sedang memeriahkan Hari Nasional. Bendera merah menghiasi segala sudut dan pintu-pintu di malam hari lentera-lentera merah bekerjapan cahayanya. Saya merasa akrab dengan pimpinan tertinggi yang bagi saya selalu tampak misterius itu. Saya merasa bisa berenang, dan merasakan betapa lelahnya berlama-lama di air. Saya 12 tahun, dan merasa kuat, tapi saya ragu apakah bisa berenang seperti Ketua Mao. Padahal, Ketua Mao toh terdiri dari darah dan daging, seperti manusia biasa. Saya makin menghormatinya. Sekali lagi saya bulatkan tekad saya untuk mengabdi kepadanya dengan sepenuh hati. *** Ayah pulang kerja dengan sejumlah informasi. Sebagai orang koran, ia tahu banvak hal lebih dulu dari orang lain. Sewaktu Ketua Mao meninggalkan Beijing beberapa bulan ini, kata Ayah, Komite Sentral telah menempuh garis revisionis - menjegal Revolusi Kebudayaan, dengan berpura-pura seolah-olah mendukungnya. Segera setelah Ketua Mao balik ke Beijing, setelah acra berenang di Sungai Yangtze, ia mengadakan rapat-rapat. Direktorat Revolusi Kebudayaan akhirnya menggariskan supaya Panitia Kerja - organ partai di unit-unit yang bertugas menggerakkan massa sesuai dengan perintah pusat - ditarik saja dari kegiatan. Ayah mendadak merendahkan suaranya. "Bahkan Ketua Liu juga dikritik dan harus menuliskan laporan ujian diri sendiri. Luar biasa," katanya, sembari menggeleng-gelengkan kepala. "Sebaiknya, kamu jangan menceritakan ke orang lain. Ini masih rahasia," katanya lagi. Saya bangga sekali: Ayah begitu tahu banyak hal. Ingin rasanya menceritakan hal ini kepada teman-teman. Tapi keinginan itu hilang melihat Ayah justru tampaknya mengalami dilema dengan kabar itu. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa di dalam Partai terjadi konflik. Belakangan, saya mengerti bahwa kepercayaan Ayah kepada Partai seperti mendapat tantangan. Rahasia itu toh tak lama kemudian meledak. Pada 5 Agustus Ketua Mao mencanangkan slogannya yang terkenal: "Mengebom markas besar". Ia mengkritik para pemimpin "dari tingkat pusat sampai daerah", mengutuk mereka sebagai "pengganjal revolusi" dan "plin-plan". Sasaran utama serangannya jelas: Liu Shao-qi, kepala negara dan wakil ketua Partai Komunis Deng Xiaoping, sekretaris jenderal Sekretariat Komite Sentral, dan Tao Zhu, sekretaris Komite Sentral Partai untuk wilayah Selatan. Suatu pagi ketika saya sedang duduk-duduk menganggur di rumah, Li Kecil datang. Dia teman baik saya yang paling cerdas, dan saya senang Li muncul. Dia duduk di pinggir dipan dengan sikapnya yang serius seperti biasa. "Kamu tahu," katanya, "semua orang telah mengutip kata-kata Ketua Mao: 'Dalam revolusi tak ada yang salah, revolusi selalu benar untuk berontak'. Kita juga harus bertindak. Di sekolah kita banyak kecenderungan kapitalistis. Kita mesti menggerakkan murid-murid lain guna melancarkan Revolusi Kebudayaan, juga di sekolah." Saya pikir, ini ide cemerlang. Kami akan mengikuti garis Ketua Mao seperti orang-orang dewasa, dan mestinya Ayah akan bangga melihat saya. Sekalian ini kesempatan saya membalas dendam kepada guru yang saya benci, lantaran dia selama ini selalu mengkritik dan mengekang saya. Kami berkumpul bersama beberapa teman lain di rumah Li Kecil, dikompleks Harian Hunan juga. Rumahnya kosong karena ibunya tinggal di unit tempatnya bekerja, sementara ayah Li (Li Tua) sebagai editor naskah selalu mendapat tugas malam di Harian Hunan. Kami mendapatkan kertas dan tinta dari kantor orangtua kami. Setiap anak diputuskan mendapatkan selembar kertas yang sudah saya gambari lebih dulu dengan gambar kartun yang satiris. Tapi, begitu kami membentangkan kertas-kertas yang sudah ditulisi itu, kami bingung sendiri - sadar bahwa kami sebenarnya tidak tahu apa yang dimaksud dengan kapitalisme dan revisionis. Hanya Li Kecil yang tampaknya mengerti apa yang dipikirkannya, dan dengan lancar mencoret posternya dengan: "Ganyang garis revisionis kapitalis yang merasuki Sekolah Dasar Harian Hunan". Bagus memang, tapi rasanya belum cukup. Kami semua terdiam, sebelum akhirnya Gang Xian memberikan usul. "Kenapa kita tidak pergi ke jalanan dan melihat contoh-contoh," katanya. Malam itu pertama kalinya saya tidak tidur di rumah. Semalaman kami keluyuran melihat-lihat berbagai poster. Tembok bangunan-bangunan yang kelabu di jalan-jalan utama Changsha kini diselaputi kertas putih bertulisan macam-macam. Etalase-etalase tertutup poster. Sudah menjelang fajar ketika kami menempelkan karya-karya kami. Sembari mencuci tangan bekas lem di baskom, saya membayangkan betapa nanti orang-orang akan menyebut kami Perintis Jalur Revolusi. Kami mengambil kertas kosong lalu membubuhkan tanda tangan masing-masing di situ. Lantas kami berpisah. Saya pulang bersama Li Kecil, dan tidur sampai siang esok harinya. Tapi kebanggaan saya tak berlangsung lama. Suatu kali, saya dan Li Kecil merasakan sebuah perubahan: anak-anak dalam gerombolan kami menyatakan keluar, dengan sikap keras dan mencemooh. Wajah mereka yang mencibir - seperti wajah semua orang yang kami temui - segera menandakan bahwa ada yang tak beres. Perasaan kami mengabarkan, kami disisihkan - dan suatu perubahan telah terjadi. Ada kecaman beredar di belakang kami. Keanehan tak lama akhirnya terungkap. "Siapa yang mau bergabung dengan anak-anak revisionis?" ujar seorang anak yang mulanya bergabung dengan kami. "Kritiklah ayah kalian sendiri, dan bersiaplah membuat kritik diri." kata van lain. Saya maklum apa maksud kata-kata itu, dan kami - saya dan Li Kecil - memburu lari ke tembok kritik tempat poster kecaman lazim ditempelkan. Dan di sanalah kami menemukan semua kelaknatan itu. Saya dan Li Kecil, dengan hati berdegup keras, membaca kritik-kritik tajam yang dilontarkan kepada ayah kami. Saya tak sempat membaca habis kritik itu: air mata mengaburkan semua pemandangan saya. Dan ketika saya berpaling, Li Kecil sudah meraung merabai poster - ia sudah lama tak lagi membaca. Seluruh kebanggaan kami runtuh tiba-tiba - dan sebagai gantinya muncul sebuah penderitaan yang bagai akan memecahkan dada. Ketika itu kami belum lagi menyadari apa risikonya, dan kecemasan kala itu belum lagi muncul. Diburu malu dan duka yang mendalam, kami berlari pulang dengan masih menangis. Sesampai di rumah, saya menabrak pintu dan memburu masuk mencari Ayah. Sebuah rasa marah yang tak tertahankan membuat saya kalap dan menyiapkan cercaan keras. Bukan lagi demi revolusi - tapi demi kenistaan yang kini saya tanggungkan karena dia. Saya menemukan Ayah duduk diam bagai tafakur di meja makan. Agaknya, ia maklum apa yang telah telah terjadi. Kata-kata saya pun menghambur. "Apa, apa artinya semua ini, Ayah," raung saya. "Mengapa tidak kau katakan sejak dulu, kau antirevolusi?" Suasana tegang. Ayah menatap saya dengan tajam, walau ia tidak tampak marah dan seolah mengerti dan memaafkan - kata-kata saya yang kasar. "Kita harus percaya pada kata-kata Ketua Mao," katanya kemudian dengan tegas, tapi agaknya dengan kebingungan yang sarat. Saya tak puas dengan jawaban itu - menganggapnya tak menuju ke persoalan. Saya kemudian memberondong Ayah dengan sejumlah pertanyaan yang berbelit, karena memang itulah keadaannya. Saya bertanya apakah Ayah menerima kesalahan itu. Ia tak menjawab. Saya menanyakan adakah kesalahan Ayah kini ada hubungannya dengan kesalahan Ibu. Ia juga tak menjawab. Dan ketika saya mulai mempertanyakan Ketua Mao, sebuah tamparan mendarat di pipi saya. Seketika saya sadar dari keadaan kalap. Suasana jadi hening, dan saya meraung dalam dekapan Ayah, menghabiskan sesal yang tak seluruhnya saya mengerti. Saya merasakan, Ayah menangis juga. Sesudah itu, keadaan menjadi lebih tenang. Juga ketika Liang Fang pulang dengan raungan yang sama kerasnya dengan tangis saya tadi - Liang Fang menghunjamkan diri ke tempat tidur dan menghabiskan tangisnya di sana berjam-jam. Sesudah reda, kami mendengarkan keluhannya dan saya, juga adik saya, Liang Wei-ping, tak mampu menahan tangis lagi. Liang Fang lebih dewasa ia menguraikan penyesalannya tanpa bertanya-tanya mengapa Ayah dikritik. Liang Fang lebih menanyakan nasib. Kata-kata Liang Fang perlahan-lahan membangun kesadaran saya: memang ada garis malapetaka yang tak kunjung habis. Bagi Liang Fang, garis itu nyata. Mula-mula ia harus berjuang di sekolah melawan citra buruk yang didapatnya dari kesalahan Ibu. Dan kini, ketika perjuangan itu hampir diatasinya dengan berhasil, kecaman pada Ayah seperti memperpanjang "dosa turunan" yang membebaninya - sementara ia sebenarnya tak berbuat apa-apa. Sejak itu, kami sekeluarga tersisih dari derap revolusi. Saya tak lagi diperkenankan berjuang betapa pun saya ingin - karena darah revisionis yang diturunkan pada saya. Dan saya, dengan jiwa berang seorang anak yang harus senantiasa siap menghadapi pertarungan bila kecaman datang, tak mampu menahan hinaan. Suatu ketika sekelompok anak gelandangan kelompok yang di masa itu tak diragukan citra revolusionernya - bukan cuma melemparkan hinaan, tapi juga batu dan tong sampah ke jendela rumah kami. Saya cuma mampu menahan diri beberapa saat. Pertarungan tak bisa dihindari, dan saya harus menerima akibatnya: babak belur. Ayah seperti hilang dari peredaran Changsha. la tekun di rumah mempelajari ajaran Mao berulang-ulang. Kendati begitu, saya yakin bahwa ia tak merasa bersalah. Ada sikap yang teguh dalam hatinya bahwa prinsip yang dipegangnya tak menyalahi alaran Mao yang sesungguhnya. Apa yang pernah dilakukannya, antara lain mengajarkan sistem jurnalistik modern, pada dasarnya adalah ikhtiar memajukan Cina. Ayah, misalnya, tak membakar buku-buku yang mengandung foto Liu Shao-qi - yang bergambar bersama Mao - melainkan menyerahkannya kepada para pengkritik. Ayah juga tak memusnahkan buku-buku yang dianggapnya bisa memajukan Cina, betapapun buku-buku itu disebut antirevolusi. Ayah juga tidak membakar sebuah lukisan kuno yang dianggapnya menggambarkan kebesaran Cina masa lalu. Lukisan itu tergantung dengan tenang di ruang tamu. Namun, keyakinan teguh yang tak diutarakan itu yang bagai keangkuhan tersembunyi - runtuh juga pada akhirnya. Suatu malam serombongan Pengawal Merah, yang terdiri dari anak-anak belasan tahun, menyerbu rumah kami. Saya tak tahu siapa mereka dan dari kelompok mana, karena mereka menutup wajah dengan kain hitam. Bahkan Liang Fang yang ketika itu juga Pengawal Merah tak bisa mengetahuinya. Rumah kami porak-peranda. Seluruh isinya dijungkirbalikkan, semua sudut digeledah. Buku-buku Ayah, termasuk lukisan kuno kesayangannya, dikumpulkan di ruang makan dan dibakar. Ayah diam saja - tak mampu berbuat apa-apa. Tapi saya tahu hatinya merintih - ia harus menghadapi anak-anak remaja yang tak mengerti apa yang mereka teriakkan. Penderitaan Ayah tak cuma sampai di situ. Pengawal Merah yang menyerbu itu tak menyisakan kemungkinan penistaan sedikit pun. Keyakinan Ayah yang dipendam dalam-dalam tak terhindar dari lirikan para Pengawal Merah yang mabuk kekuasaan, yang merasa mampu berbuat apa pun dan merasa mempunyai hak atas segala hal. Hinaan pun lengkap. Ayah dipaksa mencaci primsip-prinsipnya - entah apa itu. Setengah berlutut, dengan suara terbata-bata seperti merintih dan saya yakin dengan penderitaan batin yang mahaberat - kata-kata pun keluar satu-satu. Saya menangis sedih sekali, juga Liang Wei Ping. Liang Fang tak di rumah ketika itu. * * * Bulan demi bulan berlalul dengan kekosongan. Tapi keadaan pun berubah. Penduduk dan para pengkritik mulai melupakan Ayah yang seperti hilang. Dan karena itu kami, anak-anaknya, entah disadari entah tidak, tak diusir dari berbagai kegiatan revolusioner. Liang Fang sudah ditasbihkan menjadi Pengawal Merah - dan Ayah sangat bangga karenanya. Saya pun bisa mengikuti berbagai acara revolusioner tanpa diperhatikan. Cacian sudah banyak mereda. Maka, sebuah usaha rehabilitasi dimulai lagi. Liang Fang berusaha mati-matian menyucikan namanya, dan dengan tegar mengacuhkan kami, keluarganya. Sementara itu, saya membiarkan diri mengikuti arus. Awal September, mahasiswa, guru-guru yang revolusioner, dan murid-murid sekolah menengah diizinkan melakukan perjalanan ke pelbagai tempat dalam rangka "pertukaran pengalaman". Dalam waktu singkat seluruh kereta dan bis-bis antarkota penuh sesak. Tapi segera sebuah tahapan baru dimulai: perjalanan jarak jauh dengan jalan kaki. Itu dimulai oleh mahasiswa Institut Perkapalan Dalian. Perjalanan itu mereka maksudkan sebagai sarana penggemblengan anak-anak muda - dan penyelamatan negara dari kebangkrutan akibat biaya perjalanan. Bangsa Cina berubah menjadi aktor: kami semua membikin-bikin perjalanan yang penuh kesusahan seperti Long March Tentara Merah 30 tahun silam. Ada pilihan: berjalan menembus Pegunungan Jinggang dan Distrik Ruijing (tempat dulu Tentara Merah pada 1934 bergerilya dan sukses menggempur tentara Kuomintang), atau melakukan tapak-tilas Long March yang dipimpin Ketua Mao dulu sepanjang 25.000 li, atau berjalan dari Yanan ke Peking seperti yang ditempuh pasukan komunis yang membawa kemenangan di tahun 1949. Kami berpakaian seragam abu-abu, meniru pakaian yang dulu dikenakan para tentara sungguhan. Mengenakan sandal jerami, dan membawa beban. Mestinya saya tidak boleh ikut lantaran saya baru 12 tahun. Tapi untung ada Peng Ming, anak tetangga yang dulu dapurnya menjadi satu dengan dapur keluarga saya, yang mudik dari Beijing. Di Ibu Kota, Peng Ming adalah mahasiswa Jurusan Komposisi Institut Musik Pusat. Dialah yang menyarankan saya ikut. Sebagai anggota Pengawal Merah, Peng Ming saya kagumi. Buktinya, ia juga tahu banyak hal dibanding kami, termasuk bagaimana mengorganisasikan grup gerakan jalan kaki jarak jauh. Dengan gayanya yang memikat, sembari menggerak-gerakkan tangan, Peng Ming menjelaskan bahwa kami akan menempuh jarak sepanjang 800 li (sekitar 240 mil) menuju puncak Pegunungan Jinggang. Liang Fang, kakak saya, akhirnya juga memutuskan untuk ikut dan mengajak saya. Ayah memberi izin, dan saya senang bukan main. * * * Setelah kegiatan long march selesai, saya dan kakak saya sempat mampil di Guangzhou - kali ini sudah dengan kendaraan. Sekolah menengah belum mulai pelajaran karena sibuk terlibat revolusi. Maka, sementara kakak saya pulang ke Changsha, saya ingin mewujudkan impian besar saya: pergi ke Beijing. Di sana saya akan ketemu Peng Ming lagi. Di Beijing saya langsung mencari Institut Musik Pusat yang berada di Distrik Barat. Tentunya Peng Ming aktif pula dalam organisasi perjuangan yang memiliki stasiun radio di dekat asrama sekolahnya. Saya ke sana. Di balik kaca, Peng Ming dan kawan-kawannya tampak sibuk mendiskusikan sesuatu. Saya menunggu, takut mengganggu. Tapi begitu ia melihat saya, langsung senyumnya terbuka lebar dan bergegas keluar menyalami saya dengan hangat. Ia tampak lebih kurus, tapi masih tetap anggun dengan seragam Pengawal Merah-nya. "Kamu datang tepat pada waktunya. Ikutlah bekerja dalam organisasi Pengawal Merah kami. Melancarkan revolusi bersama kami," katanya. Saya pun dikenalkan kepada kawan-kawannya. "Kamrad," katanya. "Ini dulu bekas tetangga saya waktu ikut gerakan long march dia merupakan anggota paling muda. Ia datang jauh-jauh dari Hunan untuk membantu kita." Sejak itu, saya mendapat panggilan sebagai Hunan si Kecil. Hari-hari itu, satu hal yang membuat orang merasakan ekstase adalah melihat tampang Ketua Mao. Sejak saya di Beijing, kemungkinan itu rasanya menyembul-nyembul mengganggu pikiran saya. Dan seperti anggota Pengawal Merah lainnya, saya pertaruhkan kepala saya untuk mendapatkan kesempatan itu. Saya tergabung dalam Pengawal Merah unit pertunjukan, yang bertugas menyanyikan dan mengiringi lagu-lagu perjuangan revolusioner. Saya sudah bisa menarikan Tarian Kesetiaan untuk Ketua Mao. Sekali waktu saya juga diminta membawa drum atau instrumen lain. Peng Ming merupakan komposer utama dalam grup musik Institut Musik Pusat ini. Pada 1 Mei, Hari Buruh Internasional, kami serombongan menuju Lapangan Tien An Men. Pada harihari besar seperti itu, atau 1 Oktober, Hari Nasional, para pemimpin akan berada di panggung. Dan puluhan ribu anak muda berkumpul berebut melihat Ketua Mao. Begitulah. Karena gerakan terbatas, rombongan kami terdesak di barisan paling belakang ketika mendadak semua grup maju demi mendengar Ketua Mao tiba. Kami berdesak-desakan. Petugas keamanan dari depan menghadang massa. Tapi melihat gelagat barisan keamanan kami jadi curiga, janganjangan Ketua Mao muncul dari belakang. Dan ternyata benar. Dengan begitu, rombongan saya berada di barisan terdepan. Mobil Ketua Mao berjalan paling depan: sebuah jip tentara bernomor Beijing. Seperti dalam mimpi: saya melihatnya, memandanginya. Dia tampak sangat tinggi bagi saya, agung, benar-benar menakjubkan. Sementara itu, jip berlalu perlahan menembus massa, dia melambai-lambaikan tangan. Saya tidak bisa menguasai diri lagi, lalu menjerit seperti bayi, "Wahai jantung hatiku, matahariku yang paling gemilang!" Air mata membasahi wajah saya. Mobil Ketua Mao melintas, disusul kemudian oleh mobil Perdana Menteri Zhou. Setelah semuanya usai, orang-orang berlarian ke kantor pos untuk menelegram keluarganya di pelbagai pelosok Cina. Saya antre sampai dua jam untuk sekadar menuliskan kalimat: "Senja ini, pukul 9.15, saya menjadi orang paling bahagia di dunia". Saya tahu, Ayah tentu mengharapkan cerita yang lebih lengkap. Tapi itu tak mungkin. Dua hari kemudian saya menerima surat dari Ayah. la kangen dan menghendaki saya pulang. *** Menjelang akhir Revolusi Kebudayaan, dua pihak yang didukung kekuatan senjata saling bertentangan: kelompok Konservatif, yang tidak menerima dikritik, dan Pemberontak. Segera setelah saya kembali ke Changsha, saya sadar bahwa kekuasaan berada di tangan Pemberontak. Ketua Mao dan Direktorat Revolusi Kebudayaan mengumumkan lewat radio dukungan kepada mereka, dan mengirimkan bantuan berupa sepasukan tentara dari Satuan 47 yang bertaraf nasional. Orang-orang Konservatif pada lari mengungsi - dengan berjalan kaki - ke Xiangtan, Zhuzhou, dan ke kota-kota terpencil. Para Pemberontak menguasai sisi barat sungai yang membelah Changsha. Di sana ada Universitas Hunan, Sekolah Guru Hunan, dan Kelas Studi Ketua Mao pusat pendidikan cuci otak. Liang Fang setiap hari tidak di rumah, terlibat dalam gerakan pembersihan. Ayah - yang kini dirumahkan sehubungan dengan tuduhan sebagai intelektual tengik, dan pernah pula menikah dengan istri yang kekanan-kananan - menghendaki saya dan adik saya, Lian Wei Pin, tidak keluar rumah, tapi tinggal bersama dia. Sejak tentara melibatkan diri dalam pertentangan antarkelompok, banyak rakyat biasa yang bersenjata. Dan karena mereka tidak becus menggunakannya, tembakan nyasar dan tak bertanggung jawab tak terhitung lagi. Lebih dari itu, sering terjadi tembak-menembak antara para Pemberontak dan kelompok lain yang tak jelas lagi aliansinya. Kota makin rusuh. Darah memercik di mana-mana, sirene mengaung setiap saat. Tak ada lagi tatanan sosial. Untung, akhirnya keganasan akibat persaingan kelompok itu bisa dikuasai. Pada September 1967 Mao mengunjungi provinsi-provinsi, mengimbau supaya pertarungan dihentikan. Mahasiswa dan pelajar diminta kembali ke bangku belajar dan menyerahkan senjata kepada tentara yang tiba-tiba seperti berbalik memerangi Pemberontak, dan berusaha menguasai keadaan. Setiap provinsi kemudian didesak untuk memperkuat Persiapan Komite Revolusioner yang dibentuk bulan Agustus, yang terdiri dari wakil-wakil semua kelompok. Ini untuk mendukung persatuan dan pemerintahan pasca-Revolusi Kebudayaan. Tentu saja, dalam kenyataannya maklumat pemerintah tidak semudah itu dilaksanakan. Pelbagai golongan yang dulu bertikai tidak mudah melupakan masa lalu. Rakyat pun sadar, dalam perserikatan besar tersebut pemegang kekuasaan yang sebenarnya adalah tentara. Dan tentara tidaklah populer, sehubungan dengan bakatnya untuk konservatif. Untuk memperbaiki hubungan antara rakyat dan tentara, dilancarkan kampanye dengan soganslogan seperti: "Rakyat mendukung tentara", dan "Tentara mencintai rakyat". Di Hunan, tak sampai bulan April 1968, Komite Revolusioner terbentuk di mana-mana. Tapi itu tak lepas dari lankah awal yang diambil Persiapan Komite Revolusi bulan Oktober tahun sebelumnya. Langkah yang ditentukan adalah: "Berjuang, Mengkritik, Berunah". Yaitu menggempur semua unsur penempuh jalur kapitalis di setiap unit, dan memulihkan struktur pemerintahan lama. Dengan demikian, Revolusi Kebudayaan diarahkan kembali ke tujuannya yang asli. Semua kader yang "memendam masalah" - seperti Ayah - diberi kesempatan mengikuti program di Kelas Penelaahan Pemikiran Ketua Mao di seberang sungai. Bagi keluarga saya - yang selama ini terkucil - kesempatan Ayah untuk masuk asrama itu merupakan awal baru. Ketua Mao mengimbau, semua lulusan sekolah menengah pertama dan menengah atas "bangkit dan pergi ke pegunungan dan desa-desa". Yang segera membubuhkan tanda tangannya bersedia pergi dianggap menunjukkan kesetiaannya kepada Ketua Mao. Yang ragu-ragu membuktikan sikap politiknya diminta mundur. Murid-murid sekolah menengah di Changsha bisa memilih desa yang dituju di antara tiga distrik. Tapi mereka juga boleh menentukan desa tempat saudaranya tinggal. Sejumlah besar mengikuti anjuran. Tapi yang mendesak mereka untuk menerima tawaran itu sebenarnya keinginan menghindari suasana kota yang rudin akibat krisis, dan memulai hidup baru. Tapi kenyataan di pedalaman ternyata tidak sesuai dengan romantisme anak-anak muda itu. Grup pertama yang berangkat mengabarkan keadaan yang menyedihkan, dan program "naik ke pegunungan dan turun ke desa" tidak lagi diikuti secara sukarela. Toh tak ada pilihan lain. Pada Januari 1968, Liang Fang menyatakan kesediaannya pergi ke Kabupaten Jing, Hunan Barat. Distrik perbukitan kasar itu pilihan para anggota Pengawal Merah yang, karena orangtuanya kena kritik, ingin menghindar sejauh mungkin dari masyarakat kota yang mencemoohkan mereka. Liang Fang sudah menyerah terhadap keadaan akibat Revolusi Kebudayaan. Liang Fang berpikir, dengan pergi ke daerah paling miskin itu ia bisa mengenal Cina dan mempelajari sesuatu. Ia benar-benar percaya bahwa ia bisa memberikan bantuan untuk pembangunan desa, menjadi mesin utopia komunis. Sedang Liang Wei-ping, karena ragu-ragu akan kesanggupannya menghadapi kekerasan alam Hunan Barat, memilih Distrik Yuanjiang - dekat Danau Dongting dan Provinsi Hubei. Ia termasuk kelompok pertama yang menandatangani ikut pergi ke desa di antara teman-teman sekolahnya. Rumah terasa lengang sekali. Saya, dalam usia 13 tahun, tidak bisa betah di rumah membaca karya-karya Ketua Mao - bagaimanapun usaha saya untuk menyenangkan Ayah, yang menganjurkan saya untuk terus menekuninya. Saya merasakan, ada yang berubah di dalam diri saya. Segala keganasan revolusi telah membuat saya bebal, tak perduli lagi apakah harus ikut berpartisipasi dalam revolusi ataukah tidak. Keluarga saya telah berkorban demikian banyak, toh tak ada artinya sama sekali. Saya ingin melemparkan diri ke kehidupan yang lebih menggetarkan, di jalanan - bersama orang-orang gelandangan. Tak peduli lagi apakah akan pulang masih dalam keadaan hidup atau hanya nama. Saya pikir, tak akan ada seorang pun yang menggubris saya. Buat apa saya mesti hati-hati lagi? Sudah sejak usia tiga tahun saya tercekik akibat revolusi. Maka, musim semi yang dingin, 1968, saya mulai petualangan saya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini