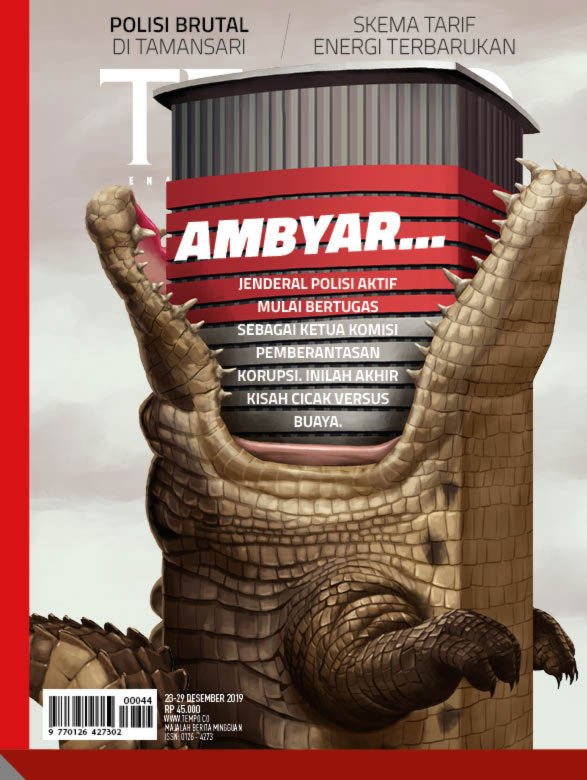Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita
Kepuasan dan klimaks tiap kali orang berjalan ke puncak gunung adalah ekspresi perasaan mistik serta kekaguman kepada yang transenden.
Ketika berada di puncak, kita menjadi tahu: bukan kejayaan yang ada di sana, melainkan diri sendiri.
Gunung bukanlah sebuah area atau kawasan yang bisa kita jadikan budak di bawah tujuan-tujuan eksistensial dan kebebasan kita, persis karena gunung juga memiliki kebebasan intrinsik yang mesti kita hargai.
MENGAPA orang naik gunung? Bersusah-susah membawa tubuh, menanggung beban, menempuh jarak, mencapai ketinggian dengan risiko kematian, hanya untuk meluncur kembali ke dasar dalam kelelahan yang sia-sia? Filsafat menyediakan setidaknya tiga pandangan untuk menjawab pertanyaan ini: transendental, antroposentrisme, dan diri-ekologis.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo