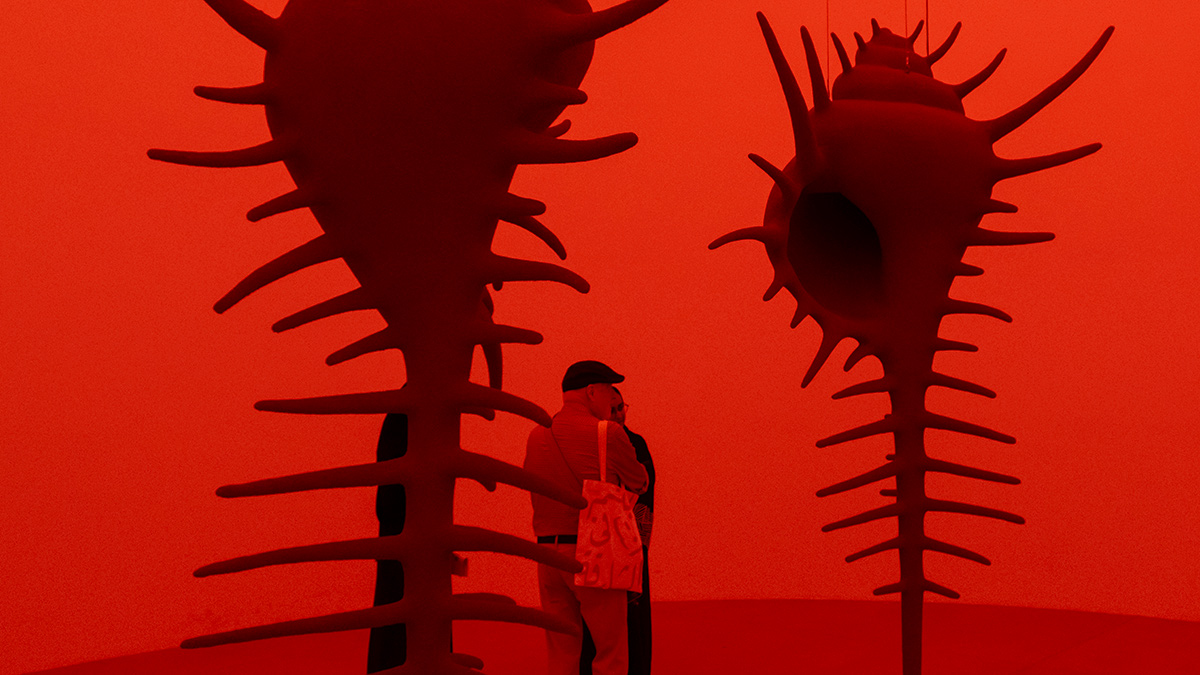Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

KETIKA Wahyu Dhyatmika, biasa disapa Komang, baru saja menginjak lantai dua rumah makan Satay House Senayan, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Wahyu Muryadi mendekat. Ketika itu malam menjelang hari pertama puasa 2009. “Kamu lulus program M2, selamat,” kata Wahyu, yang saat itu menjabat redaktur eksekutif. Komang mengira itu ucapan selamat biasa. Dia tersenyum. Tapi tiba-tiba, byurrrr, tubuhnya diguyur air putih, cendol, es teh, es jeruk, es kelapa, bahkan air kobokan.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo