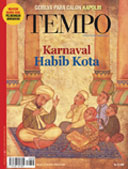Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mencari kehidupan yang lebih baik adalah fitrah manusia. Juga yang terjadi pada keturunan pasangan Fatimah az-Zahra anak pe rempuan Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abi Thalib. Husein, cucu Rasulullah, dibantai secara keji pada saat Yazid bin Muawiyah berkuasa, di Karbala, Irak. Keturunan setelah itu juga tak lepas dari ancaman dinasti yang berkuasa. Sampai pada masa kekhalifahan Bani Abbas, yang berkuasa sejak abad ke-8 sampai 13 Masehi.
Ahmad bin Isa, keturunan ke-10 dari pohon keluarga Nabi Muhammad, hi jrah dari Basrah, Irak, ke Hadramaut, jazirah selatan Arab. Hadramaut dipilih karena tanahnya subur. Ahmad wafat di Hasisah pada 345 Hijriah. Dua generasi keturunan setelah Ahmad yang beranak-pinak di Hadramaut dinamakan Alawiyin dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa.
Di Hadramaut, keturunan Nabi Muhammad itu juga tidak menjalani kehidupan mudah. Penduduk asli masih mendahulukan kesukuan dan membenci kaum Alawiyin. Kaum pindahan itu lalu terpojok tinggal di tempat-tempat tandus. Mereka mendirikan pesantren (rubat), perpustakaan, masjid, dan majelis taklim. Namun, agar mengikis kebencian penduduk lokal, Muhammad Faqih al-Muqaddam, keturunan Ahmad bin Isa, memilih mazhab yang lebih bisa diterima, Syafii. Sepeninggal Muhammad Faqih al-Muqaddam, yang wafat pada 653 Hijriah, keturunannya menyebar melintasi samudra ke Afrika Timur, India, Malaysia, Thailand (Siam), Indonesia, Tiongkok (Cina), Fi lipina, dan sekitarnya.
Menurut Ali Yahya, seorang peneliti habib, keturunan Ali bin Abi Thalib yang menyebar ke seantero kawasan Asia Tenggara itu selalu berkaitan dengan Indonesia. ”Habib yang berada di Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Thailand Selatan selalu ada kaitannya dengan Indonesia,” katanya kepada Tempo. Misalnya orang tua, kakek, atau dia dulu lahir di Indonesia. ”Indonesia ini menjadi shelter habib di timur jauh yang keluar dari Hadramaut. Sebagian referensi, Indonesia disebut Al-Mahjar at-Tsani, tempat hijrah yang kedua,” kata Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Alkisah ini.
Di bawah ini beberapa kisah habib sukses di daerahnya masing-masing.
Habib Abdurrahman bin Abdullah al-Habsyi, Palembang
Memasuki daerah 9 sampai 14 Ulu tampak nama kampung yang berbau Arab: Lorong Al-Munawar, Al-Hadad, Al-Habsy, dan Al-Kaaf. Sedangkan di Kelurahan 16 Ulu ada kompleks Assegaf. Itu adalah nama marga keturunan Alawiyin dari Hadramaut. ”Ada catatan yang menyatakan ke mana pun orang Hadramaut pergi, mereka datang ke Palembang dulu, baru menyebar ke daerah lainnya di Nusantara,” tutur Ali Yahya, seorang peneliti tentang habib.
Di Palembang, para habib ini disebut Ayib. Awalnya, kebanyakan mereka berprofesi sebagai pedagang perantara. Seiring dengan waktu, mereka kemudian menetap dan menikah dengan penduduk Palembang, sehingga mereka lebih merasa sebagai ”wong kito” dibanding orang Hadramaut. Mereka berkumpul dan mendirikan rumah di sepanjang Sungai Musi, di seberang Ilir maupun Ulu.
Jejak yang masih ada, Gerbang Pesantren Ar-Riyadh, terlihat jelas dari arah Pasar 10 Ulu. Pesantren ini salah satu peninggalan Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah al-Habsyi. Lahir di 13 Ulu pada 1310 Hijriah dari pasangan Habib Abdullah bin Aqil al-Habsyi dan Zainah bin Muhammad Al-Haddad, Habib Abdurrahman al-Habsyi sosok yang tidak asing bagi warga Palembang. Sejak usia lima tahun tertarik mempelajari Al-Quran melalui guru-gurunya. Tradisi para salaf, yang masih begitu kental pada masa itu, membentuk karakternya sebagai seorang yang akrab dengan pendidikan agama.
Pada usia 10 tahun, Abdurrahman dikirim ke Hadramaut untuk menggali ilmu dari Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi, penggubah Maulid Shimtud Durar, di Rubat (Pesantren) Sewun. Setelah empat tahun, Abdurrahman pulang ke Palembang. Selain bekerja dan berdagang untuk menghidupi keluarganya, Abdurrahman mendirikan Pesantren Ar-Riyadh, yang masih ada hingga kini.
Untuk memperluas wawasan dan jaringan, Abdurrahman berhubungan dengan habib dari Pulau Jawa, seperti Habib Abdullah bin Muhsin al-Athas, Empang, Bogor, dan Habib Ali bin Abdurrahman al-Habsyi, Kwitang, Jakarta. Selain itu, Abdurrahman menjalin persahabatan dengan ulama Timur Tengah, As-Syekh Muhammad Abduh, dan muridnya, As-Syekh Muhammad Rasyid Ridho dari Mesir.
Abdurahman dimakamkan di Pekuburuan Naga Swidak 14 Ulu, Palembang. Tiap awal bulan Rabiuts Tsani (Rabiul Akhir), khoul atau tanggal kematiannya diperingati. Pada saat itu juga, anak cucu dan keturunan Abdurrahman memanfaatkan untuk melangsungkan pernikahan.
Menurut Zein bin Umar cucu Abdurrahman al-Habsyi, kegiatan Majelis Taklim Ar-Riyadh diteruskan oleh cucu-cucunya setiap Jumat lepas asar. Acara itu dihadiri 200-300 orang. ”Memang kalah banyak dibandingkan dengan majelis taklim di Jawa, tapi di daerah ini jumlah itu sudah termasuk banyak,” katanya. Ribuan santri Ar-Riyadh menyebar ke Jambi, Talang Betutu, dan kawasan sekitarnya. ”Kelebih an pesantren ini alumninya bisa berbahasa Arab,” ujar Zein, yang juga salah satu pengurus Pesantren Ar- Riyadh.
Habib Lutfi, Pekalongan, Jawa Tengah
Daerah pesisir yang didatangi para habib selepas dari Palembang, selain Jakarta, adalah Pekalongan, Jawa Tengah. Tokoh di sana adalah Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib al-Athas. ”Mereka ditampung, diberi biaya untuk dakwah dan merantau ke daerah-daerah lain sampai Palu, Papua,” kata Ali Yahya.
Ahmad yang lahir di Hajrein, Hadramaut, sekitar 1835 Masehi, meninggal pada 1929 dan dimakamkan di pekuburan Sapuran, Pekalongan. Setiap peringatan haulnya, 15 Syakban, ratusan ribu orang datang dari berbagai penjuru. Selain Ahmad, peletak dasar pendidikan kaum Alawiyin di Pekalongan adalah Muhammad bin Abdurrahman Baragbah. Cuma namanya tak menonjol.
Kini habib yang paling top di Kota Batik itu adalah Muhammad Lutfi bin Yahya. Abdurrahman Wahid, saat menjadi presiden, sangat hormat dan sering mengunjungi kediamannya di Gang VII, Kampung Noyontaan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan petinggi di republik ini juga sering minta ”petunjuk” Ketua Tariqah Mu’tabarah an-Nahdiyah (semacam asosiasi tarekat Nah dlatul Ulama) ini. ”Mereka datang ke sini dalam kapasitasnya sebagai umat Islam. Saya tak mengundang, tapi masak pe jabat datang diusir,” kata Lutfi kepada koresponden Tempo, Edi Faisol.
Tiap hari ratusan orang datang mengunjunginya. Tak jarang jika ada acara, Jalan Dr Wahidin, salah satu jalan terbesar di Pekalongan yang menghubungkan Gang VII, harus ditutup total untuk menampung jemaah. Lutfi menetap di kampung permukiman padat itu sejak 1971. Materi kajian tarekat di Kanzul Sholawat begitu nama tempatnya tak hanya mengkaji syariat, tapi juga kecintaan terhadap Tanah Air dan wawasan kebangsaan. ”Karena itu bagian dari ajaran tarekat yang mengajak pada kemaslahatan,” ujar Lutfi. ”Islam bukan milik bangsa Arab atau Jawa saja, tapi semua manusia dan umat di dunia.”
Habib Neon, Surabaya
Dikisahkan, Habib Muhammad Husein Alaydrus pernah menghadiri majelis taklim di sebuah masjid di Surabaya. Menjelang kedatangannya, listrik di tempat pengajian padam. Panitia kebingungan. Tapi, aneh bin ajaib, saat Husein Alaydrus memasuki masjid, tiba-tiba menjadi terang benderang laksana disinari cahaya lampu neon, meski listrik masih mati. Sejak saat itu Husein Alaydrus terkenal dengan julukan Habib Neon. Dan hingga kini, makamnya di Pemakaman Umum Pegirian, Surabaya, tak pernah sepi dari peziarah.
Orang percaya, lampu neon tanpa kabel yang dipegang Husein Alaydrus bisa menyala seketika. Sampai sekarang, kisah itu terkenal di sekitar kampung Arab di Surabaya, seperti Nyamplungan, Pegirian, Ampel, dan Panggung. Putra ketiga Habib Neon, Habib Syekh bin Muhammad Alaydrus, 65 tahun, mengakui nama Habib Neon lebih dikenal masyarakat daripada nama aslinya. Mengenai kelebihan yang dimi liki mendiang ayahnya, Syekh tak mau banyak bicara. ”Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah,” katanya.
Husein Alaydrus, yang lahir pada 1888, datang dari Tarim, Hadramaut, Yaman. Menurut Muhammad Alaydrus, ayahnya itu dikirim ke Indonesia saat masih berusia 20 tahun. Sebelum menetap di Surabaya, Husein Alaydrus sempat tinggal di Singapura dan Palembang selama lima tahun. Di Palembang Husein menikah dengan sepupunya, Aisyah binti Mustafa Alaydrus, dan dikaruniai tiga anak. Setelah itu, mereka pindah ke Pekalongan sebelum akhirnya menetap di Ketapang Kecil, Surabaya.
Habib Neon berdakwah dari kampung ke kampung mendirikan majelis burdah, yakni mengaji kitab-kitab burdah setiap Kamis malam. Menurut Muhammad Alaydrus, awalnya majelis itu hanya diikuti oleh 4-5 orang. ”Lama-lama jemaahnya makin banyak,” katanya. Bahkan, setelah meninggal di usia 71 tahun, dan pengajian burdah dite ruskan Muhammad, pengikut tetap banyak, 300-500 orang setiap pekan.
Ketenaran Habib Neon membuat hari peringatan wafatnya yang diadakan setiap Rabiul Awal selalu banjir hadirin. Menurut Muhammad Alaydrus, mereka datang dari semua kalangan, mulai rakyat jelata hingga pejabat.
Habib Sholeh, Tanggul, Jember, Jawa Timur
Cuaca dingin akibat hujan deras yang terasa menusuk tubuh tak membuat Sugiman, 44 tahun, dan delapan orang lainnya beranjak. Di ruang Masjid Riyadhus Shalihin yang mirip pendapa tanpa dinding, mereka terus bertadarus (membaca Al-Quran). Di belakang masjid, ada makam Habib Sholeh bin Muhsin al-Hamid, yang dikenal alim pada masanya. Kompleks itu hanya sepelemparan batu arah selatan Stasiun Tanggul di Kampung Kauman, Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur. ”Beribadah di sini membuat saya dan keluarga lebih tenang, meskipun kami orang tak punya,” kata Sugiman, buruh tani dari Desa Jatiroto Lor. Lelaki itu mengaku sudah lima tahun terakhir menghabiskan malam Ramadan di tempat itu.
Menurut juru bicara keluarga sekaligus cicit almarhum, Haidar bin Achmad al-Hamid, setiap Ramadan, masjid dan makam Habib Sholeh selalu lebih ramai. Warga datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Jember dan sekitarnya, bahkan juga dari daerah lain di Pulau Jawa dan luar Jawa. ”Mereka datang untuk beribadah dan berziarah,” katanya.
Habib Sholeh Tanggul, begitu namanya dikenal, adalah salah seorang yang dihormati di kalangan habib. Tak aneh jika acara haul almarhum tiap tahun dihadiri lebih dari 10 ribu orang. Mereka datang beragam kalangan, mulai dari orang biasa hingga pejabat negara. ”Karena semasa hidupnya, almarhum selalu menerima siapa saja, tanpa pernah membedakan atau mengistimewakan tamunya. Hal itu tetap kami lestarikan sampai sekarang,” kata Haidar.
Menurut manaqib atau riwayat hidupnya, Habib Sholeh lahir di Korbah Ba Karman, Wadi ’Amd, sebuah desa di Hadramaut, Yaman Selatan, pada 1313 Hijriah. Orang tuanya, Habib Muhsin bin Ahmad al-Hamid terkenal dengan sebutan Al-Bakry al-Hamid dan Aisyah, dari keluarga Al-Abud Ba Umar dari Masyaikh al-’Amudi.
Pada usia 26 tahun (1921), Sholeh meninggalkan Hadramaut menuju Indonesia, bersama temannya, Syekh Fadli Sholeh Salim bin Ahmad al-Asykariy. Singgah beberapa hari di Jakarta, kemudian pindah ke rumah saudara sepupunya, Habib Muhsin bin Abdullah al-Hamid, di Lumajang. ”Tak lama kemudian, Datuk (sebutan anak cucu untuk Habib Sholeh), pindah ke Tanggul ini sampai akhir hayatnya pada 1976,” kata Haidar.
Di Tanggul, Sholeh muda mulai berdakwah dan berdagang kain serta pakaian. Lalu dia mendirikan majelis taklim dan mengelola Masjid Riyadhus Shalihin di atas tanah wakaf pemberian seorang warga kaya bernama Haji Abdurrasyid. Sholeh dikenal piawai menyampaikan dakwahnya dengan bahasa Indonesia, Jawa, dan Madura.
Habib Sholeh wafat pada 1976 di usia 83 tahun, meninggalkan enam putra-putri. Hingga kini majelis taklim di Masjid Riyadhus Shalihin diteruskan anak, cucu, dan cicit Habib Sholeh. Kegiatan majelis taklim rutin membaca wirid Ratibul Haddad selepas asar dan magrib, serta setiap malam Jumat Legi.
Habib Sholeh juga dekat dan dianggap guru oleh sejumlah politikus, penyanyi, hingga wakil presiden. Penyanyi Muchsin Alatas pernah belajar bahasa Arab dan tafsir Al-Quran kepadanya. Mantan wakil presiden Adam Malik juga punya kedekatan khusus dengan Habib Sholeh. Menurut Haidar, kedekatan itu bermula dari ancaman pembunuhan dari orang Partai Komunis Indonesia. Saat itu Adam, masih wartawan Antara, minta perlindungan kepada Habib Ali Kwitang. Habib Ali menyarankan Adam Malik mengungsi dan meminta perlindungan di rumah Habib Sholeh. Hanya sehari semalam di Tanggul, Adam disuruh kembali ke Jakarta. Habib Sholeh mengatakan Adam Malik akan aman jika tetap menjalan kan ibadah dan kewajiban sebagai muslim. ”Bahkan Datuk juga mengatakan Adam Malik akan menjadi pemimpin negara,” kata Haidar.
Setelah Adam menjadi wakil presiden, hubungan keduanya terus berlangsung. Adam pun selalu menyempatkan diri datang ke acara haul Habib Sholeh di Tanggul. Adam menganggap Habib Sholeh sebagai guru sekaligus bapaknya. ”Beliau sering pingsan jika berziarah ke makam,” kata Haidar mengenang.
Tiga Serangkai Habib, Jakarta
Abdullah, 50 tahun, percaya bila tak banyak habib dan majelis taklim di Jakarta, bencana besar akan datang. ”Untung saja Jakarta banyak habib, jadi seimbang dengan kemaksiatan yang ada,” katanya. Pendapat itu mewakili banyak penduduk Jakarta yang sering hadir setiap Ahad pagi di Islamic Centre Kwitang, Jakarta Pusat.
Islamic Centre Indonesia di Kwitang yang diresmikan Presiden Soeharto pada awal 1970-an boleh jadi majelis taklim pertama yang berani terang-terangan dan selalu dihadiri ribuan orang. Habib Ali bin Abdurahman al-Habsyi selalu memberikan kesempatan kiai lokal untuk berceramah di majelisnya. ”Sehingga kiai lokal yang semula hanya dikenal di lokalitasnya menjadi dikenal di berbagai tempat lain. Sehingga network antara kiai dan habib terbentuk erat,” kata Ismail Fajrie Alatas, kandidat doktor dari Universitas Michigan, Amerika Serikat, yang meneliti soal habib di Indonesia. Karena itu pulalah kini Habib Munzir dan Hasan bin Jakfar bisa menangguk massa anak muda Jakarta.
Habib Ali belajar ke Hadramaut saat masih usia 10 tahun. Selama enam tahun menyerap ilmu di negeri leluhurnya, pulang ke Indonesia kembali mereguk ilmu dari guru-guru yang ada di Jakarta, sembari berdagang dari kampung ke kampung sampai Bojong, Jawa Barat. ”Setiap pukul 11-12 dia tutup toko di Tanah Abang. Lalu dia naik kuda dan membawa beberapa dagangan dari kampung ke kampung di sekitar Betawi ini, sambil berdakwah,” ujar Ismail. Sampai sekarang majelis taklim di Kwitang masih berjalan, dipimpin cucunya, Habib Abdurahman bin Muhammad Al-Habsyi.
Selain Ali Al-Habsyi, Jakarta punya Habib Ali bin Husein al-Attas, yang dikenal sebagai Habib Ali Bungur. Tak seperti Habib Kwitang, Habib Ali Bungur, yang lahir di Huraidah, Hadramaut, lebih banyak mengkaji kitab. Sehingga murid hasil didikannya terkenal sangat pintar ilmu agama, bukan sekadar berbicara di atas mimbar. Karyanya yang kini masih dikenang dan menjadi kajian banyak cendekiawan muslim adalah Tajul Aras.
Yang ketiga adalah Salim bin Ahmad bin Jindan, yang dikenal sebagai ”si nga podium”. Dalam dakwahnya, dia tak segan-segan menegur pejabat yang lalai menjalankan amanat rakyat. Habib yang tinggal di Jalan Otista, Jakarta Timur, itu meninggal dalam usia 63 tahun, dan dimakamkan di daerah Cililitan, Jakarta Timur.
Ahmad Taufik, Arif Ardiansyah (Palembang), Kukuh S. Wibowo (Surabaya), Mahbub Djunaidy (Jember)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo