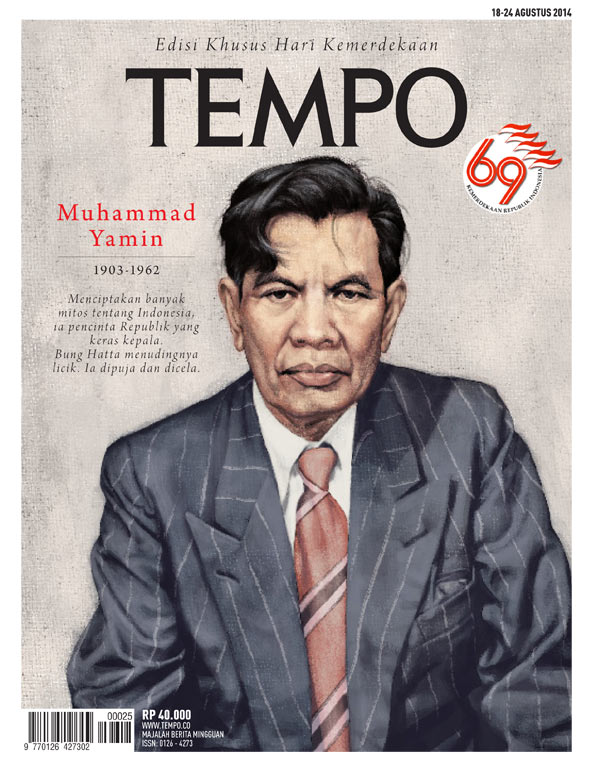Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bumerang itu berawal dari sebuah keputusan pada awal Juni 1951: Muhammad Yamin membebaskan 950 tahanan politik, hanya dua bulan setelah dia menjabat Menteri Kehakiman. Sebagian besar tahanan yang dia bebaskan adalah bekas anggota Laskar Bambu Runcing dan Gerakan Rakyat Revolusioner, kelompok pejuang rakyat yang dipimpin Chaerul Saleh. Mereka dibui rezim Sukarno karena dianggap berbahaya.
Tindakan sepihak Yamin menuai kecaman keras kalangan sipil, partai-partai oposisi, dan pers. Protes juga dilancarkan pihak tentara, terutama dari Divisi Siliwangi, dan berujung pada krisis di Kabinet Sukiman-Suwirjo. "Tapi Yamin itu gentleman. Ketika terjadi krisis, dia mengundurkan diri," kata sejarawan Restu Gunawan dalam diskusi dengan Tempo pada akhir Juli lalu.
Walhasil, jabatan sebagai menteri hanya dua bulan diembannya: 27 April-14 Juni 1951. Segera setelah Yamin mundur, Chaerul dan tahanan politik lain kembali mendekam di dalam tahanan tentara Siliwangi. Langkah blunder sang Menteri memang tak lepas dari kedekatannya dengan Chaerul Saleh.
Menurut Restu, Yamin dan Chaerul adalah karib dan teman seperjuangan. Hubungan keduanya terjalin sejak Chaerul bergabung dengan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Organisasi pemuda bercorak politik ini didirikan pada 1926 oleh Raden Tumenggung Djaksodipoera.
Sejak itu, hubungan Yamin dan Chaerul kian dekat. Chaerul amat mengagumi Yamin dan mengikuti setiap pidato politiknya. Chaerul pun tak putus memperhatikan pertukaran pikiran karibnya dengan tokoh nasional semacam Sukarno, Hatta, dan Soenario di asrama mahasiswa Menteng 31, Jakarta Pusat. "Akibat hubungan intens ini, terjalinlah persahabatan erat di antara mereka," ujar Restu.
Kekompakan Yamin dan Chaerul Saleh yang terbuhul sejak masa persiapan kemerdekaan berlanjut setelah Republik Indonesia berdiri. Ketika itu, Yamin memposisikan diri sebagai tokoh di luar pemerintahan. Ia kalah bersaing dengan teman-temannya, seperti Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, yang mengisi pos perdana menteri. "Orang luar melihat (Chaerul) seperti keponakan (Yamin). Mungkin karena sama-sama dekat dengan Tan Malaka," kata sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Taufik Abdullah.
Yamin kemudian menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh radikal, antara lain Tan Malaka, Sukarni, dan tokoh-tokoh Murba. Di sini, dia bertemu kembali dengan Chaerul. Keduanya sama-sama aktif di organisasi Persatuan Perjuangan yang diprakarsai dan dipimpin Tan Malaka. Tak kurang dari 141 organisasi menggabungkan diri ke Persatuan Perjuangan, yang dibentuk pada 4 Januari 1946 di Purwokerto .
Persatuan Perjuangan beroposisi terhadap pemerintah dan menuntut kemerdekaan Indonesia seratus persen. Mereka menolak sepenuhnya keberadaan Belanda di Tanah Air. Apalagi setelah Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia pasca-Proklamasi 17 Agustus 1945, entah melalui jalan diplomasi entah lewat jalur agresi militer.
Sebagai pemimpin pemuda, Chaerul tak pernah puas terhadap cara-cara berunding pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda. Ia terus melawan kebijakan pemerintah dari hasil perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, dan Konferensi Meja Bundar, yang dia anggap selalu merugikan Indonesia. Sikap mbalelo ini sempat menjadikannya buron politik ketika tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan ditangkap dan dihukum. Chaerul dan Adam Malik berhasil melarikan diri.
Tan Malaka dalam bukunya, Dari Penjara ke Penjara, menulis bahwa perjanjian Linggarjati dan Renville mengebiri kemerdekaan Indonesia dalam urusan luar negeri, kemiliteran, keuangan, perekonomian, dan kebudayaan. Indonesia tak lagi merdeka seratus persen, sesuai dengan tuntutan Persatuan Perjuangan. "Perjanjian yang tersebut di atas itu terang-terangan membawa Indonesia kembali ke status penjajahan, cuma dalam bentuk bungkusan baru," katanya.
Bagi kelompok oposisi, dua perundingan itu dinilai melanggar intisari Proklamasi. Dalam perjanjian Linggarjati yang diteken pada 25 Maret 1947 oleh Sutan Sjahrir, Belanda hanya mengakui wilayah Indonesia sebatas Jawa, Sumatera, dan Madura. Wilayah Tanah Air kian menciut menjadi hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera setelah perundingan Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948. Perdana Menteri Amir Sjarifuddin ketika itu memimpin delegasi Indonesia.
Perundingan Renville berdampak besar bagi kalangan militer. Puluhan ribu prajurit Divisi Siliwangi sejak 1 Februari 1948 dipaksa "hijrah" dari kantong-kantong gerilya di Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Begitu pula ribuan tentara di Jawa Timur, yang belakangan disebut Divisi Brawijaya, bergerak menuju tengah Jawa. Mereka berpindah lewat darat dengan kereta api dan melalui laut menumpang kapal.
Golongan tentara Republik, yang sempat terbelah antara pro dan kontra-Renville, semakin dirundung konflik akibat kebijakan Restrukturisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) yang dikeluarkan kabinet Hatta pada pertengahan Februari 1948. Mohammad Hatta—ketika itu merangkap jabatan sebagai wakil presiden, perdana menteri, dan menteri pertahanan—diangkat sebagai perdana menteri menggantikan Amir Sjarifuddin, yang dicopot karena dianggap gagal dalam perundingan Renville.
Kabinet Hatta, yang dilantik pada 31 Januari 1948, mengeluarkan kebijakan Re-Ra untuk mengurangi jumlah personel angkatan perang berkaitan dengan penghematan anggaran militer. Divisi Siliwangi mendukungnya, sedangkan divisi lain menolak. Restu mengatakan Divisi Siliwangi menyetujui kebijakan ini karena personelnya kebanyakan lulusan KNIL dan Peta—sehingga secara kepangkatan menjadi lebih baik setelah mengikuti Re-Ra.
Laskar-laskar rakyat mengambil sikap berbeda. Mereka, antara lain Laskar Bambu Runcing, Hizbullah, Sabilillah, dan Djakarta Raya, dengan tegas menolak kebijakan yang digodok Hatta bersama Kolonel Abdul Haris Nasution itu. Alasannya, banyak dari mereka yang tak memenuhi syarat. Kalaupun mereka diterima, pangkatnya akan turun beberapa tingkat dibanding para alumnus KNIL atau Peta. "Akhirnya, banyak anggota laskar menjadi preman," Restu menjelaskan.
Keberadaan laskar rakyat akhirnya justru mengganggu stabilitas. Mereka melakukan sejumlah pemberontakan. Padahal sebagian kelompok tentara rakyat telah terbentuk sejak zaman pra-kemerdekaan. Mereka dulu ikut memerangi Belanda ketika Tentara Nasional Indonesia belum terbentuk. Namun, menurut Restu, mereka kemudian angkat senjata dan berperang.
Itu sebabnya Sukarno dan rezimnya pada waktu itu menangkapi anggota laskar dan menjebloskan mereka ke penjara, termasuk Chaerul Saleh. Sejarawan Sutrisno Kutoyo dalam bukunya, Prof. H. Muhammad Yamin, S.H., mencatat bahwa sebenarnya pemerintah berencana membebaskan Chaerul. Ia akan dikirim belajar ke Jerman atau Swiss. Tapi Yamin rupanya tergesa-gesa. "Mereka memang terdapat banyak persamaan," tulisnya. "Watak dan ambisinya hampir sama," dia menambahkan.
Dalam buku Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan, Restu menulis bagaimana Chaerul ditangkap polisi setelah bersama laskar rakyat melawan tentara Indonesia dan tentara Belanda di daerah Banten. Ia sempat kabur ke Bogor, kemudian ke Jakarta. Di Ibu Kota, saat dia tengah jatuh sakit, polisi menangkap dan menjebloskannya ke tahanan di Gang Tengah. Ia sempat dipindahkan ke Glodok, Jakarta Barat, dan Banceuy, Bandung. Kisah pejuang dan tokoh politik Indonesia kelahiran Sawahlunto, Sumatera Barat, itu berakhir di penjara Nusakambangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo