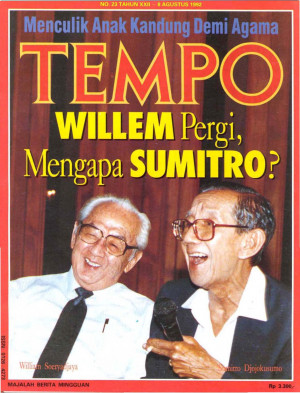DI sebuah rumah di Pangkalpinang, Pulau Bangka, seorang wanita tua berusia 70 tahun suka menghabiskan waktunya di meja judi. Itulah, katanya, cara dia melupakan masa lalunya. Meski masa itu sudah jauh 50 tahun yang lalu, masih ia rasakan tindihannya sampai sekarang. Ia tak mau ramai-ramai seperti wanita Korea memprotes pemerintah Jepang, dan kemudian minta ganti rugi. Dialah seorang saksi yang masih bisa bercerita tapi memilih diam. Yakni tentang kebrutalan tentara Jepang mencari gadis dan wanita untuk dijadikan penghuni bordil khusus buat tentara Dai Nippon. Tak mudah memintanya bercerita tentang masa itu. Bukan ia lupa, tapi ia tak tahu untuk apa harus diceritakan semua itu, semua yang bisa membikin malu anak-cucunya. Bila akhirnya ia pun menuturkan pengalamannya, ia berpesan, jangan sebutkan namanya yang sebenarnya. Ia pernah bernama Fumiko. Dengan menerima nama itu, ia tak lagi memakai baju karung goni, baju yang lazim dipakai di wilayah yang kini bernama Indonesia, dulu di tahun 1942-1945 ketika diduduki Jepang. Tubuhnya kecil, tapi menonjol di bagian dada dan bokongnya. Mukanya yang mungil dipupuri bedak tebal. Rambutnya disanggul. Itulah dandanannya sebagai Fumiko, dan waktu itu ia 20 tahun. Fumiko bersama sekitar 20 "Fumiko" lainnya menjadi penghuni tetap sebuah "rumah besar" dengan lusinan kamar dan 13 penjaga di satu tempat di kotanya. Hampir setiap sore sampai tengah malam, Fumiko diberi tugas menemani para perwira Jepang menenggak minuman keras. Mulanya ia risi mendengar teriakan-teriakan serdadu yang mabuk. Lama-lama terbiasa. Ia juga tahu, setelah itu satu di antara serdadu yang mabuk akan menyeretnya ke kamar. "Mereka tidak kejam," cerita Fumiko. "Mereka hanya menuntut pelayananan seks." Kerap setelah itu tamu-tamunya menghadiahi barang, perhiasan biasanya. Ketentuan di "rumah besar" itu memang begitu: "pelayan yang baik mendapat imbalan perhiasan." Nasib itu tampaknya karena rumah orang tuanya yang petani itu kebetulan dekat dengan tangsi serdadu Jepang. Beberapa di antara laki-laki di tangsi itu ada-ada saja yang meliriknya. Agar tak diganggu lebih jauh, Fumiko selalu mengatakan, "Suami saya sedang bekerja di kebun." Ia memang bohong. Waktu itu, pada usia 20 tahun, ia sudah janda. Celaka, suatu kali, ketika serdadu Jepang sedang mencari wanita penghibur, ada tetangganya yang berkhianat. Status jandanya dibeberkan. Maka, suatu hari datang tentara menjemputnya. "Mereka bilang saya akan dikawini dan dibawa ke Tokyo. Kehidupan orang tua saya akan dijamin," katanya mengenang. Sebagaimana hidup waktu itu, keluarganya bernapas dengan senen- kemis. "Makan saja susah. Pakaian seadanya dari karung, hingga badan mereka gatal-gatal," katanya. Tampaknya tak ada pilihan lain, baginya dan bagi orang tuanya. Jepang-Jepang itu menyandang senjata. Siapa pun tahu waktu itu, penolakan akan sia-sia, justru lebih mendatangkan bencana. "Maka, ketika tentara Jepang menyeret saya, saya hanya pasrah," katanya. Itulah awalnya ia menjadi penghuni "rumah besar". Ia ingat di dalam rumah itu banyak perempuan sebayanya dan bermata sipit. Ia menyimpulkan wanita-wanita itu dibawa dari kampung sekitar Pulau Bangka. Di sini ia, seperti yang lain, diseleksi. Wajah dan badannya diamat-amati. Beberapa waktu kemudian, sebagian dari wanita itu dibawa pergi, konon ke Bukittinggi -- salah satu dari tiga pusat pemerintahan militer pendudukan Jepang di Pulau Sumatera -- dan Padang. Ia sendiri tidak dibawa jauh-jauh. Ia hanya dipindah ke rumah besar yang lain. Mujur nasib Fumiko satu ini. Di tengah ia hampir putus asa, karena kerjanya tak lain hanya berbaring di tempat tidur, salah seorang yang memakainya ternyata menghendaki ia pindah ke tempat tinggalnya. Maka, suatu kali di tengah kemeriahan pesta di "rumah besar" itu, salah satu perwira Jepang memboyongnya. Mereka kemudian hidup serumah, sampai kekasihnya itu harus pergi karena Jepang kalah perang. Perempuan yang pernah menjadi Fumiko itu kemudian kawin dengan seorang buruh pelabuhan, melahirkan beberapa anak. Ia kini sudah bercucu pula. Ia merasa bersyukur masih bisa berkeluarga secara baik-baik, kata janda yang sampai kini buta huruf itu pada wartawati TEMPO Aina Rumiyati Azis. Bisa ditebak, "rumah besar" yang diceritakan Fumiko tak lain adalah ianjo atau rumah bordil. Dan "Fumiko-Fumiko" itulah yang disebut-sebut sebagai jugun ianfu atau wanita penghibur yang mengikuti tentara (Jepang). Soalnya, mereka memang dipindah-pindah, menutur kebutuhan tentara Jepang di sebuah lokasi. Dan lokasi itu tak cuma di satu wilayah, juga sampai menyeberang ke lain negara. 13 HALAMAN DARI KAPTEN NOGI Bila kisah Fumiko itu kurang meyakinkan adanya pemaksaan untuk dijadikan jugun ianfu, kutipan berikut merupakan pengakuan seorang perwira Jepang sendiri. Ia bernama Harumichi Nogi, kini 71 tahun, dan tinggal di Osaka. Ketika bertugas di wilayah Indonesia Timur pada zaman Perang Asia Timur Raya, ia berpangkat kapten. Kaigun Tokubetsu Keisatsutai atau Pasukan Istimewa Angkatan Laut, judul buku yang ia tulis, terbit tahun 1975, setebal 225 halaman. Dalam bahasa Jepang, tentu. Di antaranya, di bawah judul Ianfu Gari atau Memburu Wanita Penghibur, sebanyak 13 halaman. Berikut kutipan dari bagian itu: "Maret 1944, ketika saya bertugas di Pulau Ambon, masih ada rumah bordil di situ. Hampir semua penghuninya wanita lokal. Karena pengeboman besar-besaran, bordil ditutup. Wanita-wanitanya pulang ke kampung masing-masing. Yang tak pulang buka praktek di rumah-rumah atau nekat di tempat lama yang ringsek karena bom itu, dengan penerangan lilin. "Suatu hari diadakan rapat urusan politik. Ini memang rapat rutin, sekali sebulan. Hadir antara lain para komandan beserta wakilnya, wakil dari Minseibu (pemerintahan sipil angkatan laut), wakil dari kepolisian. Dan Aoki, wartawan harian Seram, serta Kimoto dari harian berbahasa Indonesia. Ada juga wakil agama, Pendeta Kato namanya. Juga ada wakil-wakil dari markas besar dan angkatan darat. Dan saya sendiri dari Tokkei atau polisi istimewa angkatan laut. "Agak berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya, rapat kali ini membicarakan soal membangun kembali bordil, dan bagaimana mengumpulkan wanita penghuninya. Rapat itu dipimpin oleh seorang kapten bernama Oshima (bukan nama sebenarnya). Saya ditanya bagaimana hal ini dilihat dari sudut keamanan. Saya menjawab bahwa saya tak punya ide kongkret. Namun, menurut saya pribadi yang masih muda ini, sebaiknya ada bordil. "Tapi jika ada paksaan terhadap wanita lokal untuk dijadikan ianfu, saya khawatir akan ada protes dari penduduk setempat. Dari segi ini saya tidak setuju. Tapi rupanya Kapten Oshima sudah memutuskan untuk mendirikan bordil, meski suara keberatan muncul dari rapat. "Lalu disusun cara mendapatkan wanita itu. Prioritas pertama adalah wanita yang pernah menjadi pelacur. Kedua, wanita yang pernah disebut-sebut terlibat kegiatan pelacuran. Meski sulit untuk membuktikan apakah ia terlibat atau tidak. Yang ketiga adalah mereka yang berminat jadi pelacur. "Kemudian dibahas cara pengumpulannya. Terlebih dulu disusun daftar calon pelacur itu. Lalu, dilakukan negosiasi dengan mereka. Tapi siapa yang melakukan negosiasi? Para peserta rapat menengok ke saya. Alasannya, dengan menggunakan nama Tokkei yang ditakuti itu, semuanya mudah terlaksana. "Saya menjawab, 'Perlu diusahakan agar kalau terjadi protes rakyat setempat tak langsung ditujukan pada pasukan Jepang. Karena itu digunakan saja polisi orang lokal atau pimpinan masyarakat.' "Kapten Oshima menanggapi ucapan saya. Katanya, 'Harus dikumpulkan sebanyak mungkin wanita, meski harus memakai paksaan.' Lalu Oshima membeberkan rencananya. Pertama-tama diadakan pengumpulan wanita di bekas sekolah agama dekat rumah sakit angkatan laut. Di situ wanita-wanita itu dijamu dengan makan enak. Pokoknya, terlebih dulu wanita-wanita itu dibuat senang. Tujuannya, agar tersebar kabar keluar bahwa wanita-wanita yang datang ke situ merasa senang, dan datang atas kemauan sendiri. Lalu dari setiap wanita itu diminta surat persetujuan menjadi pelacur. "Akhirnya, pengumpulan wanita dilakukan oleh pasukan urusan politik, dan memakai polisi warga lokal, dipimpin oleh Kapten Oshima. Pasukan Tokkei ikut membantu, juga pasukan pengawal. "Seusai perang, ketika saya ditahan sebagai penjahat perang, saya dalam urusan pengumpulan wanita itu mendapat beberapa kesukaran. Cerita ini saya peroleh dari Kimura, seorang pegawai pemerintahan sipil angkatan laut. Inilah cerita Kimura: 'Di Pulau Saparua, ketika kami berusaha menaikkan gadis-gadis ke kapal, penduduk pulau itu tiba-tiba berkumpul dan mendekat ke kapal. Kembalikan putri kami, teriak mereka. Mereka berteriak sambil mengacung-acungkan tinju. Kami sungguh takut, hampir-hampir saya mencabut pistol. Kalau ingat adegan itu saya merasa ngeri. Kalau gadis-gadis Jepang diperlakukan begitu oleh tentara Sekutu, siapa tak jengkel?' "Akhirnya bordil pun berdiri. Karena jumlah tentara Jepang terlalu banyak, untuk masuk ke bordil harus memiliki tiket. Dengan tiket itulah diatur, para prajurit dan bintara boleh pergi siang hari, dan perwira malam hari. Jadi, bila punya duit tapi tak punya tiket, tak bisa main di bordil. "Saya sendiri pernah main di bordil dekat barak Victoria dekat pantai. Bordil itu bekas asrama perwira Belanda yang selamat dari pengeboman. Saya memilih seorang gadis berdarah campuran. " Soal bordil, Nogi mempunyai pengalaman lain lagi. Sebelum ia ditunjuk sebagai kepala polisi istimewa angkatan laut, Nogi bertugas sebagai minseibu (administrator pemerintahan sipil angkatan laut) di Makassar (sekarang Ujungpandang), antara September 1942 dan Februari 1944. Makassar waktu itu adalah pusat Armada Selatan Kedua yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat. Di Makassar pun ada bordil, katanya. Namun, berbeda dengan pendirian bordil di Ambon, di Makassar proyek ini dikontrakkan ke tangan sipil. Yaitu ke seorang pengusaha Cina, konon bernama Toh, yang telah menjadi rekan angkatan laut sebagai pemasok berbagai logistik. Cina itulah yang mengusahakan jasa penyediaan wanita penghibur, pemilihan tempat usaha, dan pengelolaannya. Pihak Jepang hanya menyodorkan izin usaha. Kata Nogi, ada tiga bordil yang dihuni oleh perempuan pribumi, dan semuanya didirikan atas permintaan militer Jepang. Karena Toh dianggap sangat berjasa, kata Nogi, seusai Perang Dunia II Hotel Yamato yang letaknya tak jauh dari markas besar angkatan laut dihibahkan padanya. Hotel Yamato kini menjadi kantor perwakilan sebuah bank pemerintah. DARI HOTEL BEANGKOROP Dari cerita Kapten Nogi itu, wartawan TEMPO Waspada Santing dan Mochtar Tauwe di Ujungpandang mencoba melacak adakah bekas penghuni tiga bordil tersebut yang masih hidup. Lewat beberapa orang tua yang masih bisa mengingat-ingat masa itu, ditemukanlah dua wanita korban penjajahan Jepang. Yang seorang mengaku bekas penghuni ianjo. Yang satu lagi diam, lebih suka merahasiakan sepenggal kehidupannya itu. Wanita yang mau mengaku tersebut kini berusia 72 tahun. Melihat hidung kecilnya yang mancung, dam dagunya yang bak lebah bergantung, bisa diduga dulunya wanita ini menarik. Cerita tentang masa lalu menyangkut terus di tenggorokannya. Ia lebih banyak menjawab "tidak tahu" dan "tidak ingat", lalu menangis. Berikut kisahnya: "Dulu saya disekap di sebuah rumah di Kampung Pisang. Umur saya waktu itu sekitar 20 tahun. Di situ saya diberi nama Sitti I. Karena dari puluhan wanita di situ, ada tiga orang bernama Sitti. Saya peranakan Melayu. Orang bilang dulu wajah saya manis. Jadi saya cepat dikenal serdadu-serdadu Jepang. Saya kemudian diajak kerja, mula-mula sebagai operator di kantor. Lalu saya disuruh pindah ke Hotel Beangkorop sebagai pelayan. Di sana saya diperkosa tentara Jepang. Orangnya berpangkat. Besoknya saya bekerja rangkap menjadi pelayan dan melayani opsir-opsir di tempat tidur. "Saya kemudian dipindahkan ke sebuah rumah di Kampung Pisang. Setiap hari saya dan wanita lain di situ harus melayani tiga sampai lima tentara yang datang bergantian. Saya tidak pernah mendapat bayaran. Kalau makan, boleh sepuasnya. Pakaian dikasi. Sekali seminggu saya dan teman-teman dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. "Saya ingin sekali melepaskan diri dari tempat itu. Tapi sulit sekali. Banyak tentara di pintu gerbang. Mau loncat, pagarnya tinggi sekali. Saya dan kawan-kawan tidak mungkin melarikan diri." Kini Sitti I hidup sebatang kara. Suaminya, pemuda Jawa, telah meninggal. Mereka tak punya anak, dan tak punya apa-apa. Setiap hari ia menjajakan pakaian bekas dari satu lorong ke lorong lain. Hidupnya menumpang dari satu kenalan ke orang yang berbaik hati lainnya. MAHAKERET ATAU BERTERIAK Dua penduduk Tomohon, kota 15 km dari Manado, menjadi saksi mata penderitaan gadis-gadis Minahasa. Mereka Urbanus Taulus, petani yang kini berumur 72 tahun, dan Alex Lelengboto, bekas bupati Minahasa. Mereka bisa bercerita tentang bordil Jepang karena dulu mereka bekerja sebagai pelayan di salah satu bordil itu. "Tak lama setelah tentara masuk ke Tomohon, gadis-gadis di berbagai desa di Minahasa diciduk tentara Jepang. Umumnya dibujuk dengan janji akan disekolahkan menjahit. Kalau tak salah, ada sekitar 100 perempuan di bawah 20 tahun. Jepang mengosongkan sepuluh rumah penduduk di Desa Kakaskasen. Ke pondok-pondok itulah perempuan desa yang kena bujukan itu dimasukkan. Kompleks rumah itu kemudian dipagari. Rapat dan tinggi. Penjagaan ketat. Kami dengar mereka menyebut tempat itu 'yanjuk' (maksudnya ianjo). Pimpinan 'yanjuk' ini seorang opsir Jepang yang beristri perempuan Jerman. Mereka juga mengelola 'yanjuk' di Mahakeret di Manado. "Para serdadu mulai berdatangan sekitar pukul 3 siang, dan tempat itu terus ramai sampai pukul 7 malam. Mereka, puluhan jumlahnya, antre di muka pintu. Mereka bukan saja tentara Jepang, tapi juga eks tentara Korea, Taiwan, bahkan Heiho. Kami sering mendengar perempuan menangis dan menjerit-jerit histeris." "Jaminan hidup di 'yanjuk' itu cukup baik. Makanan dan pakaian tak pernah kurang. Perempuan-perempuan di situ mendapat upah, kesehatan dijamin. Mereka tetap cantik, dan anehnya tidak pernah sakit. Sekali terjeblos di tempat itu, jangan harap bisa keluar lagi. Pernah ada dua perempuan berhasil lari dari tempat itu. Mereka pulang ke desa. Tak berapa lama kedua wanita itu sudah tampak lagi di Kakaskasen, dijemput tentara." Sebuah bordil lagi yang dikelola oleh opsir Jepang, menurut Urbanus dan Alex, terletak di kawasan yang kini bernama Kelurahan Mahakeret. Konon, nama Mahakeret itu diberikan karena penduduk di sekitar "kompleks berpagar tinggi" itu sering mendengar suara teriakan perempuan. Mahakeret dalam bahasa setempat artinya berteriak. Salah seorang bekas penghuni Mahakeret ditemukan oleh wartawan TEMPO Phill M, Sulu. Wanita itu dulu dibujuk Jepang akan dipekerjakan di sebuah rumah sakit. Begitu sampai di bordil, ia sadar telah terperangkap. Ia mencoba melawan, tapi tak berdaya. "Sekujur tubuh saya digelitiki. Saya kegelian dan tertawa sampai capek, lemas tak berdaya," tutur wanita yang tiga tahun menderita di Mahakeret ini. Ia kini hidup tenteram bersama anak cucunya dari suaminya yang tetangga sekampung, di daerah Bitung. "Sampai sekarang saya benci sekali kalau melihat orang Jepang," katanya. "Barang-barang buatan Jepang? Huh, saya tak mau pakai." KESAKSIAN TAIRA TEIZO ATAU NYOMAN BULELENG Tampaknya nasib para jugun ianfu memang berbeda-beda. Ada yang gelap pekat, ada yang abu-abu, ada yang remang-remang. Inilah kesaksian yang bernada lain dari Taira Teizo, bekas tentara Nippon yang telah menjadi warga negara Indonesia dan berganti nama menjadi Nyoman Buleleng, kepada wartawati TEMPO Silawati: "Tahun 1942 saya berumur 23 tahun. Saya baru tiga tahun masuk ketentaraan Jepang ketika memasuki wilayah Indonesia. Sebelumnya saya bertugas di Cina dan Filipina. Saya anggota pasukan meriam dalam divisi yang didaratkan di Kranggan, Surabaya. Tugas pasukan saya membuka jalur dan menduduki suatu wilayah. "Wanita-wanita penghibur itu memang benar-benar ada. Saya merasakan sendiri. Jepang rupanya sadar bahwa kebutuhan biologis tentara tidak bisa dimatikan walaupun dalam keadaan perang. Sehingga saya melihat betapa terorganisasinya wanita-wanita itu. Di semua daerah yang telah diduduki Jepang, otomatis didirikan suatu rumah khusus untuk itu. Satu rumah bisa sampai 20 kamar dengan dikelilingi tembok bambu tinggi. Biasanya masyarakat sekitar menyebutnya "rumah bambu". "Penghuni rumah bambu macam-macam. Ada yang khusus wanita Jepang, ada juga yang menyediakan wanita campuran, Cina dan Indonesia. Yang disebut wanita Jepang itu sebetulnya banyak juga wanita keturunan Cina, Korea, atau Filipina. "Tidaklah tepat bila ada yang mengatakan bahwa wanita Indonesia diambil secara paksa oleh tentara Jepang. Biasanya mereka didapatkan lewat pengumuman yang disebarkan melalui aparat desa setempat. Setelah terkumpul, barulah mereka dibawa ke markas. Jadi, kalaupun ada pemaksaan, itu dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Sebelum terjun, wanita-wanita itu diperiksa oleh dokter. Bila ada wanita yang ketahuan berpenyakit kotor, ia tidak akan diterima. Pemerintah Jepang sangat takut bila tentaranya kena penyakit kotor. Karena itu, di rumah bambu itu selalu disediakan kondom. Tiap minggu kesehatan wanita penghiburnya juga diperiksa. "Rumah-rumah itu biasanya dibedakan. Ada yang khusus untuk opsir dan ada yang untuk bawahan. Biasanya perwira-perwira malu mengunjungi tempat semacam itu. Untuk golongan ini, biasanya mereka memelihara wanita di rumah mereka. "Acara di dalam rumah berpagar tinggi itu biasanya didahului dengan minum-minum, seperti kebiasaan kami di Jepang. Setelah lewat tengah malam, mereka yang ingin melanjutkan acara lalu membawa wanita penghibur itu ke kamar. Tapi ada juga yang hanya sekadar mabuk-mabukan. Saya benar-benar tidak melihat ada pemaksaan di situ. Semuanya tertawa dan bernyanyi-nyanyi karena semuanya minum. Saya tidak pernah tahu ada di antara wanita itu yang stres lalu bunuh diri. Saya tidak bermaksud membela Jepang. Saya kawin dan membentuk rumah tangga dengan orang Bali asli setelah Perang Kemerdekaan." CERITA DARI SEORANG SATPAM Berikut kesaksian Subadlar alias Badar, kini 75 tahun, bekas satpam di ianjo Hotel Wongaye, Denpasar. Serdadu Jepang yang datang ke Wongaye, katanya, jarang punya waktu longgar untuk bercengkerama, apalagi bernyanyi-nyanyi atau mabuk-mabukan. Keadaannya memang tak memungkinkan, karena yang datang banyak, sedangkan di situ hanya ada 20 wanita. Tugasnya mendaftar para tamu. Nama dan kesatuan pengunjung dicatat, lalu mereka disodori foto-foto para ianfu. Setelah memilih salah satu ianfu, para tamu harus membeli tiket di loket. Harganya Rp 300. "Biasanya mereka tak mampu bermain lama, cuma sepuluh menit di dalam kamar," kata Badar. Dalam satu jam, seorang ianfu bisa melayani dua sampai tiga tamu. Dari tarif Rp 300 itu, kata Badar, para ianfu mendapat bagian Rp 150. Penghasilan mereka cukup besar, mengingat satu hari mereka bisa menerima tamu lebih dari sepuluh orang. Padahal dengan gaji Rp 75, tutur Badar, ia bisa hidup layak selama sebulan. Tapi para ianfu itu merasa tertekan. "Mereka tak bisa menolak tamu, takut dibunuh," tutur Badar. Para tamu juga tak bisa berkunjung secara leluasa ke Hotel Wongaye. Ada aturan ketat. Ada jam-jam khusus untuk angkatan laut, ada jam untuk angkatan darat. Yang pasti Hotel Wongaye buka 24 jam sehari. "Saya tak tahu kapan wanita-wanita itu bisa beristirahat," kata Badar. Pernyataan serupa datang dari ingatan saksi Sulchan, 69 tahun, bekas Heiho di Rembang, Jawa Tengah. Ia ingat lokalisasi geisha Jawa itu di Hotel City (kini dekat dengan gedung bioskop Rembang). Kata Sulchan, ianfu di sana, kalau bukan pelacur profesional, ya wanita yang datang secara sukarela. Motifnya satu: bisa hidup senang. "Supaya bisa makan roti dan berpakaian bagus-bagus," kata Sulchan, yang kini tinggal di Cepu dan menjadi Ketua Yayasan Ronggolawe Cepu dan Ketua Koperasi Pepabri di kota itu. "Setahu saya, tidak ada paksaan. Kehidupan geisha lebih terjamin daripada penduduk kebanyakan," katanya kepada wartawan TEMPO M. Faried Cahyono. Dari cerita di atas, bisa dibayangkan berapa banyak wanita yang telah menjadi korban ianjo. Wartawan TEMPO Rizal Effendi mendapat keterangan dari sejumlah sumber, di Kalimantan Timur saja ada lebih dari 500 ianfu. Menurut kesaksian seorang bintara Jepang, ada 10 ianjo di Batavia. "Sebenarnya gampang memperkirakan jumlah ianjo," kata tentara yang bertugas di resimen telegraf ke-15 di Batavia waktu itu. "Di mana ada satu batalyon, di situ pasti ada sedikitnya satu ianjo ," katanya kepada wartawan TEMPO di Jepang. Bunga Surawijaya (Jakarta) dan Seiichi Okawa (Tokyo)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini