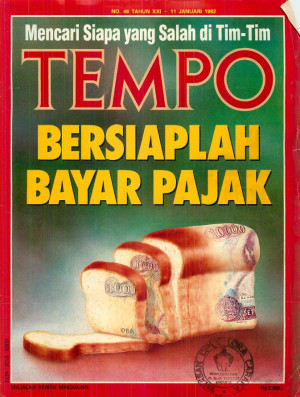Seumur-umur, ia tidak pernah punya kartu nama. Beli dasi terakhir, 2 5 tahun lalu. Di "kantor"nya tak ada sofa empuk, apalagi AC. Ada sebuah kursi plastik yang warna aslinya sudah tak jelas. Tapi ia dipa nggil boss. Peralatan paling vital di ruang kerjanya: timbangan duduk berkapasitas 300 kilogram, merek Garuda. Siapa dia? Mardjoko, umurnya 49 tahun. Setiap hari, ia bekerja dengan timbangan itu, notes dan bolpoin bekas di tangan. Kadang-kadang dengan bantuan kalkulator. Bisnis Mardjoko adalah jual beli sampah. "Ember, Bos," kata Asim, pemulung berbadan kerempeng, sambil menjatuhkan sebuah karung putih yang robek di sana sini. "Campur sendal nggak?" tanya Mardjoko. "Nggak," jawab Asim. "Pralon?" "Nggak." Pertanyaan-pertanyaan klasifikasi barang itu adalah bagian dari trans aksi. Setiap klasifikasi punya harga sendiri. Harga ember plastik berb eda dengan plastik pembungkus gula, pralon, atau sendal. Si bos mencocokkan skala timbangan, 7 kilogram. Lalu ia membuat catatan : Ember, 7 X Rp 250 Rp 1.750. Tukul, anak buah Mardjoko, mengangkat karung yang baru ditimbang dan menumpahkan isinya ke sebuah tumpukan barang plastik bekas. Sedangkan si Asim -- resminya ia pemulung sampah -- mengambil lagi barang-barang bekas dari gerobaknya. Ia datang lagi dengan sekarung boncos (ini istilah untuk segala macam jenis kertas koran, majalah bekas) sebanyak 7 kg, kardus 5 kg, karpet 3 kg, naso (ini istilah wadah plastik bekas krim deterjen) 1 kg, dan besi 8 kg. Setelah mengkonfirmasi kalkulatornya, Djoko mengambil duit Rp 5.500 dari kantong kemejanya dan menyerahkannya kepada Asim. Transaksi selesai. Dalam jaringan daur ulang sampah, usaha Mardjoko tergolong lapak, sektor penadah barang-barang bekas yang dipungut "tukang beling", seperti Asim. Barang-barang dari penadah ini, setelah melalui dua atau tiga tahap proses, menjadi bahan baku industri daur ulang di Jakarta. Kertas bekas menjadi kertas baru, ember buangan jadi perabotan mutakhir, kaleng bekas menjadi lampu tempel. Usaha Djoko, di tanah seluas 300 meter persegi -- disewanya Rp 100 ribu per bulan -- terletak di dalam sebuah bengkel mobil di belakang stasiun kereta api Manggarai, Jakarta Selatan. Ia menerima para penyuplai tak jauh dari hamparan berpuluh-puluh karung barang bekas yang letaknya berhadapan dengan bedeng-bedeng tukang ikan pindang. Bau amis pindang terbang ke mana-mana, bercampur dengan bau oli dan sampah, tentu saja. Di Jakarta ternyata cukup banyak pengusaha seperti Mardjoko. Ada paling tidak 3.200 lapak di Jakarta. Ini hasil penelitian CPIS (The Center For Policy and Implementation Studies), sebuah pusat riset antardisiplin dan konsultasi kebijaksanaan, yang didirikan pakar-pakar ekonomi antara lain Wijoyo Nitisastro dan Ali Wardhana. Sekilas lapak Djoko terbilang besar. Penyuplainya macam-macam. Ada petugas kebersihan Rukun Tetangga, yang merangkap menjadi pemulung untuk tambah-tambah gaji yang hanya Rp 30 ribu. Ada juga janda beranak tiga, membawa pungutannya dalam gendongan kain. Salah seorang penyuplai, anak kelas 5 SD, datang menawarkan kabel buangan. Penyuplai terban yak adalah laki-laki muda usia produktif. Mereka menawarkan dagangan dalam jumlah relatif banyak, diangkut dengan gerobak. Menurut Djoko, para pemulung ini memungut sampah dalam radius tiga kilometer dari lapaknya. "Setiap hari, rata-rata omzet saya Rp 400 ribu," ujar Djoko kalem. Bapak empat anak, asal Kedu, Jawa Tengah, ini penyabar. Ia tidak hanya berdagang dengan para penyuplai. Sehari-hari, ia menyediakan waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Ia bahkan bersedia mendengar penuturan pemungut sampah yang kurang waras. Djoko tidak sesederhana penampilannya. Ia pernah kuliah selama empat tahun di jurusan geografi sebuah universitas negeri. Seperti banyak kejadian lain, ia tak bisa meneruskan studinya karena tak punya dana, dan karena ia harus bekerja untuk menyambung hidup. Djoko memulai usahanya dengan modal lima ribu rupiah pada tahun 1980. Ia memborong mangkuk-mangkuk plastik bekas seharga Rp 125 per kilo. Setelah dicuci bersih, bisa laku sampai Rp 200 per kilo. Setelah keuntungannya mencapai jumlah yang cukup, ia membuka lapak. Selain di Manggarai, Djoko punya lapak di rumahnya di bilangan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di samping rumahnya, dekat tumpukan karungk arung barang bekas, ia membangun "asrama" untuk para pemulung yang tunawisma. Kapasitasnya 35 orang. Tanah miliknya total 400 meter persegi. Hanya 40 meter persegi digunakannya untuk rumah tinggal, sisanya untuk penampungan sampah dan asrama tadi. Sampah Jakarta punya nilai ekonomis. Barang-barang "tak berguna" itu diam-diam menghidupi puluhan ribu orang. Menurut hitungan CPIS, 50 ribu pemulung tersebar di Jakarta. Mereka mengutak-atik sampah rumah tan gga, menurut perkiraan Pemda DKI, jumlahnya 5.000 sampai 6.000 ton set iap hari. Sampah punya klasifikasi. Daun pisang bekas pembungkus lontong, kulit buah, dan sisa makanan disebut sampah organik. Sampah jenis ini, yang jumlahnya tiga perempat dari seluruh jumlah sampah, akan habis setelah membusuk. Sisanya sekitar 26% tergolong sampah nonorganik. Dalam banyak studi lingkungan, sebagian besar sampah ini dikenal menimbulkan masalah karena tak bisa diserap alam. Plastik, misalnya. Di Indonesia, sampah ini tidak mengganggu karena dikumpulkan dan bisa menjalani proses daur ulang. Kertas, kardus, plastik, besi, bahkan tulang hewan yang bisa dijadikan makanan ternak. Maka, setiap hari, minimal 1.250 1.500 ton sampah rumah tangga berubah status menjadi komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tidak kecil. Angka ini masih harus ditambah dengan angka sampah nonrumah tangga (kantor, pabrik, dan pasar), yang oleh Departemen Perindustrian diperkirakan sekitar 500 ton per harinya. Dari sampah ini, sekitar 50% menjadi sumber penghasilan para pemulung. Maka, bila 1.500 sampai 1.750 ton sampah bisa dikumpulkan setiap harinya, berharga rata-rata Rp 200 per kilo, omzet yang berputar dari "barang tak berguna" ini minimal Rp 300 juta, sehari. Atau, 9 milyar rupiah per bulan. Jangan menyepelekan para pengusaha sampah. Mereka berhimpun dalam sebuah yayasan, yang diberi nama Yayasan Dian Pertiwi Indonesia (YDPI) 60% dari seluruh pengusaha sampah di Jakarta. YDPI dibentuk pada 1988. "Kami mendapat dukungan dari Menteri KLH Emil Salim dan Erna Witoelar," kata Tukino Dana Direksa, Direktur Eksekutif YDPI. Kini "organisasi sampah" ini punya jaringan yang terdiri dari 8 unit kerja, 13 bandar, 225 lapak, dan 6.000 pemulung di wilayah Jabotabek. "Tiap unit kerja memutarkan uang sekitar Rp 1,2 milyar per bulan," kata Tukino di kantornya di wilayah Tebet Barat, Jakarta Selatan. Para pembantu TEMPO, Tina Gayatri, Nenti R. Dahliadini, dan Umniyati Kowi mengikuti perjalanan para pemulung ini. Ada Ibu Karsih, perempuan setengah baya, beroperasi di sekitar Kampung Melayu, Jakarta Timur. Marta, pemuda 17 tahun, yang menjelajahi Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Endi, asal Surabaya, memungut sampah secara tenatif, ke mana ia berjalan. Pak Samin, 42 tahun, petugas kebersihan operasi di kawasannya, Pondok Cina, Jakarta Selatan. Mereka inilah pasukan terdepan jaringan bisnis sampah. Sejak Oktober 1988, pemulung, yang sering dihina sebagai gelandangan, mendapat predikat istimewa dari Presiden Soeharto: "Laskar Mandiri". Kotor? Jijik? "Nggak. Di situ rezeki buat orang seperti aku," kata Endi kepada pembantu TEMPO, Nor Aizan A. Halim. Pendatang dari Surabaya ini semula kaget, sampah yang dikumpulkannya bisa diuangkan sampai Rp 150 ribu per bulan. "Dulu, waktu mengasong rokok, saya tidak pernah pegang uang sebanyak itu," katanya. Endi tergolong pemulung yang sebenar-benarnya mandiri. Mereka menjual sampahnya ke sembarang lapak. Tapi kebanyakan laskar mandiri adalah "pegawai" lapak tertentu. Dalam catatan CPIS, sekitar 80% pemungut sampah adalah pemulung terikat. Mereka punya hubungan tetap dengan penadah tertentu. Rata-rata pemulung berpenghasilan bersih Rp 3.883 per hari. Sebagai daya tarik, lapak menyediakan berbagai kemudahan untuk anak buahnya : permukiman, modal kerja, gerobak, dan pinjaman uang untuk keadaan darurat. Selain gerobak dan alat pencungkil, ada lapak yang menyediakan abu gosok sebagai penukar barang-barang bekas. Abu gosok juga yang menjadi modal Marta. Bujangan Betawi ini setiap hari mengambil rute Depok, Lenteng Agung, sampai Kali Bata, Jakarta Selatan. Ia menawarkan bahan pembersih kotoran panci itu sebagai penukar barang bekas. Ia berangkat operasi sekitar pukul 6 pagi, dan kembali pukul 4 sore ke "asrama" membawa gerobak penuh barang bekas. Ada botol kosong, ember bekas, kardus, koran, sampai aki bekas. Nah, yang di sebut terakhir ini tergolong sampah "mewah". Soalnya, satu aki bekas berharga Rp 5.000. Marta bangga menjadi tukang abu gosok. Dalam bahas anya, ia mengutarakan statusnya lebih bergengsi daripada tukang beling, yang cuma tinggal pungut. Tapi, bergengsi atau tidak bergengsi, penghasilan tukang abu gosok dan pemulung kurang lebih sama. Toto, pendatang dari Cirebon, sudah 3 tahun bekerja untuk sebuah lapak. Ia bersama 9 teman lainnya menja di anak buah seorang penadah di pinggiran Jakarta Timur. Penghasilan mereka Rp 3.000 sampai Rp 5.000 per hari. Jenis pemulung yang juga banyak, petugas kebersihan di lingkungan permukiman atau pertokoan. Mereka menambah penghasilan mereka yang tak seberapa dengan memanfaatkan sampah. Seperti yang dilakukan Samin Sutisna, 42 tahun, di Pondok Cina. Barang-barang ini tak segera disuplainya. Sebagian besar dibawa pulang untuk dipilah: kertas dengan kertas, plastik dengan plastik. Agen lapak datang secara teratur ke rumahnya. Dengan cara ini, bapak lima anak ini mendapat penghasilan paling sial Rp 1.000 per hari. Kalau untung, bisa Rp 5.000 per hari. Ini penghasilan tambahan yang sangat membantu penghasilan bulanannya yang hanya Rp 70 ribu. Setengah berseloroh, Mardjoko melempar komentar, "Saya membayar pegawai saya lebih dari ketentuan upah minimum buruh Depnaker lho. Ia mengupah 17 pekerja, termasuk sopir dan tukang angkut barang, rata-rata Rp 5.000 Rp 6.000 per hari. Ditambah dengan tip gaji rata-rata "karyawannya", Rp 200 ribu per bulan. Selama membuka "kantor" di Manggarai, lapak Mardjoko empat kali didatangi polisi yang mencurigai kantornya menadah barang curian. "Saya suruh mereka periksa apa adanya," kata Mardjoko. Tapi polisi memang tidak menemukan apa-apa. "Saya paling sedih kalau dibilang pemulung itu maling," katanya lagi. Sebagai penadah, ia sudah sangat kenal mana sampah, mana barang curian. Suatu kali ada pemulung "independen" yang menjual sejumlah lampu sen. "Langsung saya tolak. Di kotak sampah mana ada lampu sen ngumpul?" katanya. Begitu juga kalau ada yang menjual accu. "Saya tes dulu. Kalau masih bagus, saya tolak. Bisa-bisa diangkat dari bengkel," katanya lagi. Menyadari kedudukannya yang mudah dicurigai sebagai penadah barang curian, Mardjoko sangat berhati-hati dalam membuat transaksi. Ada perasaan senasib yang kuat di jaringan sampah itu. Hubungan antara juragan dan pemulung lebih mirip ikatan keluarga. Pernah suatu hari Djoko didatangi tiga pemulungnya. Satu, anaknya meninggal, kedua istrinya melahirkan, yang ketiga mengadu anak wanitanya hamil. Sehari itu Rp 75 ribu melayang dari kantong Mardjoko. "Kalau tiap hari kita berhubungan dengan manusia tapi tidak ada pengertian sama sekali, mana punya teman," kata Djoko mencoba berfilsafat. Catat: para pemulung tak punya jaminan apa-apa, kecuali janji menyetorkan barang. Djoko sendiri mudah meminjam uang dari bandar, hierarki di atasnya. "Kalau pinjam di bank, untuk satu juta saja, birokrasinya berbelit, pakai jaminan lagi. Di bandar, ngomong sedikit, bisa pinjam Rp 10 juta," katanya. Seperti juga pemulungnya, ia membayar utang dengan menyerahkan barang. Dengan cara ini, Djoko kini punya 3 Toyota bak terbuka dan satu truk untuk melancarkan usahanya. Sistem kekerabatan ternyata tumbuh dengan subur di kalangan pengusaha sampah. Di lapak Djoko di Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 24 dari 3 5 laskar mandiri yang bermukim di sana membawa keluarga: istri, adik, keponakan, dan tentu anak-anak. Seluruhnya ada 16 anak berusia 20 bulan sampai 10 tahun. Semuanya pendatang dari Jawa Tengah. Mereka menyesaki 18 kamar berukuran 3 X 3 meter pada sebuah bangunan dua lantai. "Saya menghabiskan Rp 19 juta untuk membangun kamar-kamar itu," kata Djoko, bapak 4 anak dari dua istri. Dari luar, kamar-kamar itu tampak seperti tenggelam di antara timbunan karung-karung sampah. Ruang yang tersisa di bagian dalam, pada siang hari, dihabiskan untuk menjemur pakaian. Bocah-bocah ingusan asyik memanjat dan menyelip di antara tumpukan karung. Di antaranya anak-anak Rimin yang berusia 5 sampai 9 tahun. Rimin, pemulung berusia 28 tahun, "Cita-cita saya bisa menyekolahkan anak-anak kalau sudah besar," katanya sambil mengayun bayi lelakinya. Cita-citanya ini sudah tercapai dengan meneyekolahkan putri sulungnya, Lilis, di kelas 1 SD Cawang. Tapi anak-anak di lingkungan sampah adalah sebuah dilema. Apakah mereka akan mewarisi pekerjaan orangtua mereka? Kalau ya, mengapa. Haruskah, tidak. Asep yang berusia 10 tahun, anak pemulung, sudah mulai berdiri sendiri dengan mencari sampah sebelum berangkat ke sekolah. Dengan cara ini, ia mendapat uang jajan Rp 1.500 per hari. "Kerja begini santai," kata Rimin lagi. Perantau dari Pemalang ini merasa, "Nggak susah-susah mikirin rugi." Dulu, ketika menjadi peda gang sayuran, ia sering dongkol karena rugi. Sekarang, penghasilannya antara Rp 4.000 dan Rp 7.000 per hari. Jam kerjanya 6 jam, mulai pukul 7 pagi. Berangkat pagi, baginya, adalah sebuah kiat. "Sebelum sampah yang bagus-bagus diambil orang," katanya. Setelah itu, Rimin mengaku, bersantai-santai. "Tidur atau main kartu," katanya. Para istri, di penampungan, kebanyakan berperan ganda. Di antara kesibukan mengurus anak dan memasak, Mardjoko misalnya, menyediakan kerja tambahan. Menggunting kaleng dan menggosoknya dengan sisa serutan kayu. Kaleng bekas lalu kelihatan mulus dan bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Upah menggunting kaleng Rp 50 per kilo dan biaya menggosok Rp 35 per kilo. Keluarga Wakur, yang membawa tiga anak ke Jakarta , mengambil semua kesempatan itu. Sebelum ke Ibu Kota, Wakur penarik becak. "Penghasilan narik, paling banyak Rp 2.000," katanya. "Sekarang, Rp 2.000 penghasilan paling sial." Berkat armada lepas di Manggarai dan di Pasar Rebo, setiap bulan, Djoko bisa mengumpulkan sampah kertas sebanyak 60 ton, plastik bekas 30 ton, dan besi tua 25 ton. Ia mengaku, setiap bulan mengantungi laba bersih Rp 2 juta. Sebagian besar penghasilannya dipakai untuk pendidikan. Selain biaya untuk empat anaknya, ia menjadi bapak asuh lima anak saudaranya. Tapi, untuk itu, Djoko terpaksa kehilangan hari-hari liburnya. Libur terpanjang hanya empat hari pada Idul Fitri. Hari-hari selebih nya, ia harus kerja keras, menerima pemulung, memandori pengepakan barang, dan memberi komando kepada laskarnya. Hiburan yang dinikmatinya, menonton televisi pada malam hari. Serial LA Law dan Dark Justice adalah film kegemarannya. Bunga Surawijaya
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini