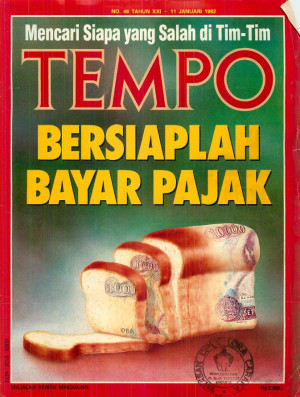Tangantangan pekerja itu terlatih. Hampir setiap pekerja ini bertug as memisah-misahkan sampah plastik berdasarkan jenis dan warna. Plastik merah, hijau, dan biru masing-masing dilemparkan ke ember yang berbari s di muka mereka. Ada potongan ember, botol penyok, tabung obat, dan mangkuk dekil. Selain memisahkan sampah plastik, dua wanita menggetokng etok kaset bekas dengan palu. Mereka mengambil badan kaset dan roda pi ta yang terbuat dari plastik. Di ruang lain, seorang pekerja memilah s ol sepatu dengan dua tang. Ini kesibukan sehari-hari PT Bukit Plastik, perusahaan plastik bekas di kawasan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Juragan mereka, Benny Kumarga, 41 tahun, bandar merangkap pemasok pabrik plastik. Ia tinggal di real estate Kelapa Gading, Jakarta Timur. Tapi hampir setiap h ari Benny, yang biasa dipanggil Bungi, datang ke bengkel plastik bekas miliknya, karena ada saja lapak yang mengirim dagangan ke situ, m arkas sampah seluas 400 meter persegi. Satu shipping dengan truk b erjumlah rata-rata 1.300 kg. Ke bandarbandar, seperti punya Bungi, sampah Jakarta melanjutkan perjalanan dari pemulung dan penadah. "Seluruh kebutuhan plastik saya dipenuhi 18 lapak," kata Bungi. Dulu, ketika baru memulai usaha, sekitar 1977, Bungi berhubungan langsung dengan pemulung. Ia ingat, waktu itu, jenis plastik masih terbatas. "Yang ada cuma ember bekas doang. Belum ada tuh botol shampo atau lotion yang bagus-bagus seperti sekarang," ujar Bungi, keturunan Cina, di kantornya berukuran 2 X 3 meter di salah satu sudut bengkelnya. Ketika usahanya berkembang, lapak besar atau kecil datang sendiri. Di bengkelnya, yang berdiri sejak 1985, kini terparkir gunung-gunung sampah plastik. Tingginya sekitar 3 meter. Seluruhnya ada 20 ton, siap untuk dipilah-pilah. "Jenis plastik itu banyak, ada puluhan macam. Ember saja ada yang high density, ada yang low density," kata Bungi. Untuk mengurus plastik yang datang itu, Bungi mempekerjakan buruh borongan dan harian. Mereka tinggal di bengkel Bukit Duri itu. Memisahkan plastik baru adalah langkah awal daur ulang plastik. Setelah dikelompokkan menurut warna dan jenis, plastik bekas dibawa ke pabrik penggilingan juga milik Bungi -- di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Ti mur. Di sini, di areal seluas 700 meter persegi, Bungi punya dua mesin penggiling. Sampah yang telah dipisahkan itu dimasukkan ke mesin untuk digiling menjadi kepingan sekitar 2 cm. Satu hari, kata Bungi, 2 ton plastik bekas diproses. Setelah itu, dicuci dan dijemur hingga siap menjadi perca plastik. Mereka menyebutnya plastik berasan. Ada pabrik yang mau menerima plastik berasan seperti hasil produksi Bungi ini sebagai bahan baku. Tapi umumnya industri perabotan plastik menerima plastik bekas yang sudah dalam bentuk biji plastik, yaitu pecahan-pecahan berukuran sekitar 1 milimeter. Untuk mencapai bentuk ini diperlukan satu proses pengolahan lagi. Pabrik-pabrik pengolah biji plastik adalah bagian akhir dari rantai daur ulang limbah plastik. Dari sini, plastik bekas sudah menjadi bahan baku plastik. Kanwil Perindustrian DKI, sampai tahun lalu, mencatat ada sekitar 17 pabrik pemroses biji plastik, yang umumnya memiliki 2 3 mesin. Setiap bulan, pabrik-pabrik itu memproduksi 400 600 ton biji plastik. Pemakai biji plastik limbah itu biasanya adalah produsen perabotan plastik untuk kelompok menengah bawah. Misalnya ember dan baskom murahan, timba untuk pekerja bangunan, peralatan rumah tangga, mainan anak-anak, mangkuk getah karet, meja, bangku, dan terbanyak sol sepatu dan sendal. Pokoknya, bukan untuk wadah makanan dan minuman. Untung Basuki, 42 tahun, dan istrinya, Rohana, dua di antara 17 pem ilik pabrik pemilik biji plastik. Untung menjalankan Tunggal Jaya Plastik Industri, sedangkan istrinya mengelola Dewi Intan Plastik. Keduanya menjalankan usaha di kawasan Teluk Gong. Untung, anak Pekalongan yang berputra empat itu, memasuki lahan bisnis ini pada tahun 1988, setelah 12 tahun menggodok nasib sebagai pemulung, pengusaha lapak, dan bandar. "Gara-gara saya dapat rezeki, bisa meminjam uang Rp 75 juta dari bank hanya dengan bunga 1 persen," katanya, "waktu itu, masa jaya sampah plastik. Pengusaha bahan baku industri yang mengejar-ngejar penadah dan bandar, membayar di muka sebagai ikatan." Untung menerima sampah plastik dari berbagai sumber. Dari pemulung di Bandengan, Jakarta Utara, dari bandar-bandar di Jakarta dan sejumlah lapak dari Bekasi, selain menerima kiriman dari Lampung, Palembang, dan Medan. Industri plastik Untung mengolah bahan baku setengah jadi dengan laba Rp 100 per kilogram. Mengurus sampah plastik, kata Bungi, bukan soal sepele. "Modal saja tidak cukup, karena usaha ini gampang-gampang susah," ujar Bungi. Contohnya, pengusaha harus tahu berapa penyusutan barang akibat air dan pasir. Menyortir barang juga bukan pekerjaan enteng. Maklumlah, laba bandar dan pemasok terletak pada berat "bruto" plastik. Di tingkat lapak, klasifikasi plastik memang tidak bisa ketat karena manual. Di tingkat bandar dan pemasok baru, plastik bekas menjalani seleksi ketat. Umpamanya jenis plastik mahal, seperti PVC Nilek, yang biasanya terdapat di sandal jepit bagian atas, tali kursi, dan sol sepatu. Plastik-plastik ini bisa dijual Rp 1.200 ke pabrik. "Sol sepatu olahraga merek terkenal malah nggak laku, karena terbuat dari karet," kata Bungi. Ember bekas juga punya klasifikasi mahalmurah. Kumpulan ember ini diseleksi dengan saksama, apakah dari bahan PE (polyethylene) atau PP (polyprophylene). Pada perbedaan keduanya, terletak perbedaan harga. PE dari kantong plastik putih harganya Rp 650 per kilo. Tapi PE kuning hanya Rp 500. Sedangkan PP yang berasal dari ember (warna) Rp 600, PP dari kantong plastik yang disebut PP Kresek harganya paling murah, Rp 200 per kilo. Penyortir berpengalaman 10 tahun biasanya cukup terlatih dalam mengklasifikasikan sampah-sampah plastik itu. Hanya dengan melihat, memegang, atau menciumnya, mereka tahu masuk kelompok mana. Pegawai baru biasanya membedakannya dengan mendengar suara gesekan atau suara bantingan. Kalau belum ketemu juga, potongan itu dibakar. Dari bau, jenisnya ketahuan. Tapi bisnis plastik bekas bukannya tak punya tantangan. Penyuplai plastik bekas kini menjerit. Mereka disaingi limbah plastik impor. "Dulu, saya bisa jual 12-13 ton perca plastik sehari. Sekarang, 4-5 ton saja sudah susah," kata Sucipto Kamidi, 37 tahun. Sucipto adalah Presiden Direktur PT Intitritunggal Nusasejahtera (IN). Markas plastiknya, di kawasan Cengkareng, Tangerang, cukup besar. Terletak di atas tanah seluas lebih dari seperempat hektare. Di situ, ia mengatur jaringan bisnis sampah dengan pekerja, yang keseluruhannya 112 orang. Seingat Sucipto, komoditi sampah plastik berkibar sejak tahun 70-an. Ia, ketika itu, pendatang dari Semarang. Karena tak ada lapangan pekerjaan lain, ia mencari sesuap nasi dengan memulung. Ternyata lumayan hasilnya. Dengan modal itu, Sucipto meningkatkan statusnya menjadi pengusaha lapak. "Tahun 1973, saya masih jadi lapak lho," katanya. Di tingkat ini, nasibnya baik. Maka, dalam tempo lima tahun, ia sudah menjadi juragan sampah. Sejengkal demi sejengkal, ia membeli tanah. Akhirnya, pada 1982, Sucipto berhasil mengumpulkan modal Rp 250 juta -- sebagian pinjaman dari bank. Uang ini dipakai untuk meluaskan lapaknya -- komoditi sampah memang makan tempat. Ia kemudian membeli tiga unit mesin biji plastik seharga Rp 18 juta. Modal juga digunakannya untuk membeli sampah dalam jumlah cukup besar, 12 ton per hari. "Sehari, saya bisa mengeluarkan Rp 6 juta untuk membeli sampah plastik," katanya kepada pembantu TEMPO, Nor Aizan A. Halim. Anak-anak buahnya dibayar mingguan, rata-rata Rp 23.000. Belakangan, pasaran anjlok. "Usaha ini mulai lesu sekitar Agustus tahun lalu (1991)," kata Sucipto. Isyaratnya sudah terlihat 4 bulan sebelumnya. Plastik jenis PE, yang biasanya Rp 900 per kilogram, harganya turun 16-22%, Maret lalu. Plastik ember, yang biasanya bisa dijual Rp 550 per kilo, turun menjadi Rp 450. Sekarang, pasaran plastik berkisar Rp 300 Rp 650 per kilo. "Sudah harga turun, penjualan pun seret. Saya tidak tahu persis kenapa permintaan menurun. Bisa karena daya beli masyarakat berkurang, tapi bisa juga karena sampah impor itu," katanya. Menurut Sucipto, sampah plastik impor masuk sejak November 1990. Mulanya, para pemasok sampah lokal belum sadar. "Karena importir dan pabrik memang bebas mengimpor sampah dengan bea masuk rendah," kata Sucipto. Sampah yang ditawarkan dari luar itu, katanya, bukan barang butut, melainkan produksi pabrik yang tidak memenuhi syarat (salah produksi). Harganya lebih mahal sedikit daripada sampah lokal, tapi kualitasnya baik karena baru dan bersih. Konon, barang itu eks Jepang, Australia, Swedia, dan Belanda. Belakangan, malah ada tawaran baru dari luar negeri. Tapi bukan limbah plastik yang punya harga. Tawaran baru ini benar-benar sampah buangan. Plastik yang sudah digiling seukuran dua jari, dari berbagai jenis, dicampur dengan kertas dan sebagainya. "Harganya hanya Rp 75 per kilo," kata Sucipto. "Tapi, kabarnya, hanya 60% yang bisa dimanfaatkan. Sisanya, mereka memang cuma mau buang sampah di Indonesia." Toh ada juga pabrik plastik yang mau membeli. Dan karena itu, sampah lokal tak dilirik lagi. Kenyataan ini perlu menjadi "pekerjaan rumah" para pengambil keputusan di Departemen Perdagangan. Ini serius. Tapi Bungi tetap optimistis dalam menjalankan usahanya. Permintaan di perusahaannya tak menurun walau harganya memang anjlok. Ia masih bisa bertahan karena kesediaannya memberi utang kepada pabrik. Ia juga merasa harus terus berupaya. "Saya sudah naro jutaan rupiah di beberapa lapak untuk modal mereka," katanya. "Mana mungkin berhenti?" Pengusaha seperti Untung Basuki juga tidak berniat mundur kendati omzet penjualannya turun 70% sampai 80% per hari. Ia akan terus. Kalau perlu, dengan perang harga. "Saya punya tanggungan 80 buruh dan 10 staf." Sementara plastik mendapat tantangan, sampah kertas yang punya daur ulang paling pendek masih lancar-lancar saja. Sampai sekarang, omzet lapak menjual kertas bekas tidak turun. Sampah kertas ini tak perlu menjalani proses lain untuk dijadikan bahan baku pabrik kertas. Tinggal memisahkan menurut jenisnya. Umumnya hanya lima macam. Setelah dipilah, diantar langsung ke pemasok pabrik kertas. Syamsuddin Aidit, 54 tahun, pemilik PT Karya Bersama Usaha Mandiri, adalah salah satu pemasok. Tiap bulan, ia menyetor 1.000-1.100 ton sampah kertas seharga rata rata Rp 200 juta ke PT Kertas Bekasi Teguh. Penyuplai seperti Syamsuddin juga tak perlu punya puluhan anak buah. Di kantornya, di bilangan Bekasi, ia hanya dibantu dua keponakan menunggu kiriman enam lapak langganannya. "Tapi saya tidak menolak lapak lain yang datang," katanya. Syamsuddin menerima barang-barang yang sudah dalam keadaan bersih, artinya sudah dipilah menurut jenisnya. Setiap kali ada mobil ekspedisi datang, dia hanya memeriksa sepintas. Tak perlu menimbang lagi. Dengan lampiran DO dari Syamsuddin, mobil masuk ke pabrik. Kertas antaran ditimbang di pabrik. Perhitungan di pabrik itu kemudian diserahkan kepada Syamsuddin untuk pembayaran sesuai dengan volume dan jenis barang. "Pabrik membayar sekitar 4 bulan setelah penyerahan barang," katanya. Syamsuddin mendapat "ongkos tunggu" alias bunga 2,5% per bulan. Dalam kurun empat bulan itu, Syamsuddin mengeluarkan modal kerja Rp 800 juta. Dua ratus juta rupiah modal dari kantongnya sendiri, sisanya dari beberapa mitra bisnisnya. Ada lima macam kertas bekas yang ditangani Syamsuddin. Kardus (boks pasar), yaitu bungkus peralatan eletronik yang tebal. Lalu karton dup leks: kotak rokok, boks makanan, dan paper tube (rol untuk menggulung kain), kertas arsip HVS, buku tulis, dan dokumen kantor. Dua jenis lagi, kantong semen dan kertas boncos (koran, majalah bekas, kertas kado, dan sebagainya). Keuntungan yang diambil Syamsuddin rata-rata Rp 21 per kilo. Keuntungan terbesar didapatnya dari kardus, dibelinya Rp 198 dari lapak bisa dijual Rp 225 ke pabrik. Keuntungan paling kecil bila memasok boncos. Dibeli dari lapak Rp 77 dan dijual ke pabrik Rp 85. Tiap bulan, menurut pengakuannya, Syamsuddin mengantongi keuntungan 3 sampai 4%, yang artinya Rp 6-8 juta. Syamsuddin yang berbadan sedang ini, bapak lima anak, mulai berurusan dengan kertas bekas sejak 1978. Asal mulanya tak sengaja. Tahun itu , Syamsuddin punya mobil omprengan Hi Ace. Sopir mobil tersebut sering mengangkut sampah kertas pesanan seorang pemasok. Mengetahui peluang bisnis itu, Syamsuddin terjun sendiri dengan mencoba menjual kertas bekas ke pabrik, setelah menghubungi seorang pemasok. Atas jasa kenalan istrinya di pabrik, perusahaan Syamsuddin akhirnya ditunjuk sebagai pemasok pada 1980. Istrinya yang mula-mula terjun ke lapangan mengurus usaha ini, sebab Syamsuddin sendiri ketika itu menjabat kepala bagian di perusahaan penerbangan MNA. Istrinya bertangan dingin. Usahanya meningkat, mulai dari pesanan sekitar 100-200 ton sebulan menjadi 600-700 ton per bulan. Sayang, istrinya keburu dipanggil Yang Mahakuasa pada 1987. Syamsuddin kemudian minta pensiun dini kendati masih punya masa kerja delapan tahun. Tak lain agar bisa terjun langsung ke bisnis kertas bekas. Tapi ia tak sia-sia meninggalkan pekerjaaan di perusahaan penerbangan yang prestius itu. Sarjana Muda Fakultas Ekonomi UGM ini bisa memutar roda bisnisnya menjadi lebih kencang dan mendapat penghasilan lebih besar. "Bisnis ini lancar. Secara umum, jumlah yang dikirim lapak selalu tertampung," katanya. Berkat sampah kertas itu, Syamsuddin kini memiliki rumah berlantai dua di atas tanah 500 meter persegi di kawasan Kemayoran. Ia juga memiliki tanah 1.100 meter persegi di Bekasi Utara, dan seluas 1.800 meter persegi di Bantar Gebang, Bekasi. Syamsuddin kini mulai melirik ke sampah plastik. Ia telah menanamkan modal Rp 35 juta untuk membuka usaha penggilingan sampah plastik di Bekasi. Adakah desakan kertas impor, seperti yang dialami plastik? "Tidak. Sampah kertas lokal tetap tertampung. Hanya harganya memang tidak pernah naik, padahal harga kertas kan naik terus," katanya. Menurut Direktur Utama Kertas Bekasi Teguh, Amut Suratman, KBT memproduksi 6 macam kertas sebanyak 8.000 ton per bulan. Lebih dari setengah kebutuhan bahan baku yang 13.200 ton berasal dari limbah kertas. "Bahan baku lokal ini potensial di kota-kota besar," katanya. Bahan baku impor hanya dijadikan penunjang bila bahan baku lokal tidak mencukupi. Per Desember lalu, umpamanya, hanya dibutuhkan pulp impor 200 ton per bulan. Sedangkan bahan baku limbah kayu, jenis Albazia (Sengon) dan Samoso, 6.000 ton. Di sektor kertas, bendera kaum pemulung masih berkibar. Para pedagang, dengan "penyakit impornya", belum sampai menggeser mereka. Bunga Surawijaya dan Indrawan
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini