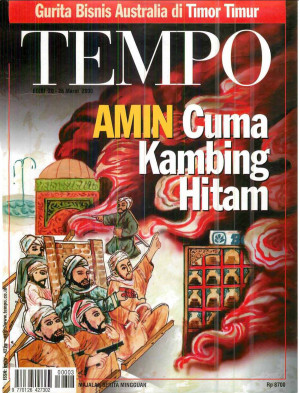NYAI Marwanih sakit-sakitan dalam usinya yang lanjut. Tubuhnya yang renta kini lebih banyak berbaring di sebuah kamar, dalam rumah kecil yang terjepit di gang sempit Sawangan, Bogor, Jawa Barat. Kerut-merut wajahnya melukiskan perjalanan panjang yang meletihkan. Sebuah perjalanan menggapai keadilan.
Marwanih sebenarnya tidaklah sangat miskin. Dia cuma menjadi korban perampokan, tapi terserat di rimba hukum justru ketika berupaya mengembalikan haknya. Pada 1990, Marwanih mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri Bogor karena tanahnya seluas 22.000 hektare diserobot sebuah konsorsium perumahan: Angkatan Laut, PT Mega Pesanggrahan Indah, dan Yayasan Setia Bujana. Setahun proses berlangsung, pengadilan mengabulkan tuntutannya, menyatakan dia sebagai pemilik tanah itu. Tapi pihak tergugat mengajukan banding. Setahun berikutnya, Pengadilan Tinggi Jawa Barat membuat keputusan sama: Marwanih menang.
Namun, cerita belum berakhir. Pihak tergugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan di sini prosesnya lebih panjang. Selama tiga tahun, perempuan tua itu mondar-mandir ke MA. Beruntung Marwanih. Pada 1995, lembaga keadilan tertinggi itu menegaskan putusan sebelumnya: MA menolak permohonan kasasi tergugat.
Para tergugat tak puas juga. Mereka mengajukan PK: peninjauan kembali terhadap putusan kasasi. Namun, dewi keadilan tetap berpihak kepada Marwanih, meski harus ditunggunya selama dua tahun. Pada 1997, dia kembali menang perkara.
Keanehan terjadi setelah itu. Saat eksekusi sedang berjalan, Oktober 1998, sebuah perintah penghentian datang dari Pengadilan Negeri Bogor yang menerima amanat dari MA: meminta eksekusi ditunda karena kasus ini sedang dalam proses PK kedua. Kasus ini tidak selesai hingga hari-hari ini.
Begitulah. Abad berganti, dan sepuluh tahun berlalu, kini Marwanih terkapar kehabisan tenaga, waktu, serta biaya.
Tragedi Marwanih hanyalah noktah kecil di antara samudra kasus hukum negeri ini. Namun, inilah salah satu yang membuat MA tampak menjadi sebuah lembaga tinggi yang rela merendahkan martabatnya sendiri dengan sibuk mengurusi kasus tanah. Juga lembaga yang korup. Kasus ini menegaskan anggapan umum bahwa penegak hukum, bahkan di tempat yang paling tinggi, selalu bisa dibeli dan senantiasa memihak yang kuat.
Tak pernah ada yang disebut PK kedua, kecuali itu rekaan para hakim agung yang kurang kerjaan atau haus uang.
Sulit dielakkan, bersama perombakan di Kejaksaan Agung, pembaruan di MA adalah salah satu agenda penting reformasi untuk membenahi krisis hukum yang parah di negeri ini. Itulah sebabnya ketika MA harus mengganti hakim agungnya bulan-bulan ini, semua mata memandang ke arahnya. Tidak pernah pemilihan ketua MA memperoleh perhatian seserius seperti sekarang.
Agustus nanti, kursi ketua MA akan ditinggalkan Sarwata, yang memasuki usia pensiun. Dan MA kini telah mengirimkan 24 nama calon hakim agung ke DPR untuk digodok sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Tapi, banyak kalangan mendesak agar ketua kali ini dipilih dari luar "tradisi MA". Presiden Abdurrahman Wahid, misalnya, mendukung pencalonan Benjamin Mangkoedilaga. Kalangan lain mencalonkan Todung Mulya Lubis, ahli hukum tata negara Bagir Manan, atau M. Mahfud. Todung jelas menolak pencalonan ini. Siapa pun mereka, DPR-lah yang akan mengetokkan palunya 15 Mei nanti.
Adalah soal siapa orangnya, dan bukan sistem, yang tampak menonjol dalam hal ini. Namun, itu bukan tanpa alasan sama sekali. Sebab, adalah antara lain oleh tingkah polah para hakim wajah MA jadi porak-poranda.
Hakim Agung Sarwata tidak terkecuali. Sumber TEMPO mengatakan bahwa melalui keterlibatan anaknya, Wawan Sarwata, sang hakim beberapa kali membuat keputusan ganjil—salah satunya dalam soal sengketa tanah. Kasus-kasus yang berbau kolusi dan suap ini juga menimpa beberapa hakim agung lain (lihat: Sindikat Alap-Alap Bertoga).
Tidak selalu pembengkokan perkara berbau uang. Banyak kasus menunjukkan para hakim agung sangat lemah berhadapan dengan penguasa eksekutif, terutama dalam perkara-perkara politik. Dengan begitu, mereka mudah tergelincir sekadar sebagai alat kekuasaan.
Pada 1996, misalnya, Sarwata secara tak langsung ikut menjebloskan Muchtar Pakpahan ke penjara. Aktivis buruh itu dituduh mendalangi kerusuhan Medan beberapa tahun sebelumnya. Pengadilan memutus bebas. Namun, belakangan, Sarwata mengeluarkan PK yang diajukan jaksa agar Pakpahan dipenjara. Ini aneh. Sebab, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, PK hanya bisa diajukan oleh terhukum, bukan oleh jaksa, dengan tujuan mengurangi hukuman. Dalam kasus ini, Sarwata justru mengabulkan permintaan PK untuk menambah hukuman bagi Pakpahan.
Soerjono, pendahulu Sarwata, punya perkara lain lagi. Dia mencabut putusan MA sebelumnya tanpa melalui PK, melainkan cuma dengan selembar memo. Dengan itu, dia menyelamatkan Gubernur Irianjaya, yang oleh masyarakat setempat dituntut ganti rugi senilai Rp 18,6 miliar karena dituduh menyerobot tanah adat.
Melihat kinerja hakim agung yang buruk, tidaklah mengherankan jika Daniel S. Lev, pengamat hukum asal Washington University, Amerika Serikat, mengusulkan perombakan radikal di tubuh MA. Bagi dia, lembaga itu perlu memensiunkan semua hakim agungnya untuk kemudian diangkat kembali setelah melalui sistem seleksi yang ketat. Melalui seleksi itu pula, calon hakim agung dari luar mahkamah bisa berkiprah. "Seleksi itu bisa dilakukan DPR," kata Lev.
Namun, kerusakan MA selama ini bukan cuma karena orangnya. Korupnya MA bisa terjadi karena tiadanya kontrol terhadap lembaga ini, kecuali kontrol penguasa eksekutif yang cenderung bertujuan memanfaatkannya. Putusan-putusan MA, misalnya, bisa melaju begitu saja tanpa ada tandingan.
Dalam keadaan digdaya seperti itulah, menurut pengacara Frans Hendra Winata, kebutuhan akan adanya Komisi Yudisial tak terelakkan. "Komisi itu bertujuan memonitor perilaku hakim dan menilai putusan-putusan yang kontroversial dan tidak bermutu," katanya. Anggota komisi ini sendiri bisa diambil dari advokat, jaksa, akademisi, dan hakim sendiri.
Selain itu, menurut Frans, perlu pula merombak Undang-Undang No. 14/1985, yang memungkinkan MA menjadi lembaga tak tersentuh. Melalui Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan yang dipimpinnya, Frans telah mengusulkan rencana undang-undang baru sebagai penggantinya. Rencana undang-undang itu, misalnya, mewajibkan MA memberikan laporan tahunan kepada masyarakat melalui DPR. Laporan itu meliputi jumlah perkara yang diputuskan, jumlah perkara yang mengalami kebuntuan, laporan masyarakat yang masuk, dan tindakan disiplin yang dijatuhkan MA kepada seluruh badan pengadilan. "Keunikan lain dari RUU ini adalah diikutsertakannya masyarakat dalam pencalonan dan pemilihan hakim agung," kata Frans.
Namun, yang lebih menarik, RUU ini dibuat dengan gagasan untuk meletakkan MA ke fungsi yang lebih mendasar, bukannya mengurusi hal-hal sepele seperti sengketa tanah. Salah satu fungsi penting MA—seperti di banyak negara lain—adalah melakukan uji material (judicial review) terhadap produk-produk hukum yang dikeluarkan badan eksekutif ataupun legislatif.
Dalam era Orde Baru, ada banyak produk hukum seperti keputusan presiden, dan bahkan peraturan menteri, yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Banyak keputusan presiden pada zaman Soeharto, misalnya, bahkan memungkinkan korupsi serta kolusi tampak menjadi legal. Namun, tak pernah ada upaya MA untuk mengkajinya ulang.
Di samping tiadanya kemauan, fungsi penting itu tampaknya juga terbengkalai oleh tumpukan kasus yang kian menggunung. Ada sekitar 2.500 kasus yang masuk ke MA setiap tahunnya, dan setiap tahun lembaga itu menunggak menyelesaikan lebih dari belasan ribu perkara. Sebagian besar kasus berkaitan dengan sengketa tanah atau perdata lainnya.
"Ini tak masuk akal," kata Lev. Mudahnya orang mengajukan kasasi membuat MA kelebihan perkara dan menyusutkannya sekadar sebagai pabrik keputusan. Padahal, semestinya MA "hanya punya tugas memutuskan perkara yang benar-benar penting saja, dan yang punya relevansi dengan pengembangan hukum".
Memfokuskan peran MA kepada fungsi yang mendasar, lebih filosofis dan teoretis, juga merupakan cara untuk memperkecil kemungkinan korupsi mencabik-cabik wajahnya. Sebuah cara agar orang-orang lemah seperti Nyai Marwanih bisa punya rasa hormat terhadap lembaga hukum tertinggi itu.
Arif Zulkifli, Ardi Bramantyo, Darmawan Sepriyossa
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini