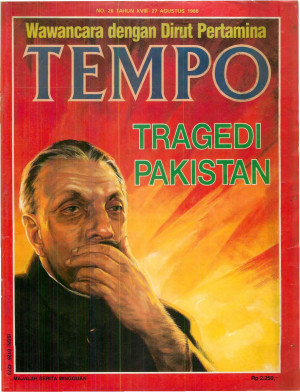Setiap usaha menegakkan hukum menjadi cerita kepahlawanan di negeri ini. Betapa tidak, kegagahan menjalankan tugas, untuk memangkas belantara yang penuh dengan bandit, taruhannya nyawa. Seperti yang dialami oleh Andi Koharidin, petugas Taman Nasional Ujungkulon. Ujungkulon diam-diam adalah sarang kejahatan yang selalu bergelolak. Memutihkan ujung barat Pulau Jawa itu masih merupakan cerita panjang, tapi, tak pelak lagi, manusia-manusia teladan macam inilah yang kita butuhkan sekarang. KOHAR tak menduga bakal terjadi sesuatu. Malam itu perasaannya enak. Suasana kota kecil Labuhan, menjelang dinihari itu, menyenangkan walaupun sepi menggigit. Bulan penuh di atas kepala. Langit terang, bintang-bintang agak tenggelam. Pohon, rumah, pagar, dan bahkan lekuk-lekuk jalan aspal tak rata, seolah lukisan tak berbingkai. "Sungguh saya tak menyangka akan terjadi apa-apa," kisah petugas Taman Nasional Ujungkulon itu. Pintu kantor sudah dikunci. Orang-orang sudah pergi. Derum mesin perahu makin lama makin sayup. Suara riak ombak Selat Sunda kembali mengatasi sunyi. Mereka memang harus pergi ke Pulau Peucang -- pulau kecil di sebelah barat Jawa. Mereka membawa berbagai perlengkapan. Besok ada tamu penting ke sana. Pejabat tertinggi bidang pelestarian alam Malaysia hendak mengunjungi Taman Nasional Ujungkulon. Kohar melangkah pulang sendirian. Rumahnya hanya berjarak empat petak dari kantor. Berbadan gempal, kumis tebal, rambut melampaui kuduk, Kohar sebenarnya lebih mirip jawara, pendekar Banten. Tapi dia petugas Taman Nasional Ujungkulon. Petugas yang selalu mengabdi kewajibannya dengan gagah. Sebuah pistol terselip di pinggangnya, tanpa sarung. Sore tadi, istrinya mengingatkan: bawa 'Colt-38 Auto' itu. Dia menurut saja. Malam sudah tinggal sepertiga. Mungkin sekarang jam 03.00 dinihari. Kalender telah menunjuk angka 16, bulan Oktober 1986. Sekitar dua rumah dari kediamannya, tiba-tiba Kohar sadar: dia bukan satu-satunya orang yang menyusur sepi malam itu. Di bawah pohon asam, dekat rumahnya, tampak dua orang berdiri. Mereka beranjak ke arahnya, berpapasan, tanpa saling menyapa. Kohar mencoba mengenali keduanya tapi sia-sia. "Mereka agak menunduk," kata Kohar mengenang. Cahaya bulan pun tak menolong. Malah hanya meninggalkan bayang hitam pada wajah mereka. Tak seluruhnya hitam. Kohar masih ingat, salah seorang di antaranya berbaju putih, dengan rambut agak panjang. Seorang lagi berbaju kotak-kotak hijau, berpotongan rambut pendek. Ah, peduli amat dengan orang lain. Kohar terus melangkah. Dia membuka pintu pagar, melewati pasir halaman rumahnya, mencapai teras, dan hendak membuka pintu rumah yang tak terkunci. Sekarang ada yang janggal: mengapa lampu teras yang biasanya hidup itu mati? Klikkk..Bunyi aneh mendadak menyentak pendengarannya. Di malam yang sepi apa yang tak terdengar, bisik pun bisa sama keras dengan teriakan di siang bolong. Cepat Kohar menoleh. Ia kaget. Kedua orang itu kini sudah berdiri sekitar 4 meter di depannya, mengancam. Yang berbaju putih mengacungkan revolver pada saya. Pemantik di ujung belakang sudah ditarik. Sedikit lagi menarik picu, saya pasti kena Tak ayal lagi saya menjatuhkan diri ke kiri." Dorrr! . . dorrr' Ledakan itu merobek malam. Tapi Kohar lolos. Terdengar gemerincing kaca pecah. Sebuah peluru menerobos ke dalam rumah, Hendra anak Kohar kelas satu SD dan Babay -- teman Hendra -- yang tidur di kursi ruang depan, terbangun. Lewat kaca pecah itu, keduanya mengintip ke luar. Dorrr-dorr! Peluru kembali berentetan mengincar tubuh Kohar. Sebutir logam runcing itu sempat menyobek celana jeans-nya, mengguratkan luka kulit di tempurung lutut. Tapi Kohar tak mau diam. Cepat dia mencabut pistol. "Mereka berlindung di balik pohon alpokat. Saya tembak ke arah kepalanya. Mereka lari menyusur pagar tanaman. Saya tembakkan pistol ke arah pagar. Ngawur." Tiba-tiba.... crass! Golok membelah bagian belakang kepala Kohar. Crass.... buk-buk. Bacokan, pukulan batang kayu, beruntung menghujani tubuhnya. "Saya tak bisa apa-apa. Pistol saya terlempar. Saya hanya bisa menangkis. Saya tak tahu siapa mereka, dan entah berapa orang. Kaus saya penuh darah. Tangan saya terpotong-potong persis seperti mau dibikin sop. Saya lalu berteriak -- dalam bahasa Sunda -- 'Ma, Bapak ditembak orang!'" Syarifah -- istri Kohar -- berlari dengan histeris ke luar, mengabaikan bahaya yang mungkin juga mengancam dirinya. Tapi tidak. Mereka, para penyerang itu, hanya diam melihatnya. Lalu kabur. Syarifah mendapati suaminya berdiri gontai di tengah teras. Kulit bagian atas kepalanya terkelupas lebar. Darah mengucur dari luka di belakang. Benjolan menyebar di kepala. Dan tangan itu ..ah, untung, masih direkat selapis urat kalau tidak akan jatuh dalam potongan-potongan kecil. Kohar bersandar ke dinding lalu merosot rebah. Kohar tak pingsan. Dia tahu tetangganya Uwen, pergi melapor kepada polisi. Dia tahu istrinya menjerit. Lalu komandan polisi datang sebelum subuh, masih bercelana pendek. Dia tahu, tubuhnya dibungkus dengan tikar butut dibawa ke puskesmas Labuhan, lalu diangkut ke rumah sakit Pandeglang -- di situ dia merasa agak ditelantarkan karena lengannya bertato. Bahkan ia sempat mendengar orang mengucap "Innalillahi...", sehingga ia terpaksa menjawab, "Saya belum mati, kok." Terkapar di rumah sakit merupakan titik balik hidup Kohar. Dibungkus seragam petugas: hem keki dengan pantalon hijau lumut, ia sangat ditakuti karena keras -- "saya memang sering menempeleng orang yang salah, misalnya pencuri" -- berkali-kali ia menjebloskan para penjarah lingkungan ke dalam penjara. Tapi ia pun perayu ulung wanita dengan rekor empat kali menikah, tiga di antaranya telah diceraikan. Petugas yang gagah itu berada di antara hidup dan mati. Bagaimana sampai itu terjadi, Kohar? "Entahlah," jawabnya pendek. "Saya yakin ini ada hubungannya dengan pekerjaan saya. Saya yakin yang hendak membunuh itu komplotan pencuri lobster. Tiga hari sebelumnya, saya menyerahkan mereka pada polisi. Mereka marah sama saya. Karena saya selalu menghalangi mereka. Saya juga menolak diajak kerja sama." Dan sikap itu telah membawanya pada cacat yang tak tersembuhkan, pada kelumpuhan tangan: dan pada akhirnya menjadikannya tak mampu lagi bertugas. Hidup Kohar dipadati pengabdian pada kerja. Alam adalah dunianya sejak kecil. Ayahnya pegawai Kebun Raya Bogor, tinggal di situ juga, memberinya nama Koharudin (kemudian disambungnya menjadi Andi Koharudin). Dia biasa bermain dengan anak Ny. Hartini (istri Bung Karno). Dia gemar permainan laki-laki: berkelahi dan "gatrik" -- mata kanannya sempat pecah kena kayu "gatrik". Sekolahnya: SD, SMP berlalu biasa saja. Dia masuk Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) Bogor atas saran Kepala Kebun Raya. "Enak, dapat ikatan dinas," kata Kohar. Waktu itulah Kohar merajah lengan kanannya dengan gambar seekor ular yang keluar dari sepatu "boot", tapi tak selesai lantaran rasa sakit. Tahun 1966, Kohar lulus. Ia ditempatkan di Bogor, kemudian pindah ke Serang -- membawahkan Mat Sahi, penjaga Pulau Dua yang telah meraih penghargaan Kalpataru -- lalu ke Ujungkulon. Enam tahun dia di kawasan cagar alam itu. Itulah tahun-tahun yang membentuknya jadi petugas keras, yang tak bisa diajak kompromi, yang berani menampar mereka yang mencoba mengaruk kawasan yang dijaganya. Sejak awal bertugas di Ujungkulon, Kohar telah memamerkan jalannya sendiri. Dia tak peduli dengan para jawara yang nongkrong di balik setiap kasus penjarahan Ujungkulon. Tak pilih bulu ia tangkap, periksa, dan seret para pemburu banteng, badak, lobster, sarang burung walet, batu apung, atau kekayaan lain taman nasional itu untuk disentuhkan pada hukum. Dia menolak suap. "Bukan saya tidak butuh uang. Tapi saya ingin membuktikan bahwa hukum memang bisa dilaksanakan." Pada tahun 1971, Kohar berhadapan dengan komplotan Usman dari daerah Cegok. Ia berhasil menangkap lima anggota kawanan itu, memperkarakannya, sampai pengadilan berhasil membuktikan bahwa mereka memang telah memasuki kawasan Ujungkulon untuk berburu badak. Enam bulan penjara. Tahun 1974, Kohar beraksi lagi menyergap Asgari dan dua kawannya yang hendak berburu banteng. Pengadilan Pandeglang mengganjar mereka 6 bulan. Setahun kemudian, Kohar menguliti belang seorang kepala desa dalam rencana pemburuan badak. Syariq, kepala desa itu, telah melalap Rp 328 ribu uang Ipeda. Dia hendak menutupnya dengan menjual cula badak hasil buruan. Untung saja, Alimin dan Muhammad yang ditugasinya berburu kepergok lantas lari meninggalkan ranselnya. Benda itulah yang menjadi petunjuk keterlibatan Syariq. Kepala desa itu pun ditendang ke dalam bui. Kejadian demi kejadian memahat nama Kohar sebagai sosok petugas PHPA yang disegani. "Korban" terus berjatuhan: para pencuri ditangkap, disidangkan, lalu dipenjarakan. Sementara itu, Kohar tetap merasa tenang, tak terancam. Begitu juga perasaannya ketika dia ditempatkan kembali ke Taman Nasional Ujungkulon untuk kedua kalinya. Tepatnya, setelah dia bertugas di Gunung Gede-Pangrango, yang lebih banyak mengurusi perkara ringan -- misalnya pendaki gunung yang memetik bunga edelweis -- ketimbang berhadapan dengan para pencuri profesional. Keadaan sudah banyak berubah ketika Kohar datang lagi ke Ujungkulon. Dia sudah bukan lagi petugas lapangan. Dia, golongan II-D, sudah menjadi orang kantoran -- praktis orang kedua di Taman Nasional Ujungkulon. Tempatnya di Labuhan. Tapi jangan lupa, kejahatan di sana pun makin tinggi. Semakin banyak komoditi yang laku dijual, semakin banyak yang diincar. Batu apung, yang dulu dibiarkan berserakan, kini menjadi incaran. Karena kawula muda menggandrungi jeans bercorak stone-washed dan ahli bangunan mengenal beton ringan, maka batu apung pun diuber-uber. Di Labuhan Kohar kembali berhadapan dengan kawanan pencuri. Dengan Raedy, jagoan dari Pulau Tidung, misalnya. Pernah petugas memergoki perahu milik Raedy memunggah 96 ekor penyu. "Mereka menangkapnya dengan menyelam," kata Kohar. Penyu yang lagi enak-enaknya makan di karang dikait siripnya, ditarik ke atas. Petugas kontan melepas binatang itu kembali ke laut. Lalu Kohar menempelengi para pencuri itu. Tersebutlah nelayan dari Pulau Raas (daerah Madura) yang sering mengusik ketenangan para petugas Ujungkulon. Perahu mereka, dua atau tiga, hanya menggunakan layar biasa. Mereka menyelam, mengambil semacam kerang, untuk mendapatkan mutiara. Kohar cepat bertindak. Tapi kemudian ia melepaskan saja orang-orang itu. "Kasihan," katanya. "Mereka hanya nelayan kecil." Yang terakhir Mulyono -- pencuri batu apung. Bersama bosnya, ia mengunjungi Kohar, minta izin mengambil lobster. Pihak Taman Nasional menolak, tapi memberi alternatif: bagaimana kalau membudidayakan lobster saja -- ini belum pernah ada. Bila setuju, pihak Taman Nasional siap membantu. Mereka setuju. Tapi sejak itu tak pernah datang lagi. Tiba-tiba Mulyono muncul di Pulau Panaitan, mengangkuti batu apung, konon sampai 300 karung. Lalu kabur, entah ke mana. Para petugas setempat diam saja. Maklum, sudah disuapi masing-masing Rp 5.000. Kohar geram. Dia, lagi-lagi, menggunakan caranya sendiri untuk menghukum anak buahnya: tempeleng. Ujungkulon memang rawan. Sungguh. Sindikat penjarah tak lagi hanya terbatas main kucing-kucingan dengan petugas. Bila perlu mereka mengancam, atawa menggoda dengan iming-iming. Raedy yang sudah kena gampar pun masih berani datang ke rumah Kohar. Ditaruhnya segepok uang di meja, sambil berkata -- menurut Kohar: "Izinkan saya menangkap penyu mengganti yang Bapak lepaskan dulu. Lima puluh ekor saja." Kohar tersenyum, lalu menjawab, "Bawalah pulang uang ini. Kalau kamu mau mencuri, ya curi sajalah. Tak usah pakai begini segala. Tapi ada syaratnya. Kalau mencuri jangan ketahuan saya, dan jangan salahkan saya kalau kapal kamu jadi bocor dan tenggelam." Raedy memang sudah tersapu. Tapi coba lihat di sekitar Kohar, macan-macan buas siap mencabik petugas itu kalau lengah. Ada sejumlah jawara acap bertandang, melempar basa-basi, main bujuk agar Kohar sudi kongkalikong. Dan lihat itu Thamrin, salah seorang bawahannya. Tampangnya, sih, bukan anak bawang yang mudah dikecoh atau disogok. Tapi dia justru sudah menjadi tokoh penting kawanan yang hendak menguras habis isi kawasan terlindung itu. Berkali-kali dia mencoba cari muka di rumah Kohar, guna melunakkan atasannya. Kohar diam saja, ia tahu semua itu. Thalib, jawara dari Cinangka yang ditakuti, pun setali tiga uang. Berulang-ulang datang ngajak ngobrol atau biasa: mengajak kerja sama. Bosnya, seorang cina Pandeglang, sempat juga dibawanya. Mereka minta agar diberi kesempatan mengambil kayu "kuderang" -- bahan pewarna batik. Kalau Kohar setuju, imbalannya "bereslah". Tapi Kohar menampik. Thamrin juga tidak malu-malu berupaya. Dia mendekati istri Kohar. "Saya disuruhnya membujuk suami saya," kata Syarifah. Kohar tak bergeming. Thamrin menawari sepeda motor Honda Astrea baru pada Syarifah. Dia bilang motor itu hanya perlu diganti dengan uang Rp 350 ribu saja. Dan itu bisa dibayar kapan pun. Kohar malah marah-marah. Tiba-tiba ada geledek. Polisi memanggil Kohar, memeriksanya, dan menyangkanya telah mencuri sarang burung walet di Sanghiang Sirah, Ujungkulon. Kohar kaget. Dia yakin benar ada teman sekantor yang memfitnahnya. Masalahnya, seperti yang dijelaskannya pada polisi, begini: dalam rapat di kantornya, Kohar mengusulkan agar secara resmi pihaknya memanen sarang burung itu. "Kalau dibiarkan, toh dicuri orang." Menjaga khusus daerah itu juga mustahil. Selain kurang tenaga, juga tak ada anggaran. Sedangkan bila dikelola, menurut dia, kelestarian walet itu akan tetap terjaga. Dan pihak Taman Nasional akan punya tambahan dana yang bisa dikontrol secara terbuka. "Lagi pula, itu baru merupakan usulan saya dalam rapat," kata Kohar. Untung, polisi mau mengerti. Ada lagi. Baru setahun Kohar di Ujungkulon, petaka terjadi. Mulanya, perahu patroli memergoki delapan orang yang menangkap lobster. Di antaranya adalah Aceng, sopir toko jamu Leo yang kabarnya biasa membawa lobster itu ke Jakarta. Mereka dibawa ke Labuhan. Kebetulan Kepala Taman Nasional, Sudradjat, saat itu sedang tak ada di tempat. Maka, Kohar mewakilinya, menyerahkan para tersangka pada polisi. Sewaktu polisi menginterogasi, mereka mengaku disuruh Thamrin yang juga petugas Taman Nasional. Kepala polisi Labuhan mendatangi Kohar, menyatakan hendak menangkap Thamrin. Kohar menyarankan agar penangkapan itu ditunda, sampai atasannya datang. Tapi sebelum Thamrin diperiksa, meledaklah peristiwa yang hingga kini menggentarkan hati setiap petugas pelindung alam di sana: penembakan dan pembacokan Kohar. Peluru dan golok, yang mudah menghunjam tubuh setiap petugas di sana, kali ini membantai Kohar. Semua tahu, nasib yang menimpa Kohar terhubungan dengan pekerjaannya mengamankan Ujungkulon. Kepala Taman Nasional Ujungkulon sekarang, Sudarmadji, pun sependapat. "Saya juga pernah diancam orang," kata Sudarmadji. Para petugas hilang nyalinya bila mendengar nama Thamrin dan komplotannya. Sebelas peluru menyobek sepi dinihari, hampir dua tahun lalu. Enam dari revolver organik FN-38 si penyerang, lima peluru dari pistol Kohar -- sebuah di antaranya melubangi tiang listrik. Lalu disusul bacokan golok itu. Semuanya memang tidak menewaskan Kohar, tapi telah memancung karier si penjaga alam itu sama sekali. Meskipun Kohar masih bisa ke kantor (sekarang di PHPA -- Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam -- Bogor), dia merasa malu: dengan kedua tangan lumpuh begitu tak banyak hal yang bisa dikerjakannya lagi. Kini Kohar hidup seadanya di Bogor, di rumah kontrakan di daerah Perumnas. Hanya sebuah TV besar yang tampak sebagai barang berharga di rumah itu. Kenaikan pangkat yang SK-nya sudah ada sejak setahun lalu belum juga dicicipinya. Lalu sang istri membantu menambah nafkah keluarga dengan berjualan es sirup di samping rumah. Maka, kadang Syarifah seperti menggugat. "Dia 'nggak' mau, 'sih', diajak begitu-begitu," ucapnya polos, menunjuk suaminya. "Kalau mau, hidup kami kan tidak begini." "Ah, begini juga baik," kata Kohar. Lalu istrinya membuka perban yang melilit lengan kirinya. Setelah sekian lama berlalu, darah masih meleleh dari sela pen logam yang menulangi, lengan Kohar. Zaim Uchrowi dan Priyono B. Sumbogo
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini