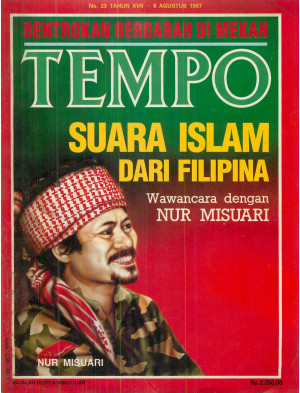LINGGA Asri memang desa Hindu. "Tapi kalau mereka ditanya banyak juga yang menyebutkan beragama Islam Jawa," ujar Marsudi atau Dipoyoso, yang menjadi lurah sejak 1979, menggantikan kakaknya. Dari lima pedukuhan di Desa Lingga Asri, tiga di antaranya boleh dikata memang desa Hindu. Lebih dari 95% warganya menjalankan upacara-upacara Hindu. Di desa yang dibatasi oleh tebing terjal dan hutan pinus, dihubungkan oleh jalan setapak, dari dukuh satu ke yang lain berjarak sekitar lima kilo meter. Tiap dukuh dihuni 200 sampai 300 warga. Sebagaimana kebanyakan desa di Jawa yang kemudian jadi "hidup", sejarah Lingga Asri pun dimulai dari datangnya seorang bangsawan yang kemudian menetap di desa. Menurut cerita-cerita orang tua yang masih diingat oleh Dipo Taruno, kakak Dipoyoso, penemu desa ini bernama Pangeran Sunyolobo. Ia salah seorang tentara Pangeran Diponegoro yang lari menyingkir dari kejaran tentara Belanda, setelah Diponegoro menyerah. Begitu tiba di Lingga, Sunyolobo merasa aman dari kejaran, karena letak desa ini di tebing yang tersembunyi. Mulailah Pangeran ini mengatur desa yang masih primitif itu bersama-sama penduduk setempat. Lalu Sunyolobo diangkat sebagai demang, jabatan yang kini setaraf lurah. Sunyolobo mempunyai anak, namanya Tjokro Manggolo -- tak jelas siapa ibunya, apakah bangsawan dari Mataram, ataukah wanita Desa Lingga. Yang diketahui, anak itu kemudian menggantikan kedudukan ayahnya sebagai demang. Tjokro kemudian mengembangkan ajaran Kejawen. Pada saat ajaran itu telah mantap merasuk di hati penduduk, Tjokro digantikan oleh Dipo Wongso, anak kandungnya sendiri, atau cucu Sunyolobo. Dipo Wongso meninggal, digantikan lagi oleh anak kandungnya, bernama Dipo Menggolo. Pada saatnya Dipo Menggolo digantikan oleh Dipo Yoso (ini bukan Marsudi adik Dipo Taruno). "Dipo Yoso itu adalah ayah saya," kata Dipo Taruno. Dan pada 1951 Dipo Yoso, ia tak menjadi demang lagi melainkan lurah, diganti oleh Dipo Taruno sampai 1979. "Saya mengundurkan diri karena sudah tua dan sakit-sakitan," tutur Dipo Taruno. Ketika pemilihan lurah diadakan dalam suasana lebih demokratis, Dipo Taruno mencalonkan adiknya sendiri, Marsudi, walau sang adik sudah memeluk agama Islam. Benar saja Marsudi terpilih, antara lain karena kewibawaan Dipo Taruno itu. Aneh juga, di desa Hindu kepala desanya ternyata Islam. Ia lalu memakai "gelar": Dipoyoso, mewarisi nama ayahnya. "Baru sekarang ini Lurah Lingga dipegang orang Islam. Sebelumnya selalu dipegang orang Kejawen, atau Hindu," ujar Dipo Taruno sambil sesekali menyedot rokok klobotnya. * * * Sebagaimana sebuah masyarakat Hindu, dibutuhkan orang yang bisa memimpin upacara-upacara, yang disebut pemangku. Supardi adalah penduduk Lingga Asri yang pertama dinobatkan sebagai pemangku di desa tebing bukit ini. Sebelum dia, pemangku itu dijabat oleh orang Pekalongan bernama Sutejo. Maka, bayangkanlah seorang Supardi, ayah delapan anak, dengan pembawaannya yang tenang ini berjalan naik turun tebing, mengunjungi dukuh demi dukuh. Lalu pengajian pun dilakukan malam hari, dengan penerangan lampu minyak tanah dan hidangan teh serta singkong rebus. "Setiap yang hadir di pengajian menyumbang Rp 100 untuk membeli teh dan minyak tanah. Singkong diambil dari kebun masing-masing," katanya. Sebuah masyarakat yang masih "utuh", masih merasa senasibsepenanggungan. Pemeluk Hindu di Lingga Asri tak berorientasi ke Bali dalam melakukan upacara. "Kami menekankan pada penyatuan dengan adat-istiadat Jawa, bukan pada adat-istiadat Bali," kata Supardi. Maka, bisa dimaklumi, meski ada perayaan Galungan, di sini tak dikenal upacara pembakaran mayat (ngaben), upacara potong gigi (metatah), dan sebagainya. "Lagi pula kami 'kan miskin," kata Supardi. "Kalau ikut-ikutan menyelenggarakan upacara-upacara itu, tak mampu. Cari makan saja susah." Untuk diketahui pula, di desa ini taman pemakaman masih bersifat umum umat Islam dan umat Hindu dikubur di pekuburan yang sama. Juga tak ada niat dari para pemeluk agama, misalnya, saling melancarkan propaganda dan mempengaruhi, agar orang berpindah agama. Kehidupan berjalan sangat harmonis. Bertambahnya umat masing-masing ditentukan oleh alam, oleh kelahiran. Bahkan perkawinan pun tak mengubah statistik pemeluk agama. Gunawan, seorang pemeluk Hindu dari Dukuh Lingga, kawin dengan perempuan Islam. Supaya tak bertele-tele dan banyak persoalan, dia kawin di KUA, Kantor Urusan Agama, karena istrinya tetap teguh pada agama yang dipeluknya. Tetapi Gunawan tetap Hindu dan ia ikut bersembahyang pada hari raya Galungan itu, tanpa ditemani istrinya. Yang tak diperoleh keterangan bagaimana nanti agama anak. Perkawinan beda agama itu banyak terjadi di Lingga Asri. Adalah Sukamto, orang Lingga Asri asli, yang kini menjadi pimpinan Parisadha Hindu Dharma Pekalongan. Sukamto, tentara di masa Perang Kemerdekaan, anggota kesatuan TNI-AL di masa kedaulatan RI, kini seorang pensiunan dan tinggal di Pekalongan sebagai wiraswasta. "Sejak lahir saya sudah Hindu. Saya menyukai adat-istiadat dan menghormati nenek moyang dan leluhur," kata Sukamto. Kesadaran orang Lingga Asri tentang miskinnya desa mereka, dan kuatnya niat untuk melaksanakan upacara agama, memang mengharukan. "Kami melaksanakan agama dengan penuh kesederhanaan. Kami bukan pemeluk Hindu yang kaya," kata Sukamto. Senyum Lurah Marsudi Keliru bila Anda membayangkan Desa Lingga Asri terpencil, apalagi terisolir. Desa ini terbelah dua oleh jalan beraspal yang menghubungkan Kota Pekalongan dengan Karangkobar (Purwokerto. Bahwa Lingga Asri tertinggal dalam pembangunan, misalkan dibandingkan dengan desa terdekatnya, Kajen atau Paninggaran, memang begitulah adanya. Lurah Marsudi, yang disebut juga Lurah Dipoyoso, tak tahu persis berapa pendapatan per kapita penduduknya. "Kira-kira sepuluh ribu rupiah sebulan pendapatan per keluarga di sini," katanya, dengan setengah yakin. Yang agak pasti ia ketahui hanyalah warga desanya enggan merantau ke kota, misalnya, untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Pak Lurah tak menyebutkan sebabnya, tapi agaknya menyangkut soal keterampilan. Sejarah desa telah membatasi keterampilan penduduk untuk cuma berkebun atau menyadap-pinus. Lebih dari separuh wilayah desa ini merupakan hutan negara yang ditanami pinus. Hamparan petak-petak sawah yang miring di lereng bukit, karena sulitnya air, hanya ditanami sayur-mayur dan ubi-ubian. Air untuk mandi, minum, dan kebutuhan sehari-hari tampaknya tak jadi masalah benar. Di mana-mana, di sudut-sudut desa terlihat pancuran. Di pancuran itulah, bila menjelang sore, para remaja berebutan mandi, bersorak-sorak, bersenda-gurau. Hampir semua rumah punya pesawat radio, meski dari kelas yang sederhana. Televisi ada juga beberapa, antenanya mencuat tinggi dan dihidupkan oleh aki. Lingga Asri belum dijamah listrik. Dan rumah-rumah yang dibuat dari papan itu pun mencekam di malam hari. Hanya gaung suara serangga hutan, yang terdengar begitu matahari menyembunyikan diri. Di desa ini, begitu seorang anak menamatkan SD, mereka dengan sendirinya langsung membantu orangtuanya. Atau, menjadi buruh di Perhutani sebagai penyadap getah pinus. Sekolah yang lebih tinggi, ke Pekalongan umpamanya? Hingga kini, tahun 1987, nyaris itu hanya impian. Bukan karena mereka tak menyadari perlunya sekolah. Kemiskinan memang membuat warga Lingga Asri berpikir praktis dan sederhana: seorang anak yang langsung bekerja berarti menambah nafkah keluarga. Sikap itu rupanya berakar kuat. Bahkan mereka yang kira-kira bisa mengirimkan anaknya ke kota, ternyata, lebih suka mendirikan warung. Laris, memang, terutama bila lagi musim orang kota mencoba otot kaki menjelajah hutan pinus, atau berenang di kolam yang dingin airnya. Warung-warung itu umumnya bersih, ditunggui gadis Lingga yang manis, diwarnai oleh lagu-lagu dangdut dari kaset. Partini bisa joget? "Tak bisa," jawab Partini, penunggu warung yang malu-malu itu. Ia tak banyak bicara, sebagaimana desanya yang tak banyak bergerak dari zaman Demang Sunyolobo. Ini memang sebuah potret masyarakat sederhana yang pelan-pelan telah pula disusupi budaya elektronik. Masyarakat miskin yang punya kesadaran religi lebih, dan karena itu tenteram. Angka kriminalitas? Lurah Marsudi menggelengkan kepala sambil senyum. Kita tak tahu sampai kapan senyum itu bertahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini