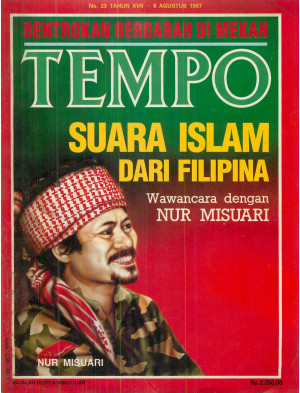ANGIN mati. Pemandangan terasa cuma sapuan bentuk dan warna. Lalu figur itu, berada di depan, dengan pandangan kosong, sulit ditebak yang dirasakannya. Itulah, kesan melihat pameran lukisan Sudarso, yang sebagian besar dari 40 kanvasnya di Bentara Budaya, Jakarta pekan lalu, menyuguhkan figur wanita. Sudarso memang tak termasuk pelukis Indonesia angkatan sebelum zaman Jepang, yang hadir dengan pengaruh besar. Ia bukan seorang pendobrak semacam Affandi, yang garang memelotot cat. Ia pun bukan Rusli, yang menyanyikan haiku lewat kuasnya. Ia bukan pula dari jenis Hendra (almarhum) yang mengabadikan gambaran masyarakat dalam satire warna-warna di kanvas besar. Lelaki bertubuh besar dan pendiam ini, toh, mesti dicatat sebagai pelukis Indonesia yang punya perhatian khusus. Lahir di Ajibarang, Purwokerto, Jawa Tengah, mengembara di Jawa Barat kala muda, kemudian hidup di Yogyakarta bertahun-tahun, sejak 1980 lalu ia bahagia tinggal di rumah kontrakan di Sanur, Bali. Dan, sebagaimana tampak dari pamerannya kini, perhatian khususnya belum berubah: Sudarso pelukis yang suka memotret wanita seluruh tubuh. Di awal-awal kariernya, hingga sekitar awal 1970-an, wanita-wanita Sudarso adalah figur-figur yang tenang, terkesan menyimpan kekuatan, berdiri di ruang "kosong". Kosong bukan dalam arti yang sesunguhnya. Sebab, di situ ada pohon, ada langit, ada batu, kadang-kadang masih ada juga bayangan. Namun, yang dimaksudkan sebagai alam di situ lebih terasa sebagai bukan alam dunia. Ruang di situ lebih mewakili sebuah simbol, sebuah gagasan. Tepatnya, ruang pada kanvas Sudarso, yang menyuguhkan figur wanita, bagi saya adalah ruang surealistis, ruang mimpi. Itulah mengapa tak dirasakan janggal bahwa seorang wanita, cantik, dengan pakaian yang baru, cemerlang, bersimpuh di tanah yang bersih. Sementara itu, di latar belakang kadang tersaji pohon-pohon dan langit, kadang cuma cakrawala dan langit. Dalam ruang seperti itu siapa pun silakan bermimpi tentang wanita ideal tanpa usah diganggu oleh realitas. Dan mimpi Sudarso, pelukis yang gemar nonton wayang kulit, adalah seorang wanita yang tanpa cela. Lihat saja, wajah tanpa guratan secoret pun. Kaki yang mulus dan bersih. Tangan yang sempurna, proporsi yang ideal. Rambut yang subur hitam, mata yang jernih. Dan wanita itu pasrah sepenuhnya. Disuruh duduk di batu menghadap samping, menghadap depan. Atau berdiri memegangi payung. Di lain kanvas, wanita itu diminta bertopang pada tangan kiri, sementara tangan yang lain berada di pahanya. Kadang-kadang si wanita disuruh duduk di kursi. Semuanya saja oleh Sudarso diberi kain dan kebaya baru. Jawa tentu saja, karena, "Saya orang Jawa." Bahkan karya-karya yang diciptakannya selama ia tinggal di Bali adalah wanita-wanita Jawa juga. Mimpi itu tak berubah karena lingkungan berubah. Memang, dunia mimpi dan realitas dua hal yang tak berkaitan langsung. Kalau toh terselip rasa erotis, di kanvas Sudarso rasa itu mengalir lembut, tak bergejolak. Dan itu agaknya karena wanita di kanvas Sudarso adalah sebuah sosok ide, bukan potret nyata. Meski Sudarso melukis dari seorang model, model itu lebih dipakai sebagai pegangan untuk menggoreskan anatomi atau posisi tubuh. Siapa model itu, ekspresi apa yang tercermin dari pribadinya dikesampingkannya. Lihat saja, hampir semua wanita pada kanvas lelaki yang kini berusia 73 tahun itu hampir sama saja ekspresi wajahnya. Jauh berbeda dengan figur wanita goresan Basuki Abdullah, yang sepertinya dipercantik, diperseksi itu. Sudarso dalam hal ini, terasa polos. Ia merasa tak perlu menonjolkan bagian tertentu dari wanita, umpamanya. Pelukis yang mengaku pertama kali belajar kepada Affandi ini memang percaya benar, figur-figur wanitanya akan berbicara sendiri. Mungkin, sikap begini boleh disebut sejenis "aliran kepercayaan". Namun, kesenian memang bukan muncul dari batu ditujukan kepada pohon kering. Ia, kesenian itu, suatu perwujudan, suatu ekspresi, suatu gagasan dari yang disebut manusia untuk manusia. Makhluk yang dalam dirinya, selain akal, juga tumbuh perasaan -- sesuatu yang tak sepenuhnya bisa dirumuskan atau didalilkan. Manusia bukan komputer, bukan robot. Ada suatu kesan yang muncul dari lukisan Sudarso, semuanya saja. Yakni kesan bahwa lukisan itu belum selesai. Pada Tiga Wanita ke Pura Bali umpamanya. Ini seperti sebuah foto yang diambil dari jarak jauh, kemudian dicetak dengan pembesaran sekian puluh kali. Yang membuat bentuk-bentuk figur dan latar belakang di situ nyaris cuma sapuan-sapuan warna tanpa detail. Bila ditengok karya pemandangan alam Sudarso, hal seperti itu terasakan juga. Lukisan Membuat Garam malahan benar-benar sapuan, istilah teknisnya, abstraksi yang kebetulan membangun sebuah sosok manusia, atau gambaran laut dan langit. Benar, Sudarso bukan seorang pelukis nonfiguratif. Analisa itu adalah sebuah upaya memahami karya-karyanya. Dengan membandingkan sejumlah figur dan pemandangan, yang seolah semuanya dipandang dari jauh, satu hal bisa disimpulkan: mimpi memang tak meninggalkan kesan detail. Mimpi lebih membekaskan kenangan suasana, daripada sosok-sosok jelas. Maka, bukan identitas, yang penting dalam karya Sudarso meski di awal 1940-an, setelah beberapa lama belajar dan mendapat kritik dari Affandi, ia melukis potret pula. Adalah suasana yang muncul dari sosok, lalu warna, lalu bekasbekas guratan kuas, perpaduan dari semua itu mestinya yang tampil. Maka, sesungguhnya wanita dalam karya Sudarso bukanlah sebuah nama. Ia, figur itu, sebenarnya mewakili alam yang besar. Lukisan Gadis Yogya, dengan selendang batiknya yang menyentuh lantai itu, adalah mewakili persepsi pelukisnya terhadap alam. Bukan alam dalam arti tafril, tapi alam kehidupan. Di situ rasa keindahan muncul dari segala sudut: bentuk kaki, warna kulit, profil, dan sapuan warna latar belakang. Yang kemudian terangkai dari semuanya itu adalah sebuah pengalaman dari petualangan menjlajahi lekuk-liku. Bukan lekuk-liku tuhuh. Tapi lekuk-liku hidup itu sendiri. Dari "ukuran" seperti itulah sebuah lukisan bisa lebih baik daripada yang lain, atau lebih buruk daripada yang satu. Menanti, karya tahun 1969, seorang wanita duduk memegang payung, termasuk satu yang berhasil. Ruang yang kosong, sosok yang lembut, payung yang gelap, lekukan bibir yang mempesona, adalah pengalaman kita semua sehari-hari. Bukan pengalaman sehubungan dengan wanita, tapi yang lebih luas dari itu. Semacam rasa lega, umpamanya, sehabis kerja keras di sebuah ruang sumpek, lalu menyaksikan sebuah pemandangan laut lepas, dan merasakan angin menerpa wajah. Entah karena usia, entah karena apa, sayangnya, bagi saya, sebagian besar karya Sudarso tahun 1987 tak sekuat Menanti. Pengalaman dari banyak karyanya kini begitu tipis. Duduk di Batu misalnya. Pengembaraan menyusuri bentuk, lekuk-liku garis lengan, lalu garis dada terus pinggul sampai kaki, tak berkesan. Ruang latar belakang pun bukan terasa seperti yang diberikan oleh terpaan angin laut -- nyata dan meninggalkan bekas -- tapi seperti angin biasa yang kita rasakan di mana saja. Singkat kata, terlalu biasa, sudah begitu kita kenal, hingga tak perlu diperhatikan. Bila melihat lukisan boleh diumpakan pengembaraan mencari pengalaman keindahan, tak banyak karya Sudarso yang meninggalkan kesan. Liku-liku pengalaman yang ia suguhkan tak terlalu unik. Toh, perjalanan hidupnya sebagai manusia adalah sebuah perjuangan tersendiri. Pada usia di awal 20-an, ia pergi dari kota kelahirannya, menjadi pengantar susu di Bandung. Salah seorang langganannya bernama Affandi, pelukis yang kala itu belum segarang sekarang. Karya Affandi di tahun-tahun itu, pertengahan 1930-an, masih kental. Sosok-sosok figur masih jelas, belum "cerai-berai", tersusun hanya dari garis-garis yang menggeliat-geliat seperti kemudian. Suatu hari, Sudarso pengantar susu terpesona oleh sebuah lukisan yang tengah dikerjakan Affandi. Ia terbengong-bengong di depan pintu. Oleh Affandi Sudarso disuruh mengantarkan susu dahulu sampai habis, dan kalau mau melihat orang melukis datang lagi saja nanti. Akhirnya hubungan antara pelukis dan si pengantar susu yang berbeda usia tujuh tahun itu jadi akrab. Dan suatu hari Affandi menghadiahkan sisa-sisa catnya. Lalu Sudarso pun mencoba-coba melukis. Bila selesai, dibawa ke rumah Affandi untuk dimintakan kritik. Tak jelas, sejak kapan lulusan Arjuna School -- sekolah dasar swasta di Ajibarang waktu zaman Belanda dulu -- kemudian tertarik melukis wanita. Tapi itu terjadi ketika ia tinggal di Sentul, Yogyakarta. Pernah sebentar ia mengajar di Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI, yang kini jadi Institut Seni Indonesia), rupanya ia tak begitu suka dengan pekerjaan itu. Sifatnya yang pendiam memang tak cocok untuk diajak bekerja sebagai guru. Tapl, dulu, sampai awal 1970-an, sanggar dan rumahnya di Sentul itu menjadi salah satu yang dikunjungi tiap tahun oleh mahasiswa baru ASRI, ketika mereka diajak berkenalan dengan pelukis-pelukis Yogya. Itulah Sudarso. Bagaimanapun, namanya memang sudah tercatat dalam sejarah seni rupa kita -- dengan ruang surealistisnya, dengan figur wanita-wanitanya. Bambang Bujono
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini