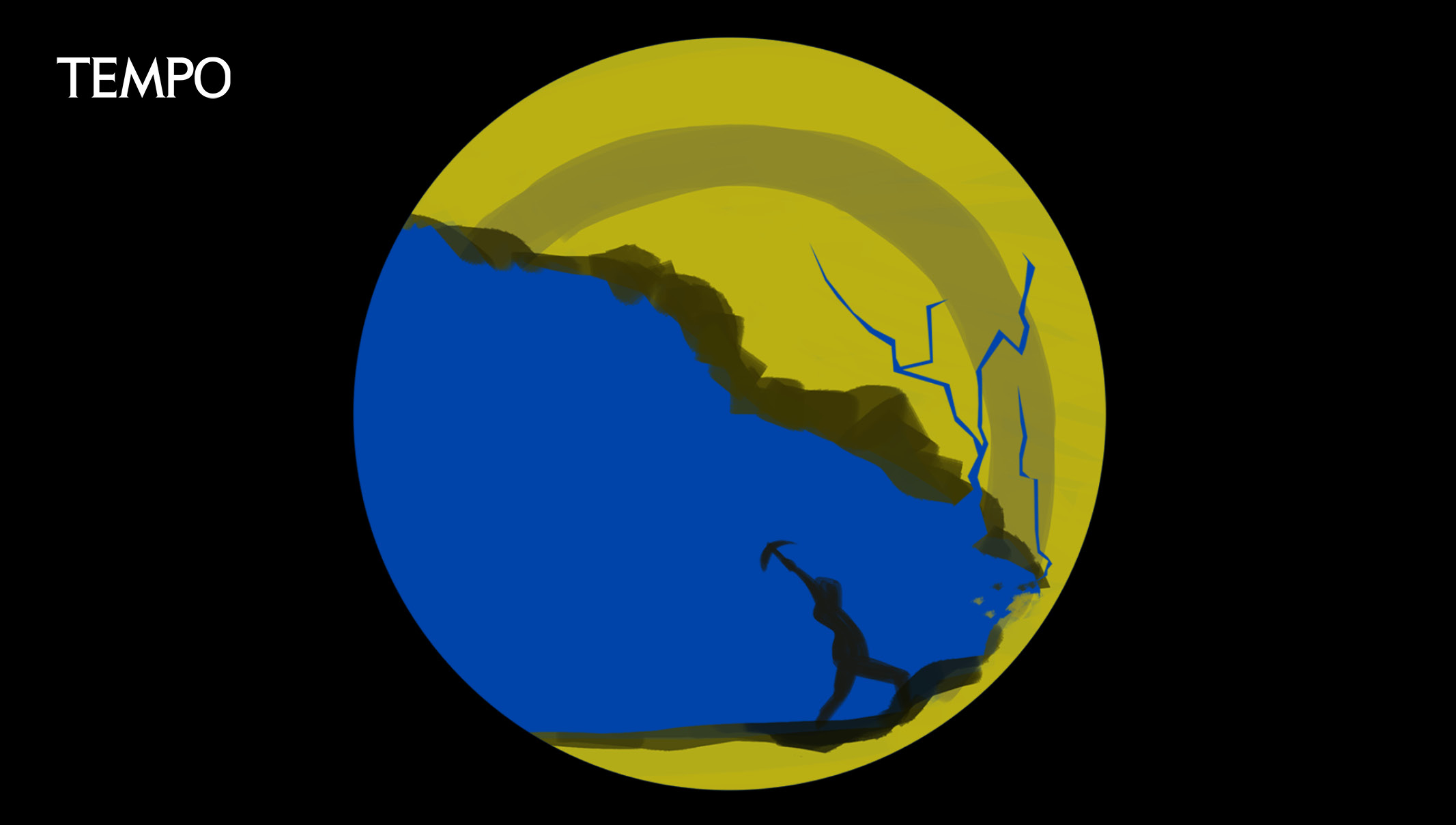Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

DOSEN dan peneliti dari Universitas Islam Indonesia (UII), Listya Endang Artiani membeberkan sederet efek domino atau berantai buntut Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG anjlok sejak pertengahan Maret 2025. Menurut Listya, anjloknya IHSG bukan sekadar volatilitas biasa, melainkan sinyal kuat pasar hilang kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

“Dalam dunia investasi, angka bukan sekadar angka tetapi cerminan ekspektasi dan psikologi pasar. Jatuhnya IHSG karena adanya kehilangan kepercayaan pasar terhadap fondasi ekonomi Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 24 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa menerapkan trading halt selama 30 menit pada Selasa, 18 Maret 2025. Hal ini buntut IHSG anjlok 5,02 persen ke level 5.146. Kendati perdagangan saham periode 17-21 Maret 2025 ditutup pada zona positif, namun IHSG masih menunjukkan tren terpuruk di angka 3,95 persen ke level 6.258,179.
Listya mengatakan, di balik anjloknya IHSG, tersimpan akar permasalahan yang lebih kompleks. Menurut Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII ini, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan sinyal yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Bisa berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, defisit fiskal yang melebar, atau kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-pasar.
Menurut Listya, terdapat beberapa efek domino dari pasar saham ke ekonomi riil, pada garis besarnya sebagai berikut:
Investor Retail Tertekan: dari Sentimen Negatif ke Aksi Jual Panik
Investor retail sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap gejolak pasar saham. Dengan jumlah yang mencapai 6 juta orang, mereka tidak hanya menghadapi risiko kerugian finansial tetapi juga tekanan psikologis yang besar akibat sentimen negatif dan ketidakpastian pasar.
Dalam Prospect Theory oleh Kahneman dan Tversky pada 1979, dijelaskan bahwa investor cenderung lebih sensitif terhadap kerugian dibandingkan keuntungan dengan nominal yang sama. Artinya, ketika IHSG anjlok, investor retail cenderung bereaksi berlebihan dan melakukan aksi jual panik, meskipun kondisi fundamental belum tentu seburuk yang mereka bayangkan.
“Kepanikan ini menciptakan efek spiral, di mana aksi jual yang semakin masif semakin menekan harga saham,” kata Listya.
Dalam teori Herding Behavior oleh Banerjee pada 1992, efek spiral ini terjadi di mana investor lain ikut menjual tanpa mempertimbangkan analisis fundamental. Individu dalam pasar cenderung mengikuti tindakan mayoritas tanpa melakukan analisis mendalam. Penurunan harga yang awalnya didorong oleh beberapa investor besar bisa berujung pada aksi jual besar-besaran oleh investor retail.
“Jika sentimen negatif terus menyebar, bursa bisa mengalami koreksi lebih dalam, menciptakan kondisi pasar yang semakin tidak stabil. Jika tidak dikendalikan, pasar bisa mengalami kapitalisasi yang menguap dalam hitungan hari, memperburuk kondisi ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Listya, meningkatnya volatilitas dan penurunan nilai aset masyarakat bisa memperburuk ketimpangan ekonomi, terutama bagi mereka yang bergantung pada investasi sebagai sumber pendapatan pasif. Koreksi pasar yang tajam dapat menciptakan peluang bagi investor dengan modal kuat untuk masuk ke saham-saham undervalued, berpotensi memperbaiki alokasi sumber daya di pasar keuangan dalam jangka panjang.
Risiko Sistemik di Sektor Keuangan: Dari Pasar Modal ke Perbankan
Menurut Listya, dampak dari kejatuhan IHSG tidak berhenti di pasar saham. Anjloknya indeks bisa memicu penarikan dana besar-besaran dari reksa dana saham, terutama oleh investor yang takut akan kerugian lebih dalam. Dalam teori Financial Accelerator oleh Bernanke, Gertler dan Gilchrist pada 1999, dijelaskan bahwa guncangan di satu sektor keuangan bisa menyebar ke sektor lain melalui mekanisme kredit dan kepercayaan pasar.
Apabila investor menarik dananya dari reksa dana saham, manajer investasi terpaksa menjual aset dalam jumlah besar, yang semakin menekan pasar. Jika kondisi ini tidak dikelola dengan baik, bisa terjadi capital flight, di mana investor asing menarik modal mereka, mengakibatkan depresiasi rupiah yang memperburuk stabilitas makroekonomi.
Peneliti UII ini berpendapat, peningkatan risiko sistemik dapat memperburuk ketahanan perbankan, yang pada akhirnya berdampak pada naiknya suku bunga kredit dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Bank dan institusi keuangan yang memiliki tata kelola yang baik dapat mengidentifikasi risiko lebih cepat dan mengambil langkah mitigasi yang membuat sistem keuangan lebih resilien dimasa depan.
“Krisis ini juga bisa menjalar ke sektor perbankan. Jika bank memiliki eksposur tinggi terhadap obligasi korporasi atau portofolio saham yang nilainya anjlok, maka stabilitas keuangan mereka bisa terganggu,” ungkapnya.
Dalam kondisi ekstrem, bank bisa mengalami kesulitan likuiditas, terutama jika nasabah mulai menarik simpanan mereka karena khawatir terhadap stabilitas sistem keuangan. Jika kondisi ini berlanjut, kita bisa menghadapi risiko kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) yang meningkat, sehingga membatasi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ke dunia usaha.
Dampak pada Perekonomian Riil: Investasi Melambat, PHK Mengancam
Menurut Listya, dalam ekonomi makro, pasar saham sering dianggap sebagai leading indicator bagi perekonomian riil. Ketika IHSG anjlok, kepercayaan dunia usaha terhadap prospek ekonomi bisa menurun drastis. Mengutip Investment Under Uncertainty Theory oleh Dixit dan Pindyck pada 1994, dalam kondisi ketidakpastian tinggi, pelaku usaha cenderung menunda investasi karena sulit memperkirakan keuntungan di masa depan.
Jika perusahaan-perusahaan besar mengalami tekanan di pasar modal, mereka akan lebih berhati-hati dalam ekspansi bisnis, yang berarti pengurangan belanja modal dan penundaan proyek investasi. Efeknya bisa meluas ke sektor tenaga kerja. Jika perusahaan publik mengalami krisis likuiditas akibat anjloknya harga saham mereka, maka langkah yang sering diambil adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk mengurangi beban biaya operasional.
Dalam teori Keynesian tentang Permintaan Agregat, dijelaskan bahwa ketika konsumsi dan investasi menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan terhambat, dan tingkat pengangguran cenderung meningkat. Jika PHK terjadi secara masif, maka daya beli masyarakat akan melemah, yang pada gilirannya menekan konsumsi domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi.
“Jika perusahaan kesulitan mendapatkan pembiayaan, maka PHK menjadi pilihan utama untuk menjaga profitabilitas. Efek ini bisa meluas ke sektor lain yang berakibat pada permintaan domestik turun, daya beli masyarakat melemah, dan konsumsi berkurang, yang pada akhirnya berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
Lebih lanjut, menurut Listya, meningkatnya angka pengangguran bisa meningkatkan ketimpangan sosial dan memperberat beban pemerintah dalam program bantuan sosial. Jika krisis ini memaksa perusahaan untuk melakukan efisiensi dan inovasi dalam model bisnis, maka dalam jangka panjang, mereka bisa menjadi lebih kompetitif di pasar global.
Dampak Politik dan Kebijakan Ekonomi: Pemerintah di Persimpangan Jalan
Listya mengatakan, gejolak di pasar saham bisa menjadi ujian besar bagi pemerintah. Tekanan dari masyarakat, dunia usaha, dan pelaku pasar keuangan bisa memaksa pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret agar kepercayaan terhadap ekonomi tidak semakin merosot.
Dalam Political Business Cycle Theory oleh Nordhaus pada 1975, dijelaskan bahwa kebijakan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh tekanan politik, terutama ketika kondisi pasar tidak stabil. Artinya, keputusan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, terutama dalam situasi krisis.
“Pemerintah dihadapkan pada dilema besar, apakah merespons dengan intervensi agresif atau membiarkan mekanisme pasar bekerja?” kata Listya.
Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.