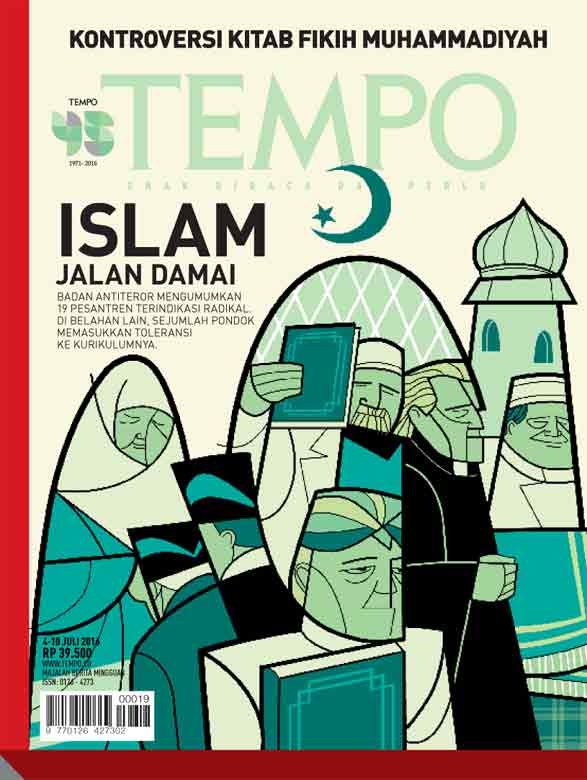Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Terry Dean mungkin tak menyangka pilihannya bakal mengubah wajah Kerajaan Inggris. Dalam referendum pada Kamis pekan lalu, pria 57 tahun asal kawasan Blackbird Leys, Oxford, Inggris, ini mendukung Brexit—akronim dari British exit. Bagi Dean, alasannya sederhana saja. Ia mengaku tidak suka negaranya didikte Uni Eropa.
"Aturan kami di sini ditulis oleh orang Eropa," kata Dean kepada wartawan Tempo di Oxford, Sadika Hamid. "Saya tidak rasis, kami tidak dapat mencegah imigrasi, saya menyayangi tetangga saya orang Asia, dan saya tidak ingin mereka pergi. Tapi asuransi kesehatan kami terbatas, tidak mencukupi jika harus dibagi dengan jumlah orang yang datang."
Di Oxford, kota sejauh 96 kilometer di barat London, Dean menjadi minoritas. Seperti London, Oxford merupakan basis utama pendukung Uni Eropa. Di Oxford, sekitar 49 ribu pemilih, setara dengan 70 persen, mencoblos Remain. Artinya, mereka ingin Kerajaan Inggris tetap di Uni Eropa. Sedangkan pemilih Leave hanya berkisar 20 ribu orang, termasuk Dean.
Namun, di seantero Kerajaan Inggris, Dean melengkapi bagian yang jauh lebih besar, yaitu kubu pro-Brexit. Kantor berita BBC melaporkan kelompok Leave, yang anti-Uni Eropa, sukses memenangi referendum bersejarah sejak 1975. Sekitar 17,4 juta warga, atau 52 persen, memilih angkat kaki dari keanggotaan blok 28 negara Benua Biru itu.
Setelah 43 tahun, negeri Ratu Elizabeth II itu pun resmi bercerai dengan Uni Eropa. "Saya sedikit terhuyung saat melihat reaksi di Facebook. Hampir semua teman saya memilih Remain," kata Sally, guru sekolah dasar di London, seperti dikutip The Guardian. Melawan arus, perempuan 34 tahun ini diam-diam mendukung Brexit.
Pada hari jajak pendapat, aktivitas kampanye di Oxford terbilang masih cukup ramai. Di Inggris, tidak seperti di Indonesia, kampanye pada hari pemungutan suara diperbolehkan. Di Cornmarket Street, misalnya, sejumlah relawan kampanye terlihat sibuk membujuk para calon pemilih hingga menit terakhir menjelang referendum.
Di jalan perbelanjaan utama dan daerah pejalan kaki di Oxford itu, orang-orang datang dan berbincang dengan puluhan relawan. Sebagian besar dari relawan itu berafiliasi dengan tim kampanye resmi. Mereka yang pro-Uni Eropa mengenakan kemeja biru bertulisan "Vote Remain" atau "I'm in". Sedangkan pihak lawan berpakaian merah dengan tulisan "Vote Leave" yang tebal.
Terselip di antara kerumunan itu adalah Holly Hathrell. Mahasiswi pascasarjana dari Universitas Oxford ini beraksi sendiri, tidak tergabung dengan tim kampanye resmi. Sambil berdiri, ia memegang poster bertulisan: "Tanya saya mengapa selebaran 'Vote Leave' ini berbohong". Poster itu ditulis dengan spidol hitam di atas kertas putih.
Kepada Tempo, Hathrell, 23 tahun, mengatakan kampanye pro-Brexit penuh ketidakjujuran. "Nenek saya menerima selebaran yang menyatakan Inggris mengirimkan 350 juta pound (sekitar Rp 6,3 triliun) ke Uni Eropa setiap minggu. Itu bohong," katanya. Sebaliknya, menurut Hathrell, Inggris justru mendapat kucuran dana 100 juta pound (sekitar Rp 1,8 triliun), itu belum termasuk potongan harga dari pasar tunggal Eropa.
Amanda McGorry, 58 tahun, memilih mengitari beberapa tempat pemungutan suara. Di Jericho, lingkungan bohemian dekat kampus Universitas Oxford, perempuan relawan ini membagikan stiker "Vote Remain" yang dapat ditempel di baju. Stiker besar bertulisan "I'm in" dan "Vote Remain" juga terlihat diplester di jendela-jendela bangunan. "Kami ingin mendorong orang untuk memilih," ujar McGorry.
Pemungutan suara di Oxford berjalan lancar. Tidak ada antrean panjang di luar bilik suara, yang bertempat di gereja, pusat komunitas, dan fasilitas publik lain yang mudah diakses. Jalan-jalan tidak lebih padat daripada biasanya. Daerah permukiman juga tenang. Hanya sesekali tampak pemilih memasuki bilik suara, yang dibuka dari pukul 07.00 hingga 22.00. Bila tidak dipasangi tanda besar bertulisan "Polling Station" di luar bangunan, bisa jadi orang luar tidak ngeh sedang terjadi peristiwa bersejarah.
Namun momen yang tenang itu mendadak heboh keesokan harinya. Kemenangan telak pendukung Uni Eropa di Oxford rupanya tidak cukup membendung hasrat kubu lawan. Menurut The New York Times, 53 persen penduduk Inggris memilih Brexit. Uni Eropa hanya beroleh dukungan kuat di Skotlandia, Irlandia Utara, London, dan Oxford.
Dalam sehari, kemenangan Brexit bergulir bak bola salju. Dampaknya membesar dan menggilas berbagai pihak. Di luar Downing Street 10 di London, Perdana Menteri David Cameron langsung mengumumkan pengunduran diri. Pemimpin Partai Konservatif ini mengatakan perdana menteri baru harus terpilih pada Oktober mendatang.
"Saya benar-benar jelas tentang keyakinan saya bahwa Inggris lebih kuat, lebih aman, dan lebih baik dalam Uni Eropa," kata Cameron, 49 tahun, yang berpidato didampingi istrinya, Samantha. "Tapi warga Inggris membuat keputusan berbeda untuk mengambil jalan berbeda. Karena itu, saya pikir negara ini membutuhkan kepemimpinan segar."
Skotlandia dan Irlandia Utara, yang masih merasa cocok dengan Uni Eropa, mewacanakan hengkang dari Kerajaan Inggris. "Konteks dan keadaan telah berubah dramatis. Kerajaan Inggris yang dipilih oleh Skotlandia sudah tidak ada lagi," kata Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon. Lewat referendum pada September 2014, rakyat Skotlandia memilih tetap bergabung dengan Kerajaan Inggris.
Akibat Brexit, nilai pound jatuh ke titik terendah dalam 30 tahun. Brexit dikhawatirkan memicu krisis keuangan global. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis François Hollande kompak menyesalkan keputusan Inggris. Beberapa politikus partai sayap kanan anti-imigran, seperti Geert Wilders dari Belanda dan Marine Le Pen di Prancis, menyerukan referendum serupa Brexit bagi negara mereka.
Bahkan sebagian penduduk Inggris panik seusai referendum. "Saya memilih Leave. Tapi esok hari setelah pemilihan, saya terkejut," kata seorang perempuan kepada saluran berita ITV News. "Bila saya memiliki kesempatan lagi, saya akan memilih Remain." Google mencatat kebingungan ini. Delapan jam setelah pemungutan suara ditutup, situs pencari terbesar itu melaporkan lonjakan tiga kali lipat atas pencarian satu item pertanyaan, yaitu, "Apa yang terjadi jika kita meninggalkan Uni Eropa?"
Kaget terhadap hasil referendum, para pemilih lantas membanjiri sebuah petisi online bikinan pengkampanye pro-Brexit, William Oliver Healey. Petisi yang digagas sejak Mei lalu itu mendesak referendum ulang bila salah satu kubu meraup kurang dari 60 persen suara. Hingga Ahad lalu, lebih dari 3,5 juta orang meneken petisi itu, meski sempat diwarnai insiden pemalsuan puluhan ribu tanda tangan oleh peretas.
Di London, perhatian tertuju pada David Cameron. Ia adalah pemimpin Inggris yang menjanjikan referendum tahun lalu. Sejak itu Cameron berdiri paling depan, menakhodai gerbong pro-Uni Eropa, dan berkampanye menentang Brexit. Namun, ironisnya, di tangan Cameron pula kartu anggota Uni Eropa lepas dari genggaman.
Demi mempopulerkan gerakan pro-Uni Eropa, Cameron harus berjibaku untuk meraup dukungan setengah hati dari kubu oposisi, Partai Buruh. Kurang dari sebulan sebelum referendum, misalnya, ia mendapat laporan tak mengenakkan dari tim khusus. Tim yang dirakit oleh Cameron untuk menjaga Inggris tetap di Uni Eropa itu khawatir terhadap polah bimbang para pemilih Partai Buruh. "Mereka juga frustrasi dengan dukungan pemimpin oposisi yang suam-suam kuku," begitu situs berita Politico melaporkan.
Di bawah besutan Jeremy Corbyn, Partai Buruh mendukung Inggris tetap di Uni Eropa. Namun sokongan itu hanya manis di bibir. Corbyn, 67 tahun, dikabarkan tidak pernah mau diajak berkampanye bersama Cameron. "Corbyn tidak ingin berurusan dengan pemimpin Tory (sebutan untuk Partai Konservatif), tidak peduli apa pun taruhannya," kata seorang pejabat senior yang dekat dengan tim kampanye Cameron.
Gordon Brown, mantan perdana menteri dari Partai Buruh, yang dikalahkan Cameron dalam pemilihan umum 2010, pernah diminta membujuk Corbyn. Namun Corbyn bergeming. Sikap Corbyn itu sempat menyulut amarah beberapa tokoh senior di tim kampanye Remain, termasuk dua orang kepercayaan Cameron, Craig Oliver dan Jim Messina, yang notabene guru kampanye Presiden Amerika Serikat Barack Obama.
Dari Corbyn, dukungan setengah hati Partai Buruh menjalar ke tingkat bawah. Partai ini, misalnya, tidak bersedia berbagi data pendaftaran pemilih yang cenderung pro-Uni Eropa. Menurut Politico, mereka takut Partai Konservatif akan mencuri informasi itu untuk pemilihan umum berikutnya. "Data kami memang bukan untuk orang lain," kata seorang pejabat senior Partai Buruh saat ditanya tentang tudingan itu.
Kondisi itu diperparah oleh kesalahan strategi tim Cameron. Berkaca dari kemenangan telak pada pemilu 2015, mereka rupanya hanya berfokus pada isu keamanan ekonomi. "Tapi strategi itu kali ini gagal total," demikian menurut Politico. Cameron tidak mengantisipasi kemarahan publik Inggris atas derasnya arus masuk pekerja migran dari negara-negara Uni Eropa lain.
"Saya memilih Brexit untuk kebijakan imigrasi yang adil," kata Andrew Riches, 54 tahun, desainer grafis dari Midlands, Inggris. Menurut Riches, ia dan istrinya, warga Thailand, mendapat perlakuan diskriminatif. Agar istrinya tidak dideportasi, Riches harus berpenghasilan sedikitnya 20 ribu pound (sekitar Rp 359 juta) per tahun. "Butuh 1.500 pound (sekitar Rp 26,9 juta) untuk memperpanjang visa istri saya tiap dua setengah tahun."
Bagi Cameron, tantangan terberat justru bersumber dari Partai Konservatif. Di kalangan internal partai penguasa itu ada "The Brexit Boys", Michael Gove dan Boris Johnson. Ibarat duri dalam daging, dua pentolan gerakan Brexit itu memimpin "pembelotan" di kabinet dan parlemen. Terlebih kampanye Gove dan Johnson mendapat dukungan luas dari media, yang sebagian besar pro-Brexit. "Cameron akhirnya terisolasi," begitu menurut Politico.
Di luar urusan partai, Cameron rupanya juga gagal merangkul seluruh lapisan rakyat Kerajaan Inggris. Statistik menunjukkan mayoritas pemilih Remain adalah mereka yang berpendidikan dan makmur. Sedangkan warga miskin di perdesaan, yang merasa kehidupan mereka terancam oleh masuknya imigran, serta khawatir bahwa pendapatan mereka tergerus, cenderung mendukung Brexit.
Brexit juga populer di kalangan pemilih tua. Sigi YouGov menunjukkan 59 persen dari penduduk di atas 65 tahun memilih Leave. Sedangkan 75 persen dari pemilih berusia 18-24 tahun menolak Brexit. "Generasi lebih tua menentukan apa yang terjadi, generasi muda yang harus menjalaninya," cuit pemilik akun Twitter @HenryGallagherx. Komentar senada dilontarkan @tay_azalea, "Generasi yang lebih tua memilih masa depan yang tidak diinginkan generasi muda."
Di Oxford, pilihan Terry Dean terbukti lebih unggul. Ia mewakili kalangan pemilih dari lingkungan kelas pekerja dari Blackbird Leys, sekitar 30 menit dari pusat kota. Banyak dari mereka lekat dengan atribut kampanye Leave. Ini berbeda dengan penduduk dari wilayah pusat kota yang lebih makmur, serta dekat dengan kawasan kampus Universitas Oxford, yang lebih bangga mengenakan stiker Remain.
Pukul 07.00, Jumat pekan lalu, Michael Gove masih dalam keadaan terperenyak ketika telepon selulernya berdering. Nama David Cameron muncul di layar ponsel Gove. Cameron menelepon untuk mengucapkan selamat kepada temannya itu, yang sukses memimpin kampanye Leave dan memenangi referendum.
Kedua pria itu, yang akrab selama lebih dari satu dasawarsa, berbicara singkat. Setahun terakhir, urusan referendum telah menguji interaksi politik antara Cameron dan Gove. Persahabatan mereka juga dipertaruhkan. "Dengan penuh hormat, Michael mengucapkan, 'Terima kasih, Perdana Menteri'," kata seseorang yang dekat dengan Gove, mengisahkan secuil dari isi percakapan itu, kepada The Telegraph.
Kepada Gove, 48 tahun, yang menjabat Menteri Kehakiman, Cameron mengatakan akan memberi pernyataan kepada publik di Downing Street pada jam berikutnya. Gove ketika itu tidak mengetahui pasti, tapi ia agaknya telah menduga Cameron akan mengumumkan keputusannya mundur. MAHARDIKA SATRIA HADI, SADIKA HAMID (OXFORD), (THE GUARDIAN, POLITICO, CNN, BBC, THE TELEGRAPH, WASHINGTON POST, THE NEW YORK TIMES)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo