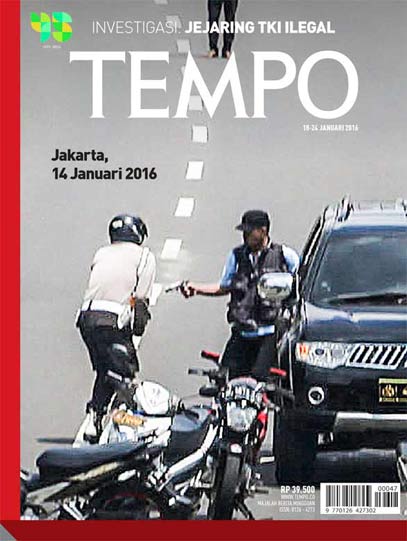Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PEREMPUAN berbaju terusan kumal itu melangkah pelan menyusuri Jalan Arif Rahman Hakim, Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa sore awal Desember tahun lalu. Usianya sekitar 40 tahun, rambut berantakan, wajahnya menghitam terbakar matahari. Kadang dia menatap lama spanduk calon bupati-wakil bupati yang terpancang di trotoar.
"Dia gila," kata Roy Lilimanak, sopir yang biasamangkaldi Tunon Taka, pelabuhan utama kota itu. Hampir semua orang di sana tahu cerita perempuan tersebut. Dulu dia TKI di Tawau, Sabah, Malaysia. Tiga tahun lalu, dia terpaksa pulang alias dideportasi, tanpa identitas secuil pun.
Warga Nunukan memanggilnya "Speaking" karena ia pintar berbahasa Inggris. SaatTempo menyapanya, dia menjawab "no comment", tertawa, lalu kembali melangkah cepat.
Kota Nunukan, yang merupakan ibu kota Kabupaten Nunukan, sudah lama menjadi tempat pemulangan bekas pekerja Indonesia dari Sabah. Setiap bulan sekitar 600 TKI dideportasi ke daerah bermoto Gerbang Emas ini. Tanpa identitas, kantong kosong, dan sering dalam keadaan sakit, kebanyakan TKI itu tertahan dan hidup susah di Nunukan. Beberapa dari mereka mengalami depresi atau hilang ingatan.
"Sebagian besar orang gila di Nunukan adalah TKI yang dideportasi," kata dokter Dulman, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan.
Karena tidak ada rumah sakit jiwa di seantero kabupaten, mereka akhirnya berkeliaran di kota. Pemerintah Kabupaten Nunukan baru akan membangun fasilitas perawatan kejiwaan tahun depan.
Selain mengalami stres, menurut Dulman, banyak TKI yang menderita hepatitis B dan gangguan saraf. Malah ada yang pulang dalam keadaan lumpuh. Pada November tahun lalu, Tempo menjumpai Muhammad, 60 tahun, asal Makassar, yang tengah terbaring lemah di Rumah Sakit Daerah Nunukan. Dia tak bisa berjalan. Imigrasi Malaysia mendeportasi buruh pengupas bakau di Sandakan, Sabah, itu empat hari sebelumnya.
"Asam urat saya kambuh di sana. Berkali-kali saya jatuh di kebun," kata Muhammad. Perusahaan tempat dia bekerja tak memberi jaminan ataupun layanan kesehatan. Lantaran tak tahan sakit-sakitan tanpa diobati, dia meminta Konsulat Republik Indonesia di Tawau memulangkannya.
Hampir semua TKI yang sakit di Nunukan tak mampu membayar biaya berobat. "Semua ditanggung pemerintah kabupaten," kata Dulman.
DEPORTASI bukan hal paling buruk yang dialami TKI ilegal. Jeki, 32 tahun, pekerja migran asal Kecamatan Ambelawi, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang ditemui Tempo di Nunukan, tak pernah bisa melupakan cambukan di pantatnya pada September tahun lalu. "Sakitnya luar biasa," ujarnya. "Selama sepuluh hari kaki saya sering terasa lumpuh."
Polisi Diraja Malaysia menangkap buruh penombak kelapa sawit itu di tempat kerjanya di Kota Kinabalu pada Juni tahun lalu lantaran tak memiliki paspor dan izin bekerja. Sebelumnya, tiga tahun berturut-turut dia selalu berhasil menghindari razia imigran ilegal. Untuk pelanggaran tersebut, dia dihukum penjara tujuh bulan. Namun, menurut hukum Malaysia, Jeki tak perlu dikurung selama itu. Asalkan sudah menjalani setengah masa hukuman, dia boleh bebas. Sisa hukuman diganti dengan tiga kali cambukan di tubuhnya.
"Saya kapok," ujarnya. Jeki pulang membawa pakaian seadanya. Hasil bekerja dengan gaji setiap bulan 800 ringgit atau sekitar Rp 2,7 juta—upah minimum buruh migran di Malaysia—tak bersisa.
Pengalaman berbeda dialami Ramzi Panama, 21 tahun, kawan seprovinsi Jeki. Enam bulan bekerja di sebuah restoran di Kota Kinabalu, lelaki asal Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, itu tak menerima bayaran seringgit pun. Padahal kadang dia bekerja hingga 12 jam sehari. Ketika dia tagih, pemilik restoran mengancam akan melaporkannya ke polisi. Maklum, meski punya paspor, Ramzi tidak memiliki izin kerja. "Akhirnya saya ke Konsulat Kota Kinabalu dan minta dipulangkan," ujarnya.
Mereka yang bekerja secara legal di kawasan timur Malaysia belum tentu bernasib lebih baik. Melani—bukan nama sebenarnya—contohnya. Perempuan 32 tahun asal Surabaya ini mengantongi izin bekerja sebagai tukang pijat di sebuah hotel di kawasan Bandar, Tawau. Jam kerjanya mulai pukul 10 pagi hingga 11 malam.
Melani mengaku diajak kawannya bekerja sebagai tukang pijat di Malaysia. Nyatanya, tak hanya bekerja sebagai pemijat, dia harus bersedia memberi layanan ekstra ke pelanggannya. Untuk setiap jam memijat, ibu satu anak tersebut mendapat upah 10 ringgit atau sekitar Rp 35 ribu dari pemilik hotel.
Melani memasang tarif 150 ringgit untuk layanan ekstra. Itu pun sebagian besar harus diberikan ke hotel. "Mereka mencatat jam tugas saya saat bersama pelanggan. Dalam satu jam, saya harus menyetor 70 ringgit," kata Melani kepada Tempo di sebuah warung makan di kawasan Bandar, dua bulan lalu.
Hidup Melani jauh dari mewah. Meski begitu, setiap bulan dia selalu mengirim Rp 2 juta untuk ibunya di kampung. Melani merasa tak punya pilihan dan tidak juga menyalahkan muncikarinya. Malah, menurut dia, bosnya tergolong baik karena selalu mengizinkan dia pulang dan libur setiap kali haid.
TUJUH salib berderet menandai petak semen di permakaman khusus kaum Kristiani, samping Gereja Bethel Tabernakel, Nunukan. Tertulis tak beraturan di dalam salib-salib itu tujuh nama: Petrus Mesa, Maria Pasa, Maria Anton, Anton Pera, Yohanes Kendek, Lukas Buntu, dan Yakobus Lalang. "Saya ingat betul, dulu saya memakamkan mereka dalam satu lubang," kata Vincentius Ruing, 51 tahun, warga Nunukan Utara.
Pemakaman tersebut terjadi pada 2002. Saat itu tenaga kerja ilegal yang dipulangkan dari Malaysia membanjiri Nunukan. Jumlah mereka sekitar 350 ribu orang, sebagian sakit berat dan hampir meninggal. "Banyak yang telantar di sini karena tak punya keluarga," ujar Vincentius.
Wahyu Susilo, peneliti Migran Care, lembaga swadaya pemerhati buruh migran, mencatat deportasi massal pada 2002-2003 sebagai yang terkelam. Setidaknya 105 TKI meninggal setelah dideportasi. "Nunukan waktu itu belum memiliki fasilitas kesehatan memadai, hanya ada puskesmas setingkat kecamatan," ujarnya. Banyak TKI sakit karena kekurangan makanan dan minum air sungai di tengah kota.
Anastasia—bukan nama sebenarnya—ikut merawat para TKI yang sakit saat itu. Di rumah kerabatnya, ada perempuan yang dideportasi dan membawa anaknya yang masih bayi. Perempuan tersebut lalu "menjual" anaknya ke Anastasia demi mendapatkan duit untuk kembali ke kampung halamannya. "Kampungnya tidak jelas di mana. Saya beri dia Rp 1 juta dan saya rawat anaknya hingga sekarang."
Bagi beberapa TKI, deportasi mendatangkan beban yang tak tertahankan. Blasius Kiabeni, 46 tahun, warga Nunukan Barat, mengatakan, pada April tahun lalu, dia menguburkan mayat laki-laki yang gantung diri di pohon. Padahal, beberapa hari sebelumnya, Blasius sempat mengajak makan TKI yang baru dideportasi itu. Tanpa identitas, laki-laki asal Nusa Tenggara Timur tersebut dimakamkan dengan nama baru: "Yosep".
Hingga kini makam TKI ilegal terus bertambah. Menurut Blasius, warga Nunukan sering mengubur jenazah TKI tanpa identitas. Biasanya penduduk melihat rambut TKI yang meninggal. Jika keriting, berarti berasal dari NTT, yang mayoritas Kristiani, lalu dikebumikan di permakaman Kristiani. "Kalau tak keriting, jenazah kami kubur secara Islam," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo