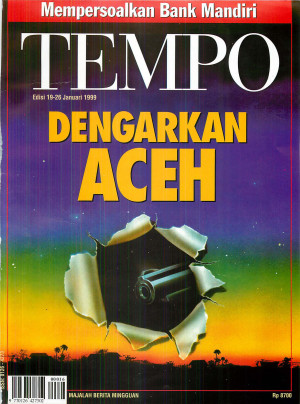Inilah wajah kereta api jurusan Tanahabang-Rangkasbitung, suatu Senin sore, pekan silam. Gerbong kereta api kelas ekonomi berukuran sekitar 10 x 3 meter persegi penuh sesak oleh manusia. Hawa panas membuat peluh berleleran membasahi wajah dan tubuh.
Udara pengap. Jendela berukuran kecil-kecil tidak cukup memasukkan hawa segar, tapi para penumpang tampaknya tenang-tenang saja. Sering-sering terdengar jeritan dari si empunya kaki yang terinjak, gesekan pantat, cubitan tangan jahil, atau orang yang tersandung tumpukan karung dan kardus yang menutup jalan di pintu-pintu masuk kereta ?selebar 1,5 meter. Juga, bayi dan anak-anak yang menjerit dan menangis dalam gendongan ibunya.
Jalur kereta api Tanahabang-Rangkasbitung melayani penumpang dua kali dalam sehari. Ada dua pilihan untuk mencapai kota kecamatan di Kabupaten Serang ini. Pertama, naik kereta api patas (cepat dan terbatas) jurusan Tanahabang-Merak dengan harga karcis Rp 1.500. Kedua, kereta api ekonomi jurusan Tanahabang-Rangkasbitung dengan harga karcis Rp 900.
Dari segi fasilitas, perbedaan itu tidak terlalu membawa arti. Paling-paling, ada palang-palang untuk berpegangan, sehinggga orang tidak perlu mengandalkan kelihaian gerak menyeimbangkan tubuh karena tiadanya palang tempat berpegangan seperti halnya di kereta ekonomi. Perbedaan harga Rp 600 itu lebih membawa implikasi pada pilihan penumpang. Orang jauh lebih rela berjejal-jejal di kereta api ekonomi karena pengorbanan itu setara artinya dengan menghemat Rp 600.
Wartawan TEMPO bergabung bersama ratusan penumpang yang merebut sekadar sebuah tempat untuk berdiri dalam kereta api ekonomi jurusan Tanahabang-Rangkasbitung, pada Senin sore itu. Kedatangan kereta itu benar-benar disambut "hangat" karena sudah terlambat satu jam lebih?dari jam berangkat yang seharusnya, pukul 14.47. Pukul 15.50, kereta enam gerbong tersebut meluncur pelan ke Stasiun Tanahabang. Para calon penumpang langsung memadati jalur enam. Selebihnya adalah adu kuat merebut tempat. Apalagi, enam gerbong kereta ini hanya bisa dimasuki dari empat gerbong.
Ketika gerbong itu sudah padat, napas mulai sesak. Udara penuh dengan zat asam arang dari sekitar 300 manusia yang berhimpun dalam kereta yang berbau pesing itu. Sulit sekali menggerakkan tubuh. Kendati tidak ada tempat berpegang, praktis orang tak perlu khawatir karena batang tubuh manusia sudah tersusun tegak dan padat, sehingga kalau pun ada guncangan mendadak, orang praktis jatuh tersandar pada tubuh orang lain.
Toh, ada saja yang merasa longgar dalam ruang sepadat itu: "Biasa saja. Ini enggak padat. Kan masih bisa jalan," ujar seorang tukang susu sembari mengangkat ember susunya. Alhasil, beberapa orang masih berusaha keras mendorong sekuat tenaga dari luar agar bisa menyusupkan tubuhnya ke dalam. Namun, dorongan itu dibalas dari dalam (kereta) dengan cara yang sama dahsyatnya. "Jangan dorong-dorongan dong," beberapa ibu tidak tahan untuk menjerit melihat adegan yang mirip syuting film di pintu-pintu gerbong kereta.
Biasanya, para penumpang dari Stasiun Jakarta Kota sudah memenuhi tempat-tempat duduk yang ada. Sehingga para penumpang di stasiun-stasiun setelah itu sudah bersyukur bila dapat berdiri tegak. Hardikan, tangisan kanak-kanak, jeritan tak sabar, maki-makian, dan tawa berbaur menjadi satu, menjadi semacam kor rutin di tengah gumam percakapan yang makin lama makin keras karena deru suara kereta yang beradu dengan rel.
Aba-aba untuk berhenti diteriakan jauh-jauh sebelumnya, diiringi dengan hardikan atau permisi yang sopan membangunkan penumpang yang bersimpuh di lantai yang kotor, panas, dan penuh lumpur musim hujan. Perkara turun pun bukan hal gampang, karena para penumpang yang membawa barang meletakkan karung-karung di depan pintu dengan perhitungan mereka bisa lebih ke luar?sehingga menghalangi benar penumpang harus bersicepat melompat turun di setiap perhentian.
Di Stasiun Sudimara, sekitar 25 persen penumpang turun. Tiba-tiba saja, tubuh menjadi lebih mudah bergerak dan napas terasa lebih enak. Seorang laki-laki berusia 50 tahun kontan menggelosor ke lantai, membuka sepatu ketsnya, lalu tangannya memijit jari-jari kakinya yang kesemutan. Berdiri satu jam lebih antara Tanahabang-Sudimara memang mudah saja membuat orang kejang dan kesemutan. Longgarnya gerbong kereta adalah kesempatan baik yang langsung disambar para pedagang makanan dan minuman. Alhasil, ruangan yang sudah agak longgar itu kembali padat oleh lalu-lalang penjaja kudapan serta buah-buahan.
Adegan-adegan yang absurd?bagi sebagian orang?adalah pemandangan biasa bagi yang lain. Seorang ibu, misalnya, kebingungan ketika anaknya yang berusia dua tahun menangis menahan pipis. Ia lalu menggamit suaminya, memberitahukan hal itu. Dan sang suami meneriakkan "aduh" sembari menepuk-nepuk jidatnya. Beberapa penumpang menyarankan agar anak itu buang air kecil di lantai kereta saja: "Ah, anak kecil ini, " beberapa penumpang berusaha memberi semangat. "Nanti bisa kena kepala orang yang duduk di bawah," ujar sang ibu masih berusaha sopan. Urusan buang air kecil itu akhirnya diputuskan "secara sosial". Anak kecil itu akhirnya diturunkan dari gendongan dan menyelesaikan hajatnya setelah diizinkan beberapa penumpang di sekitarnya.
Selepas Stasiun Parungpanjang, kondektur mulai memeriksa karcis penumpang. Petugas kereta api rupanya sudah begitu terbiasa mengandalkan "penciuman"nya. Ia tidak memeriksa semua penumpang. Hanya sebagian yang rupanya benar-benar dicurigai tidak membawa karcis, ditanya atau dicolek. Perjalanan menjadi lebih nyaman setelah Stasiun Tenjo.
Tiba-tiba suara embik kambing membuyarkan konsentrasi sekelompok penumpang yang tengah bercakap-cakap. Seorang lelaki menuntun seekor kambing dewasa, melewati kerumunan orang di emperan stasiun, lalu menghilang di sebelah peron. Tiba-tiba, astaga, lelaki dan kambing itu saling beradu cepat dengan ibu-ibu yang membawa bakul-bakul jualannya. Di pintu lain, seorang pria dengan susah-payah memasukkan sepeda gunungnya ke dalam gerbong yang licin. Peluit kereta berbunyi diiringi dengan suara embikan beberapa kambing yang mengiringi perjalanan berikutnya.
Uniknya, dalam perjalanan Tenjo-Tanahabang ada tiga pemberhentian kereta api yang bukan stasiun?masing-masing di Cilaku, Salimah, dan Basiran. Para pemakai kereta menyebutnya dengan "Pos 2.000." Artinya? "Dulu masinis mau menghentikan kereta di tempat ini dengan imbalan Rp 2.000. Tapi sekarang, "tarif" itu sudah tidak berlaku. Minimal, kita harus ngasih Rp 6.000," kata Nandar (32 tahun), seorang penumpang yang naik di Pos 2.000 Cilaku. Pengumpulan dana "pos darurat" ini dilakukan secara kolektif. Setiap orang memberi iuran Rp 300, pelajar cukup Rp 200. Setelah terkumpul, uang itu diserahkan ke masinis," tutur pria yang bekerja di sebuah bengkel di daerah Jombang, Tangerang ini.
Untuk turun?lagi-lagi, bukan di stasiun resmi?juga ada tarif tersendiri ?hanya lebih murah, Rp 3.000 sudah cukup membuat masinis mengerem kereta. Mekanisme naik-turun di pos dadakan itu bukan berarti mereka bebas dari kewajiban membeli karcis. "Kita memang harus membeli karcis. Uang Rp 6.000 itu hanya untuk menghentikan kereta saja. Tapi biasanya kami sudah berlangganan," tutur Nandar.
Urusan asmara juga bisa terjalin di kereta. Di ujung gerbong seorang wanita dikerubuti lima laki-laki. Mereka saling bercanda. Sesekali, tangan salah seorang lelaki mencolek sang nona. Yang dicolek tertawa gembira, memberi angin. Di sela-sela itu, Nurdin (28 tahun) membagi-bagikan kartu anggota Orsaka (Organisasi Sosial Anak Kereta Api), sebuah klub pengguna jasa kereta api. "Organisasi ini berdiri tiga bulan lalu. Tujuannya untuk saling membantu bila ada kesusahan. Setiap anggota ditarik iuran Rp 500-Rp 1000," tutur Nurdin yang sudah berhasil mengumpulkan 80 anggota.
Organisasi ini juga sudah mulai memikirkan kepentingan anggotanya dalam skala lebih makro. Misalnya, meminta Perumka untuk tidak mengubah jadwal dan menambah gerbong. "Selama ini, jadwal pemberangkatan selalu diubah dan gerbong tidak pernah ditambah, sehingga kereta selalu penuh sesak. Tapi itu pekerjaan bersama yang harus didukung seluruh pengguna jasa kereta api," ujarnya dengan suara yang makin lama makin bersemangat.
Perjalanan Tanahabang-Rangkasbitung menghabiskan waktu sepanjang dua jam 25 menit?bukan waktu yang sangat panjang, tapi lebih dari cukup untuk memotret beragam sketsa kehidupan manusia. Ada tragedi, komedi, juga tragikomedi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini