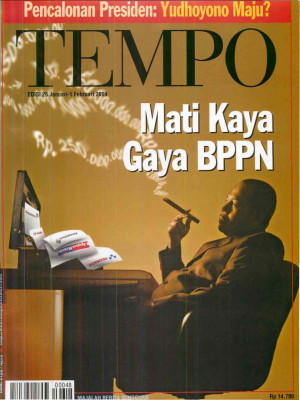Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Di Dadahup, sebuah desa nun di Kalimantan Tengah, ilalang dan padi adalah dua tanaman yang sama-sama mendebarkan petani. Di atas lahan gambut yang melingkupi desa tersebut, akar ilalang tumbuh dalam sukaria, subur, dan merdeka menjajah seantero kanal air. Sedangkan akar padi berjuang mati-matian untuk dapat menghadirkan bulir-bulirnya pada musim panen. Si padi tidak hanya bersaing dengan ilalang. Pada musim hujan, yang lazimnya berpuncak pada Maret, nafkah para petani itu kembali diuji.
Jutaan galon air bah akan merendam tanaman padi hingga ke pucuk-pucuknya. Inilah yang juga membikin resah Sukasmo, salah satu petani di desa itu. "Saya hafal kapan air bah ini datang," kata transmigran itu kepada TEMPO. Pertautan petani asal Trenggalek, Jawa Timur, itu dengan Dadahup berawal pada beberapa tahun silam ketika Sukasmo ke sana untuk mengadu untung. Terletak di Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Dadahup masuk kawasan "lahan gambut sejuta hektare". Dari sinilah pemerintah menguarkan janji kemakmuran bagi Sukasmo dan hampir 16 ribu transmigran lain dari tanah Jawa.
Di masa awal pembangunan megaproyek tersebut, Januari 1999, lahan gambut di Kalimantan Tengah itu rencananya disulap menjadi satu "metropolis pertanian" yang diisi oleh 1,6 juta transmigran. Apa yang terjadi? Metropolis itu gagal total. Yang datang ke lokasi ini hanya 16 ribu transmigran. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat pada tahun 2002 angka ini melorot ke 5.984 orang saja—sebagian hengkang karena bangkrut, sisanya bertahan karena tak ada pilihan.
Sukasmo, 53 tahun, salah satunya. Di atas lahan sawahnya seluas dua hektare, bulir-bulir padi mulai muncul beberapa pekan lalu. "Jika menguning sedikit, langsung saya panen," ujarnya dengan waswas kepada TEMPO. Ayah dua anak ini mencemaskan air bah yang bakal merendam area sawahnya pada bulan-bulan mendatang. Bencana ini kian kerap setelah pintu air dari pelat baja selebar 25 meter yang menutup kanal-kanal utama dicuri orang.
Tanpa pintu ini, air Sungai Barito akan meluap tak terkendali melalui kanal primer, sekunder, tersier, lalu ngendon di sawah-sawah, termasuk milik Sukasmo. Air bah itu menyentuh bibir lantai kayu rumah panggungnya yang kusam dan lapuk. Tapi dia memilih bertahan karena di Trenggalek toh dia tak punya apa-apa lagi. Dadahup pernah menjadi desa tersohor yang dikunjungi pembesar Jakarta, termasuk mantan presiden Soeharto. Sayang, impian Sukasmo akan kemakmuran runtuh tak lama setelah dia menginjak kampung ini. "Waktu itu saya ingin menangis dan balik lagi ke Jawa," ujarnya mengenang sambil menyedot rokoknya dalam-dalam.
Calon lumbung padi yang dijanjikan kepadanya dan belasan ribu transmigran lain itu hanya diseraki bekas batang pohon, tak siap garap. Keasaman tanahnya amat tinggi. Setiap kali hendak ditanami, tanah itu harus ditaburi kapur dulu. Itu pun tidak berhasil, lebih-lebih setelah proyek ini dinyatakan gagal. Pemerintah, menurut Sukasmo, tak lagi menyuplai kapur, pupuk, bahkan benih. Ribuan transmigran ditinggalkan begitu saja.
Untunglah tanah Dadahup lumayan subur. Zat hara yang masih bersisa setelah digerus proyek lahan gambut dapat menumbuhkan padi di tanah Sukasmo dan teman-temannya. Tapi ribuan transmigran lain berguguran. Kualitas hidup mereka melorot dari waktu ke waktu. Rumah panggungnya kian lapuk, sementara air bersih susah didapat.
Di antara mereka, ada yang memilih kembali ke Jawa setelah menjual tanahnya kepada penduduk lokal. Yang punya piutang ganti rugi dari pemerintah harus mengantre berjam-jam di Bank BNI Cabang Kapuas untuk mengambil cicilan uang ganti rugi. Wawa, 35 tahun, tukang ojek di Dadahup, misalnya. Orang tuanya mendapat total ganti rugi tanah sebesar Rp 15 juta. "Kemarin saya ambil ganti rugi tahap ketiga sebesar Rp 672 ribu," ujarnya kepada TEMPO.
Para transmigran yang gagal ini melakukan aneka upaya untuk menyambung hidup. Dua anak lelaki Sukasmo, misalnya, memburuhkan tenaga ke Kuala Kapuas, ibu kota Kabupaten Kapuas, sebagai buruh bangunan. Merasa terlalu renta menyusul kedua anaknya dan malu kembali ke Jawa, Sukasmo dan istrinya memilih menetap di Dadahup. Sawahnya dipanen maksimal dua kali setahun, memberinya hampir dua ton gabah kering—sekitar Rp 1,8 juta—sekali panen.
Kini, di ambang banjir bulan Maret, Sukasmo waswas menunggu mana yang lebih dulu tiba: panen atau air bah. n
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo