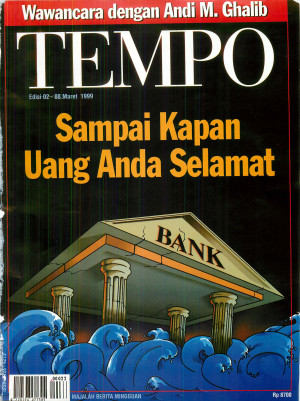Pasa Lariabangi terbaring lemah di atas kasur tipis berlapis tikar pandan di ruang tengah sebuah rumah panggung kayu di tepian Pulau Salaka. Dari kolong, terdengar suara kecipak air memukul-mukul tiang rumah yang terbuat dari batang pohon bakau. Pasa, 60 tahun, salah seorang tua-tua kampung, terbaring sakit sejak awal Februari lalu. Namun sulit baginya untuk menemui dokter atau sekadar mantri kesehatan. Sebab, siapa yang berani berdiam di Salaka?sebuah pulau kapur tandus seluas setengah hektare?kecuali 52 keluarga suku Bajau, yang menganggap laut dan pantai adalah kampung halamannya?
Lelaki tua di atas termasuk generasi kedua suku Bajau yang menghuni pulau tandus tersebut. "Ayah saya orang Bajau pertama yang tinggal di Pulau Salaka," ujarnya kepada wartawan TEMPO Tomi Lebang. Seperti rata-rata kaum lelaki Bajau, Pasa, juga anak-anak lelakinya, bekerja sebagai nelayan. Dalam struktur sosial desa, ia diangkat sebagai Mattowa Bajau, si kepala kampung. Di rumah panggung itu, ayah 12 anak itu berdiam bersama istri, beberapa anak dan menantu.
Kepulauan Togean terdiri dari rangkaian 56 pulau besar dan kecil, terhampar di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Wilayah seluas 775 kilometer persegi ini masuk ke Kabupaten Poso. Tidak semua pulau bernama?seperti halnya Salaka?di atas peta. Namun itu bukan soal penting benar. Sebab, bagi orang Bajau, yang hidup menyebar di Sulawesi atau terutama pulau-pulau Indonesia Timur lain, laut dan pesisir, di mana pun letaknya, adalah tempat menemukan rezeki dan kehidupan, seperti yang dilakukan Pasa Lariabangi dan para warga Salaka.
Di pulau itu tegak sekitar 30 rumah di atas air laut, yang dihuni para nelayan. Ritme kehidupan bergerak dari rumah panggung itu ke laut?paling jauh ke pasar-pasar tradisional, tempat hasil laut diperjualbelikan dengan uang atau tukar-menukar barang kebutuhan. Suku Bajau adalah nelayan ulung. Mereka memang dilahirkan menjadi pelaut sejati. Alhasil, kehidupan suku Bajau adalah kehidupan yang bersandar pada angin dan musim serta tanda-tanda alam.
Musim durian, misalnya, menjadi pertanda ramainya ikan kerapu berlalu-lalang di perairan sekitar. Daun-daun bakau jenis tertentu yang gugur di permukaan air adalah isyarat musim baik bagi ikan lolosi. "Bahkan, melalui dayung, mereka bisa mengetahui perairan yang sarat ikan," tutur Nizar Rahmatu, petugas lapangan Konsorsium Togean.
Pola-pola kehidupan yang mereka jalankan juga ternyata menunjang konservasi?sesuatu yang baru didengungkan para pejuang lingkungan ketika alam mulai rusak. Misalnya, karena menganggap dirinya bagian dari kehidupan laut, orang Bajau tidak mencari ikan sebanyak-banyaknya melainkan cukup untuk makan dan keperluan lain. Mereka biasa membuang kembali satu dua ikan ke laut. Tujuannya, membagi hasil dan makanan kepada "penguasa laut".
Dengan pola hidup seperti itu, sulit dibayangkan suku Bajau mencari penghidupan di darat. Tak aneh tatkala lembaga swadaya masyarakat (LSM) Liuntinuvu membujuk warga Salaka untuk pindah tiga bulan lalu, Pasa langsung menolak: "Kalau dikasih kebun, untuk apa? Kita tidak bisa berkebun," katanya.
Kabar tentang proyek pemindahan warga Salaka oleh LSM asal Palu tersebut amat meresahkan warga pulau kecil ini. "Dengar-dengar, kami akan dipindahkan ke hutan Kayome di Pulau Batudaka. Kami ini orang laut. Bisa setengah mati kalau pindah ke gunung," ujar Pasa melanjutkan. Kepulauan Togean memang dihuni beberapa etnis seperti Togean, Suluan, dan Bobongko. Namun orang Bajaulah yang terkenal sebagai pelaut dan nelayan.
Ide translokasi di atas datang dari Suaib Djafar, Ketua LSM Liuntinuvu. Pada 16 Juni 1997, ia mengajukan proporsal ke Gubernur Sulawesi Tengah, Bandjela Paliudju, untuk memukimkan warga kampung nelayan ini ke daratan Kepulauan Togean. Untuk setiap keluarga, Suaib berjanji menyediakan lahan perkebunan dua hektare. Dalam proposal tersebut Liuntinuvu meminta dana Rp 51 juta untuk kegiatan yang disebutnya sebagai kerja sama kemitraan dengan orang Bajau itu.
Dana itu dipakai untuk membeli kapal dan perahu motor, rompong (bagan), dan lampu, yang akan digunakan suku Bajau bersama LSM ini. Sebagai pengelola kapal motor, Liuntinuvu menetapkan pembagian hasil seperti ini: 30 persen untuk nelayan penjaga rompong, 30 persen untuk nelayan tenaga kerja di kapal motor, 30 persen untuk Liuntinuvu, 10 persen untuk dana operasional.
Belakangan, warga Pulau Salaka mulai mengendus akal bulus LSM ini. Sebab, petugas LSM tidak hanya mendata warga Pulau Salaka, tapi juga warga Desa Taningkola, di Pulau Batudaka, sekitar 1 kilometer di seberang Salaka. "Dengan alasan pemukiman suku Bajau, mereka mau ambil kayu di hutan," ujar Pasa menjelaskan.
Akan halnya Suaib Djafar, ketika ditemui TEMPO di Palu 10 Februari lalu, mengatakan bahwa niatnya mentranslokasi suku Bajau semata-mata mulia adanya, yakni mengentaskan penghuni kampung tersebut menjadi warga sejahtera. "Kita tidak ingin menjadikan keterbelakangan suku Bajau sebagai daya tarik wisata," ujarnya.
Masalah suku Bajau di Salaka sebetulnya hanya sebagian kecil dari sebuah problem besar yang melanda para nelayan tradisional di dalam wilayah kepulauan tersebut, yakni penangkapan ikan secara ilegal, yang menurut sumber-sumber TEMPO "disponsori" para pembeli ikan yang nota bene para pemilik kapal ikan. Caranya? Dengan bom dan racun sianida, yang bukan saja merusak biota laut dalam jumlah besar, tapi juga berbahaya bagi para konsumen karena sisa racun sianida, misalnya, belum benar-benar bersih tatkala dimasak para koki di restoran.
Setiap pagi, di seputar Pulau Batudaka?pulau terbesar di Togean?terdengar bunyi ledakan keras bom ikan dari laut disusul riak berbusa di permukaannya. Penangkapan ikan dengan cara terlarang ini telah menyebar di seluruh kawasan Teluk Tomini, terutama di tempat sunyi seperti pulau karang Angkayo dekat Pulau Malenge, pesisir Teluk Kilat dekat Lembanato, Pantai Tumbulawa di Batudaka, Tangkean, dan Tongkabo.
"Sekarang para nelayan makin berani mengebom ikan," tutur Harry Budianto, penyuluh dari Dinas Perikanan Sulawesi Tengah, kepada TEMPO di Ampana. Di Ampana?gerbang ke Kepulauan Togean dari daratan Sulawesi Tengah?pupuk urea cap Obor buatan Malaysia dan Singapura bisa dibeli dengan harga Rp 40.000 per kilogram. Jumlah ini bisa untuk merakit empat botol bom. Daya bunuh tiap bom adalah sejauh 25 meter dari titik lempar. Jenis yang menjadi sasaran bom adalah ikan rumah-rumah, katombo, lalosi, dan budara.
Kegiatan pengeboman ini makin berjaya karena jaringan nelayan pengebom, pembeli, dan pemasok bom kait-mengait dalam jaringan yang rapi, "Tidak gampang memasukkan urea jenis ini karena sudah dilarang," ujar Harry Budianto. Menurut para nelayan setempat, pemasok bahan bom kepada nelayan Togean adalah para pembeli ikan sendiri. Namun pihak pembeli menolak dituding sebagai biang keladi. Edi Jusuf dari UD Bina Togean, misalnya, membantah tuduhan keterlibatannya. "Untuk apa? Saya sendiri tidak membeli ikan hasil pengeboman," ujarnya. Edi malah menunjuk para pembeli ikan di tengah laut sebagai pemasok bom.
Gencarnya pengeboman ikan di Togean lambat laun akan merusak seluruh ekosistem di kepulauan itu. Dwi Lystio Rahayu, peneliti oseanologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang pernah meneliti terumbu karang di Teluk Tomini, menyimpulkan bahwa 50 persen terumbu karang rusak, 25 persen di antaranya kritis. Kerusakan paling parah ditemukan di bagian timur Karang Lumpatan dan di sebelah tenggara Pulau Kabalutan. "Di daerah ini banyak terumbu karang yang sudah hancur total," kata Christoverius Hutabarat, peneliti dari LSM Yayasan Bina Sains Hayati Indonesia.
Selain dengan bom, ikan juga dibunuh dengan racun sianida. Cara ini juga sangat merusak lingkungan. Praktek ini makin meluas dengan masuknya para cukong. Tingginya harga ikan di pasar luar negeri makin mendorong kegiatan meracun ikan. "Ikan goropa, yang di Togean dibeli para cukong seharga Rp 15.000 hingga Rp 20.000, di Hong Kong dilepas dengan harga US$ 15 sampai US$ 20," ujar Tommy Lantang, Direktur International Marine Alliances, kepada Verrianto Madjowa dari TEMPO.
Semua cerita di atas seakan belum lengkap menggambarkan ruwetnya problem sosial dan lingkungan di Togean. Pengeboman ikan masih "diimbangi" dengan perburuan ilegal terhadap binatang langka seperti monyet, babi rusa, biawak, ketam kelapa, dan ketam kenari. Satwa langka ini ada yang menempuh perjalanan panjang ke pasar-pasar luar negeri, tapi ada yang nasibnya berakhir di sekadar restoran lokal.
Togean memang diberkati dengan kekayaan dan kemolekan bahari dan hutan. Namun, entah bagaimana harus menggambarkan nasibnya ketika ikan dan isi laut terus-menerus dibom dan diracun, ketika satwa langka diburu secara gelap, dan ketika suku-suku pelaut yang hidup dengan kesetiaan kepada alam dipindahkan demi proyek komersial segelintir orang.
Dan persoalan tampaknya belum akan berakhir walau Februari silam Togean menerima penghargaan internasional bidang wisata di London. Sebab, lagi-lagi, entah bagaimana anugerah itu harus dilihat: sebuah ironi yang justru membawa "beban" lain. Atau permulaan sebuah masa baru yang menjanjikan lebih banyak peruntungan bagi anak negeri di kepulauan permai itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini