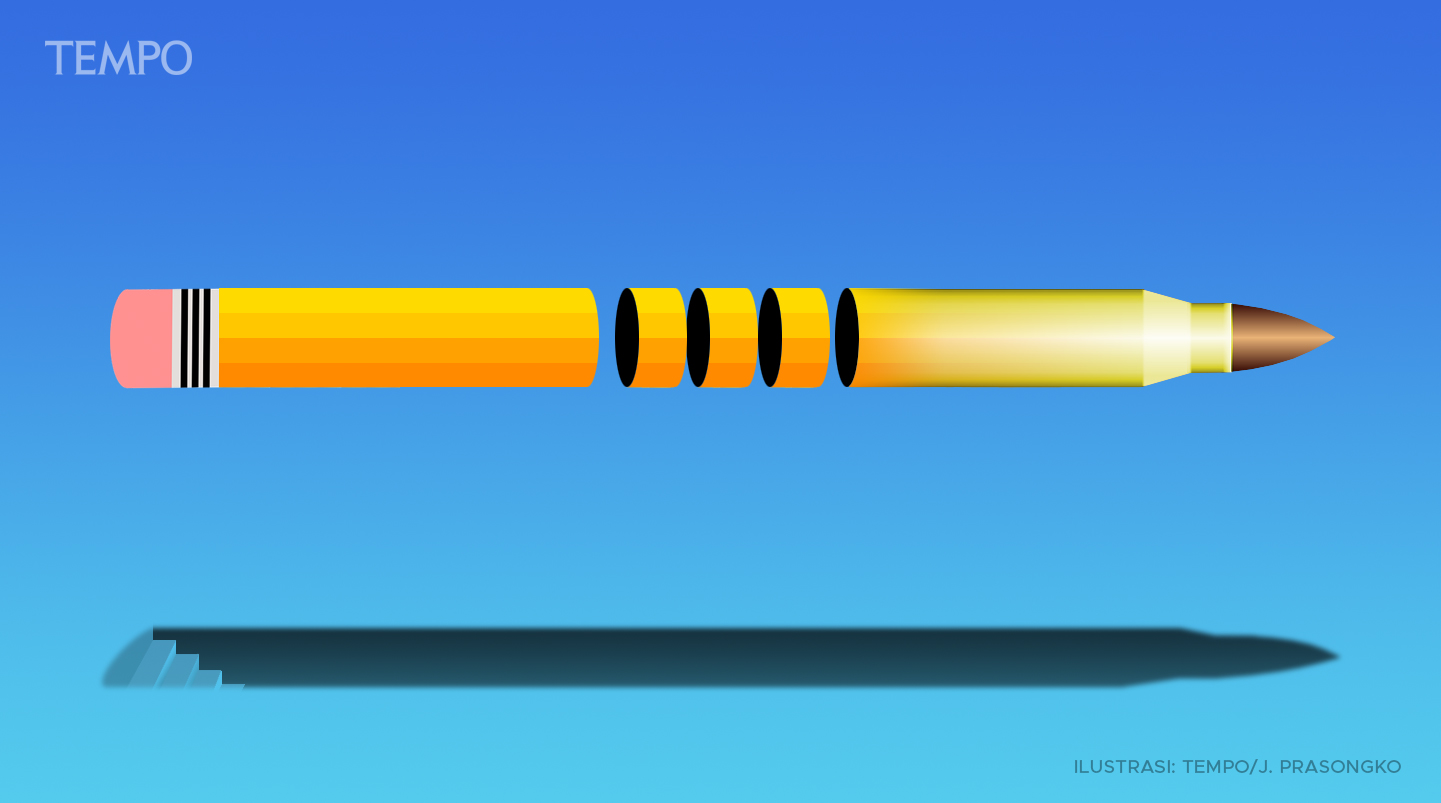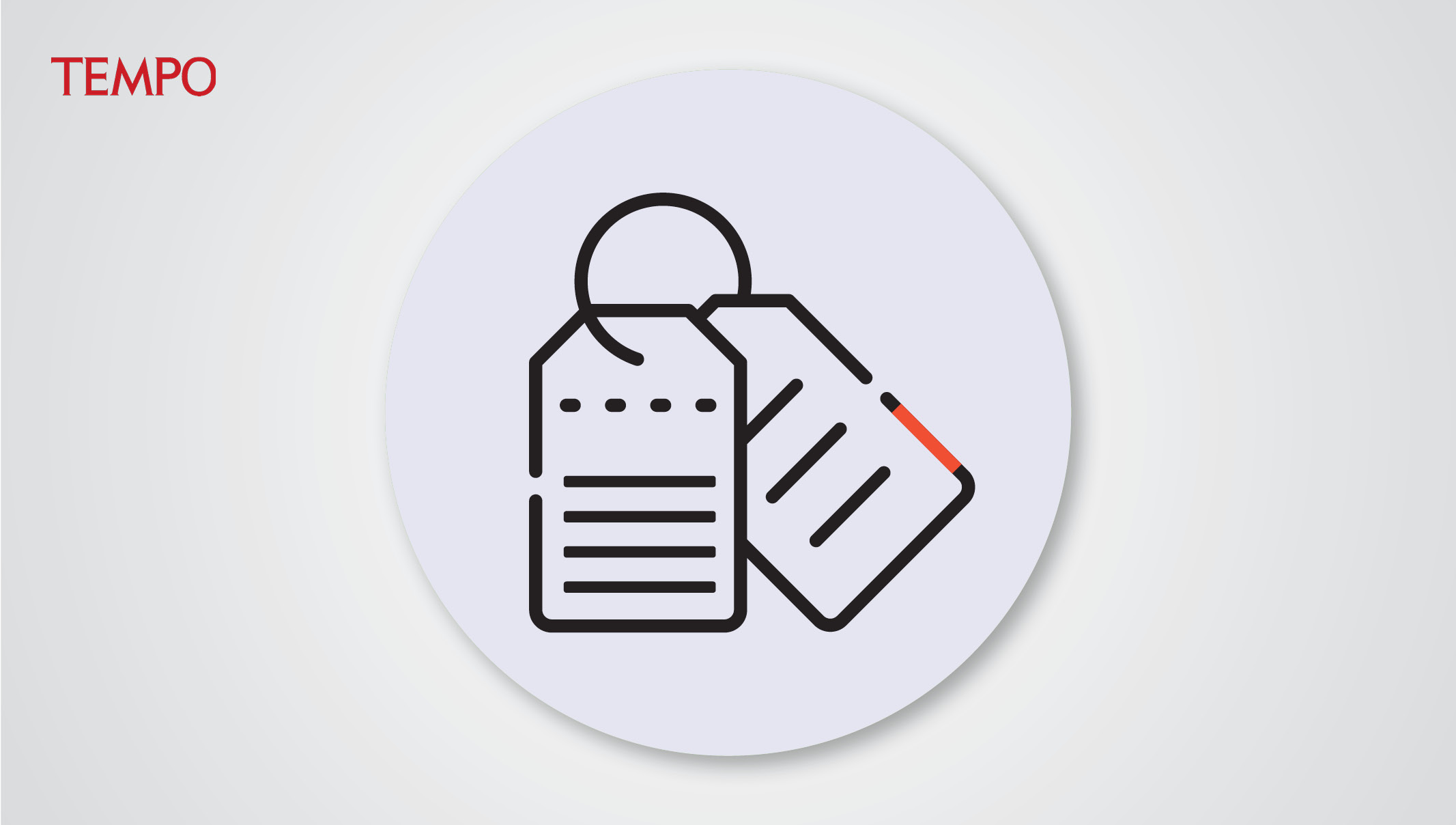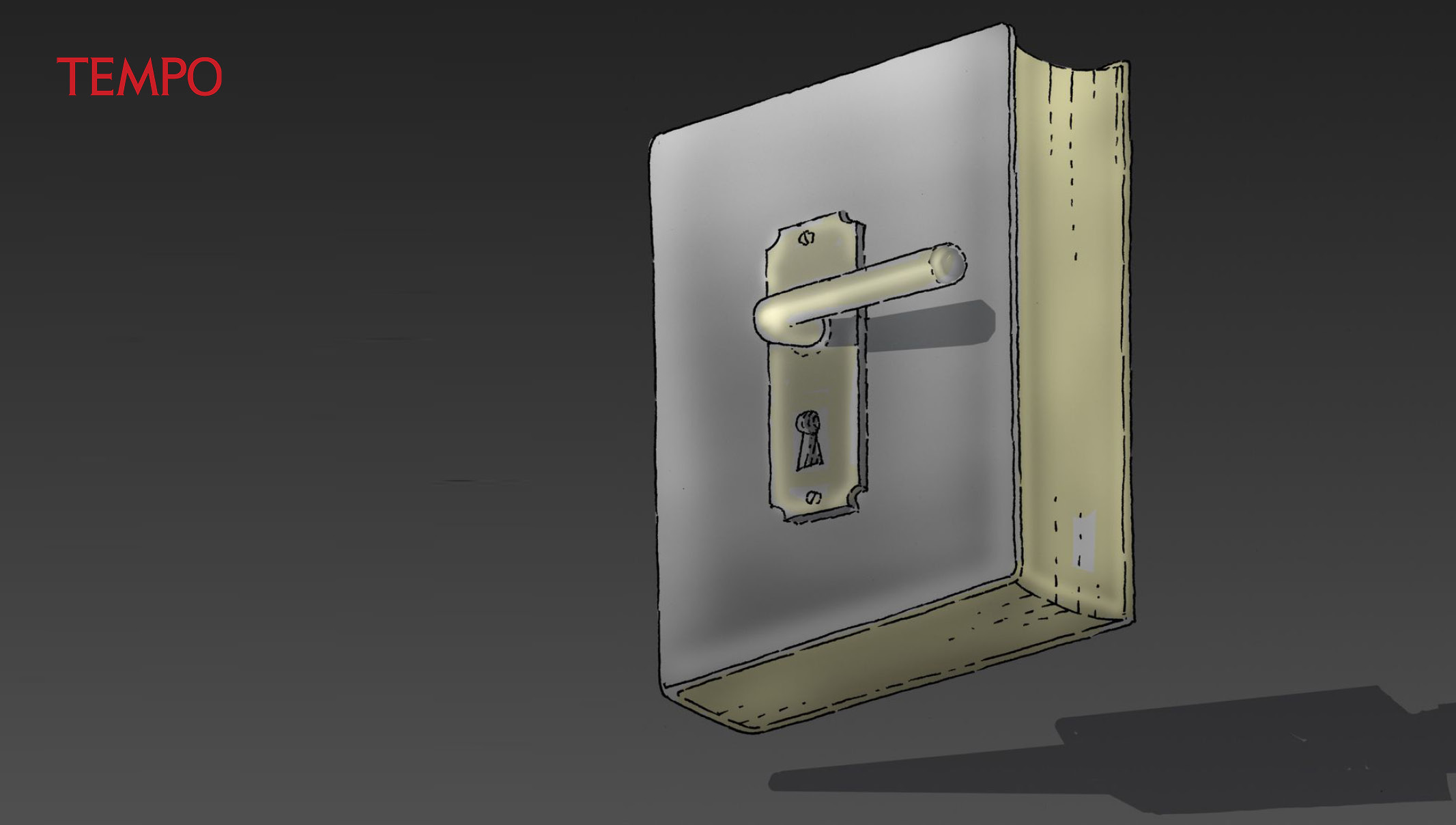Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ardhienus
Asisten Direktur di Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Dalam setiap krisis, isu likuiditas perbankan selalu menyita perhatian karena perannya sebagai pelumas kegiatan ekonomi. Bila aliran likuiditas perbankan terhambat, hal itu akan berdampak buruk pada semua sektor ekonomi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Untungnya, hingga saat ini likuiditas perbankan Indonesia masih cukup longgar. Hal ini dapat kita lihat dari pertumbuhan secara tahunan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) pada April 2020 yang melampaui penyaluran kredit. Pertumbuhan DPK mencapai 8,08 persen, sedangkan kredit naik hanya 5,73 persen. Hal ini mengakibatkan indikator likuiditas bank yang lazim dipakai, yakni rasio kredit yang diberikan terhadap perolehan DPK (LDR), menjadi 91,55 persen.
Dibandingkan dengan akhir tahun lalu, likuiditas perbankan saat ini sejatinya kian longgar. Pada Desember 2019, pertumbuhan DPK mencapai 6,54 persen, sedikit lebih tinggi dari penyaluran kredit yang naik 6,08 persen, sehingga menghasilkan rasio LDR 93,64 persen. Gambaran LDR yang makin rendah menunjukkan keseimbangan antara perolehan dana dan penyalurannya.
Bank Indonesia (BI) telah menggelontorkan likuiditas yang cukup besar ke pasar uang dan perbankan hingga mencapai Rp 386 triliun. Bahkan, pada Mei 2020, injeksi likuiditas kembali bertambah menjadi sekitar Rp 500 triliun. Kebijakan BI ini membuat likuiditas perbankan semakin gemuk. Namun likuiditas tersebut tidak merata. Bank besar kebanjiran likuiditas, sedangkan bank kecil masih berjuang mendapatkannya.
Pada periode krisis, biasanya muncul fenomena mengeringnya likuiditas di pasar uang antar-bank (PUAB), seperti yang terjadi dalam krisis keuangan Asia 1997-1998 dan krisis keuangan global 2008-2009. Hal ini terlihat pada volume PUAB yang cenderung turun dan frekuensi transaksi yang semakin jarang. Tidak banyak bank yang bertransaksi di PUAB, padahal PUAB merupakan sarana bagi bank untuk mendapatkan likuiditas jangka pendek guna mengatasi masalah liquidity mismatch yang sering terjadi.
Fenomena ini terlihat dari Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI). Pada Februari 2020, rata-rata harian volume transaksi PUAB jangka pendek (overnight) yang dominan di PUAB masih cukup tinggi, mencapai Rp 10,45 triliun. Namun, pada Maret dan April, yakni saat pandemi Covid-19 menyerang Indonesia, rata-rata harian volume transaksi menyusut masing-masing menjadi Rp 9,12 triliun dan Rp 6,02 triliun. Begitu juga dengan rata-rata harian frekuensi transaksi yang menurun tajam. Sementara pada Februari rata-rata harian frekuensi transaksi PUAB overnight masih 107 juta, pada Maret dan April menyusut masing-masing menjadi 93 juta dan 59 juta transaksi.
Fenomena kekeringan likuiditas di PUAB menyebabkan bank-bank yang membutuhkan likuiditas jangka pendek kesulitan. Imbasnya, suku bunga PUAB melonjak tinggi. Di sisi lain, muncul penjualan aset secara obral seiring dengan kebutuhan untuk segera mendapatkan likuiditas. Tentu hal ini berdampak buruk pada bank yang tidak likuid. Kemunculan fenomena ini pada akhirnya menuntun bank untuk menimbun likuiditasnya yang dapat berdampak pada kenaikan suku bunga deposito.
Dalam perspektif yang lebih luas, perilaku bank dalam menimbun likuiditas ini berpotensi menimbulkan risiko sistemis. Dalam periode dengan tekanan, jika sejumlah bankterutama bank besar yang selalu menjadi penyedia likuiditasmemutuskan menimbun likuiditas dan berhenti meminjamkannya kepada bank lain, bank-bank yang memiliki ketergantungan tinggi pada PUAB akan terpapar risiko likuiditas yang tinggi. Risiko sistemis dapat muncul dan menyebar ke bank-bank lain melalui jalur jejaring keuangan yang terbentuk di PUAB. Semakin kompleks jejaring keuangan itu, potensi timbulnya risiko sistemis kian kuat.
Perilaku bank ini, menurut berbagai literatur, didasari dua motif, yaitu berjaga-jaga dan spekulasi. Motif berjaga-jaga muncul karena beberapa hal. Mereka yakin tidak dapat memperoleh pinjaman antar-bank ketika dihadapkan pada kondisi kekurangan likuiditas atau penarikan deposan yang tidak terduga sebelumnya. Motif lain adalah mengantisipasi keketatan atau guncangan likuiditas di pasar, sehingga bank terhindar dari penjualan aset dengan harga murah yang dapat mengakibatkan bank rugi. Bank yang telanjur berkomitmen memberikan kredit akan cenderung menyimpan likuiditasnya sebagai langkah antisipasi tatkala perusahaan menarik pinjamannya.
Adapun motif spekulasi beranjak dari kondisi permintaan likuiditas yang tinggi, yang biasanya berdampak pada harga aset yang rendah. Bank yang terdesak oleh kebutuhan likuiditas akan menjual aset secara murah untuk mendapatkan likuiditas dalam waktu cepat. Bank penimbun likuiditas akan mengambil manfaat dengan membeli aset murah tersebut untuk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi ketika krisis berlalu. Acharya et al. (2012) menyebut motif spekulasi ini sebagai perilaku predator yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi suatu bank yang terdesak oleh kebutuhan likuiditas.
Karena itu, analisis dan pemantauan terhadap perilaku bank menimbun likuiditas dalam sistem perbankan pada masa krisis sangat penting. Hal ini tidak hanya berguna bagi pengelolaan risiko individu bank itu sendiri (mikroprudensial), tapi juga penting bagi bank sentral. Selain untuk mencegah dan memitigasi risiko sistemis (makroprudensial), perilaku bank menimbun likuiditas akan menghambat efektivitas kebijakan moneter BI. l
*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi.