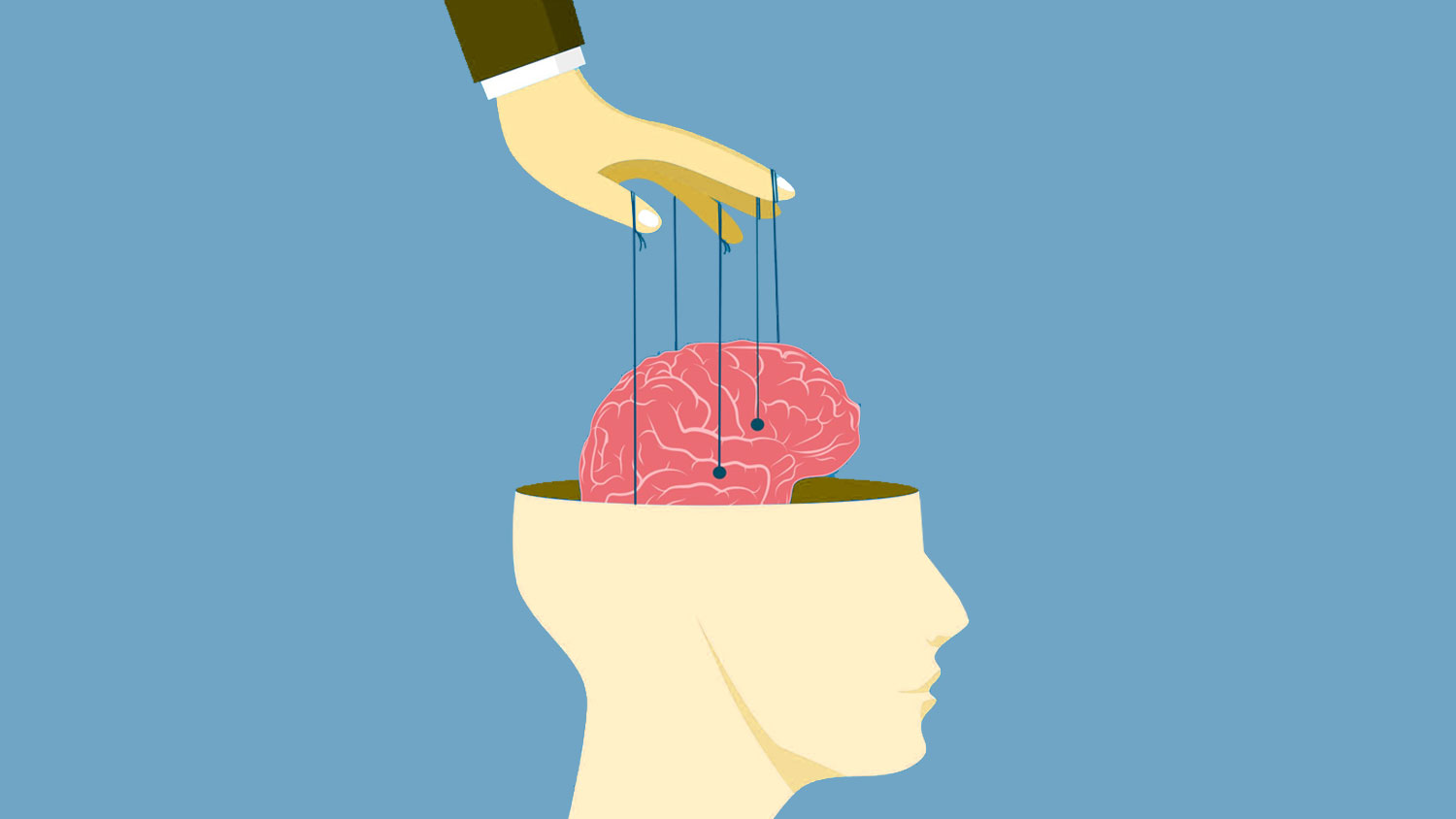Sarjana Filsafat dari Universitas Gadjah Mada (1998) dan Master Ilmu Komunikasi dari Universitas Paramadina (2020. Bergabung di Tempo sejak 2001. Meliput berbagai topik, termasuk politik, sains, seni, gaya hidup, dan isu internasional.
Di ranah sastra dia menjadi kurator sastra di Koran Tempo, co-founder Yayasan Mutimedia Sastra, turut menggagas Festival Sastra Bengkulu, dan kurator sejumlah buku kumpulan puisi. Puisi dan cerita pendeknya tersebar di sejumlah media dan antologi sastra.
Dia menulis buku Semiologi Roland Bhartes (2001), Isu-isu Internasional Dewasa Ini: Dari Perang, Hak Asasi Manusia, hingga Pemanasan Global (2008), dan Empat Menyemai Gambut: Praktik-praktik Revitalisasi Ekonomi di Desa Peduli Gambut (2020).