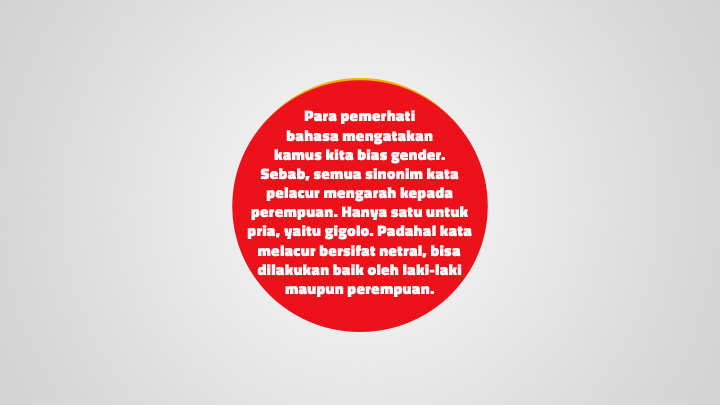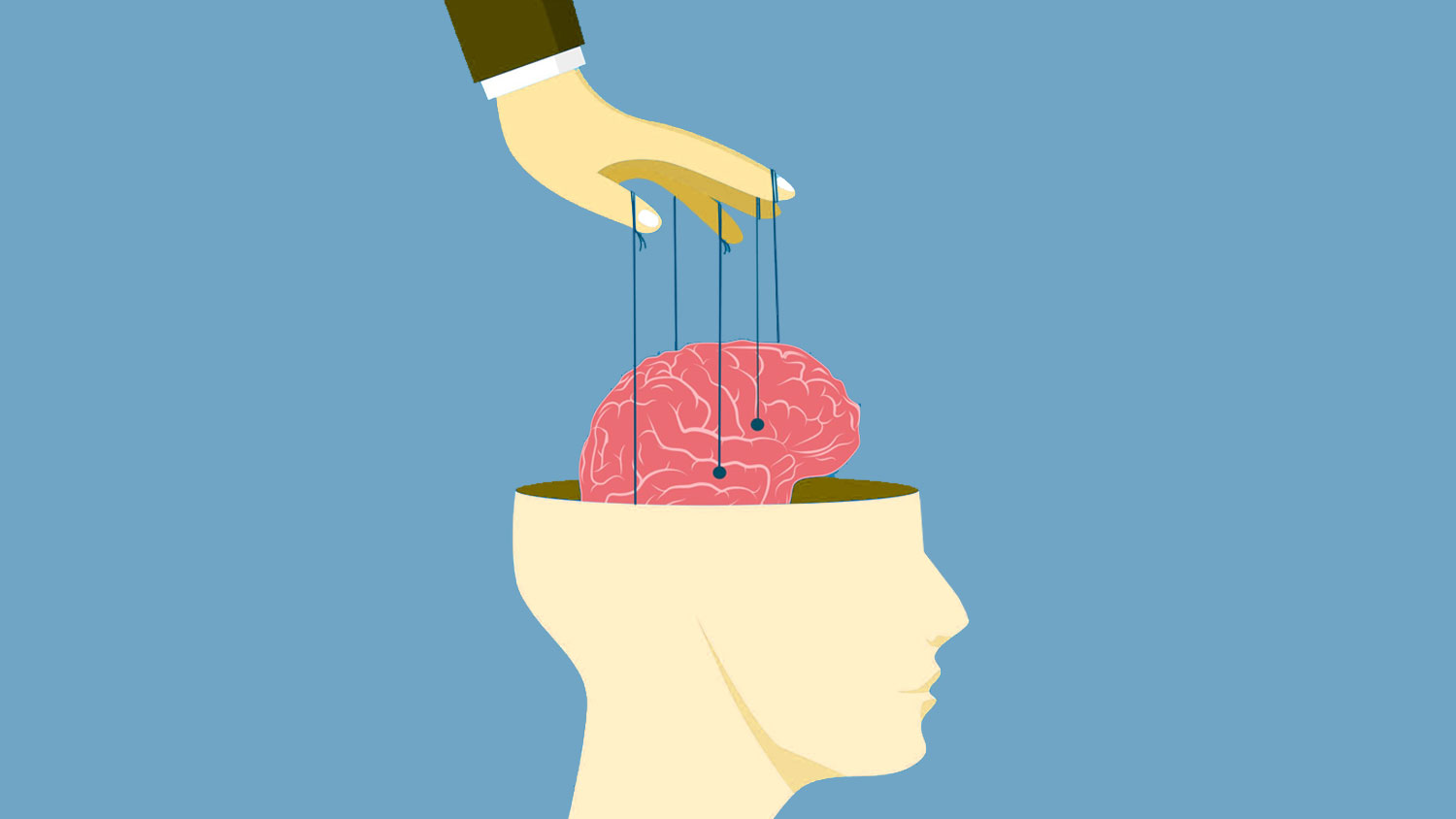Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

GELADAK adalah lantai atau dek kapal. Namun geladak bisa menjadi metafora bagi sesuatu yang ternistakan. Frasa anjing-anjing geladak, misalnya, bisa berarti anjing-anjing liar atau penjahat di pelabuhan. Geladak diasosiasikan dengan dunia kriminal, bajingan, dan preman. Film Anjing-anjing Geladak (1972) yang disutradarai Nico Pelamonia berdasarkan naskah Sjuman Djaya, misalnya, berkisah tentang sindikat narkotik. Seluruh bagian cerita mengambil adegan sudut-sudut kota. Tapi awal film ini dimulai dari penurunan peti-peti bubuk haram di sebuah dermaga.
Yang menarik, salah satu sinonim kata pelacur menggunakan kata geladak, yaitu perempuan geladak. Entah mengapa pelacur diasosiasikan dengan geladak. Perempuan geladak mungkin kini jarang digunakan, mengingat sinonim kata pelacur demikian melimpah. Para pemerhati bahasa sering heran mengapa begitu banyak sinonim kata pelacur dalam bahasa Indonesia. Ada sundal, ayam kampung, pekcun, pramunikmat, balon, pramuria, cabo, lonte, perek, kupu-kupu malam, dan sebagainya. Ini belum termasuk yang dikembangkan di daerah. Dalam bahasa prokem walikan Malang, Jawa Timur, misalnya dikenal istilah nolab, yang merupakan kebalikan kata balon. Para pemerhati bahasa mengatakan kamus kita bias gender. Sebab, semua sinonim kata pelacur mengarah kepada perempuan. Hanya satu untuk pria, yaitu gigolo. Padahal kata melacur bersifat netral, bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan.
Sesungguhnya profesi pelacur dikenal secara resmi sejak zaman Jawa kuno mulai abad ke-8 sampai ke-14. Para arkeolog menengarai istilah jalir dalam prasasti dan kakawin sebagai perempuan tunasusila. Dalam prasasti, terdapat pegawai pemerintah yang disebut juru jalir. Tugasnya diperkirakan khusus mengatur pelacuran dan menarik pajak dari pelacur. Dalam dunia Jawa kuno, pajak adalah penghasilan utama kerajaan. Dalam struktur birokrasi, ada lapisan pegawai pemungut pajak yang disebut mangilala drawya haji. Mereka menarik pajak perdagangan, pajak usaha kerajinan, pajak orang asing, pajak keluarga, sampai pajak kegiatan seni. Belum ada prasasti, misalnya, yang menampilkan perlawanan masyarakat kecil atas beratnya pajak karena prasasti selalu ditulis berdasarkan perspektif kekuasaan. Pada zaman Balitung, menurut arkeolog, terdapat kebijakan keringanan pajak yang dapat diajukan rakyat. Kita tak tahu apakah pernah seorang jalir mengajukan keberatan.
Arkeolog Dwi Cahyono dalam simposium Borobudur Writers and Cultural Festival tahun lalu mengatakan kata jalir mengacu pada perempuan dari kalangan rendahan. Ini mengingatkan kita terhadap Centhini. Serat abad ke-19 ini di satu pihak menguraikan berbagai gaya persetubuhan liar para pelacur memuaskan satu bahkan beberapa lelaki. Namun, di pihak lain, ia memberikan petunjuk tata cara santun tapi jitu menggauli istri berdasarkan hitungan tanggal bulan Jawa.
Kata jalir menghilang dalam bahasa Jawa sekarang. Dalam khazanah sastra modern Indonesia sendiri, kita lihat banyak kata pelacur dan sinonimnya digunakan. Kita ingat sajak Rendra “Bersatulah Pelacur-pelacur Jakarta” atau puisi F. Rahadi “Sumpah WTS”. Novel Remy Sylado, Ca-bau-kan, yang kemudian “dilayarperakkan” oleh Nia Dinata, mengingatkan bahwa kata cabo berasal dari khazanah Tionghoa peranakan. Dalam lirik lagu pop, kata pelacur dilantunkan suara basah Iin Parlina dalam lagu Bimbo, “Hitam Kelam”. (Almarhum) Gombloh menghasilkan lagu Loni Pelacur & Pelacurku serta Doa Seorang Pelacur. Akan halnya lagu Titiek Puspa: Kupu-kupu Malam.
Tema yang mengikat lagu-lagu itu lebih ke simpati terhadap kaum tersisih. Tidak ada vonis moral terhadap mereka—sebagaimana Riantiarno dalam Opera Kecoa membela para waria yang dikejar-kejar aparat. Saat Iwan Fals mengeluarkan lagu “Lonteku”, mungkin untuk pertama kalinya kata lonte menjadi judul lagu. Terasa menyentak. Lagu ini berkisah tentang seorang lelaki yang memiliki kekasih pelacur. Liriknya: Lonteku, terima kasih/Atas pertolonganmu di malam itu/Lonteku, dekat padaku/Mari kita lanjutkan cerita hari esok. Bila didengarkan, lirik lagu ini terasa manusiawi. Kini kata lonte menjadi kontroversi. Dalam sebuah ceramah Maulid Nabi, seorang habib mengecap seorang artis dengan sebutan itu. Terasa berbeda konteks dengan lagu Iwan Fals. Yang ini sarkastis dan tidak pada tempatnya.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo